- Beranda
- Stories from the Heart
TULAH (Jasadnya Mati, Dendamnya Beranak Pinak) ~~ Based on True Story
...
TS
the.darktales
TULAH (Jasadnya Mati, Dendamnya Beranak Pinak) ~~ Based on True Story
Salam kenal semuanya, agan-agan kaskuser dan para penghuni forum SFTH...
Perkenalkan, kami adalah empat orang anonim yang berdasar pada kesamaan minat, memutuskan untuk membuat akun yang kemudian kami namai THE DARK TALES.
Dan kehadiran kami di forum ini, adalah untuk menceritakan kisah-kisah gelap kepada agan-agan semua. Kisah-kisah gelap yang kami dengar, catat dan tulis ulang sebelum disajikan kepada agan-agan.
Semua cerita yang akan kami persembahkan nanti, ditulis berdasarkan penuturan narasumber dengan metode indepth interview atau wawancara mendalam yang kemudian kami tambahi, kurangi atau samarkan demi kenyamanan narasumber dan keamanan bersama.
Semua cerita yang akan kami persembahkan nanti, ditulis berdasarkan penuturan narasumber dengan metode indepth interview atau wawancara mendalam yang kemudian kami tambahi, kurangi atau samarkan demi kenyamanan narasumber dan keamanan bersama.
Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kami akan segera sajikan thread perdana kami.
Selamat menikmati...
Quote:

Kisah ini berdasarkan kejadian nyata, berdasarkan penuturan beberapa narasumber dan literasi tambahan. Beberapa penyamaran, penambahan dan pengurangan mengenai lokasi, nama tokoh dan alur cerita kami lakukan untuk kepentingan privasi dan keamanan.
KARAKTER




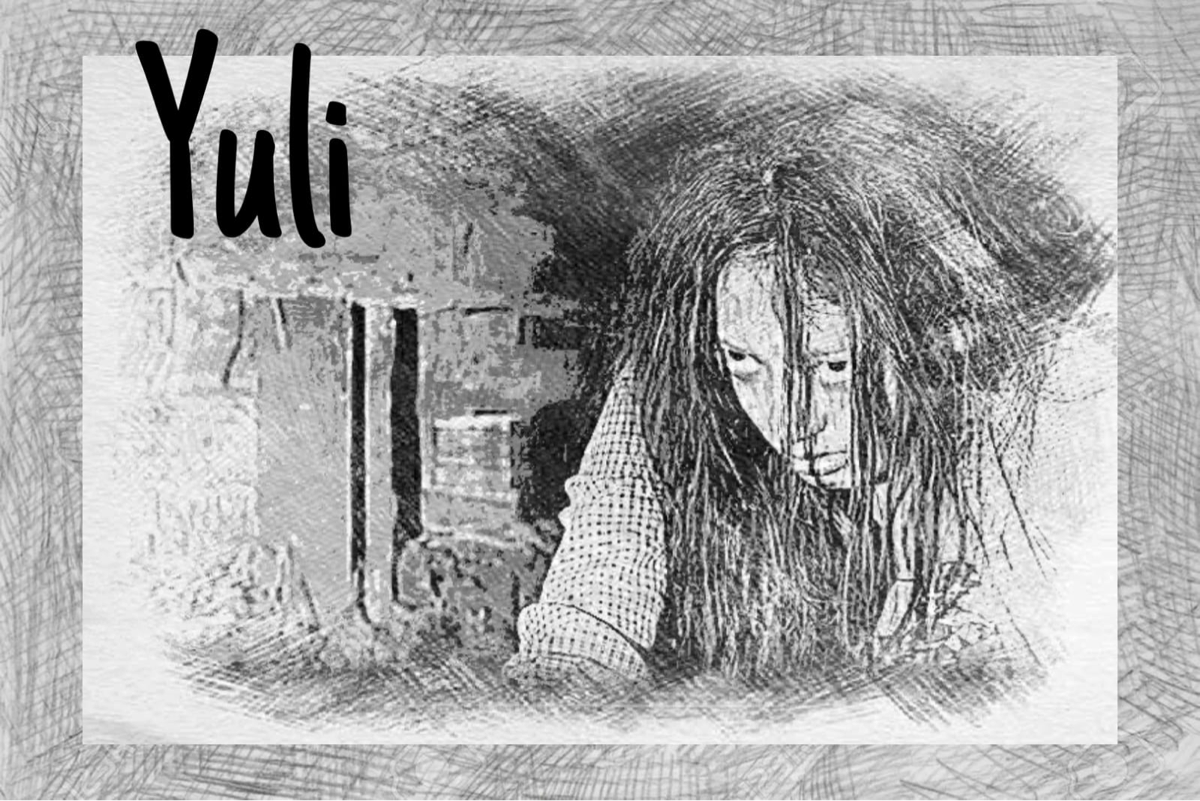
INDEX
CHAPTER SATU: MELANGGAR BATAS
PROLOG
BAGIAN 1
BAGIAN 2
BAGIAN 3
BAGIAN 4BAGIAN 10
Spoiler for Karakter:




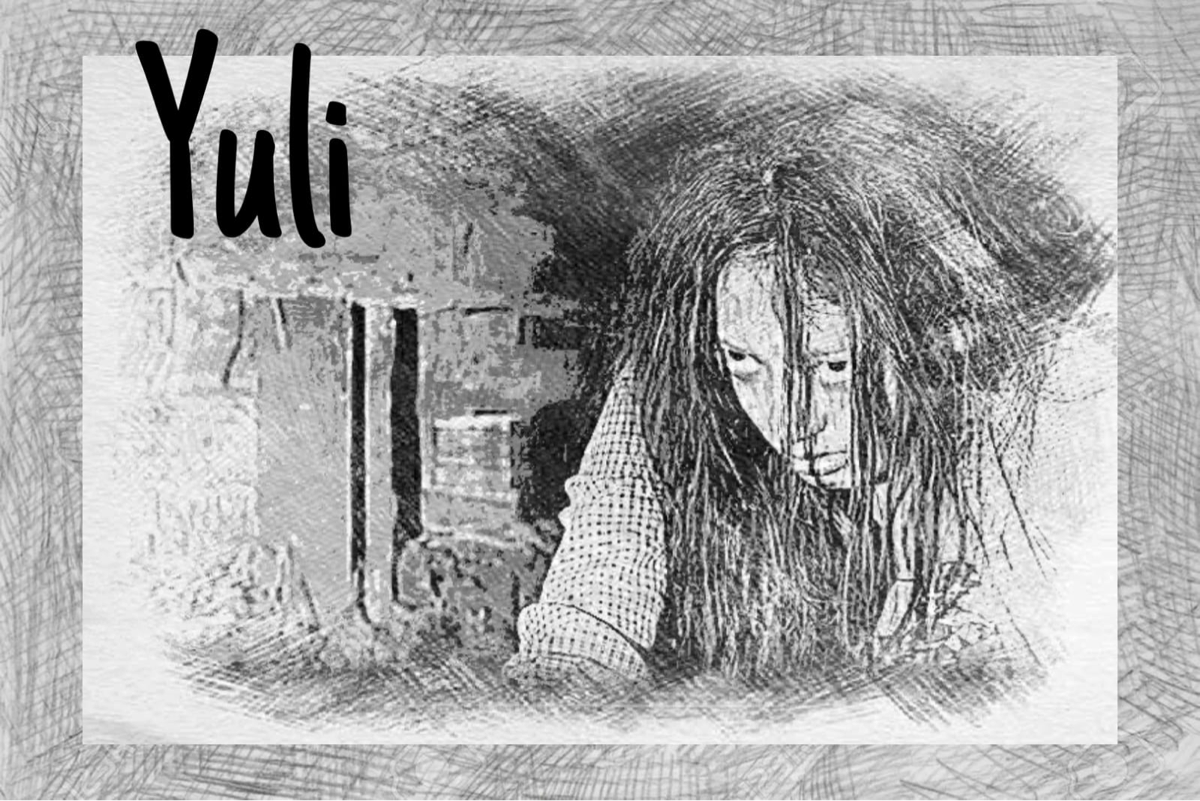
REVIEW
Spoiler for Review:
Quote:
Original Posted By gumzcadas►Udah lama sekali ga ngerasain sensasi mencekam di cerita horror, terakhir ngerasa gak nyamana baca kisah dikaskus itu, yg cerita sekian tahun tinggal dirumah hantu. Dan skrg gw ngerasain sensasinya lagi. Sehat2 terus ts. Setelah sekian tahun jd silent reader, akhirnya komen lagi dforum ini.
Quote:
Original Posted By ibunovi►Cara penulisan menggambarkan seolah2 qt ada d tempat itu....degdegan ane ga...mantapssss😌😌😌
Quote:
Original Posted By sempakloreng►Epic banget ceritanya gann

Quote:
Original Posted By aan1984►Menurut saya ceritanya sudah sangat bagus gan, gaya penulisannya bagus ane suka meskioun kdg ada typo dikit... Tetep semangat ya gan lanjutin cerita ini, ane bakal kecewa klo cerita ini ga brs 

Quote:
Original Posted By erickarif93x►Well this is the one of the best story i've ever read. Terima kasih untuk narasumber yang bersedia untuk menceritakan cerita ini.
INDEX
CHAPTER SATU: MELANGGAR BATAS
PROLOG
BAGIAN 1
BAGIAN 2
BAGIAN 3
BAGIAN 4
CHAPTER DUA: PEMBEBASAN
CHAPTER TIGA: PERBURUAN
Spoiler for Side-Story:
CHAPTER 4: AWAL MULA
[UNPUBLISHED]
CHAPTER 5: TULAH
Polling
Poll ini sudah ditutup. - 115 suara
Menurut agan-agan, perlu enggak dibuatkan kisah tentang "Jurnal"?
Bikinin gan ane penasaran!
69%
Kagak usah, langsung mulai aja Chapter 4
31%
Diubah oleh the.darktales 28-06-2022 15:07
bambu.rindang dan 268 lainnya memberi reputasi
247
321.9K
Kutip
2.6K
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.7KThread•51.4KAnggota
Tampilkan semua post
TS
the.darktales
#738
BAGIAN 15
Quote:
Tidak ada satupun yang menaruh peduli dengan Mas Supri yang terus dihujani bacokan oleh kakak iparnya di perempatan Dusun. Berkali-kali dia mencoba bangkit dan berusaha untuk kabur, tapi fisiknya sudah terlanjur kebas akibat rasa sakit dari luka terbuka di sekujur tubuh.
"Ampun, Mas..." Jadi, hanya kalimat itu yang bisa Mas Supri katakan. Memohon pengampunan seperti kucing kecil yang tak berdaya, kepada monster yang mengamuk habis-habisan karena mendapati adik perempuan kesayangannya datang ke pasar dan menemuinya dengan muka babak belur serta mata yang sembab. Tentu saja, sang kakak ipar tidak sudi menerima permintaan maaf itu. Alih-alih berhenti, ayunan golok malah makin menjadi-jadi. Mas Supri terdesak, ia silangkan kedua lengannya untuk menutupi badan.
Tapi bagaimanapun, lengan manusia hanya terdiri dari kulit, daging dan tulang. Bukan besi yang bisa menahan serangan sebuah senjata tajam. Alhasil, kini Mas Supri malah tak ubahnya seperti orang yang sedang dikuliti. Kulit lengannya mengelupas, dan darah terus mengucur deras dari luka yang terbuka itu. Daging dan tulangnya bahkan kini bisa terlihat mata.
"Bajingan! Bajingan! Bajingan!" Amarah Sang Kakak Ipar belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Aku akan mati malam ini. Dia berbisik dalam hati. Dia sudah menyerah. Kedua lengan yang menjadi tameng terakhir yang tersisa, perlahan-lahan melemah dan jatuh ke tanah. Membuat kepala dan dadanya berada dalam keadaan terbuka. Tinggal menunggu satu serangan, dan semua akan selesai.
Golok yang memerah oleh darahnya itu kemudian diangkat ke udara dengan gagahnya, seperti sesosok malaikat maut yang mengambil ancang-ancang sebelum berlari maju dan merenggut nafas terakhir Mas Supri.
Hingga kemudian, sebuah keajaiban terjadi!
"Waskito, berhenti!!"
Tubuh Mas Supri memang sudah kehilangan daya. Tapi mata dan telinganya masih berfungsi dengan baik. Dia mengenali suara itu sebagai suara milik Kepala Dusun . Lelaki paling dihormati dan dipandang tak ubahnya seperti raja di Srigati; Pak Gunardi.
Malaikat maut yang merasuki golok itu, urung mencabut nyawa Mas Supri. Sang Kakak Ipar membatalkan niatnya, dan langsung menoleh ke arah suara. Lima orang temannya yang sama-sama preman pasar itu langsung siaga menjadi pagar betis. Dengan tenaga yang tinggal sisa-sisa, Mas Supri memiringkan tubuh yang tergeletak di jalanan makadam tepat di tengah perempatan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Entah kepada siapa Mas Supri harus bersyukur atas keajaiban dan keberuntungan yang ia alami malam ini. Di sana, berjejer para warga desa dengan senter –beberapa membawa obor menyala- di tangan kiri dan berbagai macam gamandi tangan kanan. Mata mereka tajam memandang ke arah Kakak Iparnya yang sekarang tampak sedikit panik dan ketakutan. Mereka cuma berenam, jelas kalah jumlah dari warga yang sepertinya tak kurang dari dua puluh orang.
Lalu tampak berdiri di barisan paling depan, ada Pak Gunardi, anak perempuan semata wayangnya yang Mas Supri kenal bernama Astria, dan Sarmin yang berdiri tepat di samping kakek-kakek tua sesepuh dusun Srigati; Mbah Gondo.
Air mata pecah di pelupuk mata Mas Supri, terharu melihat semua ini. Tak disangka-sangka, bahwa warga Srigati yang selama ini ia kira selalu menyepelekan dan membencinya, ternyata menjadi malaikat penyelamat malam ini. Tak ada hal lain yang ada dipikiran Mas Supri, selain rasa syukur yang tak henti-henti dia ucapkan. Apapun akan dia lakukan setelah ini, bahkan jika harus mencium kaki setiap orang sebagai wujud terima kasih dan permintaan maafnya.
Kemudian terlihat, Pak Gunardi sebagai kepala Dusun, melangkah maju ke depan. Mendekat ke arah Sang Kakak Ipar dan gerombolannya. Wajahnya begitu dingin, yakin dan tak ada rasa takut sedikitpun. Kemudian dia berhenti, tepat satu jengkal di depan dada Sang Kakak Ipar.
Pergi dari dusun ini dan lepaskan Supri, atau kami bakal sikat kalian semua tanpa ampun! Mas Supri sudah membayangkan kalimat itu akan meluncur dari mulut Pak Gunardi.
Tapi...
"Iki kan urusan keluargamu to, Was?" (Ini urusan keluargamu kan, Was?)
Sang Kepala Dusun diam sejenak, mengalihkan pandangan dari Sang Kakak Ipar ke arah Mas Supri yang tergeletak di atas tanah. Seulas senyum penuh arti merekah di bibir Pak Gunardi, sebelum ia kembali melanjutkan kalimatnya yang tadi terputus.
"Aku raiso melu campur. Tapi yen arep mbeleh Supri, ojo ning tengah ndalan. Gawanen nyang pojokan kono kae." (Aku tidak bisa ikut campur. Tapi kalau mau menyembelih Supri, jangan di tengah jalan seperti ini. Bawa ke pojokan sana saja.)
Pak Gunardi mengarahkan jari telunjuknya ke satu titik di arah timur perempatan. Ke sebuah bekas bangunan yang kini sudah ditumbuhi ilalang liar setinggi kaki orang dewasa. Walaupun tak bisa dibilang masih utuh, dan atapnya hanya menyisakan kayu-kayu penyangga tanpa genting yang seluruhnya sudah runtuh serta tembok-tembok yang bernoda hitam seperti bekas habis dibakar, tapi tempat itu masih cukup tertutup dan tampak tersembunyi.
"Neg wis bar, melu aku mlebu alas. Ngewangi wong-wong iki nggoleki maling." (Kalau sudah selesai, ikut aku masuk ke hutan. Bantu anak-anak ini nangkap maling.)
Sang Kakak Ipar mengangguk takzim kepada Pak Gunardi yang tanpa peduli meninggalkan Mas Supri dan membawa barisan warga yang memegang erat senjatanya masing-masing itu menuju kandang kambing tempatnya tadi berjaga bersama Agus dan Tarto. Sedangkan dirinya sendiri, diseret oleh dua orang menuju arah lain. Ke arah bangunan tua itu. Bangunan yang kata warga, dulunya adalah mushola dusun.
"Pegat mati luwih ngirit timbang pegat urip. Duite iso dinggo Adikku golek bojo anyar. Pora yo ngono, cah? Hahahaha!" (Cerai mati lebih ngirit daripada cerai hidup. Uangnya malah bisa diapakai adikku buat nyari suami baru. Bukannya gitu, bro? Hahaha!)
Tawa gerombolan itu sepertinya akan menjadi suara tawa terakhir yang bisa didengar Mas Supri di dunia ini.
"Ampun, Mas..." Jadi, hanya kalimat itu yang bisa Mas Supri katakan. Memohon pengampunan seperti kucing kecil yang tak berdaya, kepada monster yang mengamuk habis-habisan karena mendapati adik perempuan kesayangannya datang ke pasar dan menemuinya dengan muka babak belur serta mata yang sembab. Tentu saja, sang kakak ipar tidak sudi menerima permintaan maaf itu. Alih-alih berhenti, ayunan golok malah makin menjadi-jadi. Mas Supri terdesak, ia silangkan kedua lengannya untuk menutupi badan.
Tapi bagaimanapun, lengan manusia hanya terdiri dari kulit, daging dan tulang. Bukan besi yang bisa menahan serangan sebuah senjata tajam. Alhasil, kini Mas Supri malah tak ubahnya seperti orang yang sedang dikuliti. Kulit lengannya mengelupas, dan darah terus mengucur deras dari luka yang terbuka itu. Daging dan tulangnya bahkan kini bisa terlihat mata.
"Bajingan! Bajingan! Bajingan!" Amarah Sang Kakak Ipar belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Aku akan mati malam ini. Dia berbisik dalam hati. Dia sudah menyerah. Kedua lengan yang menjadi tameng terakhir yang tersisa, perlahan-lahan melemah dan jatuh ke tanah. Membuat kepala dan dadanya berada dalam keadaan terbuka. Tinggal menunggu satu serangan, dan semua akan selesai.
Golok yang memerah oleh darahnya itu kemudian diangkat ke udara dengan gagahnya, seperti sesosok malaikat maut yang mengambil ancang-ancang sebelum berlari maju dan merenggut nafas terakhir Mas Supri.
Hingga kemudian, sebuah keajaiban terjadi!
"Waskito, berhenti!!"
Tubuh Mas Supri memang sudah kehilangan daya. Tapi mata dan telinganya masih berfungsi dengan baik. Dia mengenali suara itu sebagai suara milik Kepala Dusun . Lelaki paling dihormati dan dipandang tak ubahnya seperti raja di Srigati; Pak Gunardi.
Malaikat maut yang merasuki golok itu, urung mencabut nyawa Mas Supri. Sang Kakak Ipar membatalkan niatnya, dan langsung menoleh ke arah suara. Lima orang temannya yang sama-sama preman pasar itu langsung siaga menjadi pagar betis. Dengan tenaga yang tinggal sisa-sisa, Mas Supri memiringkan tubuh yang tergeletak di jalanan makadam tepat di tengah perempatan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Entah kepada siapa Mas Supri harus bersyukur atas keajaiban dan keberuntungan yang ia alami malam ini. Di sana, berjejer para warga desa dengan senter –beberapa membawa obor menyala- di tangan kiri dan berbagai macam gamandi tangan kanan. Mata mereka tajam memandang ke arah Kakak Iparnya yang sekarang tampak sedikit panik dan ketakutan. Mereka cuma berenam, jelas kalah jumlah dari warga yang sepertinya tak kurang dari dua puluh orang.
Lalu tampak berdiri di barisan paling depan, ada Pak Gunardi, anak perempuan semata wayangnya yang Mas Supri kenal bernama Astria, dan Sarmin yang berdiri tepat di samping kakek-kakek tua sesepuh dusun Srigati; Mbah Gondo.
Air mata pecah di pelupuk mata Mas Supri, terharu melihat semua ini. Tak disangka-sangka, bahwa warga Srigati yang selama ini ia kira selalu menyepelekan dan membencinya, ternyata menjadi malaikat penyelamat malam ini. Tak ada hal lain yang ada dipikiran Mas Supri, selain rasa syukur yang tak henti-henti dia ucapkan. Apapun akan dia lakukan setelah ini, bahkan jika harus mencium kaki setiap orang sebagai wujud terima kasih dan permintaan maafnya.
Kemudian terlihat, Pak Gunardi sebagai kepala Dusun, melangkah maju ke depan. Mendekat ke arah Sang Kakak Ipar dan gerombolannya. Wajahnya begitu dingin, yakin dan tak ada rasa takut sedikitpun. Kemudian dia berhenti, tepat satu jengkal di depan dada Sang Kakak Ipar.
Pergi dari dusun ini dan lepaskan Supri, atau kami bakal sikat kalian semua tanpa ampun! Mas Supri sudah membayangkan kalimat itu akan meluncur dari mulut Pak Gunardi.
Tapi...
"Iki kan urusan keluargamu to, Was?" (Ini urusan keluargamu kan, Was?)
Sang Kepala Dusun diam sejenak, mengalihkan pandangan dari Sang Kakak Ipar ke arah Mas Supri yang tergeletak di atas tanah. Seulas senyum penuh arti merekah di bibir Pak Gunardi, sebelum ia kembali melanjutkan kalimatnya yang tadi terputus.
"Aku raiso melu campur. Tapi yen arep mbeleh Supri, ojo ning tengah ndalan. Gawanen nyang pojokan kono kae." (Aku tidak bisa ikut campur. Tapi kalau mau menyembelih Supri, jangan di tengah jalan seperti ini. Bawa ke pojokan sana saja.)
Pak Gunardi mengarahkan jari telunjuknya ke satu titik di arah timur perempatan. Ke sebuah bekas bangunan yang kini sudah ditumbuhi ilalang liar setinggi kaki orang dewasa. Walaupun tak bisa dibilang masih utuh, dan atapnya hanya menyisakan kayu-kayu penyangga tanpa genting yang seluruhnya sudah runtuh serta tembok-tembok yang bernoda hitam seperti bekas habis dibakar, tapi tempat itu masih cukup tertutup dan tampak tersembunyi.
"Neg wis bar, melu aku mlebu alas. Ngewangi wong-wong iki nggoleki maling." (Kalau sudah selesai, ikut aku masuk ke hutan. Bantu anak-anak ini nangkap maling.)
Sang Kakak Ipar mengangguk takzim kepada Pak Gunardi yang tanpa peduli meninggalkan Mas Supri dan membawa barisan warga yang memegang erat senjatanya masing-masing itu menuju kandang kambing tempatnya tadi berjaga bersama Agus dan Tarto. Sedangkan dirinya sendiri, diseret oleh dua orang menuju arah lain. Ke arah bangunan tua itu. Bangunan yang kata warga, dulunya adalah mushola dusun.
"Pegat mati luwih ngirit timbang pegat urip. Duite iso dinggo Adikku golek bojo anyar. Pora yo ngono, cah? Hahahaha!" (Cerai mati lebih ngirit daripada cerai hidup. Uangnya malah bisa diapakai adikku buat nyari suami baru. Bukannya gitu, bro? Hahaha!)
Tawa gerombolan itu sepertinya akan menjadi suara tawa terakhir yang bisa didengar Mas Supri di dunia ini.
Quote:
Melia tidak pernah benar-benar percaya setan, demit dan hal-hal yang berbau supranatural seumur hidup. Apalagi sejak memutuskan mengambil jurusan Psikologi selepas lulus SMA dan lulus sebelum akhirnya menjadi asisten dosen sambil meneruskan S2-nya. Bagi Melia, apa yang sering dideskripsikan orang sebagai pocong, kuntilanak, genderuwo dan sejenisnya, hanyalah hasil dari imajinasi yang tumbuh karena tutur cerita, budaya dan faktor-faktor penunjang lain yang mereka dengar dan percayai sepanjang hidup mereka.
Motif lain yang semakin mendukung eksistensi hantu-hantu tersebut di tengah masyarakat adalah perkara status sosial dan uang. Dukun, paranormal, spiritualis, apapun sebutannya, menjual keberadaan entitas-entitas tak kasat mata tersebut agar namanya dipercaya orang-orang dan kemudian dilabeli sebagai orang sakti, sebelum mereka mulai mengecer jimat-jimat untuk berbagai fungsi. Pengusir demit, penglaris usaha sampai penakluk sang idaman hati. Semua ada harganya.
Sikap skeptis itu Melia pegang teguh sebagai sebuah prinsip sampai umurnya 27 tahun sekarang ini. Bahkan dulu, waktu dia masih bersama Adil, mereka berdua sering bertengkar mengenai takhayul-takhayul itu. Adil selalu memulai menceritakan pengalaman horornya setiap kali naik gunung, dan Melia selalu membantah dengan melemparkan kemungkinan-kemungkinan secara psikologi.
Tapi sekarang, bagaimana Melia harus menjelaskan tentang Mas Eko yang seluruh matanya menjadi putih dan lidahnya menjulur sampai nyaris menyentuh tanah seperti tadi? Andai itu hanya sekadar halusinasi akibat dia terlalu lama menahan rasa dingin dan sakit akibat luka di kakinya, kenapa Imas juga menyaksikan hal yang sama persis seperti yang Melia lihat? Begitupun dengan aroma prengus bercampur wangi bunga-bungaan yang seketika menyeruak bebarengan dengan munculnya sosok menyerupai Mas Eko tadi. Sangat sulit bagi otak Melia untuk mencerna semuanya secara bersamaan, apalagi sekarang fokusnya terpecah akibat rasa perih di kaki yang kian menjadi dan kondisi Imas yang membuatnya sedikit khawatir.
Imas masih terus memapahnya sambil berjalan menjauh dari tempat tadi. Melia sudah berkata bahwa dia bisa berjalan sendiri, tapi Imas sepertinya tidak percaya. Jadi, dia hanya bisa membantu meringankan beban dengan mendorong badannya dengan kaki sebelah kiri agar beban tubuhnya menjadi tidak terlalu berat.
Tapi masalahnya, apakah benar jalan ini adalah jalur awal mereka tadi? Seingat Melia, jalan setapak itu tak jauh dari titik mereka menunggu Adil dan Eko. Tapi sekarang rasanya sudah jauh mereka berjalan, hanya lebatnya hutan jati yang ada di pandangan. Kalau dihitung-hitung, harusnya mereka sudah kembali ke jalan setapak sejak tadi.
Tentu saja, kalau jalur mereka tidak salah.
"Mbak Imas...tunggu, tunggu! Berhenti sebentar!" Melia melepaskan lengannya dari pundak Imas, kemudian merebahkan punggung di pohon jati yang ada di dekatnya. Nafasnya ngos-ngosan, tenaganya habis terbagi untuk terus berlari dan menahan rasa sakit. Bahkan ketika dia memeriksa betis kanannya, jaket yang diikatkan untuk menghentikan kucuran darah itu kini benar-benar telah basah dan berubah warna menjadi merah kehitaman.
"Kenapa, Mbak Melia?? Kakimu sakit lagi?? Tahan sedikit ya? sebentar lagi kita sampai! Ayo berdiri, kita jalan!!"
Imas yang kelihatannya juga tak kalah ngos-ngosan, seperti tidak peduli. Orang ini seperti sudah kehilangan kesadarannya. Dengan cara yang kasar, dia tarik lengan Melia dan berusaha mengangkatnya kembali. Sentakan itu kemudian, mau tak mau, membuat Melia yang sudah kepayahan tersulut emosinya.
"Anjing! Apa-apaan sih lo?!" Dia menarik tangannya dari genggaman Imas dan menghadiahinya sebuah tamparan kencang di pipi. Sebuah tamparan yang membuat Imas mundur beberapa langkah dan melemparkan pandangan tak percaya campur kaget.
"Kamu kenapa sih, Mbak?! Aku salah apa?!"
Melia semakin panas. Dengan langkah terpincang-pincang, dia mendekati Imas dan menyuruhnya melihat ke sekitarnya. "Kita nyasar! Lo sadar enggak sih, kita nyasar di tengah hutan!!"
Imas memandang sekelilingnya, dan wajahnya berubah pucat seketika. Pohon-pohon jati kian rapat, dan jalan setapak yang menjadi penanda mereka untuk berada di jalur yang seharusnya sama sekali tak terlihat.
"Ndak kok! Kata siapa kita nyasar? Itu, dusun Giriwatu udah tinggal di depan situ..." Imas menggumam kosong dengan mata yang berkaca-kaca. Dia maju beberapa langkah, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka tidak tersesat. Sedang Melia mengikuti dari belakang, bersiap memaki perempuan ini karena dia tahu di depan sana tidak ada jalan setapak yang mereka cari.
Sekitar sepuluh langkah mereka ambil, sampai akhirnya Imas berhenti. Dia diam, pandangannya tertuju pada sesuatu di depannya. Melia yang penasaran, ikut maju dan berdiri sejajar dengan Imas.
Di depan mereka kini terbentang sebuah jalur sungai kecil yang tampaknya sudah mengering bertahun-tahun. Letaknya agak menjorok ke bawah, dengan bebatuan yang mencuat di sana sini. Tak ada yang spesial bagi Melia, sampai Imas tiba-tiba menoleh ke arahnya. Pandangannya kosong, serupa pandangan seseorang yang sudah habis harapan.
"Kita bener-bener tersesat, Mbak. Maaf..." Kemudian tangannya menunjuk jauh ke belakang, searah dengan jalur sungai ini. "Di depan sana, sekitar empat ratus meter mengikuti jalur sungai ini, kita akan sampai ke sawah pendem. Kita tersesat terlalu jauh."
Melia roboh seketika. Dia peluk dan benamkan wajahnya di kaki Imas yang masih berdiri mematung, karena dia menangis deras sekali dan tak ingin suaranya menggema di seluruh hutan. Perlahan perasaan yang sejak dulu selalu dia benci untuk akui itu kembali merasuk ke dalam hatinya; dia rindu Adil. Dia rindu pelukan pria itu. Karena sekarang, rasanya hanya Adillah yang mampu membuatnya merasa aman dan hangat.
"Adil, lo dimana?" Isaknya dengan begitu pilu.
Bersamaan, dari kejauhan samar terdengar suara seseorang -bukan, itu suara beberapa orang- yang saling berbicara satu sama lain. Melia yang kemudian tersadar, langsung mengarahkan pandangannya jauh ke kedalaman hutan di belakang sana. Tampak titik-titik berwarna putih dan merah memancar di antara deretan pepohonan.
Itu bukan hantu, kali ini Melia yakin. Itu cahaya senter dan obor yang dibawa oleh manusia.
"Itu orang-orang Srigati. Mereka pasti sudah sadar kalau Yuli diculik dan mereka datang kesini buat nangkep kita..." Imas balik badan dan berjalan maju menuju arah obor-obor itu. Melia yang cepat tanggap mengetahui gelagat Imas yang sudah kehilangan harapan dan akan menyerahkan diri, segera menarik perempuan itu dan memaksanya menyingkir.
Otak Melia dipaksa bekerja saat ini juga. Tidak mungkin kalau harus bersembunyi di jalur sungai karena tempatnya terlalu terbuka. Mereka akan dengan mudah ditemukan oleh orang-orang itu. Matanya kemudian berkeliling, memaksa melihat dalam gelap. Hingga di sudut sana, sekitar lima puluh meter dari tempat mereka berdiri, Melia melihat batu besar dengan cekungan ke dalam di bagian bawahnya. Tempatnya tepat di turunan menuju bekas jalur sungai. Dan kalau dilihat dari tinggi cekungan itu, sepertinya cukup bagi dua tubuh perempuan untuk bersembunyi di dalamnya.
Mungkin ini adalah ide paling memungkinkan saat ini. Setidaknya mereka bisa menghindari orang-orang Srigati sampai mereka melewati tempat ini dan pergi ke area hutan yang lain. Tapi, Melia tidak sadar bahwa di belakang mereka, sesosok bayangan muncul dari lebatnya hutan. Seorang lelaki yang memakai jaket tebal berwarna hitam, sengaja tak menghidupkan senter yang dipegangnya agar pergerakannya tidak diketahui oleh siapapun.
"Berhenti." Intonasi suaranya tenang namun jelas dan tegas. Membuat Melia dan Imas yang tak siap, melompat karena terkejut dan menoleh ke arah suara.
Kebekuan tercipta untuk beberapa saat. Sang pria misterius itu diam di tempatnya, begitupun Melia dan Imas yang tak bergerak barang sejengkalpun. Bahkan tubuh Melia bergetar hebat karena ketakutan, mengingat jarak di antara mereka cukup dekat dan pria itu bisa dengan mudah melakukan apapun dalam jarak sedekat ini.
Tapi sepertinya ini bukan antara Melia dan pria itu. Ada sesuatu yang lain, yang Melia sadari ketika tiba-tiba Imas berucap lirih. Bibirnya menyebut satu nama sambil menatap tajam ke arah si pria.
"Sarmin..."
"Imas...”
Motif lain yang semakin mendukung eksistensi hantu-hantu tersebut di tengah masyarakat adalah perkara status sosial dan uang. Dukun, paranormal, spiritualis, apapun sebutannya, menjual keberadaan entitas-entitas tak kasat mata tersebut agar namanya dipercaya orang-orang dan kemudian dilabeli sebagai orang sakti, sebelum mereka mulai mengecer jimat-jimat untuk berbagai fungsi. Pengusir demit, penglaris usaha sampai penakluk sang idaman hati. Semua ada harganya.
Sikap skeptis itu Melia pegang teguh sebagai sebuah prinsip sampai umurnya 27 tahun sekarang ini. Bahkan dulu, waktu dia masih bersama Adil, mereka berdua sering bertengkar mengenai takhayul-takhayul itu. Adil selalu memulai menceritakan pengalaman horornya setiap kali naik gunung, dan Melia selalu membantah dengan melemparkan kemungkinan-kemungkinan secara psikologi.
Tapi sekarang, bagaimana Melia harus menjelaskan tentang Mas Eko yang seluruh matanya menjadi putih dan lidahnya menjulur sampai nyaris menyentuh tanah seperti tadi? Andai itu hanya sekadar halusinasi akibat dia terlalu lama menahan rasa dingin dan sakit akibat luka di kakinya, kenapa Imas juga menyaksikan hal yang sama persis seperti yang Melia lihat? Begitupun dengan aroma prengus bercampur wangi bunga-bungaan yang seketika menyeruak bebarengan dengan munculnya sosok menyerupai Mas Eko tadi. Sangat sulit bagi otak Melia untuk mencerna semuanya secara bersamaan, apalagi sekarang fokusnya terpecah akibat rasa perih di kaki yang kian menjadi dan kondisi Imas yang membuatnya sedikit khawatir.
Imas masih terus memapahnya sambil berjalan menjauh dari tempat tadi. Melia sudah berkata bahwa dia bisa berjalan sendiri, tapi Imas sepertinya tidak percaya. Jadi, dia hanya bisa membantu meringankan beban dengan mendorong badannya dengan kaki sebelah kiri agar beban tubuhnya menjadi tidak terlalu berat.
Tapi masalahnya, apakah benar jalan ini adalah jalur awal mereka tadi? Seingat Melia, jalan setapak itu tak jauh dari titik mereka menunggu Adil dan Eko. Tapi sekarang rasanya sudah jauh mereka berjalan, hanya lebatnya hutan jati yang ada di pandangan. Kalau dihitung-hitung, harusnya mereka sudah kembali ke jalan setapak sejak tadi.
Tentu saja, kalau jalur mereka tidak salah.
"Mbak Imas...tunggu, tunggu! Berhenti sebentar!" Melia melepaskan lengannya dari pundak Imas, kemudian merebahkan punggung di pohon jati yang ada di dekatnya. Nafasnya ngos-ngosan, tenaganya habis terbagi untuk terus berlari dan menahan rasa sakit. Bahkan ketika dia memeriksa betis kanannya, jaket yang diikatkan untuk menghentikan kucuran darah itu kini benar-benar telah basah dan berubah warna menjadi merah kehitaman.
"Kenapa, Mbak Melia?? Kakimu sakit lagi?? Tahan sedikit ya? sebentar lagi kita sampai! Ayo berdiri, kita jalan!!"
Imas yang kelihatannya juga tak kalah ngos-ngosan, seperti tidak peduli. Orang ini seperti sudah kehilangan kesadarannya. Dengan cara yang kasar, dia tarik lengan Melia dan berusaha mengangkatnya kembali. Sentakan itu kemudian, mau tak mau, membuat Melia yang sudah kepayahan tersulut emosinya.
"Anjing! Apa-apaan sih lo?!" Dia menarik tangannya dari genggaman Imas dan menghadiahinya sebuah tamparan kencang di pipi. Sebuah tamparan yang membuat Imas mundur beberapa langkah dan melemparkan pandangan tak percaya campur kaget.
"Kamu kenapa sih, Mbak?! Aku salah apa?!"
Melia semakin panas. Dengan langkah terpincang-pincang, dia mendekati Imas dan menyuruhnya melihat ke sekitarnya. "Kita nyasar! Lo sadar enggak sih, kita nyasar di tengah hutan!!"
Imas memandang sekelilingnya, dan wajahnya berubah pucat seketika. Pohon-pohon jati kian rapat, dan jalan setapak yang menjadi penanda mereka untuk berada di jalur yang seharusnya sama sekali tak terlihat.
"Ndak kok! Kata siapa kita nyasar? Itu, dusun Giriwatu udah tinggal di depan situ..." Imas menggumam kosong dengan mata yang berkaca-kaca. Dia maju beberapa langkah, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka tidak tersesat. Sedang Melia mengikuti dari belakang, bersiap memaki perempuan ini karena dia tahu di depan sana tidak ada jalan setapak yang mereka cari.
Sekitar sepuluh langkah mereka ambil, sampai akhirnya Imas berhenti. Dia diam, pandangannya tertuju pada sesuatu di depannya. Melia yang penasaran, ikut maju dan berdiri sejajar dengan Imas.
Di depan mereka kini terbentang sebuah jalur sungai kecil yang tampaknya sudah mengering bertahun-tahun. Letaknya agak menjorok ke bawah, dengan bebatuan yang mencuat di sana sini. Tak ada yang spesial bagi Melia, sampai Imas tiba-tiba menoleh ke arahnya. Pandangannya kosong, serupa pandangan seseorang yang sudah habis harapan.
"Kita bener-bener tersesat, Mbak. Maaf..." Kemudian tangannya menunjuk jauh ke belakang, searah dengan jalur sungai ini. "Di depan sana, sekitar empat ratus meter mengikuti jalur sungai ini, kita akan sampai ke sawah pendem. Kita tersesat terlalu jauh."
Melia roboh seketika. Dia peluk dan benamkan wajahnya di kaki Imas yang masih berdiri mematung, karena dia menangis deras sekali dan tak ingin suaranya menggema di seluruh hutan. Perlahan perasaan yang sejak dulu selalu dia benci untuk akui itu kembali merasuk ke dalam hatinya; dia rindu Adil. Dia rindu pelukan pria itu. Karena sekarang, rasanya hanya Adillah yang mampu membuatnya merasa aman dan hangat.
"Adil, lo dimana?" Isaknya dengan begitu pilu.
Bersamaan, dari kejauhan samar terdengar suara seseorang -bukan, itu suara beberapa orang- yang saling berbicara satu sama lain. Melia yang kemudian tersadar, langsung mengarahkan pandangannya jauh ke kedalaman hutan di belakang sana. Tampak titik-titik berwarna putih dan merah memancar di antara deretan pepohonan.
Itu bukan hantu, kali ini Melia yakin. Itu cahaya senter dan obor yang dibawa oleh manusia.
"Itu orang-orang Srigati. Mereka pasti sudah sadar kalau Yuli diculik dan mereka datang kesini buat nangkep kita..." Imas balik badan dan berjalan maju menuju arah obor-obor itu. Melia yang cepat tanggap mengetahui gelagat Imas yang sudah kehilangan harapan dan akan menyerahkan diri, segera menarik perempuan itu dan memaksanya menyingkir.
Otak Melia dipaksa bekerja saat ini juga. Tidak mungkin kalau harus bersembunyi di jalur sungai karena tempatnya terlalu terbuka. Mereka akan dengan mudah ditemukan oleh orang-orang itu. Matanya kemudian berkeliling, memaksa melihat dalam gelap. Hingga di sudut sana, sekitar lima puluh meter dari tempat mereka berdiri, Melia melihat batu besar dengan cekungan ke dalam di bagian bawahnya. Tempatnya tepat di turunan menuju bekas jalur sungai. Dan kalau dilihat dari tinggi cekungan itu, sepertinya cukup bagi dua tubuh perempuan untuk bersembunyi di dalamnya.
Mungkin ini adalah ide paling memungkinkan saat ini. Setidaknya mereka bisa menghindari orang-orang Srigati sampai mereka melewati tempat ini dan pergi ke area hutan yang lain. Tapi, Melia tidak sadar bahwa di belakang mereka, sesosok bayangan muncul dari lebatnya hutan. Seorang lelaki yang memakai jaket tebal berwarna hitam, sengaja tak menghidupkan senter yang dipegangnya agar pergerakannya tidak diketahui oleh siapapun.
"Berhenti." Intonasi suaranya tenang namun jelas dan tegas. Membuat Melia dan Imas yang tak siap, melompat karena terkejut dan menoleh ke arah suara.
Kebekuan tercipta untuk beberapa saat. Sang pria misterius itu diam di tempatnya, begitupun Melia dan Imas yang tak bergerak barang sejengkalpun. Bahkan tubuh Melia bergetar hebat karena ketakutan, mengingat jarak di antara mereka cukup dekat dan pria itu bisa dengan mudah melakukan apapun dalam jarak sedekat ini.
Tapi sepertinya ini bukan antara Melia dan pria itu. Ada sesuatu yang lain, yang Melia sadari ketika tiba-tiba Imas berucap lirih. Bibirnya menyebut satu nama sambil menatap tajam ke arah si pria.
"Sarmin..."
"Imas...”
Spoiler for gaman:
Bagi yang tidak tahu gaman, itu adalah bahasa jawa yang artinya kurang lebih adalah senjata tajam. Bisa celurit, golok atau pisau daging. Saya akhirnya memakai kata gaman karena kurang bisa menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia.
wakazsurya77 dan 32 lainnya memberi reputasi
33
Kutip
Balas
Tutup