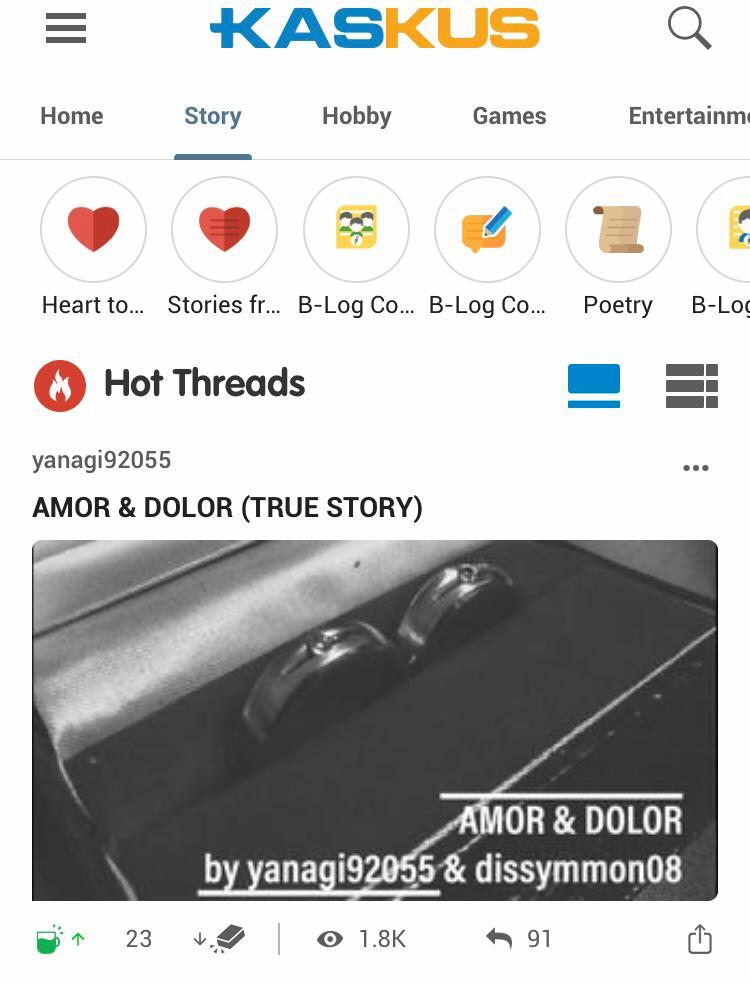- Beranda
- Stories from the Heart
AMOR & DOLOR (TRUE STORY)
...
TS
yanagi92055
AMOR & DOLOR (TRUE STORY)
Selamat Datang di Trit Kami
私のスレッドへようこそ

TERIMA KASIH BANYAK ATAS ATENSI DAN APRESIASI YANG TELAH GANSIS READERBERIKAN DI TIGA TRIT GUE DAN EMI SEBELUMNYA. SEMOGA DI TRIT INI, KAMI DAPAT MENUNJUKKAN PERFORMA TERBAIK (LAGI) DALAM PENULISAN DAN PACKAGING CERITA AGAR SEMUA READER YANG BERKUNJUNG DI SINI SELALU HAPPY DAN TERHIBUR!
Quote:
Spoiler for MUARA SEBUAH PENCARIAN (TAMAT):
Spoiler for AKHIR PENANTIANKU (ONGOING):
Spoiler for PERATURAN:
Spoiler for FAQ, INDEX, MULUSTRASI, TEASER:
HAPPY READING! 

Quote:
Diubah oleh yanagi92055 15-11-2024 12:56
uang500ratus dan 92 lainnya memberi reputasi
83
186.4K
3.2K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.7KThread•52.5KAnggota
Tampilkan semua post
TS
yanagi92055
#562
Lost_Part 5A
Sekilas tentang kantor ini. Kantor ini memiliki luas kurang lebih 300 – 500 meter persegi, dengan menguasai setengah lantai 4 sebuah gedung di bilangan Kuningan, bagian selatan Ibukota, tidak terlalu jauh dengan kantor utama gue. Kantor ini menggunakan sistem sewa per dua tahun terhadap office space gedung. Interiornya sengaja dibuat tanpa banyak sekat, kecuali untuk ruang meeting, pantry, ruang C level, dan ruang bersantai yang isinya ada video game, TV LED ukuran 65 inch dari Korea, dan ada beberapa board games yang seru kalau dimainkan berkelompok. Tersedia juga kasur lipat kecil dan beanbag yang bentuknya sama persis seperti di kontrakan Anin. Pokoknya ala-ala ruang kantor startup masa kini. Pada hampir setiap sudut ruangannya terdapat alat semprot pewangi ruangan otomatis yang mana gue yakini adalah idenya Anin. Mengakali operasional kantor dengan membuatnya lebih estetik ternyata ampuh, minimal untuk meningkatkan kinerja para staf yang berasal dari generasi sekarang, atau yang familiar kita sebut Gen Z.
Bekerjasama dengan orang-orang seumuran dengan Emi atau mungkin lebih muda lagi itu tantangannya cukup berat, karena tidak hanya disini, di kantor utama gue pun seperti itu keadaannya. Seperti tidak banyak inovasi, keinginan kuat untuk membuktikan diri tidak terlalu nampak dan lain sebagainya yang kadang kalau dipikirkan bisa bikin stres. Tetapi gue tidak mau memukul rata semua begitu, karena di divisi lain dari yang gue temukan, seperti misalnya IT, itu orang-orangnya fast learner, paced dan aktif. Agak aneh memang, karena biasanya orang-orang IT itu nerd and slow living.
Beberapa tahun ke depan gue berharap bisa mewujudkan impian gue membuat sebuah kantor sendiri, atau paling tidak menaklukkan kantor ini dan menjadi CEO-nya. Alternatif lainnya, gue akan melanjutkan karir gue di bidang pekerjaan gue yang utama, dengan menyelesaikan ujian sertifikasi terakhir. Modal buat mendirikan kantornya? Ya usaha mencari dulu. Banyak venture capital yang bisa tertarik kalo strategi gue benar dan idenya bisa diterima. Pintar-pintarnya kita pas pitching. Mungkin dari kantor gue saat ini juga bisa dapat pemasukan. Kalau tidak, ya mau tidak mau gue harus bootstrapping, yang artinya gue harus kerja lebih keras agar bisa mengumpulkan modal sendiri. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
Intinya, gue tidak ingin ekspansi dalam skala besar dulu seperti umumnya startup di negeri ini berjalan. Menjaga stabilitas cash flow dan meningkatkan kualitas layanan sepertinya lebih realistis daripada ekspansi besar-besaran dengan target pasar yang prematur dan rentan berubah-ubah. Karena, seperti yang Papa dulu pernah bilang, dalam sebuah bisnis itu intinya adalah berkelanjutan. Kita bisa membangun brand dan menyaring konsumen dalam waktu cepat, tetapi apakah kita mampu mempertahankannya? Ini yang jadi tantangan di lini bisnis manapun. Papa pun dulu membangun bisnisnya pelan-pelan, tidak bertumbuh dengan cepat, tapi pada akhirnya long last, sebelum akhirnya dihancurkan oleh orang-orang kepercayaannya sendiri.
Pertumbuhan eksponensial dan menghasilkan nilai yang besar belum tentu bisa menghasilkan keberlanjutan. Ini yang jadi titik pembeda utama prinsip gue dengan Anantya serta teman-teman di C level lainnya kedepannya. Gue membayangkan bagaimana repotnya pekerjaan-pekerjaan gue kedepannya. Gue hanya ingin menjadi yang terbaik dan membuktikan kalau gue bukanlah orang yang gagal. Tuhan sudah memberikan gue kesempatan dengan dibukanya jalan seperti ini, jadinya harus gue syukuri dan jalani dengan hati yang ikhlas, apapun tantangannya nanti.
Ia mulai tersenyum, mengangguk pelan beberapa kali, dan mulai berbicara.
“Udah bisa nebak gue siapa?”
“Nggak mungkin. Lo nggak mungkin…” gue masih tetap tidak percaya.
“Sangat mungkin. Karena emang faktanya begitu, Ja.” Sergahnya buru-buru dengan nada yakin.
Gue menggelengkan kepala berulang kali, lalu secara reflek memukulkan kepalan tangan kanan gue ke kursi yang gue duduki saat ini.
“Pantes….” Gue menggumam dan membuang muka dari pandangannya.
“Pantes kenapa?” dia bertanya.
“Dari awal lo datang tempo hari dengan gaya congkak lo itu, lo bilang tau gue.” Jawab gue.
“Hahaha. Jelas gue tau, gue selalu share informasi kok sama dia.” Katanya lagi, sekarang suaranya jauh dari kesan bengis seperti beberapa momen sebelumnya.
“Then, tell me everything…” gue tembak langsung saja cewek ini, mumpung momennya dia tidak dalam mode “bengis”.
“Mau yang mana dulu?”
“Ya hubungan lo berdua dulu deh. Baru sampai ke titik dimana lo sama dia bisa kerja bareng disini.”
“Actually, gue nggak kerja bareng disini sama dia.”
“Lah terus?”
“Eh bentar-bentar. Ini udah mau masuk waktu makan siang. Cabut, apa disini aja?” tanyanya, kali ini sudah hilang sepenuhnya kesan ketus dari raut wajahnya. Nada bicaranya pun sudah sedikit ‘friendly’.
“Cabut? Kita udah cukup private disini. Nggak keliatan dari luar juga, kenapa harus cabut?”
“Mau ngambil kesempatan dalam kesempitan lo? Hahaha.” Ujarnya, kali ini nadanya merendahkan, lagi.
“Ya nggak lah. Gue juga nggak berani. Walaupun umur kita nggak beda jauh kayaknya, tapi kan disini lo yang bosnya.”
“Gue cuma nggak mau ruangan ini beraroma kayak di kantin atau resepsi pernikahan. Bau makanan yang bercampur-campur itu nggak banget. Anti gue sama yang kayak begitu.”
“Nah terus mau kemana?”
“Cari makan di luar, sambil ngobrol lagi.”
“Hah? Lo sama gue berdua doang?”
“Kenapa kaget? Tenang aja, on me. Gue tau kok lo nggak punya banyak uang. Haha.” Katanya lantang, dengan sorot mata tajam dan menghina ke arah gue.
“Wah. Gila. Baru kali ini gue dapet bos yang ngehina terang-terangan kayak gini.” Gue sangat tidak terima dia bilang seperti itu. Ya, gue memang tidak punya banyak uang, tapi dengan kata-katanya barusan, itu betul-betul menyakitkan. Gue pun segera berdiri dan beranjak pergi dari ruangannya.
“Haha. Itu nggak seberapa, lah, ketimbang kelakuan-kelakuan lo di masa lalu..” ucapnya seakan menyanggah pernyataan gue, dan membuat gue gagal bergegas keluar dari ruangannya.
“Tau apa lo dengan masa lalu gue?” tanya gue yang saat ini telah memunggunginya.
“Haha, my eyes, is always hers. Vice versa.”
“Gila. Sampai urusan personal banget kalian share juga? Sakit emang kalian berdua.”
“Well, this is us. Orang-orang sakit yang pada kenyataannya jauh lebih bisa menikmati serunya kehidupan ketimbang lo yang stagnan nggak jelas, dan nggak punya sikap kayak gini. Pathetic.”
“Gue cabut…” gue melanjutkan langkah menuju pintu kaca yang jaraknya hanya satu meter di depan gue.
“Lo buka pintu, that means hell is already outside, for you.” Ancamnya dengan suara tegas.
“F*ck!” gue menggumam lirih sembari mengepalkan tangan.
“Ayo makan.” Ucapnya singkat lalu berdiri, meraih kunci mobil di sisi kanan meja yang tidak seperti kunci mobil pada umumnya, dan sebuah tas kecil yang lebih mirip tas pinggang yang dipakai pedagang di pasar tradisional untuk menaruh uang-uang mereka daripada tas jinjing yang biasanya jadi tren gaya hidup cewek muda nan sukses di perkotaan. Cewek yang unik.
Kemudian kami keluar dalam diam. Tya berjalan di depan gue, dan sudah bisa ditebak, semua mata tertuju kepada kami. Gue melihat Charles, Nadia, Ibnu dan Farah, menaikkan alis keheranan tanpa bersuara, tapi ada gerakan bibir 'kenapa?' dan gue balas dengan kerlingan alis juga dan gelengan kecil supaya mereka tidak terus mengikuti arah kami berjalan. Tangan kanan gue melambai turun naik ke mereka, sebagai tanda nanti akan ada yang gue ceritakan. Sementara orang-orang lain yang belum semuanya gue kenal berusaha biasa saja, tapi gue tahu pandangan mereka tetap tertuju pada gue dan Tya. Tya memang charming dan modis. Tapi gaya belagunya membuat orang-orang sepertinya kurang menaruh respek terhadapnya. Yang ada, dia sepertinya selalu jadi bahan omongan bahkan bully-an diantara staf yang ada disini.
“Lo bawa mobil gue, bisa kan?” tanyanya setelah kami turun dari lift.
“Bisa, lah. Kenapa nggak?” jawab gue.
“Ya barangkali aja lo nggak bisa bawa mobil yang merknya mahal.” Ujarnya, menghina lagi.
“Lah. Haha. Lo boleh tanya dia, berapa mobil yang keluarga gue punya dulu.” Akhirnya gue terpancing untuk mengimbanginya. Sesuatu yang amat sangat gue hindari selama ini, ketika baru berkenalan, bahkan jika sudah kenal dengan orang-orang di sekitar gue.
“Tapi ada yang keluaran terbaru dan pakai teknologi terkini?”
“Hmm. Ya kalaupun teknologi terbaru, ya sepuluh tahunan lalu kayaknya sih.”
“Nah, Makanya nggak usah sok pamer. Sekarang tu barang-barang juga udah nggak ada kan?”
“………………………..” gue terdiam. Dia bisa tahu semua. Seram sekali cewek bernama Anantya ini.
“Kenapa diam? Nggak terima ya kalo keadaan lo sekarang dibawah banget? Haha.”
“Nggak kok, gue biasa jadi orang yang sederhana. Gue nggak terbiasa manfaatin privilege orang tua gue untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Apalagi buat dipamerin atau buat ngehina orang lain. Ecek-ecek banget.” Kata gue datar tanpa ekspresi.
Tya mendadak berhenti dari Langkahnya yang cepat.
“Maksud lo, gue?” dia berbalik dan menatap gue amat tajam seraya menunjuk muka gue dengan telunjuk kanannya. Suaranya bernada tinggi yang mampu menarik perhatian orang-orang. Untung saja saat ini tidak banyak orang berlalu Lalang di jalur perjalanan kami.
“Lo ngerasa?” gue berbalik tanya.
“… rese lo!” ucapnya singkat sambil menghentakkan kakinya ke lantai dan melanjutkan jalannya.
Gue hanya tersenyum seolah gue telah memenangkan sesuatu. Melihatnya mendengus dan membuang muka seperti tadi mengingatkan gue akan Dee. Ekspresinya mirip sekali seperti itu di masa-masa indah kami berdua dulu.
“Nih.” Ucapnya singkat seraya memberikan kunci mobil yang tidak berbentuk seperti kunci mobil pada umumnya. Gue menerimanya dan kemudian menekan tombol gembok terbuka. Ada suara “bip” kecil dibarengi dengan terbukanya kaca spion kanan dan kiri. Kami bergegas masuk ke dalam mobil dan gue mendapati penataan dan aroma kabin yang mirip sekali dengan mobil Anin. Lalu gue menekan tombol start, mobil pun menyala dengan semua interior yang ada lampu-lampunya ikutan menyala.
“Bisa kan gue? Gue nggak secupu itu.” Katanya gue pelan.
“Iyaaa. Ya udah, ke SCBD aja ya.” Ia menanggapi dengan suara ketus. Sepertinya enggan mengakui kekalahannya.
“Mau dimana?”
“Ke lounge tempat lo biasa nongkrong aja.”
“Oke kalau begitu.” Gue tidak menanyainya lagi kenapa dia bisa tahu. Gue hanya memacu mobil ini menuju ke tempat tujuan. Tempat dimana gue merubah cara pandang gue terhadap Anin selama ini.
Beberapa menit kemudian gue sudah memarkirkan mobil dengan rapi di tempat yang disediakan. Gue turun berbarengan dengan Tya. Bodohnya, gue mengecek pintu lagi, apakah sudah terkunci rapat atau belum.
“Hahahaha. Emang bener kan, lo itu cuma anak orang kaya yang sekarang ini beneran nggak punya apa-apa ya.” Katanya meledek gue sembari berjalan menuju ke lounge.
“Kenapa emangnya?” gue tampak bingung.
“Ya lo ngapain meriksain itu mobil udah kekunci apa belum? Haha. Mobil kayak gitu juga lo pencet sekali nggak bakalan dia lupa ngunci, dan nggak perlu lo liat ke belakang lagi, lo tinggalin aja, itu nggak akan kenapa-kenapa. Nggak bakal bisa juga dicongkel orang. Kalaupun bisa dicongkel, emang si maling bisa ngehidupin mesinnya?” dia menjelaskan. Gue langsung teringat kalau mobil-mobil sekarang teknologinya memang seperti itu. Gue hanya terbiasa saja dengan mobil-mobil pada umumnya, mobil kelas menengah.
“Ya mastiin aja.” Kata gue, ngeles.
“Haha. Mastiin apa nggak tau?”
“Mastiin.”
“Alright…. Come.” Ucapnya singkat sembari tersenyum licik dan menggoyangkan kepalanya ke arah dalam tempat tujuan kami.
Gue langsung teringat beberapa momen penting dalam kehidupan gue ketika masuk ke dalam tempat ini. Tempat yang nyaman untuk bersantai, bercerita, atau sekadar bengong entah memikirkan apa. Gue sudah pernah melakukan itu semua disini. Utamanya, menangisi nasib gue yang tidak kunjung membaik dari segi apapun. semua adalah salah gue sendiri pada dasarnya. Tya lalu menaikkan tangan kanannya, memanggil waiter yang ada.
“Dil, biasa ya.” Katanya singkat dan disambut anggukan serta senyuman waiter bernama Fadilah itu.
Gue hanya mengernyitkan dahi, dan tanpa berbicara ke Anantya.
“Kaget ya, lo?” katanya, kembali meremehkan gue.
“Jangan bilang…..”
“Iya bisnis ini juga gue yang jalanin.” Dia memotong kalimat gue.
Hah. Anj*ng lah. Gila banget memang orang-orang ini. Gue dikelilingi orang-orang yang keren secara karir, tapi gue malah lebih memilih stagnan dan masih saja berkutat dengan perasaan hati yang seharusnya sudah fix, tidak bisa diubah lagi. Gue terlalu banyak membuang waktu gue. Padahal jaringan mereka ini bisa gue jadikan pembuka jalan cita-cita gue, demi bisa berdikari, dan tentunya membanggakan Emi dan Mama.
“Lo bengong aja, nggak mau pesan apapun? Kan enak gue jadi untung karena lo pesan. Hahaha.” Nadanya tetap mengejek. Gue harus siap mental untuk menghadapi pimpinan perempuan, apalagi yang model begini. Gue sempat teringat omongan Om Reza yang menekankan kalau perempuan itu bahaya jika jadi pemimpin. Pada dasarnya, laki-laki lah yang jadi pemimpin. Karena pada dasarnya kodratnya menggunakan perasaan ketika mengambil keputusan, bukan pakai logika. Hal ini sempat terpatahkan oleh Emi, namun kembali muncul ketika menghadapi Anantya.
“Butterscotch latte-nya deh, satu ya, Kak. Makasih.” Kata gue ke waiter tadi, diiringi senyum dan dibalas dengan senyum juga olehnya. Waiter bernama Fadilah ini sudah cukup lama ada disini, dan sepertinya dia sudah mengenali gue sebagai ‘reguleran’.
“Nggak pesan kopi beneran lo? Apa nggak bisa?”
“Lo dari tadi itu ngeledekin gue dengan pilihan-pilihan kayak gitu tuh, biar apa sih? Biar kelihatan dominan? Biar kelihatan superpower ngalahin cowok, gitu?” nada gue meninggi dan kemudian dibalas dengan tatapan tajamnya ke gue.
“Heh. Asal lo tau ya, gue emang bisa mendominasi apapun, karena memang gue punya power untuk ngelakuin itu semua. Ngerti lo?!” nadanya penuh penekanan ketika berbicara ini, ditambah dengan matanya yang melotot tajam ke arah gue.
“Udah deh. Gue nggak mau berantem sama bos gue sendiri. Bos yang super power, cerdas, berprestasi dan selalu menang di segala aspek ini.” Gue melanjutkan, tidak kalah mengejek nadanya.
“Haha. Ngaku kalah lo?”
“Nggak. Lagian gue nggak minat juga berkompetisi sama lo. Lo udah punya semuanya. Sementara gue nggak. Itu sama aja memulai dari garis start yang berbeda, which is nggak adil buat gue.”
“Kehidupan di Indonesia sini mana ada yang adil sih, Ja? Coba tunjukin mana keadilan? Bullsh*t semuanya.”
“Susah emang kalo ngomong sama orang yang nggak pernah susah hidupnya, kayak lo gini.”
“Terus gue harus jadi orang susah kayak lo dulu gitu, baru bisa nyambung ngomong sama lo? Nggak logis banget lo. Kalo emang lo dasarnya nggak mampu untuk menyamai gue, akuin aja.”
“Kok jadinya masalah nggak adil, ke masalah ketidakmampuan gue menyamai lo? Lagipula, gue nggak ada niatan mau menyamai lo.”
“Hahaha. Nggak usah muna lo, Ja. Lo pikir gue b*go dengan melihat perubahan struktur kemarin itu. 15% buat orang yang nggak ngapa-ngapain tau-tau dapat jackpot dari orang yang bahkan nggak running usaha ini secara langsung aja udah aneh banget. Mana gue dipaksa untuk terima lagi. Coba kalo lo jadi gue, terima nggak?”
“Gue nggak pernah minta. Dia yang maksa untuk gue ada disana. Nah sekarang gini aja, deh. Gue dan lo kesini kan mau cerita. Bukan mau debat masalah Share. Tapi kalo lo mau, silakan ambil semuanya. Gue nggak akan nolak. Ambil aja kalau emang semuanya lo nilai dari materi, perjuangan dan keringat lo itu.” Seketika gue ingat nama dia ada di dokumen yang gue tandatangani. Hanya saja, gue lupa berapa persen yang menjadi haknya.
“Nggak segampang itu, Ija. Gue diamanahin sama orang. Jadi nggak bisa sembarangan untuk ngubah ini itu. Tapi memang pada dasarnya, gue kesal dengan urusan ini. Apalagi gue harus berhadapan dengan lo.”
“Loh, gue ada disana diminta dia, bukan gue maksa. Setelah semua yang dia lakuin dan perjuangin untuk gue, ya gue juga mau lah nggak ngecewain dia.”
“So do I.” ucapnya lirih.
Bekerjasama dengan orang-orang seumuran dengan Emi atau mungkin lebih muda lagi itu tantangannya cukup berat, karena tidak hanya disini, di kantor utama gue pun seperti itu keadaannya. Seperti tidak banyak inovasi, keinginan kuat untuk membuktikan diri tidak terlalu nampak dan lain sebagainya yang kadang kalau dipikirkan bisa bikin stres. Tetapi gue tidak mau memukul rata semua begitu, karena di divisi lain dari yang gue temukan, seperti misalnya IT, itu orang-orangnya fast learner, paced dan aktif. Agak aneh memang, karena biasanya orang-orang IT itu nerd and slow living.
Beberapa tahun ke depan gue berharap bisa mewujudkan impian gue membuat sebuah kantor sendiri, atau paling tidak menaklukkan kantor ini dan menjadi CEO-nya. Alternatif lainnya, gue akan melanjutkan karir gue di bidang pekerjaan gue yang utama, dengan menyelesaikan ujian sertifikasi terakhir. Modal buat mendirikan kantornya? Ya usaha mencari dulu. Banyak venture capital yang bisa tertarik kalo strategi gue benar dan idenya bisa diterima. Pintar-pintarnya kita pas pitching. Mungkin dari kantor gue saat ini juga bisa dapat pemasukan. Kalau tidak, ya mau tidak mau gue harus bootstrapping, yang artinya gue harus kerja lebih keras agar bisa mengumpulkan modal sendiri. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
Intinya, gue tidak ingin ekspansi dalam skala besar dulu seperti umumnya startup di negeri ini berjalan. Menjaga stabilitas cash flow dan meningkatkan kualitas layanan sepertinya lebih realistis daripada ekspansi besar-besaran dengan target pasar yang prematur dan rentan berubah-ubah. Karena, seperti yang Papa dulu pernah bilang, dalam sebuah bisnis itu intinya adalah berkelanjutan. Kita bisa membangun brand dan menyaring konsumen dalam waktu cepat, tetapi apakah kita mampu mempertahankannya? Ini yang jadi tantangan di lini bisnis manapun. Papa pun dulu membangun bisnisnya pelan-pelan, tidak bertumbuh dengan cepat, tapi pada akhirnya long last, sebelum akhirnya dihancurkan oleh orang-orang kepercayaannya sendiri.
Pertumbuhan eksponensial dan menghasilkan nilai yang besar belum tentu bisa menghasilkan keberlanjutan. Ini yang jadi titik pembeda utama prinsip gue dengan Anantya serta teman-teman di C level lainnya kedepannya. Gue membayangkan bagaimana repotnya pekerjaan-pekerjaan gue kedepannya. Gue hanya ingin menjadi yang terbaik dan membuktikan kalau gue bukanlah orang yang gagal. Tuhan sudah memberikan gue kesempatan dengan dibukanya jalan seperti ini, jadinya harus gue syukuri dan jalani dengan hati yang ikhlas, apapun tantangannya nanti.
Spoiler for Mulustrasi Anantya:
Ia mulai tersenyum, mengangguk pelan beberapa kali, dan mulai berbicara.
“Udah bisa nebak gue siapa?”
“Nggak mungkin. Lo nggak mungkin…” gue masih tetap tidak percaya.
“Sangat mungkin. Karena emang faktanya begitu, Ja.” Sergahnya buru-buru dengan nada yakin.
Gue menggelengkan kepala berulang kali, lalu secara reflek memukulkan kepalan tangan kanan gue ke kursi yang gue duduki saat ini.
“Pantes….” Gue menggumam dan membuang muka dari pandangannya.
“Pantes kenapa?” dia bertanya.
“Dari awal lo datang tempo hari dengan gaya congkak lo itu, lo bilang tau gue.” Jawab gue.
“Hahaha. Jelas gue tau, gue selalu share informasi kok sama dia.” Katanya lagi, sekarang suaranya jauh dari kesan bengis seperti beberapa momen sebelumnya.
“Then, tell me everything…” gue tembak langsung saja cewek ini, mumpung momennya dia tidak dalam mode “bengis”.
“Mau yang mana dulu?”
“Ya hubungan lo berdua dulu deh. Baru sampai ke titik dimana lo sama dia bisa kerja bareng disini.”
“Actually, gue nggak kerja bareng disini sama dia.”
“Lah terus?”
“Eh bentar-bentar. Ini udah mau masuk waktu makan siang. Cabut, apa disini aja?” tanyanya, kali ini sudah hilang sepenuhnya kesan ketus dari raut wajahnya. Nada bicaranya pun sudah sedikit ‘friendly’.
“Cabut? Kita udah cukup private disini. Nggak keliatan dari luar juga, kenapa harus cabut?”
“Mau ngambil kesempatan dalam kesempitan lo? Hahaha.” Ujarnya, kali ini nadanya merendahkan, lagi.
“Ya nggak lah. Gue juga nggak berani. Walaupun umur kita nggak beda jauh kayaknya, tapi kan disini lo yang bosnya.”
“Gue cuma nggak mau ruangan ini beraroma kayak di kantin atau resepsi pernikahan. Bau makanan yang bercampur-campur itu nggak banget. Anti gue sama yang kayak begitu.”
“Nah terus mau kemana?”
“Cari makan di luar, sambil ngobrol lagi.”
“Hah? Lo sama gue berdua doang?”
“Kenapa kaget? Tenang aja, on me. Gue tau kok lo nggak punya banyak uang. Haha.” Katanya lantang, dengan sorot mata tajam dan menghina ke arah gue.
“Wah. Gila. Baru kali ini gue dapet bos yang ngehina terang-terangan kayak gini.” Gue sangat tidak terima dia bilang seperti itu. Ya, gue memang tidak punya banyak uang, tapi dengan kata-katanya barusan, itu betul-betul menyakitkan. Gue pun segera berdiri dan beranjak pergi dari ruangannya.
“Haha. Itu nggak seberapa, lah, ketimbang kelakuan-kelakuan lo di masa lalu..” ucapnya seakan menyanggah pernyataan gue, dan membuat gue gagal bergegas keluar dari ruangannya.
“Tau apa lo dengan masa lalu gue?” tanya gue yang saat ini telah memunggunginya.
“Haha, my eyes, is always hers. Vice versa.”
“Gila. Sampai urusan personal banget kalian share juga? Sakit emang kalian berdua.”
“Well, this is us. Orang-orang sakit yang pada kenyataannya jauh lebih bisa menikmati serunya kehidupan ketimbang lo yang stagnan nggak jelas, dan nggak punya sikap kayak gini. Pathetic.”
“Gue cabut…” gue melanjutkan langkah menuju pintu kaca yang jaraknya hanya satu meter di depan gue.
“Lo buka pintu, that means hell is already outside, for you.” Ancamnya dengan suara tegas.
“F*ck!” gue menggumam lirih sembari mengepalkan tangan.
“Ayo makan.” Ucapnya singkat lalu berdiri, meraih kunci mobil di sisi kanan meja yang tidak seperti kunci mobil pada umumnya, dan sebuah tas kecil yang lebih mirip tas pinggang yang dipakai pedagang di pasar tradisional untuk menaruh uang-uang mereka daripada tas jinjing yang biasanya jadi tren gaya hidup cewek muda nan sukses di perkotaan. Cewek yang unik.
Kemudian kami keluar dalam diam. Tya berjalan di depan gue, dan sudah bisa ditebak, semua mata tertuju kepada kami. Gue melihat Charles, Nadia, Ibnu dan Farah, menaikkan alis keheranan tanpa bersuara, tapi ada gerakan bibir 'kenapa?' dan gue balas dengan kerlingan alis juga dan gelengan kecil supaya mereka tidak terus mengikuti arah kami berjalan. Tangan kanan gue melambai turun naik ke mereka, sebagai tanda nanti akan ada yang gue ceritakan. Sementara orang-orang lain yang belum semuanya gue kenal berusaha biasa saja, tapi gue tahu pandangan mereka tetap tertuju pada gue dan Tya. Tya memang charming dan modis. Tapi gaya belagunya membuat orang-orang sepertinya kurang menaruh respek terhadapnya. Yang ada, dia sepertinya selalu jadi bahan omongan bahkan bully-an diantara staf yang ada disini.
“Lo bawa mobil gue, bisa kan?” tanyanya setelah kami turun dari lift.
“Bisa, lah. Kenapa nggak?” jawab gue.
“Ya barangkali aja lo nggak bisa bawa mobil yang merknya mahal.” Ujarnya, menghina lagi.
“Lah. Haha. Lo boleh tanya dia, berapa mobil yang keluarga gue punya dulu.” Akhirnya gue terpancing untuk mengimbanginya. Sesuatu yang amat sangat gue hindari selama ini, ketika baru berkenalan, bahkan jika sudah kenal dengan orang-orang di sekitar gue.
“Tapi ada yang keluaran terbaru dan pakai teknologi terkini?”
“Hmm. Ya kalaupun teknologi terbaru, ya sepuluh tahunan lalu kayaknya sih.”
“Nah, Makanya nggak usah sok pamer. Sekarang tu barang-barang juga udah nggak ada kan?”
“………………………..” gue terdiam. Dia bisa tahu semua. Seram sekali cewek bernama Anantya ini.
“Kenapa diam? Nggak terima ya kalo keadaan lo sekarang dibawah banget? Haha.”
“Nggak kok, gue biasa jadi orang yang sederhana. Gue nggak terbiasa manfaatin privilege orang tua gue untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Apalagi buat dipamerin atau buat ngehina orang lain. Ecek-ecek banget.” Kata gue datar tanpa ekspresi.
Tya mendadak berhenti dari Langkahnya yang cepat.
“Maksud lo, gue?” dia berbalik dan menatap gue amat tajam seraya menunjuk muka gue dengan telunjuk kanannya. Suaranya bernada tinggi yang mampu menarik perhatian orang-orang. Untung saja saat ini tidak banyak orang berlalu Lalang di jalur perjalanan kami.
“Lo ngerasa?” gue berbalik tanya.
“… rese lo!” ucapnya singkat sambil menghentakkan kakinya ke lantai dan melanjutkan jalannya.
Gue hanya tersenyum seolah gue telah memenangkan sesuatu. Melihatnya mendengus dan membuang muka seperti tadi mengingatkan gue akan Dee. Ekspresinya mirip sekali seperti itu di masa-masa indah kami berdua dulu.
“Nih.” Ucapnya singkat seraya memberikan kunci mobil yang tidak berbentuk seperti kunci mobil pada umumnya. Gue menerimanya dan kemudian menekan tombol gembok terbuka. Ada suara “bip” kecil dibarengi dengan terbukanya kaca spion kanan dan kiri. Kami bergegas masuk ke dalam mobil dan gue mendapati penataan dan aroma kabin yang mirip sekali dengan mobil Anin. Lalu gue menekan tombol start, mobil pun menyala dengan semua interior yang ada lampu-lampunya ikutan menyala.
“Bisa kan gue? Gue nggak secupu itu.” Katanya gue pelan.
“Iyaaa. Ya udah, ke SCBD aja ya.” Ia menanggapi dengan suara ketus. Sepertinya enggan mengakui kekalahannya.
“Mau dimana?”
“Ke lounge tempat lo biasa nongkrong aja.”
“Oke kalau begitu.” Gue tidak menanyainya lagi kenapa dia bisa tahu. Gue hanya memacu mobil ini menuju ke tempat tujuan. Tempat dimana gue merubah cara pandang gue terhadap Anin selama ini.
Beberapa menit kemudian gue sudah memarkirkan mobil dengan rapi di tempat yang disediakan. Gue turun berbarengan dengan Tya. Bodohnya, gue mengecek pintu lagi, apakah sudah terkunci rapat atau belum.
“Hahahaha. Emang bener kan, lo itu cuma anak orang kaya yang sekarang ini beneran nggak punya apa-apa ya.” Katanya meledek gue sembari berjalan menuju ke lounge.
“Kenapa emangnya?” gue tampak bingung.
“Ya lo ngapain meriksain itu mobil udah kekunci apa belum? Haha. Mobil kayak gitu juga lo pencet sekali nggak bakalan dia lupa ngunci, dan nggak perlu lo liat ke belakang lagi, lo tinggalin aja, itu nggak akan kenapa-kenapa. Nggak bakal bisa juga dicongkel orang. Kalaupun bisa dicongkel, emang si maling bisa ngehidupin mesinnya?” dia menjelaskan. Gue langsung teringat kalau mobil-mobil sekarang teknologinya memang seperti itu. Gue hanya terbiasa saja dengan mobil-mobil pada umumnya, mobil kelas menengah.
“Ya mastiin aja.” Kata gue, ngeles.
“Haha. Mastiin apa nggak tau?”
“Mastiin.”
“Alright…. Come.” Ucapnya singkat sembari tersenyum licik dan menggoyangkan kepalanya ke arah dalam tempat tujuan kami.
Gue langsung teringat beberapa momen penting dalam kehidupan gue ketika masuk ke dalam tempat ini. Tempat yang nyaman untuk bersantai, bercerita, atau sekadar bengong entah memikirkan apa. Gue sudah pernah melakukan itu semua disini. Utamanya, menangisi nasib gue yang tidak kunjung membaik dari segi apapun. semua adalah salah gue sendiri pada dasarnya. Tya lalu menaikkan tangan kanannya, memanggil waiter yang ada.
“Dil, biasa ya.” Katanya singkat dan disambut anggukan serta senyuman waiter bernama Fadilah itu.
Gue hanya mengernyitkan dahi, dan tanpa berbicara ke Anantya.
“Kaget ya, lo?” katanya, kembali meremehkan gue.
“Jangan bilang…..”
“Iya bisnis ini juga gue yang jalanin.” Dia memotong kalimat gue.
Hah. Anj*ng lah. Gila banget memang orang-orang ini. Gue dikelilingi orang-orang yang keren secara karir, tapi gue malah lebih memilih stagnan dan masih saja berkutat dengan perasaan hati yang seharusnya sudah fix, tidak bisa diubah lagi. Gue terlalu banyak membuang waktu gue. Padahal jaringan mereka ini bisa gue jadikan pembuka jalan cita-cita gue, demi bisa berdikari, dan tentunya membanggakan Emi dan Mama.
“Lo bengong aja, nggak mau pesan apapun? Kan enak gue jadi untung karena lo pesan. Hahaha.” Nadanya tetap mengejek. Gue harus siap mental untuk menghadapi pimpinan perempuan, apalagi yang model begini. Gue sempat teringat omongan Om Reza yang menekankan kalau perempuan itu bahaya jika jadi pemimpin. Pada dasarnya, laki-laki lah yang jadi pemimpin. Karena pada dasarnya kodratnya menggunakan perasaan ketika mengambil keputusan, bukan pakai logika. Hal ini sempat terpatahkan oleh Emi, namun kembali muncul ketika menghadapi Anantya.
“Butterscotch latte-nya deh, satu ya, Kak. Makasih.” Kata gue ke waiter tadi, diiringi senyum dan dibalas dengan senyum juga olehnya. Waiter bernama Fadilah ini sudah cukup lama ada disini, dan sepertinya dia sudah mengenali gue sebagai ‘reguleran’.
“Nggak pesan kopi beneran lo? Apa nggak bisa?”
“Lo dari tadi itu ngeledekin gue dengan pilihan-pilihan kayak gitu tuh, biar apa sih? Biar kelihatan dominan? Biar kelihatan superpower ngalahin cowok, gitu?” nada gue meninggi dan kemudian dibalas dengan tatapan tajamnya ke gue.
“Heh. Asal lo tau ya, gue emang bisa mendominasi apapun, karena memang gue punya power untuk ngelakuin itu semua. Ngerti lo?!” nadanya penuh penekanan ketika berbicara ini, ditambah dengan matanya yang melotot tajam ke arah gue.
“Udah deh. Gue nggak mau berantem sama bos gue sendiri. Bos yang super power, cerdas, berprestasi dan selalu menang di segala aspek ini.” Gue melanjutkan, tidak kalah mengejek nadanya.
“Haha. Ngaku kalah lo?”
“Nggak. Lagian gue nggak minat juga berkompetisi sama lo. Lo udah punya semuanya. Sementara gue nggak. Itu sama aja memulai dari garis start yang berbeda, which is nggak adil buat gue.”
“Kehidupan di Indonesia sini mana ada yang adil sih, Ja? Coba tunjukin mana keadilan? Bullsh*t semuanya.”
“Susah emang kalo ngomong sama orang yang nggak pernah susah hidupnya, kayak lo gini.”
“Terus gue harus jadi orang susah kayak lo dulu gitu, baru bisa nyambung ngomong sama lo? Nggak logis banget lo. Kalo emang lo dasarnya nggak mampu untuk menyamai gue, akuin aja.”
“Kok jadinya masalah nggak adil, ke masalah ketidakmampuan gue menyamai lo? Lagipula, gue nggak ada niatan mau menyamai lo.”
“Hahaha. Nggak usah muna lo, Ja. Lo pikir gue b*go dengan melihat perubahan struktur kemarin itu. 15% buat orang yang nggak ngapa-ngapain tau-tau dapat jackpot dari orang yang bahkan nggak running usaha ini secara langsung aja udah aneh banget. Mana gue dipaksa untuk terima lagi. Coba kalo lo jadi gue, terima nggak?”
“Gue nggak pernah minta. Dia yang maksa untuk gue ada disana. Nah sekarang gini aja, deh. Gue dan lo kesini kan mau cerita. Bukan mau debat masalah Share. Tapi kalo lo mau, silakan ambil semuanya. Gue nggak akan nolak. Ambil aja kalau emang semuanya lo nilai dari materi, perjuangan dan keringat lo itu.” Seketika gue ingat nama dia ada di dokumen yang gue tandatangani. Hanya saja, gue lupa berapa persen yang menjadi haknya.
“Nggak segampang itu, Ija. Gue diamanahin sama orang. Jadi nggak bisa sembarangan untuk ngubah ini itu. Tapi memang pada dasarnya, gue kesal dengan urusan ini. Apalagi gue harus berhadapan dengan lo.”
“Loh, gue ada disana diminta dia, bukan gue maksa. Setelah semua yang dia lakuin dan perjuangin untuk gue, ya gue juga mau lah nggak ngecewain dia.”
“So do I.” ucapnya lirih.
Diubah oleh yanagi92055 04-11-2024 09:28
itkgid dan 6 lainnya memberi reputasi
7
Tutup
 dan bintang 5
dan bintang 5