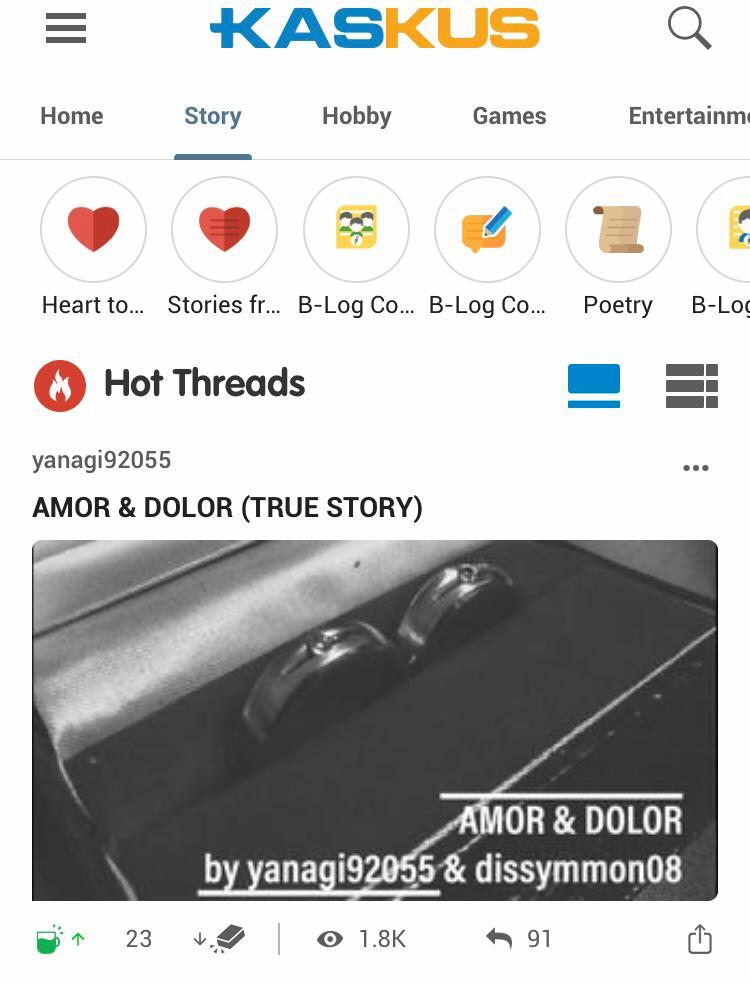- Beranda
- Stories from the Heart
AMOR & DOLOR (TRUE STORY)
...
TS
yanagi92055
AMOR & DOLOR (TRUE STORY)
Selamat Datang di Trit Kami
私のスレッドへようこそ

TERIMA KASIH BANYAK ATAS ATENSI DAN APRESIASI YANG TELAH GANSIS READERBERIKAN DI TIGA TRIT GUE DAN EMI SEBELUMNYA. SEMOGA DI TRIT INI, KAMI DAPAT MENUNJUKKAN PERFORMA TERBAIK (LAGI) DALAM PENULISAN DAN PACKAGING CERITA AGAR SEMUA READER YANG BERKUNJUNG DI SINI SELALU HAPPY DAN TERHIBUR!
Quote:
Spoiler for MUARA SEBUAH PENCARIAN (TAMAT):
Spoiler for AKHIR PENANTIANKU (ONGOING):
Spoiler for PERATURAN:
Spoiler for FAQ, INDEX, MULUSTRASI, TEASER:
HAPPY READING! 

Quote:
Diubah oleh yanagi92055 15-11-2024 12:56
uang500ratus dan 92 lainnya memberi reputasi
83
186.4K
3.2K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.7KThread•2Anggota
Tampilkan semua post
TS
yanagi92055
#560
Lost_Part 4
Emi dan Anin berasal dari almamater yang sama dengan gue, jadi sebodoh-bodohnya mereka, tidak akan sampai bodoh banget. Tidak ada yang bodoh malahan, dua-duanya berotak brilian. Setidaknya bisa nyambung diajak ngobrol. Itu sudah terbukti selama beberapa tahun terakhir, obrolan gue dengan mereka selalu ada saja bahasannya. Hanya saja, lebih banyak bahasan di luar teknis kemampuan otak jika gue bersama Emi. Karena gue berada dalam satu naungan band, suka jenis musik yang sama, satu jurusan almamater, dan bahkan kuliah S2 gue pun banyak sekali dibantu olehnya. Penyelesaian tesis gue yang ditargetkan setelah kami menikah pun lebih banyak Emi perannya daripada gue.
Anin. Entah kenapa, dia memiliki visi yang baik dan itu merupakan hal yang juga gue suka. Emi punya, tetapi tidak setajam Anin. Anin juga memiliki koneksi yang sangat luas di dunia usaha. Dunia startup. Sesuatu yang tidak dimiliki Emi. Visi besar ini yang cocok sekali dengan gue, karena kedepannya gue pun ingin membangun usaha sendiri, walaupun merangkak dari status sebagai UMKM dulu, gue tidak peduli. Anin bisa mem-provide itu, bahkan sudah membukakan jalan. Tapi gue tidak ingin jalan yang Anin bukakan ini di klaim 100% bantuan orang dalam. Gue juga ingin memperjuangkan ini sampai akhirnya gue bisa berdikari. Anin belum membicarakan ini dan gue juga tidak ingin memaksakan kehendak. Gue juga belum bisa membuktikan apapun saat ini. Ditambah lagi dengan dia benar-benar mengetahui seluk beluk gue, sampai keinginan dan kebutuhan gue dalam menjalani hidup, bagaimana dia juga bisa mengangkat mental gue dari keterpurukan dan terus bersabar, membuat gue, dan mungkin orang lain juga, akan jatuh hati dengannya.
Itu merupakan contoh kecil bagaimana gue sangat bingung dalam menentukan sikap. Sebenarnya, jika gue memilih Anin, banyak orang akan berpikir kalau gue adalah orang yang memanfaatkan keadaan saja demi materi-materi tertentu. Hanya saja yang perlu diingat, gue bukanlah orang yang senang memanfaatkan situasi untuk keuntungan gue semata. Itulah sebabnya diawal gue ragu untuk menerima ajakan Anin, karena pada dasarnya gue takut tidak bisa memenuhi harapan orang-orang lain ke gue. Anin selalu meninggikan gue seolah gue ini benar-benar dapat diandalkan, dan itu adalah beban berat untuk gue. Tapi, jika gue melewatkan kesempatan ini, gue akan semakin terseok-seok dengan Emi karena pernikahan kami sudah dimulai dengan kondisi minus yang terlalu banyak.
----
“Halo guys, perkenalkan ini Firzy, yang akan jadi rekan baru kalian disini ya. Mohon dibantu ya.” Kata Elva, salah seorang staf di kantor, yang juga kepercayaan Anin.
“Halo, Firzy.” Kata tim bersamaan, yang saat ini berada di satu ruang meeting. Gue mengedarkan pandangan. Ada empat orang. Dua cowok dan dua cewek. Gue perhatikan wajah mereka sekilas, sepertinya mereka bukanlah orang-orang yang terlalu tua. Malah mungkin umurnya jauh dibawah gue.
“Halo semuanya, saya Firzy. Teman-teman semua bisa panggil saya Ija.” Gue kemudian melambaikan tangan di depan dada, dan tersenyum lebar.
“Oh iya, jangan salah ya, dia nggak semuda yang kalian kira. Jangan ketipu sama penampilannya dan mukanya. Hehehe. Stop juga pakai ‘saya kamu’, pakai aja ‘gue lo’, biar lebih cair lah koneksinya.” Ucap Elva seraya menyeringai di depan gue.
“Apaan sih lo, El.” Kata gue berbisik di telinga kirinya sembari tersenyum kecil ke orang-orang yang mulai mengamati gue.
“Nanti plan kedepannya akan gue blast email dan jobdesk Ija juga bakalan gue email ya, biar nanti nge-blendnya cepet ya, kalian. Nggak perlu juga terlalu banyak pertanyaan karena semua udah dijelasin disitu.” Katanya melanjutkan, dan dibarengi anggukan sebagian besar orang.
Kemudian, terdengar ketukan dua kali dari sisi luar pintu kaca ruang meeting yang dihias cutting sticker logo perusahaan dan menutupi 80% materialnya, jadi tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di luar sekarang. Pintu lalu dibuka, dan masuklah seorang cewek, tingginya mungkin sekitar 156 – 160 cm, sepertinya seumuran dengan gue, dengan gaya rambut bob sebahu dengan layer cukup tipis yang mengingatkan gue dengan gaya rambut salah satu mantan rekan kantor gue bernama Fenita, di highlight biru tua di ujung-ujung helai rambutnya, memakai setelan cropped blazer warna biru dongker, baju dalamnya putih polos dan wide leg pants berwarna putih. Dia memakai sneakers paduan hitam putih yang mirip dengan pola sneakers milik Anin. Wajahnya dirias kasual dengan make up tipis bernuansa peach, tapi tetap terlihat elegan. Sedangkan tatapannya menyiratkan betapa cewek ini punya power yang besar di kantor ini. CEO material banget. Terbukti setelah dia masuk, kondisi ruang meeting yang tadinya riuh rendah langsung hening seketika. Cantik tapi kalau galak sih, nggak banget bagi gue.
Otomatis gue menjulurkan tangan gue, untuk berjabat tangan dengannya.
“Halo, saya Firzy. Bisa dipanggil Ija. Salam kenal ya, Bu.” Ujar gue sembari tersenyum.
“I know you.” Katanya singkat, tanpa menoleh ke gue, tanpa menghiraukan juluran tangan gue yang sudah bersiap untuk salaman. Gue kaget, teman-teman lainnya pun tidak kalah kaget dan mengernyitkan dahi. Sementara ekspresi datar ditampakkan oleh Elva. Dia seperti sudah biasa menghadapi gerak gerik cewek yang berdiri di depan gue ini. Gue melirik Elva dan kemudian gue melihatnya mengisyaratkan untuk diam saja dan menurunkan tangan gue.
“Ok, guys, setelah ini, sekitar jam 13.00 kita meeting ya disini.”
“Ehm, sorry, saya apa juga ikutan meeting?” tanya gue kepadanya.
“Kalo kamu mau ikutan meeting, emang kamu udah tau apa yang akan kamu kerjakan? Apa kamu tau apa yang akan kami bicarakan disini?” jawabnya datar dengan nada rendah, tapi mengancam.
“Oh, oke….” Gue tidak berbicara lagi dan kemudian izin untuk keluar dari ruang meeting.
Sejurus kemudian, gue ditemani oleh Elva berkeliling kantor. Gue berada di divisi General Affair saat ini, sesuatu yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan reguler gue. Bedanya, disini bisa bekerja remote kata Anin, sehingga tidak usah pusing kalau masalah kehadiran di kantor. Kantor gue yang utama juga sebenarnya menerapkan metode yang hampir mirip, yang penting pekerjaan kita bisa diselesaikan tepat waktu sesuai SLA (Service Level Agreement) atau semacam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak kerja, dan mudah untuk dihubungi jika tidak sedang berada di kantor.
“Lo kok bungkam banget sih soal cewek tadi, El? Dia siapa? Saudaranya Anin, kah? Dia sebagai apa disini? Gue tuh masuk sini nggak dikasih tau secara gamblang deh struktur organisasinya. Gue disuruh ngeraba sendiri, heran.” tanya gue penasaran.
“Mending lo tanya langsung sama orangnya deh, atau ya lo tanya Anin aja kalo emang lo bisa reach dia sekarang. Lagian waktu tanda tangan segala macam di depan notaris, lo nggak nanya-nanya? Atau baca dengan seksama gitu?” Jawabnya.
“Nggak sih, gue baca semuanya, tapi ya hanya nama-nama asing aja dan gue udah lupa juga siapa aja yang tercantum disitu. Ya elah, El, pake rahasia-rahasiaan sama teman.”
“Teman? Gue baru kenal sama lo satu minggu loh, Ja.” Katanya mengingatkan.
“Iya deh. Emang lo nggak mau berteman sama gue? Nanti biar gue cari tau kalo lo nggak mau kasih tau. Emang kenapa sih? Diancam lo sama Anin? Atau malah sama cewek tadi? Terus kenapa juga dia bilang tau gue, El?”
Elva hanya diam dengan ekspresi datar. Tidak lama kemudian, dia kembali berbicara.
“Gue mau kok, berteman sama lo. Asal lo tau ya, C Level disini emang suka pada sengak.” Ucapnya singkat.
“Hah? Gitu ya? Berarti Anin juga ya?” tanya gue menanggapi pernyataannya barusan.
“Hahaha. Untung lo nggak pernah kerja bareng dia.”
“Emang kenapa kalo kerja bareng dia? Tengil ya? Ngerasa sok pintar? Soalnya emang banyak lulusan kampus gue yang kayak gitu gayanya, El.”
“Nggak kok. Lo kalo ngikutin gaya kerja dia, bisa mati berdiri. Dia itu gila banget kalo kerja. Nggak kenal waktu, agile, decision maker yang ciamik, dan detail banget. Tipikal orang yang sangat cerdas dan presisi. Kalo ngikutin ritme dia, pasti banyak yang pada resign, deh. Untungnya dia nggak sebengis cewek yang tadi lo temuin. Mereka 11 12, tapi Anin masih lebih punya empati ke orang lain. Dia nggak termasuk yang sengak justru.”
Gue tertegun mendengarkan kesaksian Elva. Segitu kerennya Anin di luar sana. Selain privilege yang dia berhasil manfaatkan, dia juga membangun reputasinya sendiri dengan bekal kemampuan otak serta hasil sekolahnya yang brilian. Gue heran kenapa dia begitu tergila-gila dengan gue dari dulu. Padahal, dia sudah jauh melampaui gue secara pribadi, secara skill, secara karir dan secara materi. Kehidupannya begitu sempurna. Tapi dia malah menyia-nyiakan sedikit waktu luangnya hanya untuk memikirkan orang seperti gue.
“Kok bisa ya, Anin yang tipikalnya begitu, bisa kerjasama sama orang yang katanya dingin dan bengis itu?”
“Lo tanya aja sama orangnya langsung. Oh iya, Anin juga pesan ke gue, kalo jangan pernah kasih tau orang-orang disini tentang relasi lo dengan dia, biar natural semuanya.”
“Ah elah, balik lagi jawabannya kayak gitu. Ya udah, nanti gue coba tanyain. Nah kalo itu sih, lo bisa percaya gue. Anin juga bisa percaya gue. Semua akan natural kok. Tapi emang orang-orang disini pada tau Anin?”
“Oke, mantap, Ja. Ya tau lah. Mereka kan udah lumayan lama ada disini. Sempat lah mereka ketemu sama Anin.”
“….ingat, lo nggak boleh kecewain Anin setelah semua yang dia lakuin buat lo. Gue tau karena gue diceritain, plus dititipin. Bagusin divisi lo dulu, baru nanti lo ngobrol lagi deh, sama dia.” Elva buru-buru menambahkan kalimatnya.
“Itu pasti sih. Gue nggak akan ngecewain dia. Gue udah terlalu banyak ngecewain dia dan orang-orang di sekitar gue. Nah tapi kok, lo bilang dititipin? Emang si Anin mau kemana sih? Kan dia juga masih ada di struktur kantor ini.”
Elva hanya mengangkat bahu, tanda tidak diberitahu informasi apapun. Gue pun berusaha untuk selalu chat atau telpon dia. Semuanya normal saja, tidak ada yang aneh. Hanya gue tahu, ada yang disembunyikan oleh cewek-cewek ini, ya Anin, ya Elva, ya cewek bos yang jutek itu. Tapi apa? Pastinya ini terkait dengan gue, atau dengan nasib gue kedepannya.
----
Beberapa hari gue datang ke kantor ini, gue masih belum bisa mendapat banyak informasi mengenai cewek bos itu. Gue baru dapat namanya saja, Anantya. Dia biasa dipanggil Bu Tya. Tidak banyak juga yang mengetahui urusan pribadinya, seperti umur atau lulusan universitas mana dia. Yang jelas katanya dia lulusan luar negeri. Swasta kan juga luar negeri, ya. Hehehe.
“Ini nggak ada yang bisa ngasih info lebih banyak nih?” tanya gue ke tim.
“Nggak ada, Mas. Ya cuma itu ada yang kami tau. Kan kami juga belum lama banget disini. Perusahaan ini aja baru dua tahun berdiri. Disini itu C levelnya masih pada muda-muda, kayaknya nggak jauh beda umurnya sama lo, Mas.” Terang Ibnu, salah satu kolega baru gue disini.
“Gue bingung juga, kemarin Mbak Elva ngajak gue keliling kantor, tapi nggak satupun dia jelasin struktur organisasi disini. Cuma jelasin ada berapa divisinya aja. Sedangkan atasannya nggak dijelasin sama sekali. Termasuk si cewek jutek kemarin itu.” Kata gue menanggapi.
“Bang, kalo ngomong mending hati-hati, jangan keras-keras, takutnya kedengaran. Kantor ini kan luasnya nggak gede banget. Hehe.” Nadia memperingatkan gue.
“Iya juga sih, ya. Hehe. Bahaya juga, masih newbie malah cari perkara.” Gue menimpali pendapat Nadia, dan kemudian gelak tawa pecah seketika.
“Nah iya Mas, kami kan juga nggak mau kena imbas kalau ada apa-apa cuma gara-gara urusan sepele seperti ngegibah dengan suara lantang. Hahaha.” Kata Charles, cowok yang satu lagi.
“Oke, kan kemarin udah di email sama Mbak Elva mengenai tugas-tugas kita, so, ada yang mau usul nggak, kira-kira untuk mempercepat pekerjaan dan kolaborasi kita, bisa ditambah atu dikurangi apa ini?” tanya gue ke teman-teman. Hanya gelengan saja tanggapannya ternyata. “Beneran? Lo udah oke semua?” tanya gue lagi, meyakinkan teman-teman. Hanya anggukan serempak dan ibu jari yang mengacung diiringi senyum sumringah saja reaksi mereka.
“Kalo emang belum ada, kita kerjakan dulu apa-apa yang sudah diinstruksiin di email kemarin ya. Misalnya ada sesuatu atau kendala dan semacamnya, let me know ya. Biar coba buka diskusi untuk solusinya gimana.” Ujar gue dibarengi dengan anggukan sebagian besar teman di ruangan ini. Karena model kantornya adalah kantor masa kini, tidak ada sekat sama sekali antar meja. Semuanya dapat saling melihat di satu ruangan. Alasannya, biar semuanya gampang kenal dan kerjasamanya bisa terbangun dengan baik. Padahal kalau menurut gue, itu sebenarnya akal-akalan efisiensi pengeluaran saja, tapi bahasanya dibuat keren.
“Ija, lo dipanggil sama si jutek.” Kata Elva melalui sambungan intercom.
“Heh, lo nggak takut dia bisa nyadap?” tanya gue.
“Yah, bismillah aja. Kayaknya dia nggak setau itu juga soal teknologi, dibanding dengan Anin, sih.”
“Haha. Ya udah, ruangannya yang paling pojok sebelah kanan kan? Yang kayaknya gede sendiri?”
“Iya bener. Udah lo kesana, dia nggak suka nunggu.”
“Makasih ya, El.” Gue menutup sambungan telpon dengan Elva, dan kemudian merapikan kemeja, menyisir rambut, dan menyemprotkan parfum sedikit biar lebih segar, harapannya seperti itu. Masa iya gue bertemu dengan orang paling berpengaruh di kantor dalam keadaan kucel.
Gue bergegas untuk menuju ke ruangan Bu Anantya dengan beragam pertanyaan yang ada di kepala gue saat ini. Gue ingin tahu bagaimana cara dia mengelola kantor ini, sedekat atau sekenal apa dia dengan Anin, dan kenapa dia ketus banget kalau ketemu orang. Hanya saja, gue bisa saja tidak mendapatkan jawaban apapun, karena sikapnya yang dingin dan misterius itu. Orang-orang yang lebih lama disini saja sepertinya memilih untuk tidak banyak berurusan dengan dia. Tetapi, entah kenapa gue yakin, gue bisa ‘mengatasi’ Bu Anantya ini.
Sepanjang perjalanan pendek gue dari ruangan gue menuju ke ruang Bu Anantya yang sebagian lantainya hanya semen yang dihaluskan atau istilahnya semen expose, sebagian lagi memakai epoksi serta tidak memakai plafon gypsum, plywood, atau akustik dan sejenisnya, hampir seluruh mata entah kenapa memandangi gue, mengikuti pergerakan gue. Tidak sedikit juga yang berbisik-bisik. Gue tidak ambil pusing, karena gue juga tidak merasa salah, jadinya gue menganggap ini angin lalu saja.
Gue sudah tiba di depan ruangan Bu Anantya. Ruang ini sepertinya cukup besar untuk satu orang penghuninya. Gue pun mengetuk pelan pintu kaca rangka alumunium yang ada di depan gue. Ruangan yang hampir sepenuhnya berdinding kaca bening ini terlihat begitu elegan, dengan kombinasi cat cerah antara dinding, kusen sampai perabotannya. Tidak lama terdengar suara orang menyahut.
“Yak, silakan masuk.” Serunya dari dalam ruangan, tanpa menoleh ke arah datangnya suara. Dia terlihat terfokus pada sebuah monitor PC besar yang ada di sisi kiri mejanya. Gue tebak ukuran monitornya sekitar 24 inch. Sama seperti monitor PC gue di kantor utama.
“…duduk.” Ucapnya singkat dengan gestur tangan mempersilakan gue duduk berhadapan dengannya. Ada dua kursi yang berada tepat di depan mejanya. Kemudian dia menekan sebuah tombol dari remote kecil di sisi kanan mejanya, dan, semua kaca berubah buram. Ya, ruangan ini menggunakan smart glass film tipe PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) yang bisa multifungsi. Bisa untuk meeting private, atau bisa juga untuk persentasi. Tentunya juga untuk menambah estetika dan berkesan modern.
“….so, what do you wanna talk about?” tanyanya.
“Lah?! Excuse me?” kata gue kaget.
“Iya, gue tau lo pasti bertanya-tanya dalam beberapa hari ini tentang gue, kan? Ya udah, apa yang mau kita omongin? Atau gampangnya, lo mau informasi apa dari gue?” tanyanya lagi, nada suaranya tetap datar, tenang, dengan sesekali melirik tajam ke arah gue, kemudian kembali ke layar monitor.
“Maaf, Ibu kenapa manggil saya kesini?” gue jawab dengan pertanyaan baru.
“Bisa nggak sih, lo nggak usah manggil gue, ‘Ibu’? Gue nggak setua itu.” ujarnya ketus, tanpa menoleh ataupun melihat gue.
“Oh, oke. Terus saya mesti manggil apa dong kalau begitu?”
“Nama aja.”
“Anantya?”
Dia menggeleng.
“Tya?”
“Nah!” Serunya seraya menunjuk muka gue dengan tangan kirinya tanpa menoleh sedikit pun ke gue. ‘Gila ini orang manner-nya jelek banget’. Gue membatin.
“Saya boleh nanya ini? sebenarnya yang mau ngobrol itu anda, atau saya?”
“Anda?! Hahaha. Tua banget sih lo, Ja. Relax, dude. Natural aja nggak, sih? Lo gue aja lah.” Dia tertawa dengan nada melecehkan, tapi harus diakui, sekilas wajah yang di make up tipis ini menunjukkan aura charming-nya saat tertawa tadi.
“Beneran?”
“No worries, kok.”
“Okay, then.”
“Ya udah, sebagai pembuka obrolan kita, gue tanya dulu sama lo. Lo tau nggak kantor ini di desain pake gaya apa?” tanyanya, datar dan terdengar mengejek.
“Kalo menurut gue sih, skandinavian, tapi ada paduan industrial juga sedikit. Mungkin buat ngehemat anggaran (?)” Jawab gue.
“Hahaha. Correct! Tau alasannya kenapa dipilih desain itu?”
“Waduh, ini sih banyak kemungkinan. Tapi yang paling mungkin, karena lo dulu kuliah di luar negeri, jadi biar ada kenang-kenangan atau ngebangun feel ketika lo disana, lo pilih desain ini.” kata gue menebak-nebak kemungkinan terdekatnya.
“Gokil! Tebakan lo benar lagi.” Katanya, lalu berdiri dan memberikan tepuk tangan tiga kali, sambil tersenyum kecil. Setelahnya dia kembali duduk, tanpa ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya.
“Haha. Ya analisa dikit-dikit lah.” Timpal gue.
“Bisa nebak gue kuliah di negara mana dulu?” tanyanya lagi, kali ini ada sedikit antusiasme dari nada bicaranya, namun raut mukanya tetap ketus.
“Finland, or Denmark, maybe? Kan skandinavian, tuh. Terus yang pendidikannya bagus dari negara-negara dingin itu ya dua negara yang gue sebutin tadi.”
Dia tidak menjawab, hanya menunjukkan gestur ibu jari yang dia dekatkan dengan jari telunjuk seperti ingin mencubit sesuatu. Menandakan tebakan gue mungkin hampir benar. Lagi-lagi tanpa menoleh atau memperhatikan gue.
“Oke. Lo analisa gue sekarang, dan harusnya lo bisa nebak gue siapa.” Tiba-tiba dia bersuara dan langsung bertanya.
“Hah?! Gimana caranya?”
“Gimana caranya?! Lo nggak punya kemampuan analisa dan problem solving selama ini, hah? Lo mimpin tim lo gimana ceritanya kalo kayak gini? Bisa-bisanya ngeluarin kalimat ‘gimana caranya’? Nggak malu sama almamater, lo?” katanya, nadanya super ketus dan sangat merendahkan.
“Gue nggak ada clue, gue pun nggak tau informasi apapun karena gue aja baru ketemu lo, dan melihat lo dengan waktu yang cukup lama, ya baru sekarang. Terus lo minta gue analisa lo dan nebak lo siapa? Nggak masuk logika gue, deh. Mana ada yang bisa. Dan please, nggak usah bawa-bawa kampus gue.”
“Hahaha. Ternyata lo nggak secerdas itu ya. Dan kalaupun gue mau bawa-bawa kampus lo, itu hak gue.”
“Maksud lo gimana? Lo mau ngeledek lulusan kampus gue maksudnya?” Nada bicara gue agak meninggi, gue tidak terima di judge langsung seperti ini. Dia bahkan baru tatap muka dengan gue saat ini. Bisa-bisanya dia menilai gue tidak begitu cerdas dan bahkan seperti merendahkan lulusan kampus gue.
“Heey. Kalem lah. Haha. Lo pikir aja. Nih, lo liat muka gue. Nggak cukup juga lo mengenali siapa gue?” Dia menunjuk mukanya sendiri untuk gue perhatikan. Sorot matanya amat tajam. Gue memperhatikan cukup seksama dari ujung rambut sampai ujung dagunya, dari ujung telinga kiri sampai telinga kanan. Bentuk alis, bentuk hidung, bentuk rahang, tulang pipi sampai bibir. Tentunya dengan perasaan gugup luar biasa karena merasa terancam.
“No way! It can’t be…..”
Anin. Entah kenapa, dia memiliki visi yang baik dan itu merupakan hal yang juga gue suka. Emi punya, tetapi tidak setajam Anin. Anin juga memiliki koneksi yang sangat luas di dunia usaha. Dunia startup. Sesuatu yang tidak dimiliki Emi. Visi besar ini yang cocok sekali dengan gue, karena kedepannya gue pun ingin membangun usaha sendiri, walaupun merangkak dari status sebagai UMKM dulu, gue tidak peduli. Anin bisa mem-provide itu, bahkan sudah membukakan jalan. Tapi gue tidak ingin jalan yang Anin bukakan ini di klaim 100% bantuan orang dalam. Gue juga ingin memperjuangkan ini sampai akhirnya gue bisa berdikari. Anin belum membicarakan ini dan gue juga tidak ingin memaksakan kehendak. Gue juga belum bisa membuktikan apapun saat ini. Ditambah lagi dengan dia benar-benar mengetahui seluk beluk gue, sampai keinginan dan kebutuhan gue dalam menjalani hidup, bagaimana dia juga bisa mengangkat mental gue dari keterpurukan dan terus bersabar, membuat gue, dan mungkin orang lain juga, akan jatuh hati dengannya.
Itu merupakan contoh kecil bagaimana gue sangat bingung dalam menentukan sikap. Sebenarnya, jika gue memilih Anin, banyak orang akan berpikir kalau gue adalah orang yang memanfaatkan keadaan saja demi materi-materi tertentu. Hanya saja yang perlu diingat, gue bukanlah orang yang senang memanfaatkan situasi untuk keuntungan gue semata. Itulah sebabnya diawal gue ragu untuk menerima ajakan Anin, karena pada dasarnya gue takut tidak bisa memenuhi harapan orang-orang lain ke gue. Anin selalu meninggikan gue seolah gue ini benar-benar dapat diandalkan, dan itu adalah beban berat untuk gue. Tapi, jika gue melewatkan kesempatan ini, gue akan semakin terseok-seok dengan Emi karena pernikahan kami sudah dimulai dengan kondisi minus yang terlalu banyak.
----
“Halo guys, perkenalkan ini Firzy, yang akan jadi rekan baru kalian disini ya. Mohon dibantu ya.” Kata Elva, salah seorang staf di kantor, yang juga kepercayaan Anin.
“Halo, Firzy.” Kata tim bersamaan, yang saat ini berada di satu ruang meeting. Gue mengedarkan pandangan. Ada empat orang. Dua cowok dan dua cewek. Gue perhatikan wajah mereka sekilas, sepertinya mereka bukanlah orang-orang yang terlalu tua. Malah mungkin umurnya jauh dibawah gue.
“Halo semuanya, saya Firzy. Teman-teman semua bisa panggil saya Ija.” Gue kemudian melambaikan tangan di depan dada, dan tersenyum lebar.
“Oh iya, jangan salah ya, dia nggak semuda yang kalian kira. Jangan ketipu sama penampilannya dan mukanya. Hehehe. Stop juga pakai ‘saya kamu’, pakai aja ‘gue lo’, biar lebih cair lah koneksinya.” Ucap Elva seraya menyeringai di depan gue.
“Apaan sih lo, El.” Kata gue berbisik di telinga kirinya sembari tersenyum kecil ke orang-orang yang mulai mengamati gue.
“Nanti plan kedepannya akan gue blast email dan jobdesk Ija juga bakalan gue email ya, biar nanti nge-blendnya cepet ya, kalian. Nggak perlu juga terlalu banyak pertanyaan karena semua udah dijelasin disitu.” Katanya melanjutkan, dan dibarengi anggukan sebagian besar orang.
Kemudian, terdengar ketukan dua kali dari sisi luar pintu kaca ruang meeting yang dihias cutting sticker logo perusahaan dan menutupi 80% materialnya, jadi tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di luar sekarang. Pintu lalu dibuka, dan masuklah seorang cewek, tingginya mungkin sekitar 156 – 160 cm, sepertinya seumuran dengan gue, dengan gaya rambut bob sebahu dengan layer cukup tipis yang mengingatkan gue dengan gaya rambut salah satu mantan rekan kantor gue bernama Fenita, di highlight biru tua di ujung-ujung helai rambutnya, memakai setelan cropped blazer warna biru dongker, baju dalamnya putih polos dan wide leg pants berwarna putih. Dia memakai sneakers paduan hitam putih yang mirip dengan pola sneakers milik Anin. Wajahnya dirias kasual dengan make up tipis bernuansa peach, tapi tetap terlihat elegan. Sedangkan tatapannya menyiratkan betapa cewek ini punya power yang besar di kantor ini. CEO material banget. Terbukti setelah dia masuk, kondisi ruang meeting yang tadinya riuh rendah langsung hening seketika. Cantik tapi kalau galak sih, nggak banget bagi gue.
Otomatis gue menjulurkan tangan gue, untuk berjabat tangan dengannya.
“Halo, saya Firzy. Bisa dipanggil Ija. Salam kenal ya, Bu.” Ujar gue sembari tersenyum.
“I know you.” Katanya singkat, tanpa menoleh ke gue, tanpa menghiraukan juluran tangan gue yang sudah bersiap untuk salaman. Gue kaget, teman-teman lainnya pun tidak kalah kaget dan mengernyitkan dahi. Sementara ekspresi datar ditampakkan oleh Elva. Dia seperti sudah biasa menghadapi gerak gerik cewek yang berdiri di depan gue ini. Gue melirik Elva dan kemudian gue melihatnya mengisyaratkan untuk diam saja dan menurunkan tangan gue.
“Ok, guys, setelah ini, sekitar jam 13.00 kita meeting ya disini.”
“Ehm, sorry, saya apa juga ikutan meeting?” tanya gue kepadanya.
“Kalo kamu mau ikutan meeting, emang kamu udah tau apa yang akan kamu kerjakan? Apa kamu tau apa yang akan kami bicarakan disini?” jawabnya datar dengan nada rendah, tapi mengancam.
“Oh, oke….” Gue tidak berbicara lagi dan kemudian izin untuk keluar dari ruang meeting.
Sejurus kemudian, gue ditemani oleh Elva berkeliling kantor. Gue berada di divisi General Affair saat ini, sesuatu yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan reguler gue. Bedanya, disini bisa bekerja remote kata Anin, sehingga tidak usah pusing kalau masalah kehadiran di kantor. Kantor gue yang utama juga sebenarnya menerapkan metode yang hampir mirip, yang penting pekerjaan kita bisa diselesaikan tepat waktu sesuai SLA (Service Level Agreement) atau semacam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak kerja, dan mudah untuk dihubungi jika tidak sedang berada di kantor.
“Lo kok bungkam banget sih soal cewek tadi, El? Dia siapa? Saudaranya Anin, kah? Dia sebagai apa disini? Gue tuh masuk sini nggak dikasih tau secara gamblang deh struktur organisasinya. Gue disuruh ngeraba sendiri, heran.” tanya gue penasaran.
“Mending lo tanya langsung sama orangnya deh, atau ya lo tanya Anin aja kalo emang lo bisa reach dia sekarang. Lagian waktu tanda tangan segala macam di depan notaris, lo nggak nanya-nanya? Atau baca dengan seksama gitu?” Jawabnya.
“Nggak sih, gue baca semuanya, tapi ya hanya nama-nama asing aja dan gue udah lupa juga siapa aja yang tercantum disitu. Ya elah, El, pake rahasia-rahasiaan sama teman.”
“Teman? Gue baru kenal sama lo satu minggu loh, Ja.” Katanya mengingatkan.
“Iya deh. Emang lo nggak mau berteman sama gue? Nanti biar gue cari tau kalo lo nggak mau kasih tau. Emang kenapa sih? Diancam lo sama Anin? Atau malah sama cewek tadi? Terus kenapa juga dia bilang tau gue, El?”
Elva hanya diam dengan ekspresi datar. Tidak lama kemudian, dia kembali berbicara.
“Gue mau kok, berteman sama lo. Asal lo tau ya, C Level disini emang suka pada sengak.” Ucapnya singkat.
“Hah? Gitu ya? Berarti Anin juga ya?” tanya gue menanggapi pernyataannya barusan.
“Hahaha. Untung lo nggak pernah kerja bareng dia.”
“Emang kenapa kalo kerja bareng dia? Tengil ya? Ngerasa sok pintar? Soalnya emang banyak lulusan kampus gue yang kayak gitu gayanya, El.”
“Nggak kok. Lo kalo ngikutin gaya kerja dia, bisa mati berdiri. Dia itu gila banget kalo kerja. Nggak kenal waktu, agile, decision maker yang ciamik, dan detail banget. Tipikal orang yang sangat cerdas dan presisi. Kalo ngikutin ritme dia, pasti banyak yang pada resign, deh. Untungnya dia nggak sebengis cewek yang tadi lo temuin. Mereka 11 12, tapi Anin masih lebih punya empati ke orang lain. Dia nggak termasuk yang sengak justru.”
Gue tertegun mendengarkan kesaksian Elva. Segitu kerennya Anin di luar sana. Selain privilege yang dia berhasil manfaatkan, dia juga membangun reputasinya sendiri dengan bekal kemampuan otak serta hasil sekolahnya yang brilian. Gue heran kenapa dia begitu tergila-gila dengan gue dari dulu. Padahal, dia sudah jauh melampaui gue secara pribadi, secara skill, secara karir dan secara materi. Kehidupannya begitu sempurna. Tapi dia malah menyia-nyiakan sedikit waktu luangnya hanya untuk memikirkan orang seperti gue.
“Kok bisa ya, Anin yang tipikalnya begitu, bisa kerjasama sama orang yang katanya dingin dan bengis itu?”
“Lo tanya aja sama orangnya langsung. Oh iya, Anin juga pesan ke gue, kalo jangan pernah kasih tau orang-orang disini tentang relasi lo dengan dia, biar natural semuanya.”
“Ah elah, balik lagi jawabannya kayak gitu. Ya udah, nanti gue coba tanyain. Nah kalo itu sih, lo bisa percaya gue. Anin juga bisa percaya gue. Semua akan natural kok. Tapi emang orang-orang disini pada tau Anin?”
“Oke, mantap, Ja. Ya tau lah. Mereka kan udah lumayan lama ada disini. Sempat lah mereka ketemu sama Anin.”
“….ingat, lo nggak boleh kecewain Anin setelah semua yang dia lakuin buat lo. Gue tau karena gue diceritain, plus dititipin. Bagusin divisi lo dulu, baru nanti lo ngobrol lagi deh, sama dia.” Elva buru-buru menambahkan kalimatnya.
“Itu pasti sih. Gue nggak akan ngecewain dia. Gue udah terlalu banyak ngecewain dia dan orang-orang di sekitar gue. Nah tapi kok, lo bilang dititipin? Emang si Anin mau kemana sih? Kan dia juga masih ada di struktur kantor ini.”
Elva hanya mengangkat bahu, tanda tidak diberitahu informasi apapun. Gue pun berusaha untuk selalu chat atau telpon dia. Semuanya normal saja, tidak ada yang aneh. Hanya gue tahu, ada yang disembunyikan oleh cewek-cewek ini, ya Anin, ya Elva, ya cewek bos yang jutek itu. Tapi apa? Pastinya ini terkait dengan gue, atau dengan nasib gue kedepannya.
----
Beberapa hari gue datang ke kantor ini, gue masih belum bisa mendapat banyak informasi mengenai cewek bos itu. Gue baru dapat namanya saja, Anantya. Dia biasa dipanggil Bu Tya. Tidak banyak juga yang mengetahui urusan pribadinya, seperti umur atau lulusan universitas mana dia. Yang jelas katanya dia lulusan luar negeri. Swasta kan juga luar negeri, ya. Hehehe.
“Ini nggak ada yang bisa ngasih info lebih banyak nih?” tanya gue ke tim.
“Nggak ada, Mas. Ya cuma itu ada yang kami tau. Kan kami juga belum lama banget disini. Perusahaan ini aja baru dua tahun berdiri. Disini itu C levelnya masih pada muda-muda, kayaknya nggak jauh beda umurnya sama lo, Mas.” Terang Ibnu, salah satu kolega baru gue disini.
“Gue bingung juga, kemarin Mbak Elva ngajak gue keliling kantor, tapi nggak satupun dia jelasin struktur organisasi disini. Cuma jelasin ada berapa divisinya aja. Sedangkan atasannya nggak dijelasin sama sekali. Termasuk si cewek jutek kemarin itu.” Kata gue menanggapi.
“Bang, kalo ngomong mending hati-hati, jangan keras-keras, takutnya kedengaran. Kantor ini kan luasnya nggak gede banget. Hehe.” Nadia memperingatkan gue.
“Iya juga sih, ya. Hehe. Bahaya juga, masih newbie malah cari perkara.” Gue menimpali pendapat Nadia, dan kemudian gelak tawa pecah seketika.
“Nah iya Mas, kami kan juga nggak mau kena imbas kalau ada apa-apa cuma gara-gara urusan sepele seperti ngegibah dengan suara lantang. Hahaha.” Kata Charles, cowok yang satu lagi.
“Oke, kan kemarin udah di email sama Mbak Elva mengenai tugas-tugas kita, so, ada yang mau usul nggak, kira-kira untuk mempercepat pekerjaan dan kolaborasi kita, bisa ditambah atu dikurangi apa ini?” tanya gue ke teman-teman. Hanya gelengan saja tanggapannya ternyata. “Beneran? Lo udah oke semua?” tanya gue lagi, meyakinkan teman-teman. Hanya anggukan serempak dan ibu jari yang mengacung diiringi senyum sumringah saja reaksi mereka.
“Kalo emang belum ada, kita kerjakan dulu apa-apa yang sudah diinstruksiin di email kemarin ya. Misalnya ada sesuatu atau kendala dan semacamnya, let me know ya. Biar coba buka diskusi untuk solusinya gimana.” Ujar gue dibarengi dengan anggukan sebagian besar teman di ruangan ini. Karena model kantornya adalah kantor masa kini, tidak ada sekat sama sekali antar meja. Semuanya dapat saling melihat di satu ruangan. Alasannya, biar semuanya gampang kenal dan kerjasamanya bisa terbangun dengan baik. Padahal kalau menurut gue, itu sebenarnya akal-akalan efisiensi pengeluaran saja, tapi bahasanya dibuat keren.
“Ija, lo dipanggil sama si jutek.” Kata Elva melalui sambungan intercom.
“Heh, lo nggak takut dia bisa nyadap?” tanya gue.
“Yah, bismillah aja. Kayaknya dia nggak setau itu juga soal teknologi, dibanding dengan Anin, sih.”
“Haha. Ya udah, ruangannya yang paling pojok sebelah kanan kan? Yang kayaknya gede sendiri?”
“Iya bener. Udah lo kesana, dia nggak suka nunggu.”
“Makasih ya, El.” Gue menutup sambungan telpon dengan Elva, dan kemudian merapikan kemeja, menyisir rambut, dan menyemprotkan parfum sedikit biar lebih segar, harapannya seperti itu. Masa iya gue bertemu dengan orang paling berpengaruh di kantor dalam keadaan kucel.
Gue bergegas untuk menuju ke ruangan Bu Anantya dengan beragam pertanyaan yang ada di kepala gue saat ini. Gue ingin tahu bagaimana cara dia mengelola kantor ini, sedekat atau sekenal apa dia dengan Anin, dan kenapa dia ketus banget kalau ketemu orang. Hanya saja, gue bisa saja tidak mendapatkan jawaban apapun, karena sikapnya yang dingin dan misterius itu. Orang-orang yang lebih lama disini saja sepertinya memilih untuk tidak banyak berurusan dengan dia. Tetapi, entah kenapa gue yakin, gue bisa ‘mengatasi’ Bu Anantya ini.
Sepanjang perjalanan pendek gue dari ruangan gue menuju ke ruang Bu Anantya yang sebagian lantainya hanya semen yang dihaluskan atau istilahnya semen expose, sebagian lagi memakai epoksi serta tidak memakai plafon gypsum, plywood, atau akustik dan sejenisnya, hampir seluruh mata entah kenapa memandangi gue, mengikuti pergerakan gue. Tidak sedikit juga yang berbisik-bisik. Gue tidak ambil pusing, karena gue juga tidak merasa salah, jadinya gue menganggap ini angin lalu saja.
Gue sudah tiba di depan ruangan Bu Anantya. Ruang ini sepertinya cukup besar untuk satu orang penghuninya. Gue pun mengetuk pelan pintu kaca rangka alumunium yang ada di depan gue. Ruangan yang hampir sepenuhnya berdinding kaca bening ini terlihat begitu elegan, dengan kombinasi cat cerah antara dinding, kusen sampai perabotannya. Tidak lama terdengar suara orang menyahut.
“Yak, silakan masuk.” Serunya dari dalam ruangan, tanpa menoleh ke arah datangnya suara. Dia terlihat terfokus pada sebuah monitor PC besar yang ada di sisi kiri mejanya. Gue tebak ukuran monitornya sekitar 24 inch. Sama seperti monitor PC gue di kantor utama.
“…duduk.” Ucapnya singkat dengan gestur tangan mempersilakan gue duduk berhadapan dengannya. Ada dua kursi yang berada tepat di depan mejanya. Kemudian dia menekan sebuah tombol dari remote kecil di sisi kanan mejanya, dan, semua kaca berubah buram. Ya, ruangan ini menggunakan smart glass film tipe PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) yang bisa multifungsi. Bisa untuk meeting private, atau bisa juga untuk persentasi. Tentunya juga untuk menambah estetika dan berkesan modern.
“….so, what do you wanna talk about?” tanyanya.
“Lah?! Excuse me?” kata gue kaget.
“Iya, gue tau lo pasti bertanya-tanya dalam beberapa hari ini tentang gue, kan? Ya udah, apa yang mau kita omongin? Atau gampangnya, lo mau informasi apa dari gue?” tanyanya lagi, nada suaranya tetap datar, tenang, dengan sesekali melirik tajam ke arah gue, kemudian kembali ke layar monitor.
“Maaf, Ibu kenapa manggil saya kesini?” gue jawab dengan pertanyaan baru.
“Bisa nggak sih, lo nggak usah manggil gue, ‘Ibu’? Gue nggak setua itu.” ujarnya ketus, tanpa menoleh ataupun melihat gue.
“Oh, oke. Terus saya mesti manggil apa dong kalau begitu?”
“Nama aja.”
“Anantya?”
Dia menggeleng.
“Tya?”
“Nah!” Serunya seraya menunjuk muka gue dengan tangan kirinya tanpa menoleh sedikit pun ke gue. ‘Gila ini orang manner-nya jelek banget’. Gue membatin.
“Saya boleh nanya ini? sebenarnya yang mau ngobrol itu anda, atau saya?”
“Anda?! Hahaha. Tua banget sih lo, Ja. Relax, dude. Natural aja nggak, sih? Lo gue aja lah.” Dia tertawa dengan nada melecehkan, tapi harus diakui, sekilas wajah yang di make up tipis ini menunjukkan aura charming-nya saat tertawa tadi.
“Beneran?”
“No worries, kok.”
“Okay, then.”
“Ya udah, sebagai pembuka obrolan kita, gue tanya dulu sama lo. Lo tau nggak kantor ini di desain pake gaya apa?” tanyanya, datar dan terdengar mengejek.
“Kalo menurut gue sih, skandinavian, tapi ada paduan industrial juga sedikit. Mungkin buat ngehemat anggaran (?)” Jawab gue.
“Hahaha. Correct! Tau alasannya kenapa dipilih desain itu?”
“Waduh, ini sih banyak kemungkinan. Tapi yang paling mungkin, karena lo dulu kuliah di luar negeri, jadi biar ada kenang-kenangan atau ngebangun feel ketika lo disana, lo pilih desain ini.” kata gue menebak-nebak kemungkinan terdekatnya.
“Gokil! Tebakan lo benar lagi.” Katanya, lalu berdiri dan memberikan tepuk tangan tiga kali, sambil tersenyum kecil. Setelahnya dia kembali duduk, tanpa ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya.
“Haha. Ya analisa dikit-dikit lah.” Timpal gue.
“Bisa nebak gue kuliah di negara mana dulu?” tanyanya lagi, kali ini ada sedikit antusiasme dari nada bicaranya, namun raut mukanya tetap ketus.
“Finland, or Denmark, maybe? Kan skandinavian, tuh. Terus yang pendidikannya bagus dari negara-negara dingin itu ya dua negara yang gue sebutin tadi.”
Dia tidak menjawab, hanya menunjukkan gestur ibu jari yang dia dekatkan dengan jari telunjuk seperti ingin mencubit sesuatu. Menandakan tebakan gue mungkin hampir benar. Lagi-lagi tanpa menoleh atau memperhatikan gue.
“Oke. Lo analisa gue sekarang, dan harusnya lo bisa nebak gue siapa.” Tiba-tiba dia bersuara dan langsung bertanya.
“Hah?! Gimana caranya?”
“Gimana caranya?! Lo nggak punya kemampuan analisa dan problem solving selama ini, hah? Lo mimpin tim lo gimana ceritanya kalo kayak gini? Bisa-bisanya ngeluarin kalimat ‘gimana caranya’? Nggak malu sama almamater, lo?” katanya, nadanya super ketus dan sangat merendahkan.
“Gue nggak ada clue, gue pun nggak tau informasi apapun karena gue aja baru ketemu lo, dan melihat lo dengan waktu yang cukup lama, ya baru sekarang. Terus lo minta gue analisa lo dan nebak lo siapa? Nggak masuk logika gue, deh. Mana ada yang bisa. Dan please, nggak usah bawa-bawa kampus gue.”
“Hahaha. Ternyata lo nggak secerdas itu ya. Dan kalaupun gue mau bawa-bawa kampus lo, itu hak gue.”
“Maksud lo gimana? Lo mau ngeledek lulusan kampus gue maksudnya?” Nada bicara gue agak meninggi, gue tidak terima di judge langsung seperti ini. Dia bahkan baru tatap muka dengan gue saat ini. Bisa-bisanya dia menilai gue tidak begitu cerdas dan bahkan seperti merendahkan lulusan kampus gue.
“Heey. Kalem lah. Haha. Lo pikir aja. Nih, lo liat muka gue. Nggak cukup juga lo mengenali siapa gue?” Dia menunjuk mukanya sendiri untuk gue perhatikan. Sorot matanya amat tajam. Gue memperhatikan cukup seksama dari ujung rambut sampai ujung dagunya, dari ujung telinga kiri sampai telinga kanan. Bentuk alis, bentuk hidung, bentuk rahang, tulang pipi sampai bibir. Tentunya dengan perasaan gugup luar biasa karena merasa terancam.
“No way! It can’t be…..”
itkgid dan 7 lainnya memberi reputasi
8
 dan bintang 5
dan bintang 5