- Beranda
- Stories from the Heart
Ekspedisi Arkeologi - Kutukan Desa Mola-Mola
...
TS
wedi
Ekspedisi Arkeologi - Kutukan Desa Mola-Mola
Quote:
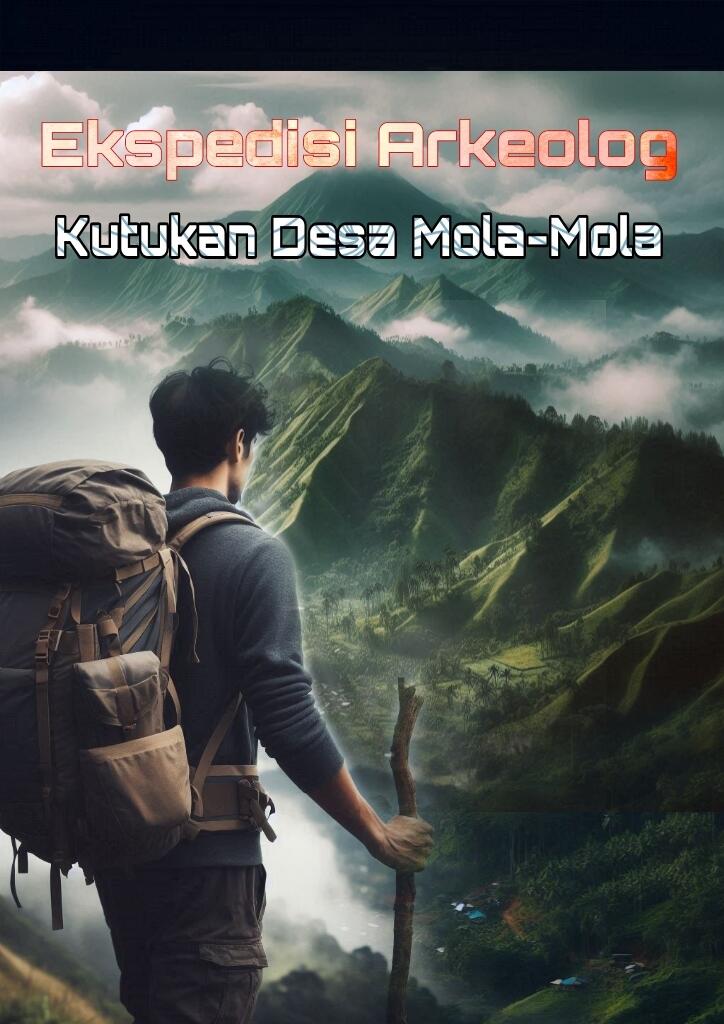
Judul: Ekspedisi Arkeologi.
Genre: Petualangan/Misteri.
Status: TAMAT.
Sinopsis:
Kutukan Desa Mola-Mola adalah sebuah novel misteri yang mengikuti perjalanan seorang arkeolog bernama Satrio dalam mengungkap rahasia kutukan yang menyelimuti desa terpencil bernama Mola-Mola. Desa ini dihantui oleh kejadian-kejadian aneh setelah melupakan tradisi leluhur mereka. Bersama tim penelitinya, Satrio menemukan petunjuk dari prasasti kuno dan artefak tersembunyi yang mengarahkan mereka pada sebauh suku besar yang kini di kenal Mola-Mola.
Di tengah pencarian, Satrio terpisah dari tim dan berjuang bertahan hidup di hutan yang penuh bahaya, sementara tim penelitinya mencoba melacak jejaknya. Makin dalam mereka menelusuri misteri desa, semakin jelas bahwa kutukan itu bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari balas dendam berdarah yang melibatkan masa lalu kelam dua keluarga besar desa. Di puncak ketegangan, mereka harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan kutukan sebelum menghancurkan desa dan seluruh penghuninya.
Berikut salah satu karya yang sudah mulai saya kerjakan. Jumlah bab sudah mencapai 42 Bab. Bahkan sudah mendekati Tamat. Dan di sini juga teman-teman tidak perlu membaca, hehe.. Saya sudah merubahnya ke Audio.
Isi Post ini akan terus saya update jika peminatnya bagus, dan saya ada rencana akan merubah semua karya saya menjadi bentuk Audio, dan saya upload di youtube.
Spoiler for Daftar Cerita:
1. Rumah Terbengkalai [TAMAT]
2. Ekspedisi Arkeologi [On Going]
3. Rumah Terbengkalai II - Awal Kebangkitan [Next Projek]
4. Amnesia [Next Projek Revisi]
2. Ekspedisi Arkeologi [On Going]
3. Rumah Terbengkalai II - Awal Kebangkitan [Next Projek]
4. Amnesia [Next Projek Revisi]
Siapa tau rejeki saya bagus di sini. Aminn..
Quote:
Untuk daftar isi sementara saya update di sini lantaran TH belum bisa di edit. Semoga bisa menghibur. Update setiap hari. InsyaAllah, sampai tamat selama masih ada pembacanya.
Daftar Isi:
Bab 1: Desa Mola-Mola
Bab 2: Arkeologi Muda
Bab 3: Kepedihan Lisa dan Desa
Bab 4: Kutukan Kembali Vol. 1
Bab 4: Kutukan Kembali Vol. 2
Bab 4: Kutukan Kembali Vol. 3
Bab 4: Kutukan kembali Vol. 4 End
Bab 5: Tekad Satrio Vol. 1
Bab 5: Awal Petualangan Vol 2 End
Bab 6: Jejak Penjelajah
Bab 7: Ancaman Hutan
Bab 8: Misteri Batu Penjelajah
Bab 9: Prasasti Di Gua Batu
Bab 10: Arah Barat
Bab 11: Aksi Melewati Sungai
Bab 12: Hutan Misterius
Bab 13: Pria Kekar
Bab 14: Pria Desa Mola-Mola
Bab 15: Legenda Batu Kuno
Bab 16: Bab 16
Bab 16: Tim Satrio
Bab 17: Teka-teki Dibalik Kutukan V1
Bab 18: Teka-teki Dibalik Kutukan V2
Bab 19: Teka-teki Dibalik Kutukan V3
Bab 20: Teka-teki Dibalik Kutukan V4
Bab 21: Teka-teki Dibalik Kutukan V5
Bab 22: Teka-teki Dibalik Kutukan V6
Bab 23: Uraian Buku Catatan Satrio.
Bab 24: Babak Akhir V1
Bab 25: Babak Akhir V2
Bab 26: Babak Akhir V3
Bab 27: Babak Akhir V4
Bab 28: Babak Akhir V5
Bab 29: Hari Baru TAMAT
Daftar Isi:
Bab 1: Desa Mola-Mola
Bab 2: Arkeologi Muda
Bab 3: Kepedihan Lisa dan Desa
Bab 4: Kutukan Kembali Vol. 1
Bab 4: Kutukan Kembali Vol. 2
Bab 4: Kutukan Kembali Vol. 3
Bab 4: Kutukan kembali Vol. 4 End
Bab 5: Tekad Satrio Vol. 1
Bab 5: Awal Petualangan Vol 2 End
Bab 6: Jejak Penjelajah
Bab 7: Ancaman Hutan
Bab 8: Misteri Batu Penjelajah
Bab 9: Prasasti Di Gua Batu
Bab 10: Arah Barat
Bab 11: Aksi Melewati Sungai
Bab 12: Hutan Misterius
Bab 13: Pria Kekar
Bab 14: Pria Desa Mola-Mola
Bab 15: Legenda Batu Kuno
Bab 16: Bab 16
Bab 16: Tim Satrio
Bab 17: Teka-teki Dibalik Kutukan V1
Bab 18: Teka-teki Dibalik Kutukan V2
Bab 19: Teka-teki Dibalik Kutukan V3
Bab 20: Teka-teki Dibalik Kutukan V4
Bab 21: Teka-teki Dibalik Kutukan V5
Bab 22: Teka-teki Dibalik Kutukan V6
Bab 23: Uraian Buku Catatan Satrio.
Bab 24: Babak Akhir V1
Bab 25: Babak Akhir V2
Bab 26: Babak Akhir V3
Bab 27: Babak Akhir V4
Bab 28: Babak Akhir V5
Bab 29: Hari Baru TAMAT
Diubah oleh wedi 17-11-2024 14:14
sukhhoi dan 10 lainnya memberi reputasi
11
2.8K
Kutip
125
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.8KThread•1Anggota
Tampilkan semua post
TS
wedi
#12
Bab 3
Spoiler for Bab 3 - Kabar Lisa:

Spoiler for Teks:
Di dalam sebuah rumah sederhana, suasana begitu hening. Udara di dalam terasa berat, seolah duka yang menyelimuti seisi ruangan tak bisa diusir. Lisa, yang baru saja menjadi korban kutukan, duduk membeku di pojok kamar. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Kehormatan yang hilang bukan hanya merenggut rasa aman, tetapi juga menghancurkan semangat hidupnya.
Bu Alezza, ibunya. Duduk di sampingnya, mengelus pundak Lisa perlahan. "Lisa, ibu di sini. Kamu harus kuat Nak." Suaranya lembut, namun terdengar getir, menyiratkan kepedihan yang tak bisa ditutupi. Lisa tetap tak merespon, matanya lurus ke depan, seolah terputus dari kenyataan yang ada di sekelilingnya.
Ketukan pintu memecah keheningan. Pak Janjan, yang sejak tadi duduk termenung di kursi di dekat pintu, segera bangkit. Dengan wajah lelah, ia membuka pintu dan mendapati Ekot, ketua pemuda desa, berdiri di ambang pintu sambil membawa keranjang buah.
"Pak Janjan, Bu Alezza, kami datang untuk menjenguk Lisa." ujar Ekot dengan suara rendah, penuh empati. "Ini ada beberapa buah dari warga, sebagai tanda simpati kami."
Pak Janjan mengangguk pelan, wajahnya masih dirundung kesedihan mendalam. "Terima kasih Ekot. Kebaikan kalian sangat berarti bagi kami."
Ekot melangkah masuk dan menghampiri Lisa, menunduk dengan hormat. "Lisa... kamu tidak sendiri. Kami semua ada di sini untukmu. Semoga kamu bisa menemukan kekuatan dalam dirimu."
Tak ada jawaban. Lisa tetap diam, matanya tak bergerak sedikit pun. Ekot menghela napas pelan, menyadari betapa dalam trauma yang dialami gadis itu. Setelah beberapa saat, ia menoleh kepada orang tua Lisa.
"Kami semua turut prihatin, Pak Janjan, Bu Alezza. Jika ada yang bisa kami bantu, jangan sungkan untuk menghubungi kami."
Bu Alezza tersenyum tipis, lemah, dan menjawab pelan. "Terima kasih Ekot. Kehadiran kalian sudah sangat membantu."
Ekot pamit, dan dengan penuh kesedihan meninggalkan rumah itu. Langkahnya perlahan menjauh, membawa beban pikiran tentang kutukan yang masih menghantui desa.
Setelah keluar dari rumah Lisa, Ekot berjalan perlahan menyusuri jalan setapak desa. Pikirannya masih tertuju pada Lisa dan keluarganya, serta beban tanggung jawab sebagai ketua pemuda yang semakin hari semakin berat. Langkahnya terhenti ketika dari kejauhan, ia melihat dua pemuda desa, Rumbun dan Mantir, berjalan dengan senyum lebar, masing-masing membawa hasil buruan di punggung mereka.
"Ekot!" panggil Rumbun ketika melihat ketua pemudanya. "Kami baru saja dari hutan. Berhasil dapat beberapa ekor buruan."
Mantir mengangkat hasil buruannya dengan bangga, "Hari ini lumayan banyak. Desa akan makan besar!"
Ekot tersenyum tipis, lalu mendekat. "Bagus sekali. Hasilnya kelihatan melimpah," katanya sambil mengamati hasil buruan itu. Namun, nadanya berubah serius. "Tapi, aku punya permintaan untuk kalian."
Rumbun dan Mantir saling pandang, penasaran. "Apa itu Ekot?" tanya Mantir.
Ekot menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku ingin kalian bagikan hasil buruan ini kepada keluarga-keluarga yang anaknya telah menjadi korban kutukan."
Kedua pemuda itu terdiam sejenak. Wajah mereka berubah serius, menyadari betapa beratnya kondisi desa akhir-akhir ini. Mereka tahu betul rasa kehilangan yang dialami keluarga korban.
"Kau benar," jawab Rumbun akhirnya. "Kami paham, keluarga-keluarga itu butuh lebih dari sekadar kata-kata. Kita harus menunjukkan dukungan nyata."
Mantir menambahkan, sambil menepuk bahu Ekot. "Betul. Kami akan langsung ke rumah-rumah mereka setelah ini,"
Ekot tersenyum lega mendengar kesediaan teman-temannya. "Terima kasih. Kalian luar biasa. Aku tahu ini bukan tugas mudah, tapi kita semua harus bersama-sama menghadapi kondisi ini."
Dengan hati ringan, ketiga pemuda itu pun melanjutkan perjalanan, membawa hasil buruan mereka untuk dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan. Di balik derita yang menyelimuti desa, rasa kebersamaan dan solidaritas mereka semakin kuat.
Beberapa saat berlalu. Di depan rumah sederhana yang terbuat dari kayu, Ekot duduk di atas bangku kayu tua sambil dengan tekun mengasah tombaknya. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan cahaya jingga yang lembut, sementara angin sore berhembus lembut menggetarkan dedaunan. Suara gesekan besi pada batu asah mengisi keheningan desa yang terasa semakin sunyi dengan kutukan yang menghantui.
Tiba-tiba, langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. Pak Labih, ayah Rina, muncul di depan gerbang. Wajahnya terlihat cemas dan lelah, seperti telah menanggung beban yang terlalu berat. Nafasnya memburu seakan dia berlari tanpa henti.
"Ekot," panggilnya dengan suara gemetar, “Tolong... Aku butuh bantuanmu malam ini. Aku tak sanggup berjaga sendiri. Rina... Aku takut kutukan itu menimpa anakku.”
Ekot menghentikan gerakannya, menatap Pak Labih dengan tatapan serius. Tombak di tangannya ia letakkan di pangkuannya. Wajah Ekot menunjukkan rasa simpati yang mendalam, namun ia tahu bahwa dirinya sudah tak bisa memenuhi permintaan itu.
“Pak Labih," jawab Ekot lembut namun tegas, "aku ingin sekali membantumu, tapi malam ini aku sudah berjanji untuk berjaga di rumah Pak Purrok. Dia juga meminta bantuanku karena keluarganya sudah terlalu ketakutan."
Pak Labih menghela napas dalam, terlihat sangat kecewa. Mata tuanya berkaca-kaca, namun ia mencoba menahan diri agar tidak terlihat rapuh di depan Ekot. “Rina satu-satunya yang kumiliki... Aku tak tahu harus bagaimana jika kutukan itu datang ke rumahku.”
Ekot memejamkan matanya sejenak, menimbang-nimbang. “Begini saja. Meskipun aku tidak bisa berjaga di rumahmu malam ini, aku akan meminta tiga warga lainnya untuk menemanimu berjaga. Aku pastikan mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan.”
Pak Labih tampak lega. Walau tak langsung dari Ekot, bantuan yang ditawarkan membuat hatinya sedikit lebih tenang. “Terima kasih Ekot... Terima kasih banyak. Aku tak tahu harus bagaimana jika tak ada yang membantuku.”
Ekot mengangguk, tersenyum tipis. “Jangan khawatir. Kita semua di desa ini sedang berjuang bersama. Aku akan segera mengirimkan mereka sebelum malam tiba.”
Pak Labih mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum akhirnya berpamitan. Setelah Pak Labih pergi, Ekot kembali mengasah tombaknya, namun kali ini pikirannya tak tenang. Kutukan yang terus meneror desa ini semakin menambah beban di pundaknya. Namun dia bertekad, walau dengan cara apa pun, dia akan melindungi warganya.
Ekot menatap punggung Pak Labih yang perlahan menjauh. Bayangannya semakin kecil di bawah cahaya temaram matahari yang mulai menghilang di balik bukit. Namun, dalam dada Ekot, rasa marah bergemuruh.
Wajahnya yang tadinya tenang kini berubah kaku, matanya menyipit penuh kemarahan. Ia menggenggam tombak di tangannya lebih erat, jari-jarinya bergetar seiring emosinya yang tak bisa ia tahan lagi.
"Setiap malam." Gumamnya dengan nada rendah, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. "Ini selalu terjadi. Tak ada yang berubah. Mereka terus hidup dalam ketakutan." Suaranya semakin serak, penuh amarah yang terpendam.
Ekot kembali mengasah ujung tombaknya dengan gerakan cepat, hampir kasar. Bunyi gesekan besi yang cumiakkan telinga terdengar lebih keras dari biasanya, seolah mengimbangi gejolak di dalam hatinya. Ujung tombak itu sudah sangat tajam, lebih dari cukup untuk memotong apa pun yang mencoba mendekati, tapi Ekot terus mengasahnya, seakan itu satu-satunya cara untuk menyalurkan kemarahannya.
Wajahnya menegang, otot-otot di leher dan lengan berkerut seolah siap meledak kapan saja. "Aku muak! Melihat mereka semua ketakutan!" pekiknya dalam hati. "Leluhur, arwah, kutukan... Apa pun itu! Aku tidak akan tinggal diam!"
Setiap kali ingatan tentang para korban, Lisa dan gadis-gadis lain melintas dalam pikirannya, kemarahannya semakin menjadi. Kutukan ini sudah terlalu lama membelenggu desanya, dan setiap kali malam menjelang, ketakutan yang sama datang, membuat setiap orang hanya bisa bersembunyi.
Ekot menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, amarah itu tak sepenuhnya surut. Ia tahu bahwa sebagai Ketua Pemuda, ia tak bisa terus diam. Sesuatu harus dilakukan. Sesuatu yang lebih dari sekadar berjaga dan bersembunyi.
Dengan satu gerakan tajam, Ekot menghentikan asahannya. Tombak itu kini berkilauan di bawah sinar senja yang tersisa. Tatapannya mantap, dipenuhi tekad.
"Malam ini... Aku takan membiarkan satu Gadis pun menjadi korban!" katanya lirih, seolah membuat janji pada dirinya sendiri.
Ia tahu, malam ini akan panjang, dan mungkin ada bahaya yang lebih besar menunggu di luar sana. Tapi kali ini, Ekot tidak akan membiarkan ketakutan mengendalikan mereka.
Hingga malam semakin larut. Langit di Desa Mola-Mola tertutup awan kelam, seolah mengirimkan isyarat gelap yang merasuk hingga ke hati para warga. Di balai desa, Ekot berdiri tegap dengan tombak di tangan, wajahnya penuh tekad meski kekhawatiran tetap membayang. Di hadapannya berkumpul beberapa warga, wajah-wajah mereka tegang namun siap menjalankan tugas.
"Pak Rumbun, Pak Mantir, Empong," Ekot memanggil nama mereka satu per satu, suaranya tegas. "Kalian bertiga berjaga di rumah Pak Labih. Pastikan tidak ada yang mencurigakan. Jaga ketat!"
Ketiganya mengangguk serentak. Pak Rumbun, yang sudah berusia di atas lima puluh tahun, menepuk bahu Ekot sejenak sebelum melangkah pergi bersama dua rekannya. Mereka paham betul, tugas malam ini bukan sekadar berjaga, tapi menjaga kehormatan keluarga yang hampir hancur karena kutukan.
"Sisanya." Ekot melanjutkan, menatap ke arah Nanjan, Simpei, Banjar, Danum, dan Balawa. "Kita berkeliling desa. Jangan biarkan satu sudut pun luput dari pengawasan."
Angin malam bertiup, membawa serta suara daun kering yang bergesekan, menambah suasana mencekam di antara mereka. Ekot memandangi teman-temannya yang siap, lalu tanpa kata lebih lanjut, mereka mulai bergerak, membagi tugas dengan diam-diam namun penuh tekad.
Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Tapi Ekot tahu, mereka tidak bisa mundur. Tidak ada yang boleh lagi jatuh menjadi korban.
Dari luar, rumah Pak Labih terlihat sunyi, hanya suara angin yang sesekali menggoyangkan dedaunan di halaman depan. Tapi di dalam, suasana jauh dari tenang. Bu Elora duduk di sudut ruangan, menggenggam erat tangan putrinya, Rina, yang gemetaran. Malam ini terasa berbeda, ketegangan menggantung di udara seolah menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi.
"Sudah-lah Rina. Jangan khawatir lagi," kata Pak Labih dengan suara pelan namun penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya ia sendiri tidak bisa menghilangkan rasa takut itu. Ia berjalan mendekati istrinya, menepuk pundaknya dengan lembut. "Malam ini mereka berjaga. Pak Mantir, Pak Rumbun, dan beberapa pemuda desa ada di luar. Kita akan aman."
Rina menatap ayahnya dengan mata penuh kecemasan, bibirnya bergetar tapi tak sepatah kata pun keluar. Ia hanya menggenggam selimutnya lebih erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa terlindungi.
"Rina, dengarkan Bapak." Pak Labih melanjutkan, berusaha menenangkan suasana. "Ini bukan pertama kalinya mereka berjaga. Setiap malam kita selamat, dan malam ini juga akan begitu."
Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Bu Elora tersentak kaget, tapi Pak Labih segera berdiri dan membuka pintu. Di depan pintu, Pak Mantir bersama Pak Rumbun dan Empong berdiri dengan wajah penuh keyakinan.
"Kami sudah di sini Pak Labih," kata Pak Mantir sambil tersenyum tipis, mencoba memberikan rasa aman pada keluarga itu. "Semua sudah siap. Jangan khawatir, kami akan berjaga semalaman."
Suasana langsung terasa lebih hidup. Pak Labih tersenyum lega, melihat rombongan yang datang dengan membawa ketenangan.
"Terima kasih Pak Mantir," jawabnya dengan nada yang lebih ringan. "Dengan kalian di sini, saya yakin semuanya akan baik-baik saja."
Pak Mantir mengangguk, lalu bersama yang lain, mereka mulai mengambil posisi di sekitar rumah, memastikan setiap sudut aman dari ancaman yang tak terlihat. Di dalam, Bu Elora mulai terlihat sedikit lebih tenang, sementara Rina perlahan-lahan melepaskan genggaman erat pada selimutnya. Malam mungkin masih panjang, tapi setidaknya mereka tahu, mereka tidak sendirian.
Pak Mantir dan Pak Rumbun baru saja selesai berkeliling mengelilingi rumah Pak Labih. Malam semakin larut, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan, sementara cahaya obor dari depan rumah berpendar hangat, menciptakan bayang-bayang panjang di tanah. Mereka berdua kembali ke halaman depan, di mana Empong sudah menunggu sambil duduk di sebuah bangku kayu kecil.
"Sudah kita cek semua," kata Pak Mantir, menghela napas lega. "Tidak ada tanda-tanda aneh di sekitar sini."
Pak Rumbun mengangguk. "Benar, malam ini terlihat tenang. Semoga memang begitu sampai pagi."
Mereka bertiga lalu duduk bersama, membiarkan angin malam yang sejuk menyapu wajah mereka. Sejenak tak ada yang berbicara, hanya suara alam yang menemani mereka. Tapi Empong akhirnya memecah keheningan, suaranya lirih namun sarat dengan perasaan.
"Aku selalu berharap. Kutukan ini cepat berakhir," ucapnya dengan nada putus asa. Matanya menerawang jauh, menatap kegelapan di kejauhan seolah mencoba mencari jawaban dari langit malam. "Sudah cukup banyak korban. Setiap malam, desa ini semakin terasa mengerikan."
Pak Mantir menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Kita semua merasakannya. Tapi tak ada yang bisa kita lakukan selain menjaga dan berharap leluhur segera menghentikan amarah mereka."
Pak Rumbun, yang sedari tadi hanya mendengarkan, akhirnya ikut angkat bicara. "Ini semua memang berat, terutama bagi yang memiliki anak gadis. Tak ada yang ingin melihat keluarganya menderita karena sesuatu yang tak bisa kita pahami sepenuhnya."
Empong menghela napas panjang, mengusap wajahnya. "Aku tahu. Tapi, berapa lama lagi kita harus hidup seperti ini? Berjaga setiap malam, takut setiap kali matahari terbenam. Ini bukan hidup."
Pak Mantir memandang Empong dengan tatapan bijaksana. "Kita tidak tahu. Tapi setidaknya, selama kita berjaga. Kita melindungi mereka yang kita sayangi. Hanya Itu yang bisa kita lakukan sekarang."
Empong terdiam, menunduk. Meskipun ia ingin sekali semuanya segera berakhir, ia tahu tidak ada pilihan lain. Di sisi lain, rasa lelah dan frustasi makin menyelimuti hatinya.
"Tidak ada yang tahu kapan ini selesai," Pak Rumbun menambahkan. "Tapi selagi kita bersama, kita bisa melewati ini."
Mereka bertiga terdiam lagi, memandangi langit malam yang tanpa bintang. Hanya angin yang terus berhembus pelan, seolah membawa harapan yang entah kapan akan terwujud.
Pak Labih dan istrinya muncul dari dalam rumah, membawa nampan berisi minuman hangat dan buah-buahan segar. Langkah mereka pelan namun penuh niat untuk memberikan sedikit rasa nyaman kepada para penjaga malam itu. Suasana yang tadinya sedikit hening berubah lebih hangat dengan kedatangan mereka.
"Maafkan aku, hanya ini yang kami punya untuk kalian," ucap Pak Labih, meletakkan nampan di tengah-tengah mereka. Ia lalu duduk di salah satu kursi bambu yang ada di halaman depan, menghela napas berat. "Kita memang harus bersama-sama menghadapi ini."
Istri Pak Labih, yang sedari tadi berdiri di belakangnya, tersenyum lemah. "Terima kasih atas kedatangan kalian di sini. Aku sangat berhutang budi pada kalian." Suaranya bergetar, dan ia berusaha menahan air mata, tapi kegelisahan tampak jelas di wajahnya.
Pak Mantir mengangguk hormat, menatap Istri Pak Labih dengan penuh pengertian. "Kami hanya melakukan apa yang seharusnya. Tapi, sebaiknya Ibu kembali ke dalam untuk menemani Rina. Biar kami yang berjaga di sini."
Istri Pak Labih terdiam sejenak, menoleh ke arah suaminya seolah meminta izin, lalu kembali menatap Pak Mantir. "Baiklah. Aku akan kembali ke dalam," katanya dengan suara pelan, sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ia kemudian melangkah kembali ke rumah, meninggalkan para pria di halaman.
Saat pintu tertutup, Pak Labih menghela napas panjang. "Istriku tak pernah berhenti khawatir setiap malam. Aku pun begitu. Tapi, apa daya, kami hanya bisa berharap malam cepat berlalu."
Pak Rumbun meraih salah satu gelas minuman dan meneguknya perlahan. "Tidak ada satu warga pun saat ini yang bisa tidur dengan nyenyak Pak Labih. Tapi percayalah, selama kita berjaga, kita akan melindungi Rina dan semua gadis lainnya."
"Itu Benar," tambah Pak Mantir, matanya menatap serius ke arah rumah. "Kita harus tetap waspada."
Pak Labih mengangguk setuju, meski rasa lelah di wajahnya tak bisa disembunyikan. Ia tahu malam ini mungkin akan panjang, seperti malam-malam sebelumnya. "Semoga saja kutukan ini segera berakhir," gumamnya, hampir seperti sebuah doa yang ia ucapkan pada angin malam.
Sambil meminum teh hangat yang dibawa istrinya, mereka kembali duduk dalam kesunyian, mata mereka sesekali menyapu sekitar, telinga mereka waspada akan setiap suara yang datang dari kegelapan.
Di sisi lain, malam terasa begitu dingin, angin gunung berembus perlahan menyapu dedaunan di sekitar rumah Pak Purrok. Ekot berdiri tegap di depan rumah, tombaknya menggantung di tangan, tajamnya berkilat di bawah sinar bulan. Udara malam yang biasanya ramai dengan suara serangga kini terasa sunyi, seolah alam pun tahu ada ketegangan yang melayang di udara.
Ekot tak bergerak, matanya menelusuri setiap sudut halaman, siap siaga. Di sekitarnya, teman-temannya. Nanjan dan Simpe juga dalam posisi siaga. Tak ada yang berbicara, hanya fokus pada tugas masing-masing.
Suara samar ranting yang patah di hutan dekat rumah membuat Simpei sedikit menegakkan tubuhnya. "Suara apa itu?" bisiknya pelan, matanya mencari-cari sumber suara.
Ekot hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tetap tenang. Ia tahu, di malam seperti ini, suara kecil bisa menipu pikiran yang sudah dipenuhi ketakutan. "Mungkin itu babi hutan," gumamnya pendek.
Namun, tak lama setelah itu, bayangan besar tampak bergerak cepat di antara pepohonan. Tapi ketika mendekati rumah, bayangan itu tiba-tiba berhenti. Bahkan binatang hutan pun tampak enggan melintasi batas di sekitar Ekot dan tombaknya. Entah mengapa, malam itu, bahkan seekor babi hutan yang kelaparan tak berani mendekat.
"Ini Aneh. Biasanya mereka tidak takut seperti itu," bisik Nanjan, melihat bagaimana bayangan itu kembali menghilang ke dalam hutan.
Ekot menajamkan matanya, tetap tidak tergoyahkan. "Mungkin malam ini mereka tahu siapa yang mereka hadapi," jawabnya dingin, menggenggam lebih erat tombaknya yang telah ia asah hingga seperti senjata dewa.
Simpei tertawa kecil, meski tawa itu lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada mengejek. "Kalau begitu, kita hanya perlu memastikan jika bukan hanya babi yang tak bernyali, tapi juga yang lainnya."
Semua kembali hening setelah itu. Ekot tetap berdiri tegak, seolah bisa menantang malam itu sendiri, tombaknya siap untuk menusuk apa pun yang berani melintasi ambang batas. Tapi yang lebih menakutkan dari bayangan hutan adalah kesunyian itu sendiri, yang terus menekan mereka seiring malam yang masih panjang berjalan tanpa kepastian.
Namun, satu hal yang pasti: selama Ekot berjaga, tak ada makhluk, manusia atau bukan yang bisa mendekati rumah Pak Purrok.
Malam semakin hening di kediaman Pak Labih, dan ketegangan yang melingkupi desa itu terasa kian mencekam. Rina yang tertidur di dalam kamarnya mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Kelopak matanya yang terpejam bergerak cepat, napasnya tersengal, seolah sedang mengalami mimpi buruk. Di sisi ranjang, Ibu Rina duduk dengan kepala hampir terkulai, berusaha melawan kantuk yang tak tertahankan, sementara tangannya masih menggenggam jemari putrinya.
Bu Alezza, ibunya. Duduk di sampingnya, mengelus pundak Lisa perlahan. "Lisa, ibu di sini. Kamu harus kuat Nak." Suaranya lembut, namun terdengar getir, menyiratkan kepedihan yang tak bisa ditutupi. Lisa tetap tak merespon, matanya lurus ke depan, seolah terputus dari kenyataan yang ada di sekelilingnya.
Ketukan pintu memecah keheningan. Pak Janjan, yang sejak tadi duduk termenung di kursi di dekat pintu, segera bangkit. Dengan wajah lelah, ia membuka pintu dan mendapati Ekot, ketua pemuda desa, berdiri di ambang pintu sambil membawa keranjang buah.
"Pak Janjan, Bu Alezza, kami datang untuk menjenguk Lisa." ujar Ekot dengan suara rendah, penuh empati. "Ini ada beberapa buah dari warga, sebagai tanda simpati kami."
Pak Janjan mengangguk pelan, wajahnya masih dirundung kesedihan mendalam. "Terima kasih Ekot. Kebaikan kalian sangat berarti bagi kami."
Ekot melangkah masuk dan menghampiri Lisa, menunduk dengan hormat. "Lisa... kamu tidak sendiri. Kami semua ada di sini untukmu. Semoga kamu bisa menemukan kekuatan dalam dirimu."
Tak ada jawaban. Lisa tetap diam, matanya tak bergerak sedikit pun. Ekot menghela napas pelan, menyadari betapa dalam trauma yang dialami gadis itu. Setelah beberapa saat, ia menoleh kepada orang tua Lisa.
"Kami semua turut prihatin, Pak Janjan, Bu Alezza. Jika ada yang bisa kami bantu, jangan sungkan untuk menghubungi kami."
Bu Alezza tersenyum tipis, lemah, dan menjawab pelan. "Terima kasih Ekot. Kehadiran kalian sudah sangat membantu."
Ekot pamit, dan dengan penuh kesedihan meninggalkan rumah itu. Langkahnya perlahan menjauh, membawa beban pikiran tentang kutukan yang masih menghantui desa.
Setelah keluar dari rumah Lisa, Ekot berjalan perlahan menyusuri jalan setapak desa. Pikirannya masih tertuju pada Lisa dan keluarganya, serta beban tanggung jawab sebagai ketua pemuda yang semakin hari semakin berat. Langkahnya terhenti ketika dari kejauhan, ia melihat dua pemuda desa, Rumbun dan Mantir, berjalan dengan senyum lebar, masing-masing membawa hasil buruan di punggung mereka.
"Ekot!" panggil Rumbun ketika melihat ketua pemudanya. "Kami baru saja dari hutan. Berhasil dapat beberapa ekor buruan."
Mantir mengangkat hasil buruannya dengan bangga, "Hari ini lumayan banyak. Desa akan makan besar!"
Ekot tersenyum tipis, lalu mendekat. "Bagus sekali. Hasilnya kelihatan melimpah," katanya sambil mengamati hasil buruan itu. Namun, nadanya berubah serius. "Tapi, aku punya permintaan untuk kalian."
Rumbun dan Mantir saling pandang, penasaran. "Apa itu Ekot?" tanya Mantir.
Ekot menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku ingin kalian bagikan hasil buruan ini kepada keluarga-keluarga yang anaknya telah menjadi korban kutukan."
Kedua pemuda itu terdiam sejenak. Wajah mereka berubah serius, menyadari betapa beratnya kondisi desa akhir-akhir ini. Mereka tahu betul rasa kehilangan yang dialami keluarga korban.
"Kau benar," jawab Rumbun akhirnya. "Kami paham, keluarga-keluarga itu butuh lebih dari sekadar kata-kata. Kita harus menunjukkan dukungan nyata."
Mantir menambahkan, sambil menepuk bahu Ekot. "Betul. Kami akan langsung ke rumah-rumah mereka setelah ini,"
Ekot tersenyum lega mendengar kesediaan teman-temannya. "Terima kasih. Kalian luar biasa. Aku tahu ini bukan tugas mudah, tapi kita semua harus bersama-sama menghadapi kondisi ini."
Dengan hati ringan, ketiga pemuda itu pun melanjutkan perjalanan, membawa hasil buruan mereka untuk dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan. Di balik derita yang menyelimuti desa, rasa kebersamaan dan solidaritas mereka semakin kuat.
Beberapa saat berlalu. Di depan rumah sederhana yang terbuat dari kayu, Ekot duduk di atas bangku kayu tua sambil dengan tekun mengasah tombaknya. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan cahaya jingga yang lembut, sementara angin sore berhembus lembut menggetarkan dedaunan. Suara gesekan besi pada batu asah mengisi keheningan desa yang terasa semakin sunyi dengan kutukan yang menghantui.
Tiba-tiba, langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. Pak Labih, ayah Rina, muncul di depan gerbang. Wajahnya terlihat cemas dan lelah, seperti telah menanggung beban yang terlalu berat. Nafasnya memburu seakan dia berlari tanpa henti.
"Ekot," panggilnya dengan suara gemetar, “Tolong... Aku butuh bantuanmu malam ini. Aku tak sanggup berjaga sendiri. Rina... Aku takut kutukan itu menimpa anakku.”
Ekot menghentikan gerakannya, menatap Pak Labih dengan tatapan serius. Tombak di tangannya ia letakkan di pangkuannya. Wajah Ekot menunjukkan rasa simpati yang mendalam, namun ia tahu bahwa dirinya sudah tak bisa memenuhi permintaan itu.
“Pak Labih," jawab Ekot lembut namun tegas, "aku ingin sekali membantumu, tapi malam ini aku sudah berjanji untuk berjaga di rumah Pak Purrok. Dia juga meminta bantuanku karena keluarganya sudah terlalu ketakutan."
Pak Labih menghela napas dalam, terlihat sangat kecewa. Mata tuanya berkaca-kaca, namun ia mencoba menahan diri agar tidak terlihat rapuh di depan Ekot. “Rina satu-satunya yang kumiliki... Aku tak tahu harus bagaimana jika kutukan itu datang ke rumahku.”
Ekot memejamkan matanya sejenak, menimbang-nimbang. “Begini saja. Meskipun aku tidak bisa berjaga di rumahmu malam ini, aku akan meminta tiga warga lainnya untuk menemanimu berjaga. Aku pastikan mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan.”
Pak Labih tampak lega. Walau tak langsung dari Ekot, bantuan yang ditawarkan membuat hatinya sedikit lebih tenang. “Terima kasih Ekot... Terima kasih banyak. Aku tak tahu harus bagaimana jika tak ada yang membantuku.”
Ekot mengangguk, tersenyum tipis. “Jangan khawatir. Kita semua di desa ini sedang berjuang bersama. Aku akan segera mengirimkan mereka sebelum malam tiba.”
Pak Labih mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum akhirnya berpamitan. Setelah Pak Labih pergi, Ekot kembali mengasah tombaknya, namun kali ini pikirannya tak tenang. Kutukan yang terus meneror desa ini semakin menambah beban di pundaknya. Namun dia bertekad, walau dengan cara apa pun, dia akan melindungi warganya.
Ekot menatap punggung Pak Labih yang perlahan menjauh. Bayangannya semakin kecil di bawah cahaya temaram matahari yang mulai menghilang di balik bukit. Namun, dalam dada Ekot, rasa marah bergemuruh.
Wajahnya yang tadinya tenang kini berubah kaku, matanya menyipit penuh kemarahan. Ia menggenggam tombak di tangannya lebih erat, jari-jarinya bergetar seiring emosinya yang tak bisa ia tahan lagi.
"Setiap malam." Gumamnya dengan nada rendah, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. "Ini selalu terjadi. Tak ada yang berubah. Mereka terus hidup dalam ketakutan." Suaranya semakin serak, penuh amarah yang terpendam.
Ekot kembali mengasah ujung tombaknya dengan gerakan cepat, hampir kasar. Bunyi gesekan besi yang cumiakkan telinga terdengar lebih keras dari biasanya, seolah mengimbangi gejolak di dalam hatinya. Ujung tombak itu sudah sangat tajam, lebih dari cukup untuk memotong apa pun yang mencoba mendekati, tapi Ekot terus mengasahnya, seakan itu satu-satunya cara untuk menyalurkan kemarahannya.
Wajahnya menegang, otot-otot di leher dan lengan berkerut seolah siap meledak kapan saja. "Aku muak! Melihat mereka semua ketakutan!" pekiknya dalam hati. "Leluhur, arwah, kutukan... Apa pun itu! Aku tidak akan tinggal diam!"
Setiap kali ingatan tentang para korban, Lisa dan gadis-gadis lain melintas dalam pikirannya, kemarahannya semakin menjadi. Kutukan ini sudah terlalu lama membelenggu desanya, dan setiap kali malam menjelang, ketakutan yang sama datang, membuat setiap orang hanya bisa bersembunyi.
Ekot menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, amarah itu tak sepenuhnya surut. Ia tahu bahwa sebagai Ketua Pemuda, ia tak bisa terus diam. Sesuatu harus dilakukan. Sesuatu yang lebih dari sekadar berjaga dan bersembunyi.
Dengan satu gerakan tajam, Ekot menghentikan asahannya. Tombak itu kini berkilauan di bawah sinar senja yang tersisa. Tatapannya mantap, dipenuhi tekad.
"Malam ini... Aku takan membiarkan satu Gadis pun menjadi korban!" katanya lirih, seolah membuat janji pada dirinya sendiri.
Ia tahu, malam ini akan panjang, dan mungkin ada bahaya yang lebih besar menunggu di luar sana. Tapi kali ini, Ekot tidak akan membiarkan ketakutan mengendalikan mereka.
Hingga malam semakin larut. Langit di Desa Mola-Mola tertutup awan kelam, seolah mengirimkan isyarat gelap yang merasuk hingga ke hati para warga. Di balai desa, Ekot berdiri tegap dengan tombak di tangan, wajahnya penuh tekad meski kekhawatiran tetap membayang. Di hadapannya berkumpul beberapa warga, wajah-wajah mereka tegang namun siap menjalankan tugas.
"Pak Rumbun, Pak Mantir, Empong," Ekot memanggil nama mereka satu per satu, suaranya tegas. "Kalian bertiga berjaga di rumah Pak Labih. Pastikan tidak ada yang mencurigakan. Jaga ketat!"
Ketiganya mengangguk serentak. Pak Rumbun, yang sudah berusia di atas lima puluh tahun, menepuk bahu Ekot sejenak sebelum melangkah pergi bersama dua rekannya. Mereka paham betul, tugas malam ini bukan sekadar berjaga, tapi menjaga kehormatan keluarga yang hampir hancur karena kutukan.
"Sisanya." Ekot melanjutkan, menatap ke arah Nanjan, Simpei, Banjar, Danum, dan Balawa. "Kita berkeliling desa. Jangan biarkan satu sudut pun luput dari pengawasan."
Angin malam bertiup, membawa serta suara daun kering yang bergesekan, menambah suasana mencekam di antara mereka. Ekot memandangi teman-temannya yang siap, lalu tanpa kata lebih lanjut, mereka mulai bergerak, membagi tugas dengan diam-diam namun penuh tekad.
Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Tapi Ekot tahu, mereka tidak bisa mundur. Tidak ada yang boleh lagi jatuh menjadi korban.
Dari luar, rumah Pak Labih terlihat sunyi, hanya suara angin yang sesekali menggoyangkan dedaunan di halaman depan. Tapi di dalam, suasana jauh dari tenang. Bu Elora duduk di sudut ruangan, menggenggam erat tangan putrinya, Rina, yang gemetaran. Malam ini terasa berbeda, ketegangan menggantung di udara seolah menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi.
"Sudah-lah Rina. Jangan khawatir lagi," kata Pak Labih dengan suara pelan namun penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya ia sendiri tidak bisa menghilangkan rasa takut itu. Ia berjalan mendekati istrinya, menepuk pundaknya dengan lembut. "Malam ini mereka berjaga. Pak Mantir, Pak Rumbun, dan beberapa pemuda desa ada di luar. Kita akan aman."
Rina menatap ayahnya dengan mata penuh kecemasan, bibirnya bergetar tapi tak sepatah kata pun keluar. Ia hanya menggenggam selimutnya lebih erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa terlindungi.
"Rina, dengarkan Bapak." Pak Labih melanjutkan, berusaha menenangkan suasana. "Ini bukan pertama kalinya mereka berjaga. Setiap malam kita selamat, dan malam ini juga akan begitu."
Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Bu Elora tersentak kaget, tapi Pak Labih segera berdiri dan membuka pintu. Di depan pintu, Pak Mantir bersama Pak Rumbun dan Empong berdiri dengan wajah penuh keyakinan.
"Kami sudah di sini Pak Labih," kata Pak Mantir sambil tersenyum tipis, mencoba memberikan rasa aman pada keluarga itu. "Semua sudah siap. Jangan khawatir, kami akan berjaga semalaman."
Suasana langsung terasa lebih hidup. Pak Labih tersenyum lega, melihat rombongan yang datang dengan membawa ketenangan.
"Terima kasih Pak Mantir," jawabnya dengan nada yang lebih ringan. "Dengan kalian di sini, saya yakin semuanya akan baik-baik saja."
Pak Mantir mengangguk, lalu bersama yang lain, mereka mulai mengambil posisi di sekitar rumah, memastikan setiap sudut aman dari ancaman yang tak terlihat. Di dalam, Bu Elora mulai terlihat sedikit lebih tenang, sementara Rina perlahan-lahan melepaskan genggaman erat pada selimutnya. Malam mungkin masih panjang, tapi setidaknya mereka tahu, mereka tidak sendirian.
Pak Mantir dan Pak Rumbun baru saja selesai berkeliling mengelilingi rumah Pak Labih. Malam semakin larut, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan, sementara cahaya obor dari depan rumah berpendar hangat, menciptakan bayang-bayang panjang di tanah. Mereka berdua kembali ke halaman depan, di mana Empong sudah menunggu sambil duduk di sebuah bangku kayu kecil.
"Sudah kita cek semua," kata Pak Mantir, menghela napas lega. "Tidak ada tanda-tanda aneh di sekitar sini."
Pak Rumbun mengangguk. "Benar, malam ini terlihat tenang. Semoga memang begitu sampai pagi."
Mereka bertiga lalu duduk bersama, membiarkan angin malam yang sejuk menyapu wajah mereka. Sejenak tak ada yang berbicara, hanya suara alam yang menemani mereka. Tapi Empong akhirnya memecah keheningan, suaranya lirih namun sarat dengan perasaan.
"Aku selalu berharap. Kutukan ini cepat berakhir," ucapnya dengan nada putus asa. Matanya menerawang jauh, menatap kegelapan di kejauhan seolah mencoba mencari jawaban dari langit malam. "Sudah cukup banyak korban. Setiap malam, desa ini semakin terasa mengerikan."
Pak Mantir menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Kita semua merasakannya. Tapi tak ada yang bisa kita lakukan selain menjaga dan berharap leluhur segera menghentikan amarah mereka."
Pak Rumbun, yang sedari tadi hanya mendengarkan, akhirnya ikut angkat bicara. "Ini semua memang berat, terutama bagi yang memiliki anak gadis. Tak ada yang ingin melihat keluarganya menderita karena sesuatu yang tak bisa kita pahami sepenuhnya."
Empong menghela napas panjang, mengusap wajahnya. "Aku tahu. Tapi, berapa lama lagi kita harus hidup seperti ini? Berjaga setiap malam, takut setiap kali matahari terbenam. Ini bukan hidup."
Pak Mantir memandang Empong dengan tatapan bijaksana. "Kita tidak tahu. Tapi setidaknya, selama kita berjaga. Kita melindungi mereka yang kita sayangi. Hanya Itu yang bisa kita lakukan sekarang."
Empong terdiam, menunduk. Meskipun ia ingin sekali semuanya segera berakhir, ia tahu tidak ada pilihan lain. Di sisi lain, rasa lelah dan frustasi makin menyelimuti hatinya.
"Tidak ada yang tahu kapan ini selesai," Pak Rumbun menambahkan. "Tapi selagi kita bersama, kita bisa melewati ini."
Mereka bertiga terdiam lagi, memandangi langit malam yang tanpa bintang. Hanya angin yang terus berhembus pelan, seolah membawa harapan yang entah kapan akan terwujud.
Pak Labih dan istrinya muncul dari dalam rumah, membawa nampan berisi minuman hangat dan buah-buahan segar. Langkah mereka pelan namun penuh niat untuk memberikan sedikit rasa nyaman kepada para penjaga malam itu. Suasana yang tadinya sedikit hening berubah lebih hangat dengan kedatangan mereka.
"Maafkan aku, hanya ini yang kami punya untuk kalian," ucap Pak Labih, meletakkan nampan di tengah-tengah mereka. Ia lalu duduk di salah satu kursi bambu yang ada di halaman depan, menghela napas berat. "Kita memang harus bersama-sama menghadapi ini."
Istri Pak Labih, yang sedari tadi berdiri di belakangnya, tersenyum lemah. "Terima kasih atas kedatangan kalian di sini. Aku sangat berhutang budi pada kalian." Suaranya bergetar, dan ia berusaha menahan air mata, tapi kegelisahan tampak jelas di wajahnya.
Pak Mantir mengangguk hormat, menatap Istri Pak Labih dengan penuh pengertian. "Kami hanya melakukan apa yang seharusnya. Tapi, sebaiknya Ibu kembali ke dalam untuk menemani Rina. Biar kami yang berjaga di sini."
Istri Pak Labih terdiam sejenak, menoleh ke arah suaminya seolah meminta izin, lalu kembali menatap Pak Mantir. "Baiklah. Aku akan kembali ke dalam," katanya dengan suara pelan, sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ia kemudian melangkah kembali ke rumah, meninggalkan para pria di halaman.
Saat pintu tertutup, Pak Labih menghela napas panjang. "Istriku tak pernah berhenti khawatir setiap malam. Aku pun begitu. Tapi, apa daya, kami hanya bisa berharap malam cepat berlalu."
Pak Rumbun meraih salah satu gelas minuman dan meneguknya perlahan. "Tidak ada satu warga pun saat ini yang bisa tidur dengan nyenyak Pak Labih. Tapi percayalah, selama kita berjaga, kita akan melindungi Rina dan semua gadis lainnya."
"Itu Benar," tambah Pak Mantir, matanya menatap serius ke arah rumah. "Kita harus tetap waspada."
Pak Labih mengangguk setuju, meski rasa lelah di wajahnya tak bisa disembunyikan. Ia tahu malam ini mungkin akan panjang, seperti malam-malam sebelumnya. "Semoga saja kutukan ini segera berakhir," gumamnya, hampir seperti sebuah doa yang ia ucapkan pada angin malam.
Sambil meminum teh hangat yang dibawa istrinya, mereka kembali duduk dalam kesunyian, mata mereka sesekali menyapu sekitar, telinga mereka waspada akan setiap suara yang datang dari kegelapan.
Di sisi lain, malam terasa begitu dingin, angin gunung berembus perlahan menyapu dedaunan di sekitar rumah Pak Purrok. Ekot berdiri tegap di depan rumah, tombaknya menggantung di tangan, tajamnya berkilat di bawah sinar bulan. Udara malam yang biasanya ramai dengan suara serangga kini terasa sunyi, seolah alam pun tahu ada ketegangan yang melayang di udara.
Ekot tak bergerak, matanya menelusuri setiap sudut halaman, siap siaga. Di sekitarnya, teman-temannya. Nanjan dan Simpe juga dalam posisi siaga. Tak ada yang berbicara, hanya fokus pada tugas masing-masing.
Suara samar ranting yang patah di hutan dekat rumah membuat Simpei sedikit menegakkan tubuhnya. "Suara apa itu?" bisiknya pelan, matanya mencari-cari sumber suara.
Ekot hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tetap tenang. Ia tahu, di malam seperti ini, suara kecil bisa menipu pikiran yang sudah dipenuhi ketakutan. "Mungkin itu babi hutan," gumamnya pendek.
Namun, tak lama setelah itu, bayangan besar tampak bergerak cepat di antara pepohonan. Tapi ketika mendekati rumah, bayangan itu tiba-tiba berhenti. Bahkan binatang hutan pun tampak enggan melintasi batas di sekitar Ekot dan tombaknya. Entah mengapa, malam itu, bahkan seekor babi hutan yang kelaparan tak berani mendekat.
"Ini Aneh. Biasanya mereka tidak takut seperti itu," bisik Nanjan, melihat bagaimana bayangan itu kembali menghilang ke dalam hutan.
Ekot menajamkan matanya, tetap tidak tergoyahkan. "Mungkin malam ini mereka tahu siapa yang mereka hadapi," jawabnya dingin, menggenggam lebih erat tombaknya yang telah ia asah hingga seperti senjata dewa.
Simpei tertawa kecil, meski tawa itu lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada mengejek. "Kalau begitu, kita hanya perlu memastikan jika bukan hanya babi yang tak bernyali, tapi juga yang lainnya."
Semua kembali hening setelah itu. Ekot tetap berdiri tegak, seolah bisa menantang malam itu sendiri, tombaknya siap untuk menusuk apa pun yang berani melintasi ambang batas. Tapi yang lebih menakutkan dari bayangan hutan adalah kesunyian itu sendiri, yang terus menekan mereka seiring malam yang masih panjang berjalan tanpa kepastian.
Namun, satu hal yang pasti: selama Ekot berjaga, tak ada makhluk, manusia atau bukan yang bisa mendekati rumah Pak Purrok.
Malam semakin hening di kediaman Pak Labih, dan ketegangan yang melingkupi desa itu terasa kian mencekam. Rina yang tertidur di dalam kamarnya mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Kelopak matanya yang terpejam bergerak cepat, napasnya tersengal, seolah sedang mengalami mimpi buruk. Di sisi ranjang, Ibu Rina duduk dengan kepala hampir terkulai, berusaha melawan kantuk yang tak tertahankan, sementara tangannya masih menggenggam jemari putrinya.
Diubah oleh wedi 17-11-2024 14:16
itkgid dan 3 lainnya memberi reputasi
4
Kutip
Balas
Tutup