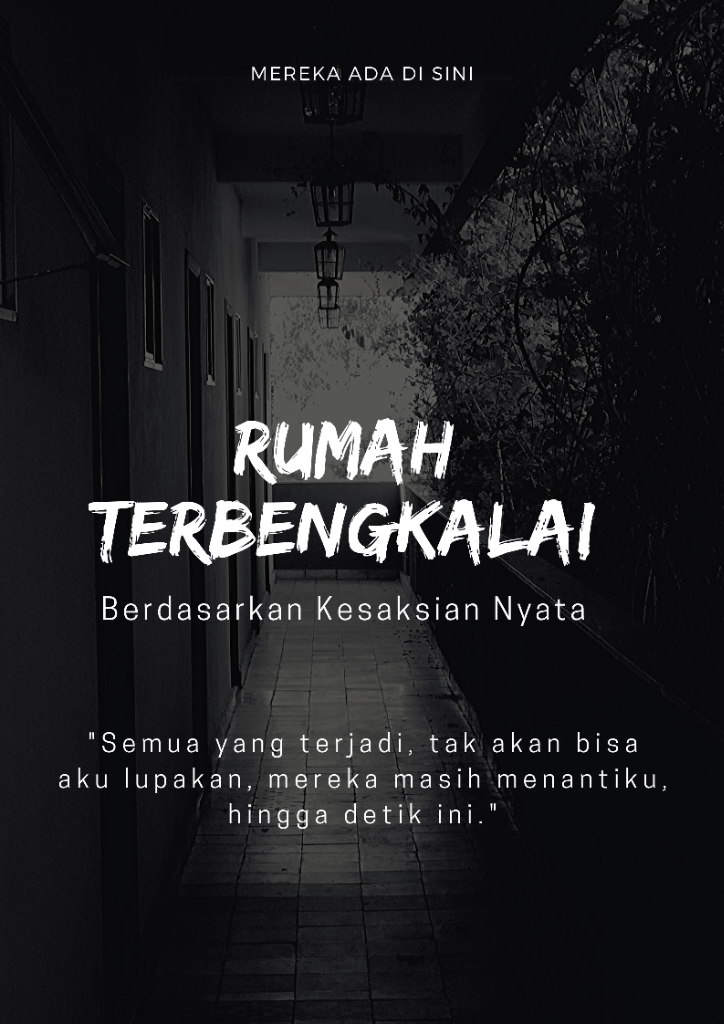Quote:
Setelah percakapan dengan Deni, aku berjalan keluar dari kamar menuju ruang utama. Ruangan itu terasa kosong, hanya diisi dengan beberapa kursi kayu dan meja. Cahaya siang yang menerobos melalui lubang-lubang di dinding semakin menegaskan kesan suram yang sudah melekat di tempat ini. Di kepalaku, berbagai pikiran berkecamuk—tentang Deni, tentang Andre, dan tentang bagaimana aku harus menjalankan rencana ini tanpa membuat Rifaldy curiga.
Aku tahu, mencari seseorang yang bahkan aku tidak pernah melihat atau mengenalnya bukanlah hal yang mudah. Mungkin akan memakan waktu yang lama, dan Rifaldy adalah tipe orang yang cepat curiga jika ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi Deni sudah memintaku untuk merahasiakan hal ini, dan aku tidak akan mengecewakannya.
Sambil berpikir, aku melangkah dengan hati-hati, keluar dari kamar. Suara burung di luar terasa kontras dengan suasana sunyi di dalam. Aku berhenti tepat di ambang pintu kamar, lalu menoleh ke halaman depan. Di kejauhan, aku bisa melihat sosok Rifaldy yang sedang berbicara dengan Mang Tohir di teras depan rumah. Mereka berdua tampak sibuk, seolah membicarakan sesuatu yang penting.
Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba mencari cara agar mereka tidak mencium gelagat aneh. Aku tidak bisa mendadak menghilang atau bersikap mencurigakan. Mereka sudah lama mengawasi segala gerak-gerikku di sini, terutama Rifaldy, yang selalu punya firasat kuat terhadap apapun.
Satu hal yang pasti: aku harus memainkan peran seolah tidak ada yang berubah.
Entah mengapa, aku masih merasa ada yang kurang dan masuk kembali ke kamar Deni. Matanya masih terpejam, namun ia tampak sedikit lebih tenang setelah mengutarakan rencananya. Aku duduk dekat tempat tidurnya dan berbicara dengan pelan, meski tahu ia mungkin setengah tertidur.
“Den, gue janji mulai nyari info soal Andre, tapi gue minta waktu. Ini gak bisa gue lakuin dalam sehari atau dua hari, gw harap lo bisa sedikit bersabar,” kataku. "Lo tau kan, Rifaldy itu peka banget sama gerak-gerik orang."
Deni membuka matanya perlahan, wajahnya masih terlihat lelah, namun ia tetap mendengarkan. “Makasih, Vin. Maaf, kalau gue ngerepotin, lu. Dan gue percaya lo bisa jaga rahasia ini.”
Aku mengangguk, meskipun di dalam hati sadar betapa sulitnya tugas ini. “Pertama. Gue harus cari cara biar Rifaldy gak banyak tanya, walau gw sering keluar.”
Deni mengangguk pelan, menatapku dengan penuh harap. “Hati-hati, Vin... Rumah ini... udah ngambil banyak dari kita. Jangan sampe lo juga kebawa.”
Aku tersenyum tipis, meski di dalam hati ada rasa cemas yang mulai mengakar. “Emang lo kenal di mana sama dia, Den?” Mengalihkan pembicaraan yang mulai membuatku merasa cemas.
"Gw ketemu dia, waktu pertama kali datang ke rumah ini... " Sorot matanya masih terlihat lemas dan tak bergairah. Ia menoleh lalu melanjutkan perkataannya, "kalau gak salah lo juga datang malam itu."
Aku mengernyitkan alis, mencoba masuk kedalam ingatan, hingga aku tersedar akan sosok samar yang bersama Bang Ferdy saat pertama kali aku ke rumah ini, "Ohhh.... Itu. Iya gw inget, Den! Waktu itu dia lagi duduk sama Bang Ferdy di depan." Deni tersenyum tipis, lalu mengganguk samar.
Sosok yang kulihat itu, berbadan cukup kekar, penampilannya pun tampak rapih, dan rambutnya ikal, dengan kulit coklat keputihan. Walau begitu, tetap saja aku tak pernah melihat Andre sebelumnya.
"Ya, udah. Lo istirahat, Den," ucapku, menerik selimutnya, "sabar, ya. Semoga ini cepat berlalu."
Aku pun meninggalkan kamar Deni dengan tekad bulat. Mencari seseorang tanpa jejak bukanlah hal yang mudah, tapi aku harus memulainya dari suatu tempat. Mungkin aku bisa mulai bertanya-tanya di sekitar, mencari informasi tentang keluarga yang dulu tinggal di rumah ini—tanpa membuat Rifaldy atau Bang Ferdy curiga. Mereka berdua sudah terlalu dalam terlibat dalam rumah aneh ini, dan jika sampai mereka tahu aku mencari Andre, semuanya bisa jadi lebih rumit.
Aku tahu perjalanan ini akan panjang, atau mungkin berbahaya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Demi sahabat baik-ku, aku harus tetap optimis.
Setelah keluar dari kamar, aku melangkah perlahan menuju ruang utama. Di sana, Rifaldy dan Mang Tohir masih terlibat dalam percakapan serius. Suasana di luar rumah loji terasa hangat, meski tembok-tembok dingin yang membalut bangunan itu tetap menyisakan aura kesunyian. Matahari bersinar cerah, tapi bayangan bangunan yang belum rampung membuat tempat ini terasa suram dan penuh kesedihan yang samar.
Ketika aku mendekat, Rifaldy tiba-tiba menghentikan pembicaraannya. Tatapannya terarah padaku, seolah mencari jawaban yang tersembunyi. “Ada apa, Vin?” tanyanya dengan nada yang tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya.
Aku merangkai kata-kata dengan hati-hati, berusaha agar tak memicu kecurigaan. “Oh, itu cuma nanya soal kejadian semalam,” jawabku, berusaha terdengar sesantai mungkin.
Mang Tohir yang duduk di sebelah Rifaldy hanya mengangguk kecil, ekspresinya datar tapi penuh pengertian.
Rifaldy menyipitkan matanya, seperti sedang menimbang jawabanku. Meski begitu, aku bisa menangkap kilatan kelembutan yang tak biasa di balik tatapannya. “Syukurlah kalau dia masih bisa diajak bicara,” ucapnya lirih.
Aku mengangguk cepat, meyakinkan. “Dia juga bilang 'cuma butuh waktu dan semua akan baik-baik aja', katanya.”
Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya Rifaldy tampak menerima penjelasanku. Ia mengangguk pelan, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang terlihat lelah. “Ya udah, kalau gitu.”
Aku menghela napas panjang, sedikit merasa lega, meski jauh di dalam hati, keresahan tetap menghantui. Sulit rasanya berpura-pura tenang di tengah situasi yang terus mencekam. Waktu terus bergulir, dan aku sadar pencarian yang sebenarnya belum dimulai.
Mataku beralih ke pintu kamar Deni. Di balik pintu itu, ia terbaring lemah. Dalam benakku, aku memikirkan alasan apa yang bisa kutawarkan agar Rifaldy memberiku izin untuk keluar dari rumah ini, tanpa memancing terlalu banyak pertanyaan.
“Rif,” panggilku dengan nada yang sengaja kubuat lebih serius, berharap dia akan langsung mengerti bahwa ada hal penting yang ingin kubicarakan. Rifaldy menoleh, tatapannya menyelidik.
"Udah beberapa minggu ini gw gak pulang ke rumah. Gw izin pulang dulu, bisa?” tanyaku, mencoba meyakinkannya.
Wajah Rifaldy tampak sedikit tegang. Ia menggigit bibir, tampak ragu. Jemarinya sesaat menggaruk alisnya, seakan gelisah mendengar permintaanku.
"Nanti gw balik lagi, kok. Paling sore," tambahku cepat, seolah ingin menenangkan pikirannya yang mungkin khawatir kalau aku tak akan kembali.
Rifaldy menarik napas panjang, lalu melepasnya perlahan. “Serius lu?” tanyanya dengan nada penuh penekanan. Aku mengangguk, menunjukkan keyakinan melalui ekspresi wajahku.
“Lebih baik sekarang, Mas, sebelum sore keburu datang,” saran Mang Tohir, nada bicaranya terdengar halus namun jelas ingin menyarankan agar aku benar-benar kembali.
Rifaldy merogoh saku celananya dan mengeluarkan kunci motor. “Nih,” katanya sambil menyodorkan kunci ke arahku. Tanpa ragu, aku meraihnya. "Kalau sampe lu gak balik, awas aja lu!” Ia mencoba terdengar galak, tapi senyum kecil di sudut bibirnya membuatnya terlihat sedang bercanda.
“Ya, udah. Gw cabut dulu, ya,” ucapku setelah kunci motor berpindah tangan.
Rifaldy mengangguk kecil, tapi raut wajahnya masih menunjukkan keseriusan. “Oke, hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, langsung telpon.”
Aku segera melangkah keluar, berusaha menenangkan kegelisahan yang terus menyelimuti hati. Sesampainya di luar, angin sepoi-sepoi menyambut wajahku. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk memulai pencarianku. Harapanku kini tertuju pada satu hal: semoga semuanya berjalan sesuai rencana.
Aku menyalakan motor, memutar gas perlahan, membiarkan mesin tua ini bergemuruh. Suara berat dari mesinnya seakan menyatu dengan keheningan alam di sekitarku, menciptakan harmoni yang ganjil. Di tengah suara deru motor, ada perasaan asing yang menyusup, sesuatu yang tak bisa kujelaskan.
Jalan di depan rumah loji berdebu, meliuk di antara pepohonan tua yang menjulang, ranting-rantingnya seolah membentuk gerbang alami yang menyeramkan. Tiap kali aku melewati tempat ini, ada getaran aneh yang merayap di punggungku, membuat bulu kuduk berdiri. Rumah itu seperti diselubungi sesuatu yang tak kasat mata, aura berat dan menekan, seolah menantang siapa saja yang berani mendekat. Aku sendiri tak pernah bisa lepas dari sensasi ganjil itu.
Motor mulai melaju, namun pikiranku tak pernah benar-benar fokus. Aku berkecamuk, mencoba menyusun rencana untuk menemukan seseorang bernama Andre. Mungkin saja akan lebih mudah jika aku bertanya langsung pada Bang Ferdy. Namun, rasanya seperti berhadapan dengan tembok besar—tak mungkin aku lakukan itu.
Setibanya di pinggir kota, laju motorku melambat dengan sendirinya, bersamaan dengan pikiranku yang mulai melayang tak tentu arah. Aku tak tahu harus kemana, tak ada petunjuk pasti dalam pencarian ini. Hanya jalan panjang yang kosong, menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab.
Lalu, pandanganku tertumbuk pada sebuah warung kecil di pinggir jalan. Di sana, seorang pria paruh baya tampak sibuk, merapikan botol-botol minuman di rak kayunya yang tua dan reyot. Mungkin dia bisa memberiku sedikit petunjuk, pikirku. Aku mengarahkan motor ke arahnya, berhenti tepat di sisi warung, dan menurunkan standar.
"Pak," sapaku dengan nada yang kugunakan agar tidak mengganggunya terlalu banyak. Pria paruh baya itu menoleh, alisnya sedikit terangkat, lalu menghentikan gerakannya.
“Ya, ada apa, Jang?” jawabnya, suaranya ramah, namun tubuhnya sedikit menegang, menandakan kewaspadaan.
"Saya mau numpang tanya, Pak," ucapku, mencoba tetap tenang.
Tatapan pria itu tenang, meski bibirnya mengerucut, seolah mencoba menebak apa yang akan kutanyakan. "Tanya apa, Jang?"
"Abah sudah lama jualan di sini?" tanyaku, membuka pembicaraan dengan cara yang halus.
"Lumayan," jawabnya. Kerut di dahinya mengisyaratkan bahwa ia sedang menimbang-nimbang sesuatu.
"Bapak tahu rumah di dekat Loji, rumah besar yang agak tersembunyi di balik pohon-pohon besar itu?" tanyaku, mencoba menggali informasi.
Pria itu terdiam sejenak, matanya berkedip perlahan seolah menelusuri ingatan. "Rumah mana, Jang?" jawabnya dengan ekspresi bingung, mencoba mengingat.
Aku menjelaskan lebih detail, mulai dari letaknya hingga bentuk rumah besar yang kusaksikan di samping rumah loji. Namun meski sudah kujabarkan dengan jelas, pria paruh baya itu tetap tak tahu apa-apa soal rumah tersebut.
"Abah kurang hapal, Jang. Memangnya kenapa, ada apa?" tanyanya lagi, kali ini suaranya sedikit ragu, seolah tak yakin apakah ia harus ikut campur.
Aku tersenyum tipis, meski sedikit kecewa. "Nggak, Pak. Saya cuma lagi nyari pemilik rumah itu," jawabku singkat. "Terima kasih, Pak." Aku mengangguk sopan, lalu menyalakan motor lagi, meninggalkan warung kecil itu.
Perjalanan kembali kulanjutkan, namun rasa frustrasi mulai merayapi benakku. Setiap warung yang kusinggahi, setiap orang yang kutanya, tak satu pun yang tahu tentang Andre, bahkan rumah loji yang begitu mencolok itu seolah tak pernah ada di ingatan mereka. Aneh. Sangat aneh.
Langit mulai meredup, semburat merah di ufuk barat semakin memudar. Aku sadar, perjalananku sudah terlalu jauh dan malam sebentar lagi tiba. Tampaknya, tak ada pilihan lain selain kembali ke rumah loji dengan tangan kosong. Pikiranku semakin gelisah, dan misteri ini semakin dalam menenggelamkanku.
Perasaan cemas dan penuh keraguan mulai merajai diriku. Jantungku berdegup kencang, seperti detak mesin tua yang sedang kupacu. Aku melaju lebih cepat, tak ingin terjebak di jalan sunyi ini ketika malam menutup langit. Beberapa menit berlalu, dan dari kejauhan, rumah loji itu mulai nampak—menjulang di tengah pepohonan liar yang tak terawat, bayangannya menyeruak di antara kegelapan yang perlahan mengintai.
Motor mulai melambat, meski pikiranku justru melaju cepat, dipenuhi oleh kilasan berbagai pikiran yang berputar-putar tanpa arah. Mataku menatap tajam ke arah sebuah rumah yang berdiri tepat di samping rumah Bang Ferdy. Rumah itu, berwarna putih dengan dua lantai dan sebuah balkon sedang tepat di atas pintu utamanya. Pekarangannya luas, penuh dengan pohon-pohon rindang yang menghalangi pandangan. Meski sering kulihat rumah ini dari kejauhan, selama berada di loji, tak sekali pun aku melihat penghuni atau tamu yang datang ke sana. Rasanya aneh, seperti rumah itu ada namun tidak ada.
“Mas!” Suara lantang membuatku terkesiap. Itu Mang Tohir, berdiri di ambang pintu loji, tampak melambaikan tangan. Sepertinya suara motor tua ini menarik perhatiannya. “Saya kira nggak balik lagi,” ucapnya sambil tersenyum kecil, raut wajahnya sedikit lega.
“Pulang, Mang,” jawabku singkat, menurunkan standar motor dengan tangan yang terasa berat. Pikiran-pikiranku masih berputar-putar, tak ada satu pun yang benar-benar jelas di kepalaku. Mulai dari kondisi Deni, sosok Andre yang misterius, hingga alasan apa yang harus kuberikan besok agar Rifaldy tidak mencurigai gerak-gerikku.
“Kusut amat, Vin,” suara Rifaldy tiba-tiba memotong lamunanku. Ia tampak memperhatikanku dengan mata yang sedikit curiga. “Lu pulang? Kenapa nggak sekalian ganti baju?"
Aku tercekat, lidahku kelu mencari alasan yang masuk akal. “I-itu… eh…” jawabku terbata-bata, otakku memutar cepat untuk menemukan jawaban yang tidak mencurigakan. “Gw… nggak jadi pulang, Rif. Lu tahu, kan? Rumah gw jadi tempat kumpul saudara-saudara nyokap… Jadi… ya, males buat masuk rumah. Mungkin besok aja, Rif.”
Rifaldy menyeringai, matanya menyipit seakan menilai alasan yang kuberikan. “Vin… Kevin… aneh! Sebegitunya lu ngga suka sama ibu-ibu?” ucapnya dengan tawa kecil, nada suaranya sedikit bercanda. Aku menghela napas lega. Setidaknya ia menerima alasanku dengan baik.
Aku bersyukur, banyak orang yang sudah terbiasa dengan kebiasaanku yang tak menyukai keramaian. Mereka mungkin menganggap aku pemalu, dan walaupun kadang itu jadi bahan olokan, kali ini kebiasaan itu menyelamatkanku dari situasi sulit.
“Oh ya, kondisi Deni gimana, Rif?” tanyaku, berusaha mengalihkan perhatian. Seketika senyum di wajah Rifaldy menghilang, tatapannya berubah serius. Mang Tohir yang berada di dekatnya hanya diam, raut wajahnya mendadak murung seolah ada beban berat yang tak ingin mereka bahas.
Dari perubahan ekspresi mereka, aku sudah tahu jawaban yang menunggu. Namun, aku tak bisa menahan diriku untuk tetap melangkah menuju kamar Deni. Tanganku hampir menyentuh gagang pintu ketika suara menggeram keras terdengar dari balik pintu, disertai ucapan tak jelas yang menyeramkan. Suara itu menghentikan langkahku, memaksaku menarik tangan yang hendak membuka pintu. Jantungku berdegup cepat, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisku.
"Maaf, Den... Hari ini aku pulang tanpa hasil," bisikku dalam hati. Penyesalan menghantamku seperti ombak yang menghantam karang, membuatku merasa tak berdaya, seperti pecundang yang tak mampu membantu apa-apa.
“Udah gw kasih obat,” suara Rifaldy terdengar pelan namun tegas dari belakangku. Ia menepuk pundakku lembut, seolah mencoba menenangkanku. “Tapi kayaknya nggak ngaruh apa-apa.”
Aku menghela napas panjang, berat. Tatapanku jatuh ke lantai, seolah mencari jawaban yang mungkin tak akan pernah kudapat. Harapan yang ada terasa kian memudar, digerus oleh situasi yang tak kunjung membaik.