- Beranda
- Stories from the Heart
RODEO (18++)
...
TS
mikamaesla
RODEO (18++)
Welcome!
Sebelumnya saya permisi dulu kepada Moderator dan Penghuni forum Stories From The Heart Kaskus
Saya lagi mencoba untuk menulis sebua novel, dan berharap bisa menghibur forum ini. Maaf kalau banyak salah, karena saya masih newbie.
Selain terinspirasi oleh para cerita suhu dan sesepuh, mohon minta dukungan dan masukannya.
kondisi Novel masih raw dan ongoing.

Saya lagi mencoba untuk menulis sebua novel, dan berharap bisa menghibur forum ini. Maaf kalau banyak salah, karena saya masih newbie.
Selain terinspirasi oleh para cerita suhu dan sesepuh, mohon minta dukungan dan masukannya.
kondisi Novel masih raw dan ongoing.
Genre: Drama, Crime, Romance (18+)
Update diusahakan setiap tiga hari.
Dimohon untuk tidak kopas.
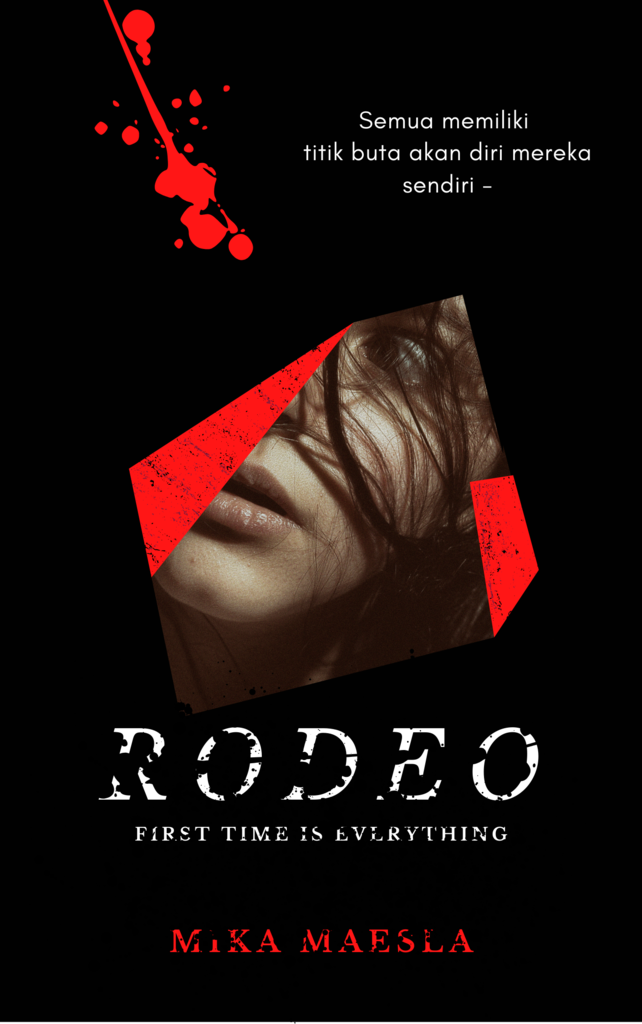
Spoiler for INDEX:
Spoiler for Yang suka Pake Watty:
Spoiler for Epilog 1:
Diubah oleh mikamaesla 15-12-2020 10:35
mdn92 dan 13 lainnya memberi reputasi
14
8.7K
23
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.7KThread•51.8KAnggota
Tampilkan semua post
TS
mikamaesla
#7
Ereksi
Sabila pasti tidak mempunyai pilihan lain selain menemuiku malam ini.
Walaupun, sebetulnya bukan dia yang aku harapkan. Aku menunggu pesan dari Indira. Aku hanya ingin menanyakan kabarnya dan mengklarifikasi masalah semalam. Harusnya aku tidak perlu mempertimbangkan apa yang sudah terjadi, biarkan seperti apa semestinya. Sudah dua puluh menit kami tidak mengeluarkan sepatah katapun setelah berbasa-basi menanyakan kabar, dan hanya memandangi orang-orang yang sedang menikmati malam di Taman Sempur. Aku dan Sabila menaiki undakan paling tinggi karena itu area yang paling sepi. Tapi tidak lama kemudian sepasang kekasih ikut naik, pindah dari tempat duduknya di bawah ke—tidak jauh, sebelah kami. Mereka membawa jajanan anak-anak yang di beli di area kaki lima.
“Kamu sudah makan?” pertanyaan biasa di saat pria tidak punya topik.
Sabila menggeleng. “Belum, tapi tidak nafsu.”
“Temen kamu siapa aja yang sudah keluar?”
“Banyak beberapa, sebagian ada yang kangen sama kamu.” dan kamu juga.
Aku memandang wajahnya yang menatap jauh ke arah lapangan dimana orang-orang masih ada yang berolahraga di jam malam, ada yang bilang itu lebih efektif dibandingkan pagi hari. Masing-masing ada keuntungannya sendiri. Dia memeluk kakinya.
“Kamu baik, kata mereka. Tidak seperti manajer yang sekarang, tidak jelas dan hanya mencari muka.”
“Aku tidak baik.” Dan itu jujur.
“Mereka yang mengatakannya, bukan aku.”
“Jadi kamu tidak menganggapku baik?”
Sabila menatapku. “Tergantung.”
“Oh, begitu. Ya sudah.”
“Ih, bercanda.” dia mengadukan pundaknya ke pundak ku.
“Bagus, hampir saja aku ingin mendorongmu ke bawah sini.” Sambil menunjuk bawah undakan.
“Kejam sekali, nanti aku terguling sampai ke bawah.”
Yep, that’s right. Dan aku mau tahu apakah kau akan selamat atau tidak.
“Jadi pulang naik apa?”
“Belum tahu, dan sepertinya angkot jam segini sudah tidak ada.”
“Kenapa tidak naik motor.”
Dia menjawab sambil mengangkat bahunya, “sedang di bengkel.”
Kita tahu kalau itu bohong.Angkot ke arah Gadog jam sepuluh baru mereka menghentikan aktivitasnya. Aku berdiri, menepuk bokongku yang kotor karena duduk di tanah, “ya sudah, menginap di tempatku saja.”
Sabila menampilkan giginya yang rata dan mengikutiku bangkit ke arah parkiran. Sepasang kekasih yang duduk di sebelah kami bangkit dan pindah ke tempat dimana kami duduk, memang areanya gelap, persis di bawah pohon, dan aktivitas apapun di sana akan terlihat samar.
Aku membawa Sabila ke Cafeku, dia terlihat terpukau dengan banyaknya buku yang aku jejerkan di rak menempel di sekeliling ruangan, di atas kursi pelanggan, dia menarik satu, membukanya dan menaruhnya kembali.
“Konsepnya sederhana: orang datang ke sini selain mereka menikmati kopi tapi mereka juga bisa membaca santai ditemani lagu-lagu melankolis.”
Aku sedikit kecewa dengan para pelanggan sebetulnya, karena mereka jarang sekali menarik salah satu buku dan membacanya. Mereka selalu kembali pada hp mereka masing-masing.
“Semuanya punya kamu?”
“Begitu lah.”
“Pantas dulu kamu sering bawa-bawa buku yang berbeda-beda kalau kerja, ternyata banyak koleksinya, ya.”
“Masih kurang, sih menurutku.”
“Yang mana favorit kamu?”
Aku melangkah mendekat, menarik salah satu buku dan menyerahkannya. Dia mengernyitkan alisnya.
“Ini Bahasa Inggris.”
“Ya, dan itu karya terbaik.” Sabila diam dan aku melanjutkan, “Ceritanya tentang seseorang yang terobsesi dengan lukisan yang menampilkan cerminannya sendiri. Karya Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray.” Aku tahu dia tidak mengerti apa yang aku bicarakan, karena aku tahu dalam hidupnya dia belum pernah membaca dan menghabiskan satu buku pun. Aku hanya ingin mengesankannya, dan itu berhasil ketika dia menjulurkan jarinya untuk menyibakkan rambut depanku yang terjuntai di dahi. Tapi dia berhenti dan duduk di salah satu sofa, menghela nafasnya.
“Aku mau minta maaf.”
Ok, ini tidak seperti biasanya, dia seharusnya memulai dan kenapa berhenti.
“Untuk apa?”
“Aku tidak seharusnya menghubungimu lagi. Aku menemui Irvan setelah waktu itu.”
Aku hanya diam mendengarkan.
“Dia tahu aku berhubungan denganmu, dan ingin sekali menemuimu.”
“Bagaimana bisa?”
“Mungkin Feri. Dia tidak merasa puas sebelum aku menderita.”
Seandainya dia tahu.
“Aku khawatir waktu itu. Dia sangat memaksa ingin bertemu denganmu.”
“Apa yang dia mau?” Aku mendekat perlahan, dia menyelipkan rambut panjangnya ke telinga, dan sekarang aku dapat melihat lehernya yang jenjang.
“Dia hanya ingin berbicara dan mau menyerahkanku sepenuhnya padamu, dan menjagaku.”
Roman picisan, Irvan pikir ini Sinetron. Dia juga memaksaku untuk menemuinya dan menjadi seperti teror di facebook, padahal aku bilang Feri adalah biangnya. Entah berapa lama dia menunggu di taman waktu itu.
Sabila melanjutkan, “dan aku menyesal. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu.”
Yes! Itu yang aku mau: penyesalan. Dia menutup wajahnya dengan telapak tangan, siku bersandar di kakinya. Tolong jangan menangis karena aku sedang berpikir haruskah aku akhiri sampai di sini atau kita bawa permainan ini ke tahap berikutnya.
Aku mendekatinya, berjongkok dan menarik telapak tangan itu. Oh dia tidak menangis, dan matanya tidak berkaca-kaca, wajahnya merona.
“Kamu pasti sangat membenciku?”
Aku hanya terdiam, menyisir rambutnya dengan kedua tanganku, —aku tidak hanya membencinya tapi membenci semua wanita yang tidak bisa menempatkan dirinya lalu aku menarik wajahnya menempelkan bibirku ke bibirnya dengan lembut. Dia menarik wajahnya perlahan, memandang mataku dengan dalam, dan dia sekarang yang menarik wajahku. Dia menungguku memulai.
Aku mendorong tubuhku sehingga dia merebahkan dirinya di sofa, bibir kami tidak terlepas, tanganku membelai payudaranya, dia mendesah, mengangkat pinggulnya kemudian dia menahan pundakku saat kami mendengar suara motor yang lewat.
Ok, aku lupa kalau kafeku tidak menggunakan tirai yang hampir semua dindingnya jendela, dan orang yang lewat pasti akan memergoki kami. Tapi bukankah itu tantangannya. Aku mendekatkan lagi wajahku, dan dia menyambutnya tapi tangannya tetap menahan.
Dia menoleh ke arah jendela, kemudian bangkit, payudaranya sudah hampir menyembul keluar. Aku bangun, menarik tangannya dan membawa tasnya ikut bersama kami. Di pojok ada kamar khusus untuk istirahat lengkap dengan ranjang. Aku mematikan lampu tengah, sambil menggiring Sabila. Menutup pintu kamar dan melanjutkan pergumulan. Dia mendorongku jatuh ke ranjang, membuka high heelsnya kemudian melompat menindihku, dia menciumi leherku, nafasnya cepat, dan membuas, membantuku melepaskan kaosku dan aku membantunya melepaskan kemejanya, tidak biasanya dia memakai rok panjang, bokongnya menggesek kejantananku, aku melepas kutangnya dan langsung meraih putingnya yang sudah mengeras, dia memejamkan matanya.
“Tunggu sebentar.” Hp di kantong celanaku bergetar, aku memeriksanya dan itu pesan dari Indira, aku tidak memahami maksudnya karena dia hanya mengirimkan emoji acungan jempol. Apa dia tidak membaca pesanku? Aku ingin segera membalasnya tapi Sabila menarik hp itu dan melemparkannya ke meja, dia mulai menggerayangiku, mencium dari kuping, turun ke bibir, ke leher, ke dada, dan dia membuka ikat pinggangku. Dan mulai mengulum kejantananku, aku hanya menatap langit-langit memikirkan apa yang dimaksud Indira.
Sabila berhenti, aku melihat kebawah, kekecewaan terlihat di wajahnya. Oh, fuck!
Dia bangkit duduk, “kenapa?”
“Huh, apa?”
Dia merayap ke atas, payudaranya menempel di dadaku dengan tangan tetap mengelus di bawah, aku meraih wajahnya, tapi sepertinya tidak berhasil. Dia menyerah bangkit dan memakai kutangnya dan kemejanya sambil menatapku tersenyum. “Tidak apa-apa.”
Ini bukan masalah tidak apa-apa—libidoku dan begini ternyata rasanya disaat ada wanita tanpa busana dan menggerayangimu tapi kau tidak bisa ereksi, tapi memang sepertinya kita harus berhenti sampai di sini. Aku tidak seharusnya melanjutkan ini, dan aku sudah cukup memberikannya hukuman. Dan saatnya aku harus mengatakan yang sejujurnya.
“Sabila,” kataku lembut, “hubungan kita berakhir sampai disini. Jangan pernah datang lagi, atau menghubungi aku lagi.”
Dia membelalakan matanya, “maksud kamu?”
“Kamu tahu maksud aku?”
“Lalu apa yang baru saja kita lakukan?”
“Kita belum melakukan apa apa.”
“Selama ini?”
“Bukan itu maksudku. Malam ini. Dan ini yang terakhir.”
Matanya melotot, dia bergerak mondar mandir, lalu menarik rambutnya.
“Kamu bajingan, Niko!”
I deserve that.
Aku mengambil tasnya dan sepatunya, dia duduk di pinggir ranjang, menunduk.
“Aku pikir kamu cinta sama aku.”
“Tidak ada yang namanya cinta.” (yang aku tahu kamu bekerja sebagai bawahanku, dan di saat kita bersama tidak ada hal-hal romantis yang terjadi, hanya makan-sex-tidur, dan itu tidak bisa dibilang cinta. Aku tidak merasakannya apa yang orang bilang: getaran.)
Dia mengangkat wajahnya seolah-olah ingin melempar sesuatu ke arah wajahku yang datar. Fuck, Indira. Ok, dan kenapa harus Indira.
“Semua lelaki sama saja!”
Dia tidak melemparkan sesuatu tapi kata-katanya menampar keras ke wajahku.
“Maksud kamu apa?”
“Lelaki maunya hanya baik!” dia menarik tasnya dari tanganku. Dan kali ini aku yang naik pitam, aku harusnya bisa mengontrol emosiku, dia hanya memancing.
“Yang lucunya dari mereka gak ada yang bisa memuaskan aku.”
Ok, apakah aku bagian dari “mereka”.
“Sabila, aku tahu aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu, tapi ini semua ulahmu sendiri.”
Kali ini aku kata-kataku yang menamparnya. “Siapa yang memulai? Dan siapa yang menyuruhku naik ke ranjang bersamamu?”
“Tapi kau mendekatiku, kau mengajakku- Sudah lah.”
“Harusnya kamu bersyukur Irvan sudah memaafkanmu, tapi kamu malah bermain dengan Feri.”
Apa yang aku pikirkan, shit! Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Sekarang pandangan Sabila lebih tajam daripada pisau. Dan aku sadar sudah keceplosan.
“Apa maksudmu? Ada apa dengan Feri?”
Aku bangkit dari ranjang dan mencoba meraih tangannya, dia menepis.
“Apa yang dikatakan Feri?”
Kau sudah bertunangan, segera menikah tapi malah main hati dengan pria lain. Dan aku menyampaikannya pada Irvan bukan Feri; dia hanya kambing hitam. Aku tidak bisa menjawabnya.
“Ya, Tuhan! Kau yang bicara dengan Feri. Kau orang tengah yang mengacaukan semuanya. That is right, but.
“Pelankan suaramu, biarkan aku menjelaskannya”—sebetulnya tidak perlu, aku paham apa yang aku perbuat.
“Kau Iblis,” cetusnya.
Aku mendekatinya, “aku tidak bermaksud-”
“Jangan mendekat!” suaranya terlalu tinggi.
Darahku ikut naik, aku harus menarik nafas panjang. “Ok, Bila, tolong pulang sekarang juga.”
“Atau apa?” dia bangkit mendekatiku. Dan aku harus menjaga emosiku, kau bisa.
“Atau apa?” dia mendorongku, aku mendekat ke arah pintu, membukanya, dia mengayunkan tasnya ke arah tanganku, dan aku menghindarinya cepat.
“Sabila, Cukup!” suaraku meninggi. “Tolong jangan buat keributan. Atau kalau kamu mau bicara bersikap dengan tenang.” aku menatapnya tajam, dia sempat terdiam tapi sepertinya pikirannya semakin kacau. Dan apa yang seharusnya pria lakukan di dalam kondisi ini? Memeluknya? Tapi dia terus mendorongku.
“Biarkan! Biarkan semua orang tau kalau aku pramuria dan kau salah-satu orang yang menikmatinya!” aku mundur, dia tetap mendorongku.
“Jadi selama ini kamu hanya memanfaatkanku, bagaimana rasanya? Enak?! ‘Oh, Sabila lemah, dan dia sedang kacau jadi bagaimana kalau aku pakai saja dia?!’”
Caught red-handed.
Kafeku ada ditengah jalan dan di kota, mustahil orang tidak lalu-lalang walau sudah malam. Aku harus menenangkannya. Aku meraih pundaknya.
Dia menepis dan tidak sengaja tangannya menamparku, aku kaget dan secara spontan aku menarik pundaknya dengan sebelah tangan dan mengayunkan tanganku satu lagi ke wajahnya, dia terpelanting dan aku mendengar suara benturan di ujung ranjang, aku tidak sengaja, dia mengejutkanku, dan, -is that...? Goddamnit!
Aku berjongkok mengecek kepalanya, dia pingsan, aku masih bisa merasakan nafasnya. Aku merasakan ruangan menjadi sangat panas, ini tidak seharusnya terjadi jika saja dia mau menurut dan pergi.
Sekarang apa yang harus aku lakukan?
Membawanya ke dokter, apa yang akan dikatakannya nanti, dan Indira, oh, kau mengacaukan ini, bukan aku yang mengacaukannya, dan sekarang aku sedang panik, aku harus menarik nafas atau aku yang nantinya malah pingsan. Jam berapa sekarang, mana handphoneku.
Jam dua belas. Cepat sekali waktu berjalan.
Aku harus tetap tenang, dia masih bernapas dan aku hanya perlu menunggunya ba-
Sabila terjaga, dia menggumam pelan, “Niko.”
“Hey, maaf aku...”
Dia bangun dengan cepat, bergerak mundur menyeret pantatnya, punggungnya menabrak ranjang, dan tetap mundur sampai menempel ke tembok, darah di lantai tersapu dan membekas panjang, juga ada di ujung sprei dekat besi dimana kepalanya terbentur. Aku mendekat.
“Jangan mendekat, Niko.” suaranya kini tidak kencang tapi bergetar, aku tahu dia mengalami syok atau mungkin trauma, sambil menempel pada dinding.
Aku memberinya isyarat dengan menunjuk kepalaku, dia menyentuh lukanya dan kesakitan sendiri, air mata mengalir di pipinya tapi tidak ada isakan, aku mendekatinya, dan dia kaget, terbata-bata, berusaha memeluk tembok. Aku berhenti.
“Sabila, biarkan aku menolongmu, kamu terluka.”
“Jangan mendekat.’
“Kamu yang me-”
Dia menjerit, ujung jeritannya mengecil, kemudian tersedu sedan, darah di tangannya mengotori tembok.
“Tolong, Niko.” suaranya menjadi serak, aku tidak tahu kalau itu bisa berubah apalagi karena tangis yang ditahan bercampur dengan rasa takut.
Aku berjongkok, mendekat perlahan, aku mengulurkan tanganku, dan ditepis ketika hampir menyentuhnya, dia melompat ke belakang, membenturkan kepalanya sendiri, memberontak berusaha kabur. Entah lucu atau iba, aku tidak melakukan apa-apa aku hanya ingin menolongnya, dia berusaha melewatiku sambil merangkak, aku menarik pundaknya, dia menepisnya, berusaha meraih gagang pintu, berusaha berdiri tapi tidak mampu, kemudian menyerah, membalikkan badan, mata terpejam, menjerit tanpa suara, dan mulai tenang.
Huft!
Dia hanya duduk dalam diam, memeluk kakinya, badannya bergetar, rambutnya berantakan, kancing kemejanya belum rapih. Aku juga diam, belum bisa bertindak atau berbicara. Menunggu adalah hal yang baik, terutama untuk membuatnya merasa aman.
Manis terasa di lidahku, ternyata tamparannya membekaskan luka. Dan ini terjadi hanya karena kemaluan yang tidak mau ereksi?
Nafasnya yang terengah-engah sudah mulai normal, sepertinya saatnya aku mendekatinya, tubuhku mulai kedingingan, hari semakin larut sepertinya. Aku merapikan sepatu dan tasnya, kemudian aku mencoba untuk meraih Sabila mengajaknya untuk naik keranjang beristirahat, dia pasti lelah dan sangat syok, tubuhnya bergetar, aku menyibakkan rambutnya dan melihat ke area yang terluka.
Tapi dorongan cepat tangannya membuatku terpental jatuh kebelakang, dia berdiri, mengambil tas dan sepatunya, membuka pintu dan berlari.
“TOLONG!”
Suaranya sudah kembali normal. Sial. Kepala berdarah, bajunya berantakan. Sabila! Maksudnya apa?
Aku harus bangkit dan mengejarnya cepat.
Aku meraih pundaknya dia memukulku dengan tasnya, aku sudah siap dengan itu, sepertinya aku harus memeluknya, aku berhasil, tapi dia mengadukan kepalanya ke belakang membentur hidungku dengan keras, efeknya membuatku seperti melihat sinar Matahari secara langsung.
“Sabila!”
Dan Tuhan sedang menikmati sekali momen pengejaran ini, oleh karenanya dia menyediakan air di lantai dan membuatku terpeleset ke depan, aku berhasil menahan kepalaku agar tidak membentur, aku melihat sabila menengok, dan kembali berusaha ke ruangan depan sambil masih tetap berteriak, kemana orang-orang. Aku bisa dikeroyok oleh mereka karena salah paham. Aku merangkak, dan ketika Sabila hampir sampai ke ruangan depan aku melompat kodok, menarik kakinya.
Walaupun, sebetulnya bukan dia yang aku harapkan. Aku menunggu pesan dari Indira. Aku hanya ingin menanyakan kabarnya dan mengklarifikasi masalah semalam. Harusnya aku tidak perlu mempertimbangkan apa yang sudah terjadi, biarkan seperti apa semestinya. Sudah dua puluh menit kami tidak mengeluarkan sepatah katapun setelah berbasa-basi menanyakan kabar, dan hanya memandangi orang-orang yang sedang menikmati malam di Taman Sempur. Aku dan Sabila menaiki undakan paling tinggi karena itu area yang paling sepi. Tapi tidak lama kemudian sepasang kekasih ikut naik, pindah dari tempat duduknya di bawah ke—tidak jauh, sebelah kami. Mereka membawa jajanan anak-anak yang di beli di area kaki lima.
“Kamu sudah makan?” pertanyaan biasa di saat pria tidak punya topik.
Sabila menggeleng. “Belum, tapi tidak nafsu.”
“Temen kamu siapa aja yang sudah keluar?”
“Banyak beberapa, sebagian ada yang kangen sama kamu.” dan kamu juga.
Aku memandang wajahnya yang menatap jauh ke arah lapangan dimana orang-orang masih ada yang berolahraga di jam malam, ada yang bilang itu lebih efektif dibandingkan pagi hari. Masing-masing ada keuntungannya sendiri. Dia memeluk kakinya.
“Kamu baik, kata mereka. Tidak seperti manajer yang sekarang, tidak jelas dan hanya mencari muka.”
“Aku tidak baik.” Dan itu jujur.
“Mereka yang mengatakannya, bukan aku.”
“Jadi kamu tidak menganggapku baik?”
Sabila menatapku. “Tergantung.”
“Oh, begitu. Ya sudah.”
“Ih, bercanda.” dia mengadukan pundaknya ke pundak ku.
“Bagus, hampir saja aku ingin mendorongmu ke bawah sini.” Sambil menunjuk bawah undakan.
“Kejam sekali, nanti aku terguling sampai ke bawah.”
Yep, that’s right. Dan aku mau tahu apakah kau akan selamat atau tidak.
“Jadi pulang naik apa?”
“Belum tahu, dan sepertinya angkot jam segini sudah tidak ada.”
“Kenapa tidak naik motor.”
Dia menjawab sambil mengangkat bahunya, “sedang di bengkel.”
Kita tahu kalau itu bohong.Angkot ke arah Gadog jam sepuluh baru mereka menghentikan aktivitasnya. Aku berdiri, menepuk bokongku yang kotor karena duduk di tanah, “ya sudah, menginap di tempatku saja.”
Sabila menampilkan giginya yang rata dan mengikutiku bangkit ke arah parkiran. Sepasang kekasih yang duduk di sebelah kami bangkit dan pindah ke tempat dimana kami duduk, memang areanya gelap, persis di bawah pohon, dan aktivitas apapun di sana akan terlihat samar.
Aku membawa Sabila ke Cafeku, dia terlihat terpukau dengan banyaknya buku yang aku jejerkan di rak menempel di sekeliling ruangan, di atas kursi pelanggan, dia menarik satu, membukanya dan menaruhnya kembali.
“Konsepnya sederhana: orang datang ke sini selain mereka menikmati kopi tapi mereka juga bisa membaca santai ditemani lagu-lagu melankolis.”
Aku sedikit kecewa dengan para pelanggan sebetulnya, karena mereka jarang sekali menarik salah satu buku dan membacanya. Mereka selalu kembali pada hp mereka masing-masing.
“Semuanya punya kamu?”
“Begitu lah.”
“Pantas dulu kamu sering bawa-bawa buku yang berbeda-beda kalau kerja, ternyata banyak koleksinya, ya.”
“Masih kurang, sih menurutku.”
“Yang mana favorit kamu?”
Aku melangkah mendekat, menarik salah satu buku dan menyerahkannya. Dia mengernyitkan alisnya.
“Ini Bahasa Inggris.”
“Ya, dan itu karya terbaik.” Sabila diam dan aku melanjutkan, “Ceritanya tentang seseorang yang terobsesi dengan lukisan yang menampilkan cerminannya sendiri. Karya Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray.” Aku tahu dia tidak mengerti apa yang aku bicarakan, karena aku tahu dalam hidupnya dia belum pernah membaca dan menghabiskan satu buku pun. Aku hanya ingin mengesankannya, dan itu berhasil ketika dia menjulurkan jarinya untuk menyibakkan rambut depanku yang terjuntai di dahi. Tapi dia berhenti dan duduk di salah satu sofa, menghela nafasnya.
“Aku mau minta maaf.”
Ok, ini tidak seperti biasanya, dia seharusnya memulai dan kenapa berhenti.
“Untuk apa?”
“Aku tidak seharusnya menghubungimu lagi. Aku menemui Irvan setelah waktu itu.”
Aku hanya diam mendengarkan.
“Dia tahu aku berhubungan denganmu, dan ingin sekali menemuimu.”
“Bagaimana bisa?”
“Mungkin Feri. Dia tidak merasa puas sebelum aku menderita.”
Seandainya dia tahu.
“Aku khawatir waktu itu. Dia sangat memaksa ingin bertemu denganmu.”
“Apa yang dia mau?” Aku mendekat perlahan, dia menyelipkan rambut panjangnya ke telinga, dan sekarang aku dapat melihat lehernya yang jenjang.
“Dia hanya ingin berbicara dan mau menyerahkanku sepenuhnya padamu, dan menjagaku.”
Roman picisan, Irvan pikir ini Sinetron. Dia juga memaksaku untuk menemuinya dan menjadi seperti teror di facebook, padahal aku bilang Feri adalah biangnya. Entah berapa lama dia menunggu di taman waktu itu.
Sabila melanjutkan, “dan aku menyesal. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu.”
Yes! Itu yang aku mau: penyesalan. Dia menutup wajahnya dengan telapak tangan, siku bersandar di kakinya. Tolong jangan menangis karena aku sedang berpikir haruskah aku akhiri sampai di sini atau kita bawa permainan ini ke tahap berikutnya.
Aku mendekatinya, berjongkok dan menarik telapak tangan itu. Oh dia tidak menangis, dan matanya tidak berkaca-kaca, wajahnya merona.
“Kamu pasti sangat membenciku?”
Aku hanya terdiam, menyisir rambutnya dengan kedua tanganku, —aku tidak hanya membencinya tapi membenci semua wanita yang tidak bisa menempatkan dirinya lalu aku menarik wajahnya menempelkan bibirku ke bibirnya dengan lembut. Dia menarik wajahnya perlahan, memandang mataku dengan dalam, dan dia sekarang yang menarik wajahku. Dia menungguku memulai.
Aku mendorong tubuhku sehingga dia merebahkan dirinya di sofa, bibir kami tidak terlepas, tanganku membelai payudaranya, dia mendesah, mengangkat pinggulnya kemudian dia menahan pundakku saat kami mendengar suara motor yang lewat.
Ok, aku lupa kalau kafeku tidak menggunakan tirai yang hampir semua dindingnya jendela, dan orang yang lewat pasti akan memergoki kami. Tapi bukankah itu tantangannya. Aku mendekatkan lagi wajahku, dan dia menyambutnya tapi tangannya tetap menahan.
Dia menoleh ke arah jendela, kemudian bangkit, payudaranya sudah hampir menyembul keluar. Aku bangun, menarik tangannya dan membawa tasnya ikut bersama kami. Di pojok ada kamar khusus untuk istirahat lengkap dengan ranjang. Aku mematikan lampu tengah, sambil menggiring Sabila. Menutup pintu kamar dan melanjutkan pergumulan. Dia mendorongku jatuh ke ranjang, membuka high heelsnya kemudian melompat menindihku, dia menciumi leherku, nafasnya cepat, dan membuas, membantuku melepaskan kaosku dan aku membantunya melepaskan kemejanya, tidak biasanya dia memakai rok panjang, bokongnya menggesek kejantananku, aku melepas kutangnya dan langsung meraih putingnya yang sudah mengeras, dia memejamkan matanya.
“Tunggu sebentar.” Hp di kantong celanaku bergetar, aku memeriksanya dan itu pesan dari Indira, aku tidak memahami maksudnya karena dia hanya mengirimkan emoji acungan jempol. Apa dia tidak membaca pesanku? Aku ingin segera membalasnya tapi Sabila menarik hp itu dan melemparkannya ke meja, dia mulai menggerayangiku, mencium dari kuping, turun ke bibir, ke leher, ke dada, dan dia membuka ikat pinggangku. Dan mulai mengulum kejantananku, aku hanya menatap langit-langit memikirkan apa yang dimaksud Indira.
Sabila berhenti, aku melihat kebawah, kekecewaan terlihat di wajahnya. Oh, fuck!
Dia bangkit duduk, “kenapa?”
“Huh, apa?”
Dia merayap ke atas, payudaranya menempel di dadaku dengan tangan tetap mengelus di bawah, aku meraih wajahnya, tapi sepertinya tidak berhasil. Dia menyerah bangkit dan memakai kutangnya dan kemejanya sambil menatapku tersenyum. “Tidak apa-apa.”
Ini bukan masalah tidak apa-apa—libidoku dan begini ternyata rasanya disaat ada wanita tanpa busana dan menggerayangimu tapi kau tidak bisa ereksi, tapi memang sepertinya kita harus berhenti sampai di sini. Aku tidak seharusnya melanjutkan ini, dan aku sudah cukup memberikannya hukuman. Dan saatnya aku harus mengatakan yang sejujurnya.
“Sabila,” kataku lembut, “hubungan kita berakhir sampai disini. Jangan pernah datang lagi, atau menghubungi aku lagi.”
Dia membelalakan matanya, “maksud kamu?”
“Kamu tahu maksud aku?”
“Lalu apa yang baru saja kita lakukan?”
“Kita belum melakukan apa apa.”
“Selama ini?”
“Bukan itu maksudku. Malam ini. Dan ini yang terakhir.”
Matanya melotot, dia bergerak mondar mandir, lalu menarik rambutnya.
“Kamu bajingan, Niko!”
I deserve that.
Aku mengambil tasnya dan sepatunya, dia duduk di pinggir ranjang, menunduk.
“Aku pikir kamu cinta sama aku.”
“Tidak ada yang namanya cinta.” (yang aku tahu kamu bekerja sebagai bawahanku, dan di saat kita bersama tidak ada hal-hal romantis yang terjadi, hanya makan-sex-tidur, dan itu tidak bisa dibilang cinta. Aku tidak merasakannya apa yang orang bilang: getaran.)
Dia mengangkat wajahnya seolah-olah ingin melempar sesuatu ke arah wajahku yang datar. Fuck, Indira. Ok, dan kenapa harus Indira.
“Semua lelaki sama saja!”
Dia tidak melemparkan sesuatu tapi kata-katanya menampar keras ke wajahku.
“Maksud kamu apa?”
“Lelaki maunya hanya baik!” dia menarik tasnya dari tanganku. Dan kali ini aku yang naik pitam, aku harusnya bisa mengontrol emosiku, dia hanya memancing.
“Yang lucunya dari mereka gak ada yang bisa memuaskan aku.”
Ok, apakah aku bagian dari “mereka”.
“Sabila, aku tahu aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu, tapi ini semua ulahmu sendiri.”
Kali ini aku kata-kataku yang menamparnya. “Siapa yang memulai? Dan siapa yang menyuruhku naik ke ranjang bersamamu?”
“Tapi kau mendekatiku, kau mengajakku- Sudah lah.”
“Harusnya kamu bersyukur Irvan sudah memaafkanmu, tapi kamu malah bermain dengan Feri.”
Apa yang aku pikirkan, shit! Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Sekarang pandangan Sabila lebih tajam daripada pisau. Dan aku sadar sudah keceplosan.
“Apa maksudmu? Ada apa dengan Feri?”
Aku bangkit dari ranjang dan mencoba meraih tangannya, dia menepis.
“Apa yang dikatakan Feri?”
Kau sudah bertunangan, segera menikah tapi malah main hati dengan pria lain. Dan aku menyampaikannya pada Irvan bukan Feri; dia hanya kambing hitam. Aku tidak bisa menjawabnya.
“Ya, Tuhan! Kau yang bicara dengan Feri. Kau orang tengah yang mengacaukan semuanya. That is right, but.
“Pelankan suaramu, biarkan aku menjelaskannya”—sebetulnya tidak perlu, aku paham apa yang aku perbuat.
“Kau Iblis,” cetusnya.
Aku mendekatinya, “aku tidak bermaksud-”
“Jangan mendekat!” suaranya terlalu tinggi.
Darahku ikut naik, aku harus menarik nafas panjang. “Ok, Bila, tolong pulang sekarang juga.”
“Atau apa?” dia bangkit mendekatiku. Dan aku harus menjaga emosiku, kau bisa.
“Atau apa?” dia mendorongku, aku mendekat ke arah pintu, membukanya, dia mengayunkan tasnya ke arah tanganku, dan aku menghindarinya cepat.
“Sabila, Cukup!” suaraku meninggi. “Tolong jangan buat keributan. Atau kalau kamu mau bicara bersikap dengan tenang.” aku menatapnya tajam, dia sempat terdiam tapi sepertinya pikirannya semakin kacau. Dan apa yang seharusnya pria lakukan di dalam kondisi ini? Memeluknya? Tapi dia terus mendorongku.
“Biarkan! Biarkan semua orang tau kalau aku pramuria dan kau salah-satu orang yang menikmatinya!” aku mundur, dia tetap mendorongku.
“Jadi selama ini kamu hanya memanfaatkanku, bagaimana rasanya? Enak?! ‘Oh, Sabila lemah, dan dia sedang kacau jadi bagaimana kalau aku pakai saja dia?!’”
Caught red-handed.
Kafeku ada ditengah jalan dan di kota, mustahil orang tidak lalu-lalang walau sudah malam. Aku harus menenangkannya. Aku meraih pundaknya.
Dia menepis dan tidak sengaja tangannya menamparku, aku kaget dan secara spontan aku menarik pundaknya dengan sebelah tangan dan mengayunkan tanganku satu lagi ke wajahnya, dia terpelanting dan aku mendengar suara benturan di ujung ranjang, aku tidak sengaja, dia mengejutkanku, dan, -is that...? Goddamnit!
Aku berjongkok mengecek kepalanya, dia pingsan, aku masih bisa merasakan nafasnya. Aku merasakan ruangan menjadi sangat panas, ini tidak seharusnya terjadi jika saja dia mau menurut dan pergi.
Sekarang apa yang harus aku lakukan?
Membawanya ke dokter, apa yang akan dikatakannya nanti, dan Indira, oh, kau mengacaukan ini, bukan aku yang mengacaukannya, dan sekarang aku sedang panik, aku harus menarik nafas atau aku yang nantinya malah pingsan. Jam berapa sekarang, mana handphoneku.
Jam dua belas. Cepat sekali waktu berjalan.
Aku harus tetap tenang, dia masih bernapas dan aku hanya perlu menunggunya ba-
Sabila terjaga, dia menggumam pelan, “Niko.”
“Hey, maaf aku...”
Dia bangun dengan cepat, bergerak mundur menyeret pantatnya, punggungnya menabrak ranjang, dan tetap mundur sampai menempel ke tembok, darah di lantai tersapu dan membekas panjang, juga ada di ujung sprei dekat besi dimana kepalanya terbentur. Aku mendekat.
“Jangan mendekat, Niko.” suaranya kini tidak kencang tapi bergetar, aku tahu dia mengalami syok atau mungkin trauma, sambil menempel pada dinding.
Aku memberinya isyarat dengan menunjuk kepalaku, dia menyentuh lukanya dan kesakitan sendiri, air mata mengalir di pipinya tapi tidak ada isakan, aku mendekatinya, dan dia kaget, terbata-bata, berusaha memeluk tembok. Aku berhenti.
“Sabila, biarkan aku menolongmu, kamu terluka.”
“Jangan mendekat.’
“Kamu yang me-”
Dia menjerit, ujung jeritannya mengecil, kemudian tersedu sedan, darah di tangannya mengotori tembok.
“Tolong, Niko.” suaranya menjadi serak, aku tidak tahu kalau itu bisa berubah apalagi karena tangis yang ditahan bercampur dengan rasa takut.
Aku berjongkok, mendekat perlahan, aku mengulurkan tanganku, dan ditepis ketika hampir menyentuhnya, dia melompat ke belakang, membenturkan kepalanya sendiri, memberontak berusaha kabur. Entah lucu atau iba, aku tidak melakukan apa-apa aku hanya ingin menolongnya, dia berusaha melewatiku sambil merangkak, aku menarik pundaknya, dia menepisnya, berusaha meraih gagang pintu, berusaha berdiri tapi tidak mampu, kemudian menyerah, membalikkan badan, mata terpejam, menjerit tanpa suara, dan mulai tenang.
Huft!
Dia hanya duduk dalam diam, memeluk kakinya, badannya bergetar, rambutnya berantakan, kancing kemejanya belum rapih. Aku juga diam, belum bisa bertindak atau berbicara. Menunggu adalah hal yang baik, terutama untuk membuatnya merasa aman.
Manis terasa di lidahku, ternyata tamparannya membekaskan luka. Dan ini terjadi hanya karena kemaluan yang tidak mau ereksi?
Nafasnya yang terengah-engah sudah mulai normal, sepertinya saatnya aku mendekatinya, tubuhku mulai kedingingan, hari semakin larut sepertinya. Aku merapikan sepatu dan tasnya, kemudian aku mencoba untuk meraih Sabila mengajaknya untuk naik keranjang beristirahat, dia pasti lelah dan sangat syok, tubuhnya bergetar, aku menyibakkan rambutnya dan melihat ke area yang terluka.
Tapi dorongan cepat tangannya membuatku terpental jatuh kebelakang, dia berdiri, mengambil tas dan sepatunya, membuka pintu dan berlari.
“TOLONG!”
Suaranya sudah kembali normal. Sial. Kepala berdarah, bajunya berantakan. Sabila! Maksudnya apa?
Aku harus bangkit dan mengejarnya cepat.
Aku meraih pundaknya dia memukulku dengan tasnya, aku sudah siap dengan itu, sepertinya aku harus memeluknya, aku berhasil, tapi dia mengadukan kepalanya ke belakang membentur hidungku dengan keras, efeknya membuatku seperti melihat sinar Matahari secara langsung.
“Sabila!”
Dan Tuhan sedang menikmati sekali momen pengejaran ini, oleh karenanya dia menyediakan air di lantai dan membuatku terpeleset ke depan, aku berhasil menahan kepalaku agar tidak membentur, aku melihat sabila menengok, dan kembali berusaha ke ruangan depan sambil masih tetap berteriak, kemana orang-orang. Aku bisa dikeroyok oleh mereka karena salah paham. Aku merangkak, dan ketika Sabila hampir sampai ke ruangan depan aku melompat kodok, menarik kakinya.
mmuji1575 memberi reputasi
1