- Beranda
- Stories from the Heart
Rasa yang Sudah Tak Seirama
...
TS
WardahRos
Rasa yang Sudah Tak Seirama
Kisah tentang minda yang terabaikan

Malam yang gigil, hanya tikus dan kucing yang tak lelah saling berkejaran di luar sana. Aku membuka kembali laptop dan membaca deretan email yang terkirim. 105 email telah kukirimkan kepadamu, tapi tak sekalipun kau balas. Nomerku sudah kamu blokir, jadi hanya inilah satu-satunya cara agar aku bisa menghubungimu.

Empat tahun lalu kamu berjanji akan menikahiku. Tidakkah kamu tahu bahwa meskipun kamu mengucapkannya dengan candaan tapi aku sungguh mengutipnya dan menyimpannya rapat-rapat di kedalaman hatiku?
Aku sampai rela tak melirik pria lain dalam kurun waktu itu. Aku rela menolak lamaran Farel, anak dari teman baik ayahku. Demi kamu. Demi seorang pria dengan senyum termanis yang telah mencuri hatiku.
Dulu kamu berpamitan padaku untuk kuliah di negara lain. Padahal kita sebelumnya berencana untuk masuk ke kampus yang sama. Tapi apalah dayaku? Orangtuamu ingin kamu kuliah di sana sedangkan aku di sini menahan diri agar tak berlaku murahan, merengek-rengek agar kamu tak menuruti orangtuamu.
Sebulan, dua bulan, sampai hampir satu semester kamu masih lancar berkirim pesan bahkan bertelepon tiap hari. Aku habis pulsa internet berapapun tak masalah. Demi bisa mendengar suaramu, atau melihat wajahmu ketika melakukan panggilan video.
Bulan berikutnya kamu mulai jarang bertelepon. Aku memakluminya karena kamu mulai sibuk ujian, aku di sini juga sudah mulai sibuk. Entah sejak kapan pastinya kamu sudah tak pernah mengirimku pesan lebih dulu. Aku yang berinisiatif berkirim pesan percakapan, menanyakan kabarmu, menanyakan hal-hal remeh seperti sudah makan atau belum. Bahkan sekedar pesan stiker yang menggambarkan suasana hatiku saat itu.
Kamu selalu menjawabnya, tapi dengan kalimat yang sangat singkat. Kungin kamu tahu kalau aku berharap lebih. Rindu ini semakin menggerogotiku. Setidaknya ijinkan aku mendengar suaramu atau melihat wajahmu meskipun ragamu tak berada di sini.
Aku beranikan diri untuk menelepon lebih dulu karena sudah tak sanggup menahannya. Lama panggilan itu belum kau jawab. Aku sampai berkali-kali melihat jam dan konversi waktunya di negara yang kamu tinggali.
Apakah terlalu malam? Tidak, kita hanya berjarak satu jam saja. Kemudian kamu mengangkat panggilanku. Kau tahu rasanya? Seperti ada bunyi “POP!” di dalam dadaku. Dan sesuatu yang meledak di dalam sana mengeluarkan kupu-kupu multi warna.
Namun, sayangnya kamu tak merasakan hal yang sama denganku. Jawabanmu sangat datar, seperti seorang teman yang tidak terlalu dekat. Padahal kita sudah menjalani hubungan lebih dari itu.
Sebuah kecurigaan melintas di kepalaku, tapi segera kutepis dengan alasan mungkin kamu sedang capek. Atau mungkin mengantuk, dan alasan-alasan klise yang kuciptakan sendiri.
Perlahan tapi pasti, kamu menjauh dariku. Kita hampir lulus. Aku fokus kepada tugas akhir sehingga tak dapat menghubungimu.
Sampai saat reuni tiba. Kamu tak datang waktu itu, dengan alasan harus menghabiskan waktu bersama keluarga karena tidak bisa libur lama. Kamu berencana terbang kembali keesokan harinya.
Kata teman SMA kita, dia bertemu kamu di sebuah mall. Kamu terlihat merangkul seseorang. Dara cantik berambut panjang sepinggang, senyumnya sangat manis. Aku menghibur diri dengan asumsi bahwa kalian hanya teman.
Dengan bodohnya aku mengirimkan pesan kepadamu kalau aku akan ke rumahmu. Aku sengaja mematikan ponsel setelah yakin pesan itu terkirim. Agar aku tak mendengarkan atau membaca pesan penolakan darimu.
Hanya sekarang satu-satunya kesempatanku untuk bertemu. Besok kamu kembali meninggalkan negara ini.
Bergegas kutinggalkan acara reuni yang belum usai, menuju ke rumahmu.
Dengan harapan sebesar gunung Himalaya, kupacu motor. Debaran di dada semakin menggila dengan hentakan dari rasa terpendam untuk bisa bertemu denganmu dan melepas rindu.
Tak berharap banyak, ekedar bicara secara langsung saja aku sudah berpuas diri. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar tugas akhirmu? Apa rencanamu setelah lulus? Aku ingin mendengarkan jawaban itu langsung dengan melihat wajahmu. Seperti dulu, empat tahun lalu ketika kita masih sering menikmati es krim bersama setelah bimbel di lapangan sekolah.
Aku ingin bercerita tentang betapa susahnya membuat skripsi. Kamu tahu bahwa dari dulu aku tak suka pelajaran mengarang bebas. Sedangkan menyusun skripsi seperti halnya menulis untuk sebuah buku cerita.
Aku ingin mengetuk pintu rumahmu dan berteriak, “Surprise!”
Sayangnya anganku itu menguap tak bersisa. Kamu ada di sana, di halaman kecil samping rumah. Wajahmu terlihat lebih dewasa dengan rahang yang membentuk tegas. Senyum yang sama, cara bicara yang sama.
Akan tetapi, di sebelahmu ada dia. Dara cantik berambut panjang dengan senyuman manis.
Dengan gerakan pelan aku mundur. Tak ingin mengagetkan kalian yang tampak menciptakan dunia kalian sendiri.
Dia bukan teman biasa. Aku tahu dari cara kamu memandanginya. Seperti itu juga kamu memandangku empat tahun lalu.
Sayangnya, kakiku yang bodoh ini menginjak kerikil dan menimbulkan bunyi yang mengagetkanmu.
Kamu sontak berdiri, dan aku membeku di tempat. Ada yang ingin kutanyakan padamu, tapi aku lupa apa itu. Ada yang ingin kusampaikan padamu tapi aku juga lupa.
“Siapa dia?” adalah pertanyaan pertama kali yang meluncur dari bibirku.
“Dia ... Karin.”
“Aku tak butuh namanya.” Kalimat tegas itu membuatmu terkejut. “Apa hubunganmu dengannya?” lanjutku bertanya.
“Dia ... kami jalan sekarang.”
Butuh beberapa detik untuk mencerna kalimat itu. Namun butuh waktu lebih lama untuk meredam gejolak di dada setelah paham artinya.
Kau hancurkan angan yang sudah aku pupuk selama bertahun-tahun. Setidaknya jujurlah padaku. Walau sesakit apa, aku akan tahan. Bukan dengan cara seperti itu.
Kehilanganmu mungkin memang sebuah keniscayaan yang telah terlintas di benakku sejak lama. Namun aku menolak untuk percaya. Terpisah jarak dan waktu, bahkan mungkin restu orang tua tapi aku tak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Semua itu tak terjawab karena kamu memutuskan kontak denganku.
Aku tersenyum dan menganggap bahwa itu merupakan tindakanmu yang paling dewasa menurut versimu sendiri. Aku jadi bertanya-tanya selama ini apa arti diriku untukmu?
Mungkin aku hanya ingin menghibur diri, dengan mengirimkan tiap hari email yang nyatanya tak pernah engkau baca. Namun, hati ini tak ingin berhenti melakukannya. Jari-jariku seakan terprogram untuk mengirimkannya setiap hari tanpa lelah.
Setidaknya bacalah sekali saja. Kamu akan tahu bahwa aku sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor kecil yang bergerak di bidang ekspor impor. Jaraknya sekitar satu jam perjalanan dari rumahku. Melenceng sedikit dari cita-citaku dulu yang ingin bekerja di sebuah bank.
Setidaknya bacalah email terakhir yang kukirimkan. Kamu akan tahu bahwa aku baru mendapatkan lamaran dari Farel lagi. Namun, kali ini aku menerimanya.


Malam yang gigil, hanya tikus dan kucing yang tak lelah saling berkejaran di luar sana. Aku membuka kembali laptop dan membaca deretan email yang terkirim. 105 email telah kukirimkan kepadamu, tapi tak sekalipun kau balas. Nomerku sudah kamu blokir, jadi hanya inilah satu-satunya cara agar aku bisa menghubungimu.

Empat tahun lalu kamu berjanji akan menikahiku. Tidakkah kamu tahu bahwa meskipun kamu mengucapkannya dengan candaan tapi aku sungguh mengutipnya dan menyimpannya rapat-rapat di kedalaman hatiku?
Aku sampai rela tak melirik pria lain dalam kurun waktu itu. Aku rela menolak lamaran Farel, anak dari teman baik ayahku. Demi kamu. Demi seorang pria dengan senyum termanis yang telah mencuri hatiku.
Dulu kamu berpamitan padaku untuk kuliah di negara lain. Padahal kita sebelumnya berencana untuk masuk ke kampus yang sama. Tapi apalah dayaku? Orangtuamu ingin kamu kuliah di sana sedangkan aku di sini menahan diri agar tak berlaku murahan, merengek-rengek agar kamu tak menuruti orangtuamu.
Sebulan, dua bulan, sampai hampir satu semester kamu masih lancar berkirim pesan bahkan bertelepon tiap hari. Aku habis pulsa internet berapapun tak masalah. Demi bisa mendengar suaramu, atau melihat wajahmu ketika melakukan panggilan video.
Bulan berikutnya kamu mulai jarang bertelepon. Aku memakluminya karena kamu mulai sibuk ujian, aku di sini juga sudah mulai sibuk. Entah sejak kapan pastinya kamu sudah tak pernah mengirimku pesan lebih dulu. Aku yang berinisiatif berkirim pesan percakapan, menanyakan kabarmu, menanyakan hal-hal remeh seperti sudah makan atau belum. Bahkan sekedar pesan stiker yang menggambarkan suasana hatiku saat itu.
Kamu selalu menjawabnya, tapi dengan kalimat yang sangat singkat. Kungin kamu tahu kalau aku berharap lebih. Rindu ini semakin menggerogotiku. Setidaknya ijinkan aku mendengar suaramu atau melihat wajahmu meskipun ragamu tak berada di sini.
Aku beranikan diri untuk menelepon lebih dulu karena sudah tak sanggup menahannya. Lama panggilan itu belum kau jawab. Aku sampai berkali-kali melihat jam dan konversi waktunya di negara yang kamu tinggali.
Apakah terlalu malam? Tidak, kita hanya berjarak satu jam saja. Kemudian kamu mengangkat panggilanku. Kau tahu rasanya? Seperti ada bunyi “POP!” di dalam dadaku. Dan sesuatu yang meledak di dalam sana mengeluarkan kupu-kupu multi warna.
Namun, sayangnya kamu tak merasakan hal yang sama denganku. Jawabanmu sangat datar, seperti seorang teman yang tidak terlalu dekat. Padahal kita sudah menjalani hubungan lebih dari itu.
Sebuah kecurigaan melintas di kepalaku, tapi segera kutepis dengan alasan mungkin kamu sedang capek. Atau mungkin mengantuk, dan alasan-alasan klise yang kuciptakan sendiri.
Perlahan tapi pasti, kamu menjauh dariku. Kita hampir lulus. Aku fokus kepada tugas akhir sehingga tak dapat menghubungimu.
Sampai saat reuni tiba. Kamu tak datang waktu itu, dengan alasan harus menghabiskan waktu bersama keluarga karena tidak bisa libur lama. Kamu berencana terbang kembali keesokan harinya.
Kata teman SMA kita, dia bertemu kamu di sebuah mall. Kamu terlihat merangkul seseorang. Dara cantik berambut panjang sepinggang, senyumnya sangat manis. Aku menghibur diri dengan asumsi bahwa kalian hanya teman.
Dengan bodohnya aku mengirimkan pesan kepadamu kalau aku akan ke rumahmu. Aku sengaja mematikan ponsel setelah yakin pesan itu terkirim. Agar aku tak mendengarkan atau membaca pesan penolakan darimu.
Hanya sekarang satu-satunya kesempatanku untuk bertemu. Besok kamu kembali meninggalkan negara ini.
Bergegas kutinggalkan acara reuni yang belum usai, menuju ke rumahmu.
Dengan harapan sebesar gunung Himalaya, kupacu motor. Debaran di dada semakin menggila dengan hentakan dari rasa terpendam untuk bisa bertemu denganmu dan melepas rindu.
Tak berharap banyak, ekedar bicara secara langsung saja aku sudah berpuas diri. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar tugas akhirmu? Apa rencanamu setelah lulus? Aku ingin mendengarkan jawaban itu langsung dengan melihat wajahmu. Seperti dulu, empat tahun lalu ketika kita masih sering menikmati es krim bersama setelah bimbel di lapangan sekolah.
Aku ingin bercerita tentang betapa susahnya membuat skripsi. Kamu tahu bahwa dari dulu aku tak suka pelajaran mengarang bebas. Sedangkan menyusun skripsi seperti halnya menulis untuk sebuah buku cerita.
Aku ingin mengetuk pintu rumahmu dan berteriak, “Surprise!”
Sayangnya anganku itu menguap tak bersisa. Kamu ada di sana, di halaman kecil samping rumah. Wajahmu terlihat lebih dewasa dengan rahang yang membentuk tegas. Senyum yang sama, cara bicara yang sama.
Akan tetapi, di sebelahmu ada dia. Dara cantik berambut panjang dengan senyuman manis.
Dengan gerakan pelan aku mundur. Tak ingin mengagetkan kalian yang tampak menciptakan dunia kalian sendiri.
Dia bukan teman biasa. Aku tahu dari cara kamu memandanginya. Seperti itu juga kamu memandangku empat tahun lalu.
Sayangnya, kakiku yang bodoh ini menginjak kerikil dan menimbulkan bunyi yang mengagetkanmu.
Kamu sontak berdiri, dan aku membeku di tempat. Ada yang ingin kutanyakan padamu, tapi aku lupa apa itu. Ada yang ingin kusampaikan padamu tapi aku juga lupa.
“Siapa dia?” adalah pertanyaan pertama kali yang meluncur dari bibirku.
“Dia ... Karin.”
“Aku tak butuh namanya.” Kalimat tegas itu membuatmu terkejut. “Apa hubunganmu dengannya?” lanjutku bertanya.
“Dia ... kami jalan sekarang.”
Butuh beberapa detik untuk mencerna kalimat itu. Namun butuh waktu lebih lama untuk meredam gejolak di dada setelah paham artinya.
Kau hancurkan angan yang sudah aku pupuk selama bertahun-tahun. Setidaknya jujurlah padaku. Walau sesakit apa, aku akan tahan. Bukan dengan cara seperti itu.
Kehilanganmu mungkin memang sebuah keniscayaan yang telah terlintas di benakku sejak lama. Namun aku menolak untuk percaya. Terpisah jarak dan waktu, bahkan mungkin restu orang tua tapi aku tak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Semua itu tak terjawab karena kamu memutuskan kontak denganku.
Aku tersenyum dan menganggap bahwa itu merupakan tindakanmu yang paling dewasa menurut versimu sendiri. Aku jadi bertanya-tanya selama ini apa arti diriku untukmu?
Mungkin aku hanya ingin menghibur diri, dengan mengirimkan tiap hari email yang nyatanya tak pernah engkau baca. Namun, hati ini tak ingin berhenti melakukannya. Jari-jariku seakan terprogram untuk mengirimkannya setiap hari tanpa lelah.
Setidaknya bacalah sekali saja. Kamu akan tahu bahwa aku sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor kecil yang bergerak di bidang ekspor impor. Jaraknya sekitar satu jam perjalanan dari rumahku. Melenceng sedikit dari cita-citaku dulu yang ingin bekerja di sebuah bank.
Setidaknya bacalah email terakhir yang kukirimkan. Kamu akan tahu bahwa aku baru mendapatkan lamaran dari Farel lagi. Namun, kali ini aku menerimanya.

Diubah oleh WardahRos 03-08-2020 11:10
riwidy dan 46 lainnya memberi reputasi
47
1.4K
66
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
31.5KThread•41.6KAnggota
Tampilkan semua post
TS
WardahRos
#2
November Rain
Cerpen Baper

November Rain
Seharusnya kamu di sini. Mendengarkan curhat recehku tentang betapa capeknya tadi saat pulang. Aku terpaksa harus menuntun sepeda motor karena ban belakangnya bocor.
Seharusnya kamu di sini. Mengajak anak ke-tiga kita yang masih batita berkeliling komplek sebelum berangkat kerja.
Seharusnya kamu di sini. Menjadi kuda-kudaan Mita anak ke-dua kita, atau sekedar mengajak Arsya–si sulung naik mobil-mobilan di wahana permainan, sebagai hadiah karena berhasil meraih rangking pertama di kelas.
Seharusnya kamu di sini. Mengantar anak-anak ke sekolah sedangkan aku menjemput mereka.
Seharusnya kamu di sini. Mendengarkan ocehan si bungsu yang sekarang bisa bicara beberapa kata dengan lidah yang masih cadel.
***
Ingatanku melompat jauh ke awal November, tiga tahun lalu. Kamu berangkat bekerja di ibu kota saat aku hamil anak ke-tiga. Kamu tahu bagaimana inginnya aku mengikutimu, mendampingimu, berjuang bersamamu. Namun, apa daya, aku terpaksa menetap di kota ini. Karena baru menjadi pegawai sipil, aku tak bisa mengajukan mutasi. Tak mungkin aku melepaskan pekerjaan yang kuraih dengan susah payah. Kamu juga ingat kalau aku sudah bekerja honorer selama bertahun-tahun, dan baru mendapatkan sertifikat. Empat tahun penuh keringat pengorbanan orang tua untuk membiayai kuliahku, tak mungkin aku melepaskannya begitu saja. Dan juga enam tahun mengabdi di bawah standar upah yang layak, tak mungkin aku sia-siakan.
Dua tahun berlalu, karirmu menanjak dengan pesat. Namun, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerpanya. Mahligai rumah tangga kita mulai mendapat hantaman. Bagimu ia suatu pilihan halal dari surgawi, tapi bagiku ianya adalah Tsunami.
Saat kamu bertanya, “Mana yang lebih sakit?” Membayangkanmu selingkuh dan berbuat dosa, atau membayangkanmu bersanding dengan wanita lain tapi di jalan yang halal.
Aku terdiam. Ragu dan takut untuk menjawab. Sebagian kecil dari diriku menjerit. Namun, kepalaku masih ingin terangkat dan dibuai oleh panggilan semu 'wanita shalihah'.
Kali ini aku akan jujur. Jawabannya ... sama saja. Sama sakitnya.
Yang kamu tawarkan adalah sebuah pernikahan. Sebuah solusi, atas masalah kebutuhan biologismu yang terbentur oleh jauhnya jarak di antara kita.
Aku sadar sepenuhnya, meskipun aku menolak, pernikahan itu akan tetap berlangsung. Hubungan yang sah dalam hukum agama. Jika aku mengijinkan, maka di mata hukum juga sah.
Tak ada teman yang tahu tentang kamu menikah lagi. Hanya keluarga terdekat kita. Semua saudaraku bilang aku ini bodoh. Mau saja dimadu. Padahal masih muda, masih sanggup memenuhi permintaan hasrat suami.
Juga ustazah Halimah yang kamu juga mengenalnya. Aku curhat padanya hanya untuk meminta petunjuk, bagaimana aku harus bersikap. Namun, sungguh ia lebih dari yang kuharapkan. Di saat-saat terpurukku, dia selalu menenangkanku dengan nasehat-nasehatnya. Aku suka caranya bicara, memberitahuku apa yang baik dan menurut syariat tanpa berkesan terlalu menggurui.
Karena dia, aku bisa menerima takdir kita. Karena dia, aku ikhlas kamu menikah lagi. Karena sudah takdirku untuk dimadu. Jika aku ikhlas, maka hatiku akan terbebas dari cemburu dan kemarahan. Ikhlas akan membuatku tetap menjadi bidadari bagimu. Sebuah perhiasan dunia yang paling berharga untukmu.
Ia juga selalu menyempatkan diri datang ke rumah. Kadang hanya ingin menyapa ketiga anak kita. Kadang memberi sekotak kue buatannya, dan dia selalu punya selusin alasan saat menatap wajahku. Mungkin hanya untuk memastikan, aku masih tersenyum hari ini.
Terima kasih untuknya, karena sampai hari ini aku masih bisa tersenyum. Melihat pernikahan kita sebagai ladang pahala. Di setiap peluh dan kepayahan yang kurasakan saat merawat ketiga anak kita, dan pekerjaan rumah yang seperti tak ada habisnya, ada pahala di sana.
Pahala dan surga, kamu mungkin takkan pernah bisa mengetahui bagaimana kedua kata itu mempunyai kekuatan. Mampu membuat punggungku tegak, daguku terangkat. Dan percaya, esok akan jauh lebih indah.
***
Pengecut, itulah diriku. Takut kalau kamu akan marah, saat aku tanya berapa yang kamu berikan untuknya. Takut kejadian pahit terulang.
Masih membekas di benakku saat kamu pulang beberapa bulan lalu, kuberanikan diri bertanya, “Mas, Ibu minggu depan mau operasi, meskipun biayanya sudah ditanggung asuransi pemerintah, tapi ada beberapa obat yang harus ditebus di luar, tidak ter-cover asuransi dan harganya mahal.”
Kamu tak mau, atau tak bisa memberi sejumlah uang untuk meringankan biaya obatnya. Aku terlalu takut untuk bertanya lebih detail berapa tabunganmu, apa bisa mengambil uang tabungan dulu, karena ini adalah demi orang tua kita. Namun, engkau diam di atas keengganan. “Tidak bisa,” jawabmu singkat.
Meskipun Ibu adalah ibu mertuaku, tapi rasa sayangku padanya seperti layaknya kepada ibu sendiri. Lagipula Ibu yang selama ini membantuku menjaga anak-anak. Di rumah cuma ada seorang asisten rumah tangga, itupun digaji hanya untuk memasak dan membersihkan rumah, bukan sebagai pengasuh anak-anak.
Biarlah aku yang mengalah, aku berhutang kepada temanku, secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah aku bisa melunasinya saat uang gajian kuterima. Akan tetapi, apa yang kuterima selanjutnya sungguh di luar bayanganku. Kamu marah, karena pada akhirnya semua keluarga tahu kalau itu uangku. Hingga tersebar rumor, kamu tidak mampu membiayai kita, karena gajimu terbagi untuk istri ke-dua.
Egomu terpukul. Dan aku jadi benci dengan diriku sendiri. Kebaikanku yang di luar ijinmu, menjadi bumerang untuk kita.
Bukan hanya bagimu, bagiku juga. Aku juga merasa terpukul. Imamku menanggung malu karena perbuatanku.
***
Aku masih ingat rayuanmu untuk mengikhlaskan kalian menikah. Dia mandul. Menurut dokter, uterusnya tidak normal, dan lebih dari sebuah keajaiban agar Dia bisa hamil. Sehingga kau menghujaniku dengan rayuan, “Kaulah yang pertama. Bidadari istimewa. Kamu berbeda, kamu yang memberiku anak-anak yang lucu.”
Maka saat kemarin aku memaksa video-call, dan mendesakmu mengatakan apa alasan kamu tidak pulang empat bulan berturut-turut, ketika akhirnya kamu mengatakan alasannya, “Aku tak tega meninggalkannya. Ini kehamilan pertamanya, mual muntah terus ....”
Ambyar.
Aku tak ingat lagi apa lanjutan dari kalimatmu. Dadaku bergemuruh Cumiakkan telinga. Hatiku retak dan hancur berkeping-keping.
Kini, di antara kepingan yang tak lagi bisa utuh, kumencari di mana letak adil itu. Untuk diriku dan anak-anak yang bersabar menunggu dirimu pulang dua bulan sekali ke Surabaya. Untuk dirinya yang bisa bertemu denganmu setiap hari karena kalian memang tinggal bersama.
Nafkah? Aku tidak berani bertanya. Kamu pernah memberitahuku slip gaji, tapi itu sudah terlalu lama, sebelum kamu naik jabatan sebagai manajer.
Aku memberi ruang lebih lebar dalam hati. Sebuah ruang yang kupersiapkan untuk menambah kesabaran. Namun, ternyata aku salah. Ruang itu hampa.
Semakin jarang kamu pulang ataupun bicara padaku melalui telepon, chat, video-call, dengan alasan sibuk, semakin lebar ruang itu. Semakin hebat usahaku untuk menggali lebih dalam demi memahami hatiku sendiri, semakin diriku tersesat. Tak ada cahaya di sana.
Padahal sedikit lengkungan di bibirmu saja, mampu membuatku berdebar. Seulas sentuhan telapak tanganmu yang kasar, mampu membuat setiap inci syarafku tersulut. Kini hambar, aku lupa rasa itu semua. Dan yang kutakutkan menjadi nyata, aku lupa cara mencintaimu.
Percayalah, tidak ada setitik pun angkara untukmu, ataupun dia. Ini sudah takdir. Aku akan sampaikan ini semua kalau kamu mau pulang.
***
“Kumohon, pulanglah hari Minggu ini, aku ingin bicara.” Di layar ponsel, wajahku terlihat begitu putus asa. Tak mungkin kamu tak bisa merabanya.
Sayangnya, kamu tetap menjawab, “Maaf, aku tak bisa.”
Bukan itu jawaban yang kuminta.
Tadinya aku berharap, kedatanganmu mampu memercikkan kembali api asmara yang terlanjur padam. Kedatanganmu mampu membuka kembali ingatan tentang cita-cita kita bersama, mengarungi mahligai ini sampai rambut kita memutih dan maut menjemput. Sehingga layaknya sebuah hentakan di bahu, aku tersadar kembali dan terlecut untuk bertahan lebih lama lagi.
Wajahmu, tak menampakkan penyesalan yang berat. Mungkin kami sudah tak terlalu berharga lagi di matamu. Mungkin melewatkan jatah perjumpaan kita terasa sepele, seiring rasa sayang yang semakin memurba.
Kugigit bibir bawahku. Wajahmu semakin terlihat buram karena genangan yang tercipta di pelupukku. Padahal kuyakin air mataku sudah mengering, setelah semalaman tertumpah di atas sajadah.
Sekali lagi aku bergantung pada seutas tali rapuh bernama harapan. “Tolong pulanglah, anak-anak butuh kamu.”
Kamu terlihat menghela napas. “Tidak bisa, Ma. Aku takut ninggal dia sendirian. Ini kehamilan pertamanya, dan dia ....”
Pupus. Airmataku tak mampu lagi kubendung. Dadaku terasa semakin sesak, napasku tersengal. Tak ada daya lagi untuk bergantung pada tali yang sama.
“Pulanglah, kita bicara,”—susah payah aku mengatur napas agar kalimat berikutnya mampu kamu dengar dengan jelas—“untuk yang terakhir kali sebagai keluarga. Kamu boleh membawanya juga.”
Kamu tampak mengerutkan dahi. “Apa maksudmu untuk terakhir kali, Ma?” Sedikit kepanikan terbetik di netramu.
Aku menggeleng, menggigit bibir bawahku lebih kuat sambil memejamkan mata. Terlalu kuat sehingga rasa besi memenuhi rongga mulutku.
“Halo, Ma ... Ma ....”
Kututup panggilan video-call secara sepihak. Kuhela napas berat. Harum petrichor menelusup ke indera penciuman.
Surabaya, 18 November 2019
Disclaimer:
Murni fiksi
Cerpen ini pernah saya posting di platform lain.
Sumber gambar:
Pinterest
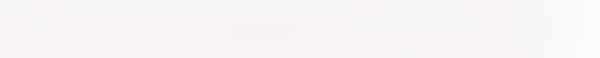

November Rain
Seharusnya kamu di sini. Mendengarkan curhat recehku tentang betapa capeknya tadi saat pulang. Aku terpaksa harus menuntun sepeda motor karena ban belakangnya bocor.
Seharusnya kamu di sini. Mengajak anak ke-tiga kita yang masih batita berkeliling komplek sebelum berangkat kerja.
Seharusnya kamu di sini. Menjadi kuda-kudaan Mita anak ke-dua kita, atau sekedar mengajak Arsya–si sulung naik mobil-mobilan di wahana permainan, sebagai hadiah karena berhasil meraih rangking pertama di kelas.
Seharusnya kamu di sini. Mengantar anak-anak ke sekolah sedangkan aku menjemput mereka.
Seharusnya kamu di sini. Mendengarkan ocehan si bungsu yang sekarang bisa bicara beberapa kata dengan lidah yang masih cadel.
***
Ingatanku melompat jauh ke awal November, tiga tahun lalu. Kamu berangkat bekerja di ibu kota saat aku hamil anak ke-tiga. Kamu tahu bagaimana inginnya aku mengikutimu, mendampingimu, berjuang bersamamu. Namun, apa daya, aku terpaksa menetap di kota ini. Karena baru menjadi pegawai sipil, aku tak bisa mengajukan mutasi. Tak mungkin aku melepaskan pekerjaan yang kuraih dengan susah payah. Kamu juga ingat kalau aku sudah bekerja honorer selama bertahun-tahun, dan baru mendapatkan sertifikat. Empat tahun penuh keringat pengorbanan orang tua untuk membiayai kuliahku, tak mungkin aku melepaskannya begitu saja. Dan juga enam tahun mengabdi di bawah standar upah yang layak, tak mungkin aku sia-siakan.
Dua tahun berlalu, karirmu menanjak dengan pesat. Namun, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerpanya. Mahligai rumah tangga kita mulai mendapat hantaman. Bagimu ia suatu pilihan halal dari surgawi, tapi bagiku ianya adalah Tsunami.
Saat kamu bertanya, “Mana yang lebih sakit?” Membayangkanmu selingkuh dan berbuat dosa, atau membayangkanmu bersanding dengan wanita lain tapi di jalan yang halal.
Aku terdiam. Ragu dan takut untuk menjawab. Sebagian kecil dari diriku menjerit. Namun, kepalaku masih ingin terangkat dan dibuai oleh panggilan semu 'wanita shalihah'.
Kali ini aku akan jujur. Jawabannya ... sama saja. Sama sakitnya.
Yang kamu tawarkan adalah sebuah pernikahan. Sebuah solusi, atas masalah kebutuhan biologismu yang terbentur oleh jauhnya jarak di antara kita.
Aku sadar sepenuhnya, meskipun aku menolak, pernikahan itu akan tetap berlangsung. Hubungan yang sah dalam hukum agama. Jika aku mengijinkan, maka di mata hukum juga sah.
Tak ada teman yang tahu tentang kamu menikah lagi. Hanya keluarga terdekat kita. Semua saudaraku bilang aku ini bodoh. Mau saja dimadu. Padahal masih muda, masih sanggup memenuhi permintaan hasrat suami.
Juga ustazah Halimah yang kamu juga mengenalnya. Aku curhat padanya hanya untuk meminta petunjuk, bagaimana aku harus bersikap. Namun, sungguh ia lebih dari yang kuharapkan. Di saat-saat terpurukku, dia selalu menenangkanku dengan nasehat-nasehatnya. Aku suka caranya bicara, memberitahuku apa yang baik dan menurut syariat tanpa berkesan terlalu menggurui.
Karena dia, aku bisa menerima takdir kita. Karena dia, aku ikhlas kamu menikah lagi. Karena sudah takdirku untuk dimadu. Jika aku ikhlas, maka hatiku akan terbebas dari cemburu dan kemarahan. Ikhlas akan membuatku tetap menjadi bidadari bagimu. Sebuah perhiasan dunia yang paling berharga untukmu.
Ia juga selalu menyempatkan diri datang ke rumah. Kadang hanya ingin menyapa ketiga anak kita. Kadang memberi sekotak kue buatannya, dan dia selalu punya selusin alasan saat menatap wajahku. Mungkin hanya untuk memastikan, aku masih tersenyum hari ini.
Terima kasih untuknya, karena sampai hari ini aku masih bisa tersenyum. Melihat pernikahan kita sebagai ladang pahala. Di setiap peluh dan kepayahan yang kurasakan saat merawat ketiga anak kita, dan pekerjaan rumah yang seperti tak ada habisnya, ada pahala di sana.
Pahala dan surga, kamu mungkin takkan pernah bisa mengetahui bagaimana kedua kata itu mempunyai kekuatan. Mampu membuat punggungku tegak, daguku terangkat. Dan percaya, esok akan jauh lebih indah.
***
Pengecut, itulah diriku. Takut kalau kamu akan marah, saat aku tanya berapa yang kamu berikan untuknya. Takut kejadian pahit terulang.
Masih membekas di benakku saat kamu pulang beberapa bulan lalu, kuberanikan diri bertanya, “Mas, Ibu minggu depan mau operasi, meskipun biayanya sudah ditanggung asuransi pemerintah, tapi ada beberapa obat yang harus ditebus di luar, tidak ter-cover asuransi dan harganya mahal.”
Kamu tak mau, atau tak bisa memberi sejumlah uang untuk meringankan biaya obatnya. Aku terlalu takut untuk bertanya lebih detail berapa tabunganmu, apa bisa mengambil uang tabungan dulu, karena ini adalah demi orang tua kita. Namun, engkau diam di atas keengganan. “Tidak bisa,” jawabmu singkat.
Meskipun Ibu adalah ibu mertuaku, tapi rasa sayangku padanya seperti layaknya kepada ibu sendiri. Lagipula Ibu yang selama ini membantuku menjaga anak-anak. Di rumah cuma ada seorang asisten rumah tangga, itupun digaji hanya untuk memasak dan membersihkan rumah, bukan sebagai pengasuh anak-anak.
Biarlah aku yang mengalah, aku berhutang kepada temanku, secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah aku bisa melunasinya saat uang gajian kuterima. Akan tetapi, apa yang kuterima selanjutnya sungguh di luar bayanganku. Kamu marah, karena pada akhirnya semua keluarga tahu kalau itu uangku. Hingga tersebar rumor, kamu tidak mampu membiayai kita, karena gajimu terbagi untuk istri ke-dua.
Egomu terpukul. Dan aku jadi benci dengan diriku sendiri. Kebaikanku yang di luar ijinmu, menjadi bumerang untuk kita.
Bukan hanya bagimu, bagiku juga. Aku juga merasa terpukul. Imamku menanggung malu karena perbuatanku.
***
Aku masih ingat rayuanmu untuk mengikhlaskan kalian menikah. Dia mandul. Menurut dokter, uterusnya tidak normal, dan lebih dari sebuah keajaiban agar Dia bisa hamil. Sehingga kau menghujaniku dengan rayuan, “Kaulah yang pertama. Bidadari istimewa. Kamu berbeda, kamu yang memberiku anak-anak yang lucu.”
Maka saat kemarin aku memaksa video-call, dan mendesakmu mengatakan apa alasan kamu tidak pulang empat bulan berturut-turut, ketika akhirnya kamu mengatakan alasannya, “Aku tak tega meninggalkannya. Ini kehamilan pertamanya, mual muntah terus ....”
Ambyar.
Aku tak ingat lagi apa lanjutan dari kalimatmu. Dadaku bergemuruh Cumiakkan telinga. Hatiku retak dan hancur berkeping-keping.
Kini, di antara kepingan yang tak lagi bisa utuh, kumencari di mana letak adil itu. Untuk diriku dan anak-anak yang bersabar menunggu dirimu pulang dua bulan sekali ke Surabaya. Untuk dirinya yang bisa bertemu denganmu setiap hari karena kalian memang tinggal bersama.
Nafkah? Aku tidak berani bertanya. Kamu pernah memberitahuku slip gaji, tapi itu sudah terlalu lama, sebelum kamu naik jabatan sebagai manajer.
Aku memberi ruang lebih lebar dalam hati. Sebuah ruang yang kupersiapkan untuk menambah kesabaran. Namun, ternyata aku salah. Ruang itu hampa.
Semakin jarang kamu pulang ataupun bicara padaku melalui telepon, chat, video-call, dengan alasan sibuk, semakin lebar ruang itu. Semakin hebat usahaku untuk menggali lebih dalam demi memahami hatiku sendiri, semakin diriku tersesat. Tak ada cahaya di sana.
Padahal sedikit lengkungan di bibirmu saja, mampu membuatku berdebar. Seulas sentuhan telapak tanganmu yang kasar, mampu membuat setiap inci syarafku tersulut. Kini hambar, aku lupa rasa itu semua. Dan yang kutakutkan menjadi nyata, aku lupa cara mencintaimu.
Percayalah, tidak ada setitik pun angkara untukmu, ataupun dia. Ini sudah takdir. Aku akan sampaikan ini semua kalau kamu mau pulang.
***
“Kumohon, pulanglah hari Minggu ini, aku ingin bicara.” Di layar ponsel, wajahku terlihat begitu putus asa. Tak mungkin kamu tak bisa merabanya.
Sayangnya, kamu tetap menjawab, “Maaf, aku tak bisa.”
Bukan itu jawaban yang kuminta.
Tadinya aku berharap, kedatanganmu mampu memercikkan kembali api asmara yang terlanjur padam. Kedatanganmu mampu membuka kembali ingatan tentang cita-cita kita bersama, mengarungi mahligai ini sampai rambut kita memutih dan maut menjemput. Sehingga layaknya sebuah hentakan di bahu, aku tersadar kembali dan terlecut untuk bertahan lebih lama lagi.
Wajahmu, tak menampakkan penyesalan yang berat. Mungkin kami sudah tak terlalu berharga lagi di matamu. Mungkin melewatkan jatah perjumpaan kita terasa sepele, seiring rasa sayang yang semakin memurba.
Kugigit bibir bawahku. Wajahmu semakin terlihat buram karena genangan yang tercipta di pelupukku. Padahal kuyakin air mataku sudah mengering, setelah semalaman tertumpah di atas sajadah.
Sekali lagi aku bergantung pada seutas tali rapuh bernama harapan. “Tolong pulanglah, anak-anak butuh kamu.”
Kamu terlihat menghela napas. “Tidak bisa, Ma. Aku takut ninggal dia sendirian. Ini kehamilan pertamanya, dan dia ....”
Pupus. Airmataku tak mampu lagi kubendung. Dadaku terasa semakin sesak, napasku tersengal. Tak ada daya lagi untuk bergantung pada tali yang sama.
“Pulanglah, kita bicara,”—susah payah aku mengatur napas agar kalimat berikutnya mampu kamu dengar dengan jelas—“untuk yang terakhir kali sebagai keluarga. Kamu boleh membawanya juga.”
Kamu tampak mengerutkan dahi. “Apa maksudmu untuk terakhir kali, Ma?” Sedikit kepanikan terbetik di netramu.
Aku menggeleng, menggigit bibir bawahku lebih kuat sambil memejamkan mata. Terlalu kuat sehingga rasa besi memenuhi rongga mulutku.
“Halo, Ma ... Ma ....”
Kututup panggilan video-call secara sepihak. Kuhela napas berat. Harum petrichor menelusup ke indera penciuman.
Sore hari di bulan November setelah hujan ... hamba menyerah kalah.
Surabaya, 18 November 2019
Disclaimer:
Murni fiksi
Cerpen ini pernah saya posting di platform lain.
Sumber gambar:

Diubah oleh WardahRos 03-08-2020 23:36
riwidy dan 15 lainnya memberi reputasi
16
Tutup