- Beranda
- Stories from the Heart
Cinta Bersemi di Kedai Serabi
...
TS
suciasdhan
Cinta Bersemi di Kedai Serabi
Kumpulan Cerita Romantis Bikin Baper

Sumber: gambar di sini
Sepagi ini kedai Mak Otih sudah penuh sesak. Serabi buatan Mak Otih memang yang paling terkenal di desa Cipedes ini. Penganan yang terbuat dari campuran tepung terigu yang gurih dan air kelapa, banyak diburu oleh warga desa ini dan menjadi alternatif pilihan untuk sarapan. Cara memasaknya yang masih tradisional—menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat serta kayu bakar di bawahnya untuk mematangkan serabinya—membuat serabi ini memiliki rasa dan aroma yang khas. Varian serabinya hanya dua macam, yaitu topping oncom sangrai untuk rasa asin, dan serabi disiram kuah gula merah atau kinca untuk yang rasa manis. Bahkan, untuk serabi topping oncom bisa ditambahkan telur agar rasanya semakin gurih.
Sopi mengamati tangan Mak Otih yang menyendok adonan serabi ke dalam wajan tanah liat dengan cekatan. Adonan yang masih cair itu kemudian ditaburi oncom sangrai. Asap mengepul dari sana. Aroma serabi yang hampir matang membuat gadis itu menelan saliva berulang kali. Perutnya semakin keroncongan. Terbayang di mulutnya rasa legit kuah kinca bercampur dengan kue serabi yang gurih, lezat rasanya.
Empat orang pemuda iseng mulai melirik nakal ke arah Sopi yang terlihat cantik. Salah satu dari mereka mulai menggodanya.
"Hai, Neng geulis, sendirian aja nih. Boleh Akang temenin?"
"Akang mah mau langsung kenalan aja, boleh enggak?" Seorang pemuda lainnya mulai mendekati Sopi. Sementara dua pemuda yang lainnya hanya tertawa-tawa.
Sopi mulai jengah dengan gangguan dari keempat pemuda itu. Bahkan salah satunya yang tadi minta kenalan mulai berani mencolek lengannya. Segera saja Sopi menepis tangan jahil pemuda jangkung berambut keriting itu. Memangnya aku ini sabun colek apa? pikir Sopi, kesal.
"Widih, si Eneng meuni sombong ih. Belum tahu ya kita ini siapa? Kita teh F4, tapi bukan pemeran di drama Meteor Garden ya. Saya Firman, itu Fikri, Farid, dan Ferdi." Pemuda berkaus biru donker berlogo salah satu superhero terkenal di dunia, menunjuk ke arah ketiga temannya sambil ikut mendekat ke arah Sopi.
Sopi masih membisu, dalam hati ia geram dengan tingkah para pemuda itu. Perempuan di kedai ini kan banyak, kenapa hanya aku yang diperlakukan seperti ini? gumamnya.
Melihat gadis itu beranjak dari tempat duduknya, hendak berlalu dari kedai, keempat pemuda itu malah semakin gencar menggodanya.
"Mau ke mana Neng? Buru-buru amat. Kita kan belum saling mengenal. Tukeran nomor hp aja belum, udah mau pergi. Rumahnya di mana sih? Akang antar ya. Tenang, dijamin aman, selamat sampai tujuan." Pemuda berkaus hitam bergambar logo band Linkin Park mengejar Sopi dan menggenggam tangan gadis itu.
Sopi berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman tangan pemuda itu malah semakin kuat. Ia meringis kesakitan. Keempat pemuda itu tertawa puas.
"Heii, kalian! Lepaskan gadis itu. Belum tahu ya kalau dia itu pacar saya? Seenaknya main antar pacar orang. Yuk, Neng Akang antar." Suara seorang lelaki tampan berdandan ala Kabayan berhasil menghalau keempat pemuda itu. Mereka pun menjauh dari Sopi. Setelah berpamitan pada Emaknya yang tengah membalikkan serabi dari wadah, pemuda itu pun berjalan beriringan dengan sang gadis.
"Yuk, Neng. Enggak usah takut, saya mah bukan lelaki cunihin seperti mereka. Kalau mau jahil ke perempuan, saya selalu ingat sama Emak. Gimana kalau Emak juga digodain kayak gitu? Saya pasti marah besar," ucap lelaki itu setelah agak menjauh dari kedai.
Dalam hati, Sopi memuji ucapan pemuda di sampingnya yang sangat santun dan hormat memperlakukan ibunya. Yang jadi istrinya, sudah pasti akan diperlakukan dengan baik juga. Sopi malu sendiri, dan buru-buru menepis pikiran yang baru saja terlintas di benaknya. Mereka berjalan berdampingan. Keduanya sama-sama merasa canggung, tak ada yang berani membuka percakapan. Hanya sesekali mereka saling beradu pandang, kemudian sama-sama tersenyum dan menunduk, malu. Hingga tiba di tempat tujuan pun, mereka masih diam seribu bahasa.
Sementara itu, Pak Asep yang sedari tadi merasakan perasaannya tak enak, selalu terbayang wajah putri cantiknya. Rasa kuatir menggelayuti pikirannya, takut sesuatu menimpa Sopi. Sesekali ia menatap ke arah jalan, mencari sosok yang membuat hatinya gelisah. Tidak berapa lama, ia melihat gadis itu. Namun, ia tidak sendirian, seorang pemuda jangkung terlihat berjalan di sampingnya.
"Hei, pemuda, siapa kamu? Kenapa tampang anakku seperti ketakutan begitu? Hmm, mau macam-macam ya sama anak Jawara Pencak Silat ini? Hayu lah, Bapak mah enggak takut. Kita tandang di lapang sebelah!" Pak Asep sudah pasang kuda-kuda, bersiap untuk menyerang sosok yang terlihat sebagai ancaman bagi putri tersayangnya. Sopi dan Aden pun bengong.
Dengan kekuatan penuh, Pak Asep bersiap melayangkan pukulan ke arah pemuda tampan yang sedang berdiri di samping putrinya.
“Daddy—Daddy, calm down.” Sopi menghalangi serangan ayahnya dengan menggenggam tangan pria paruh baya itu yang sudah bulat terkepal dengan sempurna.
“Minggir, Sopi. Biar dia merasakan bogem mentah Bapak. Walau Bapakmu ini sudah tua, tapi Bapak masih kuat. Ayo sini, pemuda, lawan!” Pak Asep menghempaskan tangan Sopi yang menghalanginya.
“Pak Asep? Ini benar Pak Asep kan? Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu juga.” Aden mencium punggung tangan pria di hadapannya yang napasnya masih tak beraturan. Emosi memenuhi rongga dadanya. Kedua matanya memelotot ke arah pemuda itu.
“Apa-apaan kamu? Diajak tanding malah cium tangan? Nyalimu ciut, Jang?” Pak Asep menghempaskan tangan Aden dengan kasar.
“Bapak lupa ya? Ini teh Aden, putranya Mak Otih. Dulu waktu SD Aden kan belajar pencak silat dari Bapak. Wah senangnya masih bisa berjumpa dengan guru bela diri favorit Aden.”
Mendengar penuturan pemuda yang berdiri di hadapannya, perlahan-lahan emosi Pak Asep menurun. “Jadi, ini Aden? Masya Allah, meuni kasep. Maafkan Bapak yang terlalu kuatir dengan keselamatan putri Bapak satu-satunya. Maklum, sejak Ibunya meninggal, hanya dia yang Bapak miliki di dunia ini. Bapak enggak mungkin lupa, hanya tadi mah pangling aja, sampai-sampai enggak ngenalin. Kamu kan yang pernah ngompol, ketakutan karena Bapak bentak, hahaha. Terus kamu itu terkenal paling cengeng di antara murid-murid Bapak yang lain. Kesenggol sedikit saja nangis kejer.” Pak Asep menepuk-nepuk pundak bekas murid pencak silatnya itu.
Aden tersipu malu sambil melirik gadis cantik di sampingnya yang sedang bengong menyaksikan percakapan antara dirinya dan Pak Asep. “Jadi, Eneng ini teh putrinya Bapak?” lanjutnya.
“Iya, ini namanya Sopi, anak Bapak. Hayu atuh masuk, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Sopi suguhkan makanan sama minuman.”
Sopi beranjak menuju dapur menyiapkan suguhan untuk sang tamu. Sementara itu Aden dan sang Ayah sudah duduk di kursi ruang tamu. Sesekali, Pak Asep melirik Aden yang mencuri pandang ke arah Sopi. Sepertinya pemuda itu tertarik pada putrinya. Sebuah senyuman tersungging di bibir lelaki paruh baya itu. Sementara Aden, yang kepergok sedang curi-curi pandang, jadi salah tingkah. Hatinya mengakui perempuan itu memang cantik, hanya dandanannya saja yang menurutnya terlalu berlebihan alias menor. Andai gadis itu berdandan sederhana, aura kecantikannya akan terpancar alami. Tidak berapa lama, Sopi muncul dengan baki berisi dua gelas teh manis dan beberapa stoples berisi kue kering juga makanan ringan.
“Ayo—ayo dimakan, Den,” tawar Pak Asep setelah Sopi menaruh semua bawaannya di atas meja.
“Eh iya, ngomong-ngomong serabi pesanan Bapak mana?” Kali ini pandangan mata pria itu beralih pada Sopi.
“My mood is going down, Daddy. So maafkan Sovia yang tak jadi membelinya.”
Aden menatap heran gadis yang duduk di samping Pak Asep. Buset, bukan hanya dandanannya yang lain, cara bicaranya juga aneh, gumamnya.
“Kok bisa?” Kening Pak Asep berkerut. Tak mengerti dengan kalimat yang diucapkan putrinya barusan. Sejurus kemudian, lelaki itu manggut-manggut menyimak cerita putrinya.
“Duh, Den. Maafkan Bapak yang sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Terima kasih telah menyelamatkan putri Bapak." Sudah waktunya Sopi punya pendamping hidup, yang akan melindunginya dari marabahaya, gumam Pak Asep dalam hati sambil menatap lekat-lekat Aden yang sedang mencuri pandang ke arah wajah Sopi. Untung saja, pemuda ini baik hati, jadi dia tetap membiarkan Aden memandang wajah Sopi sampai puas. Kalau pemuda culas yang melakukannya, pasti sudah dia gibas tanpa ampun sampai kapok.
***
“Daddy, ini kopinya.”
“Terima kasih, Sopi.” Gadis cantik itu mengangguk dan beranjak hendak menuju kamarnya.
“Sopi, mau ke mana? Sini duduk dulu sebentar, Bapak mau bicara.”
“Daddy, Sovia mau ke kamar, belum beres merapihkan alis.”
“Bentar doang kok. Enggak nyampe lima belas menit.” Pak Asep menyeruput kopinya. “Sopi, kopi buatan kamu mengingatkan Bapak sama almarhumah Ibumu. Racikannya sama-sama enak. Rasa kopi dan gulanya seimbang, pas.”
Sopi tersenyum melihat Ayahnya yang begitu penuh penghayatan menyeruput kopinya, terlihat sekali pria paruh baya itu menikmati setiap tegukan cairan hitam itu yang masuk ke kerongkongannya.
“Jadi begini, Geulis. Kamu sekarang sudah besar. Kuliah pun sudah selesai.” Pak Asep menatap wajah putri tersayangnya sebelum ia melanjutkan bicara. Pria itu tampak memutar otak mencari kalimat yang pas untuk menyampaikan maksudnya pada Sopi. “Sudah saatnya Bapak melepasmu, Sopi,” lanjutnya.
“Maksud Daddy?” Sopi tercengang mendengar ucapan lanjutan dari Ayahnya. Dahinya berkerut, tak paham dengan arah pembicaraan sang Ayah.
“Begini, Neng. Maksud Bapak—kamu—sudah waktunya kamu punya pendamping hidup.”
“What? Jadi maksud Daddy Sovia harus segera married? Menikah begitu? No, Daddy!”
“Dengar dulu Sopi. Bapak sudah pikirkan matang-matang hal ini. Bapak ....”
“Tapi, Daddy. Sovia enggak mau berpisah dari Daddy.” Sopi mulai terisak.
“Jangan nangis atuh, Neng. Bapak kan jadi ikut sedih. Setelah menikah nanti Sopi boleh kok tinggal di sini. Lagian calon kamu juga tinggalnya deket-deket sini kok.” Pak Asep mengelus lembut punggung putri tercintanya itu.
“Memangnya siapa orangnya, Daddy?” tanya Sopi, heran. Keningnya berkerut, seolah mencari siapa sosok pemuda yang tinggal di dekat sini. Ia menggelengkan kepalanya, nihil. Tak satu pun wajah lelaki yang bisa terbayang di benaknya.
“Kamu mau kan Bapak nikahkan sama Aden?” Pak Asep malah balik bertanya.
Sopi terperanjat mendengar Ayahnya menyebut nama itu. “What? Daddy enggak salah jodohin Sovia sama dia? Orangnya ganteng sih, tapi dandanannya persis seperti si Kabayan. Jangan-jangan dia juga pemalas, sama seperti Kabayan itu.”
“Sopi, kamu ingat waktu dia melindungi kamu dari pemuda-pemuda yang mengganggu?” Sopi mengangguk. “Nah, Bapak rasa dia bisa menjaga kamu dengan baik. Kesan pertama melihat dia, Bapak yakin dia anak yang baik, tidak seperti kebanyakan pemuda lainnya.”
Sopi tertegun. Pak Asep membiarkan gadis itu hanya diam saja, mungkin putrinya sedang mencoba meresapi semua ucapannya. Hanya helaan napas gadis cantik itu yang sesekali terdengar.
Setelah hening beberapa saat, tak lama kemudian, Sopi pun buka suara, “Baiklah, Daddy, beri Sovia waktu untuk berpikir.” Gadis itu menyeret langkahnya menuju kamar, meninggalkan Pak Asep yang di hatinya tengah berharap sang putri mau menerima rencana perjodohan ini.
Satu jam berlalu. Namun, tak ada tanda-tanda Sopi keluar dari kamarnya. Pak Asep pun merasa heran. Ia mulai mengetuk pintu kamar Sopi.
“Sopi, Neng, sarapan yuk.” Tak ada sahutan. “Geulis, Bapak udah bikinin telor ceplok kesukaan kamu. Kita makan bareng yuk.” Tetap tak ada sahutan. “Sopi, lagi apa di dalam? Masih dandan atau lanjutin mimpi? Masa baru juga bangun udah tidur lagi.”
Karena tak terdengar juga sahutan dari Sopi, Pak Asep membuka pintu kamar yang ternyata tak dikunci oleh pemiliknya. Namun, betapa kagetnya Pak Asep saat ia tak menemukan putrinya di dalam kamar itu. Ia mendapati jendela kamar putrinya terbuka lebar.
“Sopi? Kamu di mana, Nak? Ini mah ngajak Bapak main petak umpet ya?” Pak Asep mulai berkeliling ke seluruh ruangan, tetapi tetap saja ia tak menemukan putrinya. “Duh, Sopi. Kamu teh ke mana atuh? Bapak jadi kuatir.” Pak Asep memutuskan kembali ke kamar Sopi, siapa tahu di sana dia bisa menemukan petunjuk. Netra Pak Asep jatuh pada secarik kertas di atas nakas yang berisi tulisan tangan Sopi.
Daddy, maaf, Sovia gak bermaksud bikin Daddy cemas. Sovia hanya kesal mendengar rencana Daddy. Biarlah Sovia bertemu jodoh Sovia dengan sendirinya. Dan Sovia akan menikah setelah benar-benar merasa siap. Don’t worry Daddy, saat Daddy membaca surat ini, Sovia sudah berada di rumah Grandma.
Setelah membaca surat itu, Pak Asep yang sedari tadi pikirannya kalut, kini merasa lega. Bergegas lelaki itu melangkah ke luar hendak menyusul Sopi ke rumah Mak Onah. Wanita itu tampak sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya. Ia merasa heran saat dari kejauhan tampak putranya sedang berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Wanita itu pun menyuruh putranya masuk dan menyodorkan segelas air putih yang langsung diteguk habis oleh Pak Asep.
“Heh, nyari apaan kamu teh? Tuh minum udah Emak ambilin. Kalau cemilan mah kebetulan lagi kosong.” Mak Onah memandang heran putranya yang mengedarkan pandangan ke seluruh sudut rumahnya.
“Mak, Sopi ada di sini?” Kembali Pak Asep mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan di rumah Emaknya.
Kening Mak Onah berkerut, heran dengan pertanyaan putranya. “Kalian kan tinggal serumah, kok nanya Sopi ke Emak?”
“Jadi, Sopi enggak ada di sini?” Pak Asep malah balik bertanya. Wajahnya mulai terlihat panik. Ia pun bangkit dari duduknya.
“Mau ke mana, Sep? Ada apa sebenarnya?” Asep menyerahkan surat yang ditulis Sopi kepada Mak Onah. Sejurus kemudian wanita itu membacanya dengan saksama. Raut wajahnya tampak serius.
“Seharusnya sudah sejam yang lalu dia tiba di sini,” ucap Mak Onah pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri.
“Duh, Sopi teh ke mana atuh ya, Mak?” Hati Pak Asep semakin diliputi rasa kuatir. Peluh mulai bercucuran di pelipisnya. Raut wajah Mak Onah pun sama-sama tegang, ikut merasakan kegelisahan yang sedang melanda putranya.
“Makanya, ini kan bukan zaman Siti Nurbaya. Kamu teh meuni seenaknya jodoh-jodohin Sopi.”
Pak Asep menyesali tindakannya, hingga membuat gadis itu pergi dari rumah. Kini entah di mana putrinya berada. Tak berapa lama, ia pun pamit untuk mencari putri kesayangannya. Namun, Mak Onah yang juga merasa sangat kuatir akan keberadaan cucunya, minta untuk ikut mencari. Akhirnya, mereka berdua berjalan menyusuri desa, berharap menemukan sosok cantik yang sangat dicintai.
“Sep, ngapain kamu bawa Emak ke kedai ini? Kamu belum sarapan? Kenapa tadi enggak makan di rumah Emak atuh?!” Mak Onah tampak kesal saat putranya membawa dia ke kedai serabi milik orang yang sangat dibencinya. Dulu, Mak Otih pernah berusaha merebut sang suami. Untunglah almarhum suaminya itu setia, sehingga tidak tergoda sedikit pun. Matanya menerawang, senyumnya terkembang ketika membayangkan sosok gagah perkasa sang suami yang mirip Gatotkaca.
Pak Asep memandang heran Mak Onah yang memasang muka cemberut. Sungguh, ia tak mengerti mengapa Ibunya begitu membenci Mak Otih dan sama sekali tak mau makam kue serabi yang terkenal lezat ini.
“Assalamuaalaikum, Mak. Aden ada?” Pak Asep mencium takzim punggung tangan Mak Otih. Mak Onah memalingkan wajah melihatnya. Sebal.
“Waalaikumsalam, ada, sebentar ya, Den, Aden, ada yang nyari nih!” teriak Mak Otih. Tidak berapa lama, Aden pun keluar.
“Eh, Pak Asep, ada apa Pak?” Aden mencium tangan Pak Asep, kemudian ia hendak mencium punggung tangan Mak Onah, namun Neneknya Sopi itu tak membalas uluran tangan pemuda ganteng itu.
“Sep, Emak mah pulang aja ya, panas lama-lama berada di sini. Kabari Emak kalau Sopi sudah ditemukan.” Mak Onah melangkahkan kakinya lebar-lebar, bergegas meninggalkan kedai itu, diiringi tatapan bengong Pak Asep dan pandangan heran Aden juga Mak Otih.
“Maafin Emak saya, ya. Beliau lagi sakit gigi, jadinya agak sensitif begitu.” Pak Asep mencoba mencari alasan atas sikap Mak Onah.
Aden memandang heran ke wajah mantan guru pencak silatnya yang kelihatan tegang itu. Pak Asep menceritakan tentang kepergian Sopi dari rumah yang katanya mau minggat ke rumah Nenek, tetapi gadis itu tak diketahui ke mana rimbanya. Setelah pamit pada Mak Otih, mereka berdua pun berangkat menyusuri setiap sudut desa mencari keberadaan gadis cantik itu.
***
“Duh, Den, kita harus cari ke mana lagi ya? Belum terlihat tanda-tanda keberadaan Sopi. Kamu di mana atuh Geulis? Baik-baik aja kan di sana?” Pak Asep terlihat sangat cemas. Wajahnya membiaskan kelelahan. Namun, ia tepiskan rasa itu. Kuatir akan keadaan putrinya lebih besar dibandingkan apapun juga.
“Sabar, Pak, kita belum menyusuri seluruh ruas jalan desa ini. Udah Zuhur, Pak. Kita salat dulu di masjid itu yuk, sambil memanjatkan doa buat Neng Sopi juga.” Aden menunjuk sebuah mesjid besar yang terletak di ujung gang.
Pak Asep mengangguk lemah. Tidak berapa lama, mereka berdua sudah berbaur dengan orang-orang, khusyuk menunaikan salat Zuhur berjamaah di mesjid itu serta memanjatkan doa untuk Sopi.
“Den, kita istirahat sebentar di sini.” Pak Asep menenggak air mineral di dalam botol, kemudian ia menyodorkan satu botol lagi pada Aden. “Nih, minum dulu, Den.”
“Terima kasih, Pak. Oh, ya, boleh Aden tanya-tanya tentang Neng Geulis?” ucap Aden dengan nada ragu dan malu-malu.
“Tentu saja, biar lebih tahu tentang calon istrimu.” Pak Asep memandang wajah pemuda calon menantunya itu, yang raut wajahnya sedang tampak merah jambu itu.
Pipi Aden bersemu merah, hatinya berdesir aneh. “Pak, ngomong-ngomong sejak kapan Ibunya Neng Sopi meninggal?”
“Ibunya meninggal saat melahirkan dia. Makanya Bapak selalu berusaha membahagiakan dia, kasihan sejak kecil dia enggak merasakan kasih sayang seorang Ibu.” Netra Pak Asep berkaca-kaca. Sekelebat bayang wajah sang istri muncul di pelupuk matanya.
Aden manggut-manggut, “Lantas, Pak—maaf sebelumnya kalau Aden lancang, tetapi Aden penasaran sama dandanan juga gaya bicara Neng Geulis yang—maaf, terlihat aneh.”
“Hahaha, iya dia memang unik. Logat bicaranya dan dandanannya seperti itu sejak lulus kuliah jurusan sastra Inggris. Bapak juga enggak tahu dia dapat pengaruh dari mana.” Pak Asep tergelak membayangkan style dandanan dan gaya bicara putri semata wayangnya itu.
Oh, pantesan atuh si Eneng teh begitu. Sekali lagi Aden manggut-manggut.
“Makanya, Den, kalau memang kalian ditakdirkan berjodoh, Bapak titip Sopi ya. Selama ini Bapak belum maksimal membimbing dia, terutama dalam hal agamanya. Tolong, bimbing dia untuk lebih mengenal Islam.” Pak Asep menepuk-nepuk pundak Aden.
Aden mengangguk. “Pak, udah enggak capek kan? Kita lanjutkan mencari Neng Sopi yuk.”
Pak Asep mengangguk, kemudian dua laki-laki itu beranjak dari teras mesjid. Berdua mereka melangkah meninggalkan mesjid, melanjutkan pencarian.
***
Baca cerpen lainnya di sini:
[Link DISINI[URL=]link di sini[/URL]


Sumber: gambar di sini
Sepagi ini kedai Mak Otih sudah penuh sesak. Serabi buatan Mak Otih memang yang paling terkenal di desa Cipedes ini. Penganan yang terbuat dari campuran tepung terigu yang gurih dan air kelapa, banyak diburu oleh warga desa ini dan menjadi alternatif pilihan untuk sarapan. Cara memasaknya yang masih tradisional—menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat serta kayu bakar di bawahnya untuk mematangkan serabinya—membuat serabi ini memiliki rasa dan aroma yang khas. Varian serabinya hanya dua macam, yaitu topping oncom sangrai untuk rasa asin, dan serabi disiram kuah gula merah atau kinca untuk yang rasa manis. Bahkan, untuk serabi topping oncom bisa ditambahkan telur agar rasanya semakin gurih.
Sopi mengamati tangan Mak Otih yang menyendok adonan serabi ke dalam wajan tanah liat dengan cekatan. Adonan yang masih cair itu kemudian ditaburi oncom sangrai. Asap mengepul dari sana. Aroma serabi yang hampir matang membuat gadis itu menelan saliva berulang kali. Perutnya semakin keroncongan. Terbayang di mulutnya rasa legit kuah kinca bercampur dengan kue serabi yang gurih, lezat rasanya.
Empat orang pemuda iseng mulai melirik nakal ke arah Sopi yang terlihat cantik. Salah satu dari mereka mulai menggodanya.
"Hai, Neng geulis, sendirian aja nih. Boleh Akang temenin?"
"Akang mah mau langsung kenalan aja, boleh enggak?" Seorang pemuda lainnya mulai mendekati Sopi. Sementara dua pemuda yang lainnya hanya tertawa-tawa.
Sopi mulai jengah dengan gangguan dari keempat pemuda itu. Bahkan salah satunya yang tadi minta kenalan mulai berani mencolek lengannya. Segera saja Sopi menepis tangan jahil pemuda jangkung berambut keriting itu. Memangnya aku ini sabun colek apa? pikir Sopi, kesal.
"Widih, si Eneng meuni sombong ih. Belum tahu ya kita ini siapa? Kita teh F4, tapi bukan pemeran di drama Meteor Garden ya. Saya Firman, itu Fikri, Farid, dan Ferdi." Pemuda berkaus biru donker berlogo salah satu superhero terkenal di dunia, menunjuk ke arah ketiga temannya sambil ikut mendekat ke arah Sopi.
Sopi masih membisu, dalam hati ia geram dengan tingkah para pemuda itu. Perempuan di kedai ini kan banyak, kenapa hanya aku yang diperlakukan seperti ini? gumamnya.
Melihat gadis itu beranjak dari tempat duduknya, hendak berlalu dari kedai, keempat pemuda itu malah semakin gencar menggodanya.
"Mau ke mana Neng? Buru-buru amat. Kita kan belum saling mengenal. Tukeran nomor hp aja belum, udah mau pergi. Rumahnya di mana sih? Akang antar ya. Tenang, dijamin aman, selamat sampai tujuan." Pemuda berkaus hitam bergambar logo band Linkin Park mengejar Sopi dan menggenggam tangan gadis itu.
Sopi berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman tangan pemuda itu malah semakin kuat. Ia meringis kesakitan. Keempat pemuda itu tertawa puas.
"Heii, kalian! Lepaskan gadis itu. Belum tahu ya kalau dia itu pacar saya? Seenaknya main antar pacar orang. Yuk, Neng Akang antar." Suara seorang lelaki tampan berdandan ala Kabayan berhasil menghalau keempat pemuda itu. Mereka pun menjauh dari Sopi. Setelah berpamitan pada Emaknya yang tengah membalikkan serabi dari wadah, pemuda itu pun berjalan beriringan dengan sang gadis.
"Yuk, Neng. Enggak usah takut, saya mah bukan lelaki cunihin seperti mereka. Kalau mau jahil ke perempuan, saya selalu ingat sama Emak. Gimana kalau Emak juga digodain kayak gitu? Saya pasti marah besar," ucap lelaki itu setelah agak menjauh dari kedai.
Dalam hati, Sopi memuji ucapan pemuda di sampingnya yang sangat santun dan hormat memperlakukan ibunya. Yang jadi istrinya, sudah pasti akan diperlakukan dengan baik juga. Sopi malu sendiri, dan buru-buru menepis pikiran yang baru saja terlintas di benaknya. Mereka berjalan berdampingan. Keduanya sama-sama merasa canggung, tak ada yang berani membuka percakapan. Hanya sesekali mereka saling beradu pandang, kemudian sama-sama tersenyum dan menunduk, malu. Hingga tiba di tempat tujuan pun, mereka masih diam seribu bahasa.
Sementara itu, Pak Asep yang sedari tadi merasakan perasaannya tak enak, selalu terbayang wajah putri cantiknya. Rasa kuatir menggelayuti pikirannya, takut sesuatu menimpa Sopi. Sesekali ia menatap ke arah jalan, mencari sosok yang membuat hatinya gelisah. Tidak berapa lama, ia melihat gadis itu. Namun, ia tidak sendirian, seorang pemuda jangkung terlihat berjalan di sampingnya.
"Hei, pemuda, siapa kamu? Kenapa tampang anakku seperti ketakutan begitu? Hmm, mau macam-macam ya sama anak Jawara Pencak Silat ini? Hayu lah, Bapak mah enggak takut. Kita tandang di lapang sebelah!" Pak Asep sudah pasang kuda-kuda, bersiap untuk menyerang sosok yang terlihat sebagai ancaman bagi putri tersayangnya. Sopi dan Aden pun bengong.
Dengan kekuatan penuh, Pak Asep bersiap melayangkan pukulan ke arah pemuda tampan yang sedang berdiri di samping putrinya.
“Daddy—Daddy, calm down.” Sopi menghalangi serangan ayahnya dengan menggenggam tangan pria paruh baya itu yang sudah bulat terkepal dengan sempurna.
“Minggir, Sopi. Biar dia merasakan bogem mentah Bapak. Walau Bapakmu ini sudah tua, tapi Bapak masih kuat. Ayo sini, pemuda, lawan!” Pak Asep menghempaskan tangan Sopi yang menghalanginya.
“Pak Asep? Ini benar Pak Asep kan? Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu juga.” Aden mencium punggung tangan pria di hadapannya yang napasnya masih tak beraturan. Emosi memenuhi rongga dadanya. Kedua matanya memelotot ke arah pemuda itu.
“Apa-apaan kamu? Diajak tanding malah cium tangan? Nyalimu ciut, Jang?” Pak Asep menghempaskan tangan Aden dengan kasar.
“Bapak lupa ya? Ini teh Aden, putranya Mak Otih. Dulu waktu SD Aden kan belajar pencak silat dari Bapak. Wah senangnya masih bisa berjumpa dengan guru bela diri favorit Aden.”
Mendengar penuturan pemuda yang berdiri di hadapannya, perlahan-lahan emosi Pak Asep menurun. “Jadi, ini Aden? Masya Allah, meuni kasep. Maafkan Bapak yang terlalu kuatir dengan keselamatan putri Bapak satu-satunya. Maklum, sejak Ibunya meninggal, hanya dia yang Bapak miliki di dunia ini. Bapak enggak mungkin lupa, hanya tadi mah pangling aja, sampai-sampai enggak ngenalin. Kamu kan yang pernah ngompol, ketakutan karena Bapak bentak, hahaha. Terus kamu itu terkenal paling cengeng di antara murid-murid Bapak yang lain. Kesenggol sedikit saja nangis kejer.” Pak Asep menepuk-nepuk pundak bekas murid pencak silatnya itu.
Aden tersipu malu sambil melirik gadis cantik di sampingnya yang sedang bengong menyaksikan percakapan antara dirinya dan Pak Asep. “Jadi, Eneng ini teh putrinya Bapak?” lanjutnya.
“Iya, ini namanya Sopi, anak Bapak. Hayu atuh masuk, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Sopi suguhkan makanan sama minuman.”
Sopi beranjak menuju dapur menyiapkan suguhan untuk sang tamu. Sementara itu Aden dan sang Ayah sudah duduk di kursi ruang tamu. Sesekali, Pak Asep melirik Aden yang mencuri pandang ke arah Sopi. Sepertinya pemuda itu tertarik pada putrinya. Sebuah senyuman tersungging di bibir lelaki paruh baya itu. Sementara Aden, yang kepergok sedang curi-curi pandang, jadi salah tingkah. Hatinya mengakui perempuan itu memang cantik, hanya dandanannya saja yang menurutnya terlalu berlebihan alias menor. Andai gadis itu berdandan sederhana, aura kecantikannya akan terpancar alami. Tidak berapa lama, Sopi muncul dengan baki berisi dua gelas teh manis dan beberapa stoples berisi kue kering juga makanan ringan.
“Ayo—ayo dimakan, Den,” tawar Pak Asep setelah Sopi menaruh semua bawaannya di atas meja.
“Eh iya, ngomong-ngomong serabi pesanan Bapak mana?” Kali ini pandangan mata pria itu beralih pada Sopi.
“My mood is going down, Daddy. So maafkan Sovia yang tak jadi membelinya.”
Aden menatap heran gadis yang duduk di samping Pak Asep. Buset, bukan hanya dandanannya yang lain, cara bicaranya juga aneh, gumamnya.
“Kok bisa?” Kening Pak Asep berkerut. Tak mengerti dengan kalimat yang diucapkan putrinya barusan. Sejurus kemudian, lelaki itu manggut-manggut menyimak cerita putrinya.
“Duh, Den. Maafkan Bapak yang sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Terima kasih telah menyelamatkan putri Bapak." Sudah waktunya Sopi punya pendamping hidup, yang akan melindunginya dari marabahaya, gumam Pak Asep dalam hati sambil menatap lekat-lekat Aden yang sedang mencuri pandang ke arah wajah Sopi. Untung saja, pemuda ini baik hati, jadi dia tetap membiarkan Aden memandang wajah Sopi sampai puas. Kalau pemuda culas yang melakukannya, pasti sudah dia gibas tanpa ampun sampai kapok.
***
“Daddy, ini kopinya.”
“Terima kasih, Sopi.” Gadis cantik itu mengangguk dan beranjak hendak menuju kamarnya.
“Sopi, mau ke mana? Sini duduk dulu sebentar, Bapak mau bicara.”
“Daddy, Sovia mau ke kamar, belum beres merapihkan alis.”
“Bentar doang kok. Enggak nyampe lima belas menit.” Pak Asep menyeruput kopinya. “Sopi, kopi buatan kamu mengingatkan Bapak sama almarhumah Ibumu. Racikannya sama-sama enak. Rasa kopi dan gulanya seimbang, pas.”
Sopi tersenyum melihat Ayahnya yang begitu penuh penghayatan menyeruput kopinya, terlihat sekali pria paruh baya itu menikmati setiap tegukan cairan hitam itu yang masuk ke kerongkongannya.
“Jadi begini, Geulis. Kamu sekarang sudah besar. Kuliah pun sudah selesai.” Pak Asep menatap wajah putri tersayangnya sebelum ia melanjutkan bicara. Pria itu tampak memutar otak mencari kalimat yang pas untuk menyampaikan maksudnya pada Sopi. “Sudah saatnya Bapak melepasmu, Sopi,” lanjutnya.
“Maksud Daddy?” Sopi tercengang mendengar ucapan lanjutan dari Ayahnya. Dahinya berkerut, tak paham dengan arah pembicaraan sang Ayah.
“Begini, Neng. Maksud Bapak—kamu—sudah waktunya kamu punya pendamping hidup.”
“What? Jadi maksud Daddy Sovia harus segera married? Menikah begitu? No, Daddy!”
“Dengar dulu Sopi. Bapak sudah pikirkan matang-matang hal ini. Bapak ....”
“Tapi, Daddy. Sovia enggak mau berpisah dari Daddy.” Sopi mulai terisak.
“Jangan nangis atuh, Neng. Bapak kan jadi ikut sedih. Setelah menikah nanti Sopi boleh kok tinggal di sini. Lagian calon kamu juga tinggalnya deket-deket sini kok.” Pak Asep mengelus lembut punggung putri tercintanya itu.
“Memangnya siapa orangnya, Daddy?” tanya Sopi, heran. Keningnya berkerut, seolah mencari siapa sosok pemuda yang tinggal di dekat sini. Ia menggelengkan kepalanya, nihil. Tak satu pun wajah lelaki yang bisa terbayang di benaknya.
“Kamu mau kan Bapak nikahkan sama Aden?” Pak Asep malah balik bertanya.
Sopi terperanjat mendengar Ayahnya menyebut nama itu. “What? Daddy enggak salah jodohin Sovia sama dia? Orangnya ganteng sih, tapi dandanannya persis seperti si Kabayan. Jangan-jangan dia juga pemalas, sama seperti Kabayan itu.”
“Sopi, kamu ingat waktu dia melindungi kamu dari pemuda-pemuda yang mengganggu?” Sopi mengangguk. “Nah, Bapak rasa dia bisa menjaga kamu dengan baik. Kesan pertama melihat dia, Bapak yakin dia anak yang baik, tidak seperti kebanyakan pemuda lainnya.”
Sopi tertegun. Pak Asep membiarkan gadis itu hanya diam saja, mungkin putrinya sedang mencoba meresapi semua ucapannya. Hanya helaan napas gadis cantik itu yang sesekali terdengar.
Setelah hening beberapa saat, tak lama kemudian, Sopi pun buka suara, “Baiklah, Daddy, beri Sovia waktu untuk berpikir.” Gadis itu menyeret langkahnya menuju kamar, meninggalkan Pak Asep yang di hatinya tengah berharap sang putri mau menerima rencana perjodohan ini.
Satu jam berlalu. Namun, tak ada tanda-tanda Sopi keluar dari kamarnya. Pak Asep pun merasa heran. Ia mulai mengetuk pintu kamar Sopi.
“Sopi, Neng, sarapan yuk.” Tak ada sahutan. “Geulis, Bapak udah bikinin telor ceplok kesukaan kamu. Kita makan bareng yuk.” Tetap tak ada sahutan. “Sopi, lagi apa di dalam? Masih dandan atau lanjutin mimpi? Masa baru juga bangun udah tidur lagi.”
Karena tak terdengar juga sahutan dari Sopi, Pak Asep membuka pintu kamar yang ternyata tak dikunci oleh pemiliknya. Namun, betapa kagetnya Pak Asep saat ia tak menemukan putrinya di dalam kamar itu. Ia mendapati jendela kamar putrinya terbuka lebar.
“Sopi? Kamu di mana, Nak? Ini mah ngajak Bapak main petak umpet ya?” Pak Asep mulai berkeliling ke seluruh ruangan, tetapi tetap saja ia tak menemukan putrinya. “Duh, Sopi. Kamu teh ke mana atuh? Bapak jadi kuatir.” Pak Asep memutuskan kembali ke kamar Sopi, siapa tahu di sana dia bisa menemukan petunjuk. Netra Pak Asep jatuh pada secarik kertas di atas nakas yang berisi tulisan tangan Sopi.
Daddy, maaf, Sovia gak bermaksud bikin Daddy cemas. Sovia hanya kesal mendengar rencana Daddy. Biarlah Sovia bertemu jodoh Sovia dengan sendirinya. Dan Sovia akan menikah setelah benar-benar merasa siap. Don’t worry Daddy, saat Daddy membaca surat ini, Sovia sudah berada di rumah Grandma.
Setelah membaca surat itu, Pak Asep yang sedari tadi pikirannya kalut, kini merasa lega. Bergegas lelaki itu melangkah ke luar hendak menyusul Sopi ke rumah Mak Onah. Wanita itu tampak sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya. Ia merasa heran saat dari kejauhan tampak putranya sedang berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Wanita itu pun menyuruh putranya masuk dan menyodorkan segelas air putih yang langsung diteguk habis oleh Pak Asep.
“Heh, nyari apaan kamu teh? Tuh minum udah Emak ambilin. Kalau cemilan mah kebetulan lagi kosong.” Mak Onah memandang heran putranya yang mengedarkan pandangan ke seluruh sudut rumahnya.
“Mak, Sopi ada di sini?” Kembali Pak Asep mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan di rumah Emaknya.
Kening Mak Onah berkerut, heran dengan pertanyaan putranya. “Kalian kan tinggal serumah, kok nanya Sopi ke Emak?”
“Jadi, Sopi enggak ada di sini?” Pak Asep malah balik bertanya. Wajahnya mulai terlihat panik. Ia pun bangkit dari duduknya.
“Mau ke mana, Sep? Ada apa sebenarnya?” Asep menyerahkan surat yang ditulis Sopi kepada Mak Onah. Sejurus kemudian wanita itu membacanya dengan saksama. Raut wajahnya tampak serius.
“Seharusnya sudah sejam yang lalu dia tiba di sini,” ucap Mak Onah pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri.
“Duh, Sopi teh ke mana atuh ya, Mak?” Hati Pak Asep semakin diliputi rasa kuatir. Peluh mulai bercucuran di pelipisnya. Raut wajah Mak Onah pun sama-sama tegang, ikut merasakan kegelisahan yang sedang melanda putranya.
“Makanya, ini kan bukan zaman Siti Nurbaya. Kamu teh meuni seenaknya jodoh-jodohin Sopi.”
Pak Asep menyesali tindakannya, hingga membuat gadis itu pergi dari rumah. Kini entah di mana putrinya berada. Tak berapa lama, ia pun pamit untuk mencari putri kesayangannya. Namun, Mak Onah yang juga merasa sangat kuatir akan keberadaan cucunya, minta untuk ikut mencari. Akhirnya, mereka berdua berjalan menyusuri desa, berharap menemukan sosok cantik yang sangat dicintai.
“Sep, ngapain kamu bawa Emak ke kedai ini? Kamu belum sarapan? Kenapa tadi enggak makan di rumah Emak atuh?!” Mak Onah tampak kesal saat putranya membawa dia ke kedai serabi milik orang yang sangat dibencinya. Dulu, Mak Otih pernah berusaha merebut sang suami. Untunglah almarhum suaminya itu setia, sehingga tidak tergoda sedikit pun. Matanya menerawang, senyumnya terkembang ketika membayangkan sosok gagah perkasa sang suami yang mirip Gatotkaca.
Pak Asep memandang heran Mak Onah yang memasang muka cemberut. Sungguh, ia tak mengerti mengapa Ibunya begitu membenci Mak Otih dan sama sekali tak mau makam kue serabi yang terkenal lezat ini.
“Assalamuaalaikum, Mak. Aden ada?” Pak Asep mencium takzim punggung tangan Mak Otih. Mak Onah memalingkan wajah melihatnya. Sebal.
“Waalaikumsalam, ada, sebentar ya, Den, Aden, ada yang nyari nih!” teriak Mak Otih. Tidak berapa lama, Aden pun keluar.
“Eh, Pak Asep, ada apa Pak?” Aden mencium tangan Pak Asep, kemudian ia hendak mencium punggung tangan Mak Onah, namun Neneknya Sopi itu tak membalas uluran tangan pemuda ganteng itu.
“Sep, Emak mah pulang aja ya, panas lama-lama berada di sini. Kabari Emak kalau Sopi sudah ditemukan.” Mak Onah melangkahkan kakinya lebar-lebar, bergegas meninggalkan kedai itu, diiringi tatapan bengong Pak Asep dan pandangan heran Aden juga Mak Otih.
“Maafin Emak saya, ya. Beliau lagi sakit gigi, jadinya agak sensitif begitu.” Pak Asep mencoba mencari alasan atas sikap Mak Onah.
Aden memandang heran ke wajah mantan guru pencak silatnya yang kelihatan tegang itu. Pak Asep menceritakan tentang kepergian Sopi dari rumah yang katanya mau minggat ke rumah Nenek, tetapi gadis itu tak diketahui ke mana rimbanya. Setelah pamit pada Mak Otih, mereka berdua pun berangkat menyusuri setiap sudut desa mencari keberadaan gadis cantik itu.
***
“Duh, Den, kita harus cari ke mana lagi ya? Belum terlihat tanda-tanda keberadaan Sopi. Kamu di mana atuh Geulis? Baik-baik aja kan di sana?” Pak Asep terlihat sangat cemas. Wajahnya membiaskan kelelahan. Namun, ia tepiskan rasa itu. Kuatir akan keadaan putrinya lebih besar dibandingkan apapun juga.
“Sabar, Pak, kita belum menyusuri seluruh ruas jalan desa ini. Udah Zuhur, Pak. Kita salat dulu di masjid itu yuk, sambil memanjatkan doa buat Neng Sopi juga.” Aden menunjuk sebuah mesjid besar yang terletak di ujung gang.
Pak Asep mengangguk lemah. Tidak berapa lama, mereka berdua sudah berbaur dengan orang-orang, khusyuk menunaikan salat Zuhur berjamaah di mesjid itu serta memanjatkan doa untuk Sopi.
“Den, kita istirahat sebentar di sini.” Pak Asep menenggak air mineral di dalam botol, kemudian ia menyodorkan satu botol lagi pada Aden. “Nih, minum dulu, Den.”
“Terima kasih, Pak. Oh, ya, boleh Aden tanya-tanya tentang Neng Geulis?” ucap Aden dengan nada ragu dan malu-malu.
“Tentu saja, biar lebih tahu tentang calon istrimu.” Pak Asep memandang wajah pemuda calon menantunya itu, yang raut wajahnya sedang tampak merah jambu itu.
Pipi Aden bersemu merah, hatinya berdesir aneh. “Pak, ngomong-ngomong sejak kapan Ibunya Neng Sopi meninggal?”
“Ibunya meninggal saat melahirkan dia. Makanya Bapak selalu berusaha membahagiakan dia, kasihan sejak kecil dia enggak merasakan kasih sayang seorang Ibu.” Netra Pak Asep berkaca-kaca. Sekelebat bayang wajah sang istri muncul di pelupuk matanya.
Aden manggut-manggut, “Lantas, Pak—maaf sebelumnya kalau Aden lancang, tetapi Aden penasaran sama dandanan juga gaya bicara Neng Geulis yang—maaf, terlihat aneh.”
“Hahaha, iya dia memang unik. Logat bicaranya dan dandanannya seperti itu sejak lulus kuliah jurusan sastra Inggris. Bapak juga enggak tahu dia dapat pengaruh dari mana.” Pak Asep tergelak membayangkan style dandanan dan gaya bicara putri semata wayangnya itu.
Oh, pantesan atuh si Eneng teh begitu. Sekali lagi Aden manggut-manggut.
“Makanya, Den, kalau memang kalian ditakdirkan berjodoh, Bapak titip Sopi ya. Selama ini Bapak belum maksimal membimbing dia, terutama dalam hal agamanya. Tolong, bimbing dia untuk lebih mengenal Islam.” Pak Asep menepuk-nepuk pundak Aden.
Aden mengangguk. “Pak, udah enggak capek kan? Kita lanjutkan mencari Neng Sopi yuk.”
Pak Asep mengangguk, kemudian dua laki-laki itu beranjak dari teras mesjid. Berdua mereka melangkah meninggalkan mesjid, melanjutkan pencarian.
***
Baca cerpen lainnya di sini:
[Link DISINI[URL=]link di sini[/URL]

Diubah oleh suciasdhan 30-06-2020 09:33
novianalinda dan 79 lainnya memberi reputasi
80
14.2K
634
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.7KThread•52KAnggota
Tampilkan semua post
TS
suciasdhan
#27
You're My Destiny
Penantian Tiada Akhir
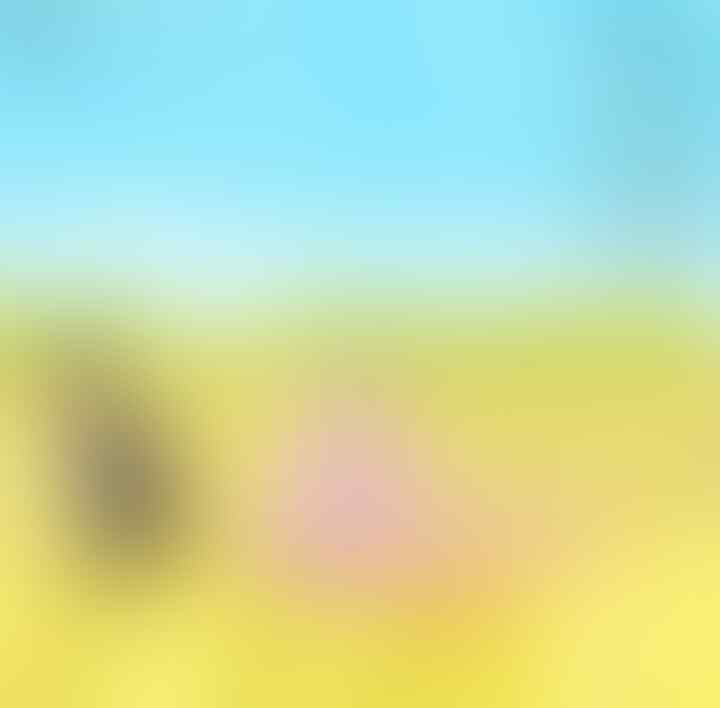
Sumber:
gambar di sini
“Sudah, Rin, nggak usah ditungguin lagi, ikhlaskan. Mas-mu sudah tenang di sisi-Nya.” Bu Ranty menatap iba putri kesayangannya yang masih termenung berjam-jam menatap senja dari jendela rumah.
“Ibu jangan bicara begitu. Aku yakin Mas Arya suatu saat pasti pulang.” Rintan mulai terisak, matanya berkaca-kaca. Pandangannya masih terpaku, lurus menatap senja.
“Rin, tujuh tahun tanpa kabar, orang tua Nak Arya juga sudah ikhlas, putranya telah tiada. Saatnya kamu membuka mata dan hatimu, kamu berhak untuk bahagia, walau pun itu dengan lelaki lain. Ibu yakin, Mas-mu di alam sana ikhlas, ikut senang jika kamu berbahagia.”
“Cukup Bu, aku yakin dia suatu saat akan datang,” Rintan berlari menuju kamar. Air matanya mengalir deras, tak mampu dibendung. Hatinya seketika merasakan sakit, perih yang teramat sangat.
Ingatannya kembali pada kenangan saat Mas Arya tunangannya pamit dan berjanji akan kembali kemudian meminangnya menjadi istri. Janji inilah yang Rintan pegang hingga kini.
***
“Rin, alhamdulillah Mas diterima kerja di proyek daerah Kalimantan,” ucap Arya pada Rintan, gadis berkulit kuning langsat dan berlesung pipit yang sudah satu tahun ini menjalin kasih dengannya.
Seketika wajah Rintan muram. “Jadi Mas tega ninggalin aku di Jakarta?” Entah mengapa perasaan Rintan menjadi tak menentu.
“Rin, Mas sudah lama menantikan kabar gembira ini, Mas sangat ingin bekerja di sana, gaji nya kan lumayan, Rin. Dan nantinya dipakai buat masa depan kita juga.”
“Tapi kita bakal jarang bertemu ...,” lirihnya, penuh keraguan melepas sang kekasih merantau.
“Rin, walau pun Mas jauh, Mas akan tetap setia. Mas janji sepulang dari sana Mas akan melamarmu, kita nikah, Mas pasti kembali, tunggu kepulangan Mas di taman ini ya,” Arya mengelus lembut rambut sebahu tunangannya, berusaha menepis keraguan sang pujaan hati.
Rintan mengangguk, ia menyandarkan kepala di bahu Arya, berusaha mengusir gelisah dalam dada. Taman favorit mereka ini menjadi saksi akan janji yang diucapkan sang kekasih pada Rintan. Semilir angin sore menerpa wajah keduanya, menambah syahdu suasana.
“Happy first anniversary, Rintan Sayang, I love you so much.” Arya berlutut di hadapan sang kekasih yang tengah duduk di bangku taman dan memberikan setangkai mawar merah padanya.
Debar di dada Rintan semakin menggebu, ia tersipu sekaligus bahagia diperlakukan demikian. Namun entah mengapa, ia tetap merasa gelisah, apa karena ke depannya jarak akan memisahkan mereka? Diambilnya mawar merah itu dari genggaman Arya, ia hirup dalam-dalam wanginya. Semoga selamanya masih bisa menghirup wanginya, karena ini yang selalu mengingatkanku padamu, Mas, I’ll be missing you, gumamnya sembari menatap lekat wajah sang kekasih yang sebentar lagi akan LDR-an dengannya.
Seminggu sejak kepergian Arya, masih juga mengundang gundah di hati Rintan. Ia berusaha menepis perasaan resahnya, mungkin ia rindu pikirnya. Malam yang sunyi ini membuat rasa kangennya semakin menggebu. Rintan tengah membolak-balik majalah, tiba-tiba ia dikagetkan suara dering ponselnya. Muncul nama kontak Bu Darmi, calon mertuanya. Deg, seketika perasaan resah itu kembali mendera. Ada apa gerangan Ibu menghubungi malam-malam begini?
“Nak, Rintan, yang sabar ya. Kamu harus kuat, Arya kecelakaan, bus yang ditumpanginya masuk jurang, banyak korban yang belum ditemukan jasadnya, termasuk Arya.” Terbata-bata suara dari seberang sana berusaha tegar menyampaikan kabar buruk itu.
Ponsel dalam genggaman Rintan jatuh. Seketika pandangannya terasa mengabur, perlahan semua menjadi gelap, sayup-sayup terdengar suara Ibu memanggil namanya.
***
Tujuh tahun sejak kabar tragis itu, Rintan masih saja tak bisa membuka diri untuk lelaki lain singgah di hatinya. Sebenarnya, ada beberapa yang berusaha mendekati, malah Ibu pun pernah beberapa kali menjodohkannya, tetapi tetap ia bergeming pada pendiriannya. Entah mengapa, ia selalu punya keyakinan, Mas Arya itu masih hidup. Kekasihnya itu berada di suatu tempat, baik-baik saja, dan akan menepati janjinya untuk pulang. Baginya, Mas Arya itu menjadi satu-satunya yang mampu mengisi duka lara sejak ayahnya berpulang. Rintan yang sangat dekat dengan sosok sang Ayah, begitu terpukul mendapati ayahnya telah tiada. Arya-lah yang setia menghibur, membuat ia bangkit dari keterpurukan.
Hubungannya dengan orang tua Arya pun saat ini masih tetap erat. Ia sudah menganggap kedua orang tua Arya layaknya Ayah dan Ibunya sendiri. Meskipun mungkin akhirnya ia tak bisa menjadi menantu di keluarga itu, namun setiap pagi sambil berangkat kerja, ia selalu menyempatkan mampir dan membawa makanan. Sore harinya sepulang kerja, ia pergi ke taman favorit Arya dan dirinya. Di sana ia menghabiskan waktu hanya sekedar duduk berlama-lama, mengenang kebersamaannya dengan sang kekasih. Di lubuk hatinya yang paling dalam, ia berharap Arya datang menemuinya di tempat favorit mereka, seperti janji Mas Arya yang sempat terucap. Entahlah, walau pun orang-orang percaya Arya telah tiada, tetapi ia sangat yakin, pujaannya itu masih ada. Suatu saat akan pulang, kembali menemuinya, menepati janji yang telah terucap.
Pagi ini Rintan telah bersiap berangkat kerja. Ia membawa dus berisi bolu pandan kesukaan Ibunya Arya. Ini hal rutin yang selalu ia lakukan sebelum berangkat kerja, mampir ke rumah Arya, bercerita dengan Ibu Darmi tentang masa kecil Arya, atau sekedar membuka-buka album foto dengan wajah Arya terpampang di sana. Aktivitas ini bisa membuat kedua wanita itu tertawa dan menangis bersama.
Sesampainya Rintan di halaman rumah Arya, langkahnya terhenti sejenak. Gadis itu menghela napas, melihat sekeliling. Dadanya terasa sesak.
Betapa banyak kenangan manis bersamamu, Mas, mana mungkin aku bisa lupa, ia bersenandika.
“Assalamu alaikum, Bu, ini Rintan.” Berkali-kali ia mengetuk pintu, tetapi tak ada sahutan.
Dari balik pintu yang masih ditutup rapat, terdengar isakan Bu Darmi, “Rintan, sudah, Nak. Ibu mohon jangan ke sini lagi, lupakan Ibu, lupakan juga Arya, ia telah tiada. Kamu berhak bahagia, Nak, jalanmu masih panjang. Ibu mohon, jangan datang lagi.”
“Bu, memangnya aku salah datang ke mari?”
“Iya, Nak, ini hanya akan membuat Ibu semakin teringat Arya. Ibu juga kasihan padamu, Nak. Sampai kapan kamu akan menyimpan harapan semu? Berhenti meyakini Arya masih ada, dia sudah tenang di sana, Ibu juga sangat kehilangan dia, Nak. Namun Ibu ikhlas, Allah lebih sayang padanya. Terimalah kenyataan, walau itu pahit, saatnya kamu melanjutkan hidup.”
Rintan berbalik dan berlari menjauh dari halaman rumah Bu Darmi. Dari balik jendela, wanita paruh baya itu menatap kepergian Rintan dengan sedih. Hatinya teriris pedih. “Maafkan Ibu, Nak. Ibu tak bermaksud menyakitimu, Ibu lakukan ini demi kebaikanmu ...,” ucapnya lirih.
Air mata Rintan membanjiri pipi. Sakit rasanya hati ini, ia berlari menjauh dari sana, mood nya untuk berangkat kerja seketika hilang. Gadis itu berbalik arah menuju taman kota, menumpahkan segala luka hatinya di sana.
“Mas ..., kumohon datanglah, aku yakin kau masih ada. Aku percaya, kau lelaki yang tak pernah ingkar, kau akan menepati janji, iya, ‘kan? Kau akan datang ke taman ini menemuiku ....” Rintan mulai terisak, bulir bening membanjiri pipinya.
Menjelang malam, ia pulang ke rumah. Dengan langkah gontai, ia masuk kamar, mengurung diri, hal yang selalu ia lakukan saat ia merasa tak berdaya. Ibu menyaksikan langkah gontai putri semata wayangnya itu dengan tatapan sedih, tak tega untuk mengutarakan tanya. Ia tahu saat ini perasaan putrinya tengah hancur.
***
“Mau ke mana, Rin, pagi-pagi begini sudah rapi?”
“Rintan mau ke taman Bu, sekalian jogging.” Rintan mengikat tali sepatunya, bersiap untuk berangkat. Gadis itu mengenakan setelan trening biru langit, menambah ayu parasnya.
“Rin, mau apa kamu ke sana? Masih tetap menunggu Arya datang? Sampai kapan sih kamu akan terus-menerus seperti ini? Mumpung hari Minggu, mending temenin Ibu arisan yuk, anaknya teman Ibu ada yang mau kenalan sama kamu.”
“Ibu, udah deh, ini bukan zaman Siti Nurbaya.” Gadis itu memutar kedua bola matanya, seraya menghela napas berat, kesal.
“Rin, Ibu cuma kasihan sama kamu. Sampai kapan kamu tetap menanti Arya-mu yang tak kunjung datang itu? Kamu mau seumur hidup nggak nikah-nikah?”
“Ibu, salahkah Rintan yang memiliki keyakinan kalau Mas Arya itu masih hidup?”
“Ya, ampun, Rin, sudah delapan tahun. Kamu masih tetap percaya dia masih ada?”
“Iya, Bu, Rintan sangat percaya, kecuali kalau jasadnya sudah benar-benar ditemukan tak bernyawa, baru Rintan percaya ia tiada.” Rintan mencium takzim punggung tangan sang Ibu kemudian melangkah ke luar.
Ibu menatap punggung putri kesayangannya dengan mata berkaca-kaca. Langkah gadis itu semakin menjauh. Entah apa lagi yang harus dia lakukan untuk menyadarkan putrinya agar bisa ikhlas menerima kenyataan.
Sesampainya Rintan di taman, ia duduk di bangku tempat dulu dirinya dan Arya sering menghabiskan waktu bersama. Gadis itu menghela napas berat, andai kau menemaniku di sini, Mas. Sungguh, aku rindu.
Satu-persatu air mata Rintan luruh. “Happy eighth anniversary, Mas. Kalau Mas ada di sini, pasti bawain aku cokelat sama setangkai mawar merah, terus malamnya ada kejutan candle light dinner. Mas, sungguh, aku kangen kebersamaan kita.” Rintan tergugu. Bahunya berguncang karena tangisnya kini mulai pecah. Gadis itu tak mampu membendung rinai yang mulai menggenang di pelupuk matanya.
“Selamat hari jadi yang ke delapan, Rintan Sayang. Ini untukmu.” Terdengar suara seseorang yang sudah sangat Rintan kenal, berasal dari arah belakang.
Gadis itu berbalik dan betapa terperanjatnya Rintan, tak menyangka dengan sosok yang selama ini sangat dirindukan, kini hadir di hadapannya. Tubuh Rintan bergetar, merasa tak percaya, seolah ia sedang berada di alam mimpi.
“Ya, Allah, Mas Arya ....” Hanya itu yang mampu terucap dari bibir mungilnya. Ia menghambur ke pelukan lelaki yang sangat dicintainya itu.
Lelaki itu memakai kruk. Tumbuh cambang di sekitar dagunya. Rambutnya agak sedikit gondrong. Penampilan Arya sekarang tampak lebih tua dari usianya. Tangan kanannya menggenggam setangkai mawar merah. Arya biarkan sang pujaan tergugu dalam pelukannya.
“Mas, ke mana saja selama ini? Mas tega membiarkanku menunggu selama delapan tahun tanpa kabar?” tanya Rintan dengan suara bergetar di sela-sela isak tangisnya.
“Maafkan aku, Rin. Kecelakaan itu mengakibatkan kedua kakiku harus diamputasi karena sebagian badan bus menimpa kakiku. Aku selama ini dirawat oleh keluarga yang baik hati di Kalimantan sana. Mereka yang mengurus ke rumah sakit, hingga aku berangsur membaik. Maaf aku tak buru-buru pulang. Aku ... aku takut, Rin ....”
“Takut apa, Mas?” Rintan menatap lekat wajah sang pujaan dengan pandangan heran.
“Aku takut kamu melihat keadaanku seperti ini, kamu nggak mau menerimaku lagi. Sempat aku berpikir untuk melepasmu, kamu berhak bahagia dan memiliki masa depan yang baik dengan lelaki normal. Bukan dengan lelaki cacat sepertiku.” Nada bicara Arya bergetar. Netranya mulai berkaca-kaca.
“Mas, selama ini aku selalu setia menantimu. Setiap sore sepulang kerja aku selalu mampir ke taman ini. Berharap Mas datang memenuhi janji. Mas, walau pun semua orang bilang Mas sudah meninggal, hati kecilku selalu membisikkan bahwa Mas masih hidup. Dan, alhamdulillah keyakinanku terbukti. Bagaimana pun keadaanmu, Mas, hati ini hanya milikmu, Mas adalah takdirku. Aku menerimamu apa adanya Mas, karena bahagiaku hanya bersamamu.”
Bergetar Arya mendengar penuturan Rintan. Debar di dadanya kian berpacu. “Jadi masih maukah kamu menjadi istriku, Rin? Walau pun keadaanku begini?”
Rintan mengangguk mantap. Ia semakin mempererat pelukannya. Gadis berlesung pipit itu benar-benar bahagia. Momen inilah yang paling dinantikannya sejak lama. Begitu pun Arya, kebahagiaan membuncah di dadanya, ia merasa bersyukur memiliki kekasih yang begitu tulus mencintainya. Terbukti, walau ia tak lagi seperti dulu, Rintan tetap membuka hati menerimanya kembali.
Ciwidey, 23 Januari 2020
Suci Rahayu
Baca cerpen lainnya di sini:
Indeks Link

Sumber:
gambar di sini
“Sudah, Rin, nggak usah ditungguin lagi, ikhlaskan. Mas-mu sudah tenang di sisi-Nya.” Bu Ranty menatap iba putri kesayangannya yang masih termenung berjam-jam menatap senja dari jendela rumah.
“Ibu jangan bicara begitu. Aku yakin Mas Arya suatu saat pasti pulang.” Rintan mulai terisak, matanya berkaca-kaca. Pandangannya masih terpaku, lurus menatap senja.
“Rin, tujuh tahun tanpa kabar, orang tua Nak Arya juga sudah ikhlas, putranya telah tiada. Saatnya kamu membuka mata dan hatimu, kamu berhak untuk bahagia, walau pun itu dengan lelaki lain. Ibu yakin, Mas-mu di alam sana ikhlas, ikut senang jika kamu berbahagia.”
“Cukup Bu, aku yakin dia suatu saat akan datang,” Rintan berlari menuju kamar. Air matanya mengalir deras, tak mampu dibendung. Hatinya seketika merasakan sakit, perih yang teramat sangat.
Ingatannya kembali pada kenangan saat Mas Arya tunangannya pamit dan berjanji akan kembali kemudian meminangnya menjadi istri. Janji inilah yang Rintan pegang hingga kini.
***
“Rin, alhamdulillah Mas diterima kerja di proyek daerah Kalimantan,” ucap Arya pada Rintan, gadis berkulit kuning langsat dan berlesung pipit yang sudah satu tahun ini menjalin kasih dengannya.
Seketika wajah Rintan muram. “Jadi Mas tega ninggalin aku di Jakarta?” Entah mengapa perasaan Rintan menjadi tak menentu.
“Rin, Mas sudah lama menantikan kabar gembira ini, Mas sangat ingin bekerja di sana, gaji nya kan lumayan, Rin. Dan nantinya dipakai buat masa depan kita juga.”
“Tapi kita bakal jarang bertemu ...,” lirihnya, penuh keraguan melepas sang kekasih merantau.
“Rin, walau pun Mas jauh, Mas akan tetap setia. Mas janji sepulang dari sana Mas akan melamarmu, kita nikah, Mas pasti kembali, tunggu kepulangan Mas di taman ini ya,” Arya mengelus lembut rambut sebahu tunangannya, berusaha menepis keraguan sang pujaan hati.
Rintan mengangguk, ia menyandarkan kepala di bahu Arya, berusaha mengusir gelisah dalam dada. Taman favorit mereka ini menjadi saksi akan janji yang diucapkan sang kekasih pada Rintan. Semilir angin sore menerpa wajah keduanya, menambah syahdu suasana.
“Happy first anniversary, Rintan Sayang, I love you so much.” Arya berlutut di hadapan sang kekasih yang tengah duduk di bangku taman dan memberikan setangkai mawar merah padanya.
Debar di dada Rintan semakin menggebu, ia tersipu sekaligus bahagia diperlakukan demikian. Namun entah mengapa, ia tetap merasa gelisah, apa karena ke depannya jarak akan memisahkan mereka? Diambilnya mawar merah itu dari genggaman Arya, ia hirup dalam-dalam wanginya. Semoga selamanya masih bisa menghirup wanginya, karena ini yang selalu mengingatkanku padamu, Mas, I’ll be missing you, gumamnya sembari menatap lekat wajah sang kekasih yang sebentar lagi akan LDR-an dengannya.
Seminggu sejak kepergian Arya, masih juga mengundang gundah di hati Rintan. Ia berusaha menepis perasaan resahnya, mungkin ia rindu pikirnya. Malam yang sunyi ini membuat rasa kangennya semakin menggebu. Rintan tengah membolak-balik majalah, tiba-tiba ia dikagetkan suara dering ponselnya. Muncul nama kontak Bu Darmi, calon mertuanya. Deg, seketika perasaan resah itu kembali mendera. Ada apa gerangan Ibu menghubungi malam-malam begini?
“Nak, Rintan, yang sabar ya. Kamu harus kuat, Arya kecelakaan, bus yang ditumpanginya masuk jurang, banyak korban yang belum ditemukan jasadnya, termasuk Arya.” Terbata-bata suara dari seberang sana berusaha tegar menyampaikan kabar buruk itu.
Ponsel dalam genggaman Rintan jatuh. Seketika pandangannya terasa mengabur, perlahan semua menjadi gelap, sayup-sayup terdengar suara Ibu memanggil namanya.
***
Tujuh tahun sejak kabar tragis itu, Rintan masih saja tak bisa membuka diri untuk lelaki lain singgah di hatinya. Sebenarnya, ada beberapa yang berusaha mendekati, malah Ibu pun pernah beberapa kali menjodohkannya, tetapi tetap ia bergeming pada pendiriannya. Entah mengapa, ia selalu punya keyakinan, Mas Arya itu masih hidup. Kekasihnya itu berada di suatu tempat, baik-baik saja, dan akan menepati janjinya untuk pulang. Baginya, Mas Arya itu menjadi satu-satunya yang mampu mengisi duka lara sejak ayahnya berpulang. Rintan yang sangat dekat dengan sosok sang Ayah, begitu terpukul mendapati ayahnya telah tiada. Arya-lah yang setia menghibur, membuat ia bangkit dari keterpurukan.
Hubungannya dengan orang tua Arya pun saat ini masih tetap erat. Ia sudah menganggap kedua orang tua Arya layaknya Ayah dan Ibunya sendiri. Meskipun mungkin akhirnya ia tak bisa menjadi menantu di keluarga itu, namun setiap pagi sambil berangkat kerja, ia selalu menyempatkan mampir dan membawa makanan. Sore harinya sepulang kerja, ia pergi ke taman favorit Arya dan dirinya. Di sana ia menghabiskan waktu hanya sekedar duduk berlama-lama, mengenang kebersamaannya dengan sang kekasih. Di lubuk hatinya yang paling dalam, ia berharap Arya datang menemuinya di tempat favorit mereka, seperti janji Mas Arya yang sempat terucap. Entahlah, walau pun orang-orang percaya Arya telah tiada, tetapi ia sangat yakin, pujaannya itu masih ada. Suatu saat akan pulang, kembali menemuinya, menepati janji yang telah terucap.
Pagi ini Rintan telah bersiap berangkat kerja. Ia membawa dus berisi bolu pandan kesukaan Ibunya Arya. Ini hal rutin yang selalu ia lakukan sebelum berangkat kerja, mampir ke rumah Arya, bercerita dengan Ibu Darmi tentang masa kecil Arya, atau sekedar membuka-buka album foto dengan wajah Arya terpampang di sana. Aktivitas ini bisa membuat kedua wanita itu tertawa dan menangis bersama.
Sesampainya Rintan di halaman rumah Arya, langkahnya terhenti sejenak. Gadis itu menghela napas, melihat sekeliling. Dadanya terasa sesak.
Betapa banyak kenangan manis bersamamu, Mas, mana mungkin aku bisa lupa, ia bersenandika.
“Assalamu alaikum, Bu, ini Rintan.” Berkali-kali ia mengetuk pintu, tetapi tak ada sahutan.
Dari balik pintu yang masih ditutup rapat, terdengar isakan Bu Darmi, “Rintan, sudah, Nak. Ibu mohon jangan ke sini lagi, lupakan Ibu, lupakan juga Arya, ia telah tiada. Kamu berhak bahagia, Nak, jalanmu masih panjang. Ibu mohon, jangan datang lagi.”
“Bu, memangnya aku salah datang ke mari?”
“Iya, Nak, ini hanya akan membuat Ibu semakin teringat Arya. Ibu juga kasihan padamu, Nak. Sampai kapan kamu akan menyimpan harapan semu? Berhenti meyakini Arya masih ada, dia sudah tenang di sana, Ibu juga sangat kehilangan dia, Nak. Namun Ibu ikhlas, Allah lebih sayang padanya. Terimalah kenyataan, walau itu pahit, saatnya kamu melanjutkan hidup.”
Rintan berbalik dan berlari menjauh dari halaman rumah Bu Darmi. Dari balik jendela, wanita paruh baya itu menatap kepergian Rintan dengan sedih. Hatinya teriris pedih. “Maafkan Ibu, Nak. Ibu tak bermaksud menyakitimu, Ibu lakukan ini demi kebaikanmu ...,” ucapnya lirih.
Air mata Rintan membanjiri pipi. Sakit rasanya hati ini, ia berlari menjauh dari sana, mood nya untuk berangkat kerja seketika hilang. Gadis itu berbalik arah menuju taman kota, menumpahkan segala luka hatinya di sana.
“Mas ..., kumohon datanglah, aku yakin kau masih ada. Aku percaya, kau lelaki yang tak pernah ingkar, kau akan menepati janji, iya, ‘kan? Kau akan datang ke taman ini menemuiku ....” Rintan mulai terisak, bulir bening membanjiri pipinya.
Menjelang malam, ia pulang ke rumah. Dengan langkah gontai, ia masuk kamar, mengurung diri, hal yang selalu ia lakukan saat ia merasa tak berdaya. Ibu menyaksikan langkah gontai putri semata wayangnya itu dengan tatapan sedih, tak tega untuk mengutarakan tanya. Ia tahu saat ini perasaan putrinya tengah hancur.
***
“Mau ke mana, Rin, pagi-pagi begini sudah rapi?”
“Rintan mau ke taman Bu, sekalian jogging.” Rintan mengikat tali sepatunya, bersiap untuk berangkat. Gadis itu mengenakan setelan trening biru langit, menambah ayu parasnya.
“Rin, mau apa kamu ke sana? Masih tetap menunggu Arya datang? Sampai kapan sih kamu akan terus-menerus seperti ini? Mumpung hari Minggu, mending temenin Ibu arisan yuk, anaknya teman Ibu ada yang mau kenalan sama kamu.”
“Ibu, udah deh, ini bukan zaman Siti Nurbaya.” Gadis itu memutar kedua bola matanya, seraya menghela napas berat, kesal.
“Rin, Ibu cuma kasihan sama kamu. Sampai kapan kamu tetap menanti Arya-mu yang tak kunjung datang itu? Kamu mau seumur hidup nggak nikah-nikah?”
“Ibu, salahkah Rintan yang memiliki keyakinan kalau Mas Arya itu masih hidup?”
“Ya, ampun, Rin, sudah delapan tahun. Kamu masih tetap percaya dia masih ada?”
“Iya, Bu, Rintan sangat percaya, kecuali kalau jasadnya sudah benar-benar ditemukan tak bernyawa, baru Rintan percaya ia tiada.” Rintan mencium takzim punggung tangan sang Ibu kemudian melangkah ke luar.
Ibu menatap punggung putri kesayangannya dengan mata berkaca-kaca. Langkah gadis itu semakin menjauh. Entah apa lagi yang harus dia lakukan untuk menyadarkan putrinya agar bisa ikhlas menerima kenyataan.
Sesampainya Rintan di taman, ia duduk di bangku tempat dulu dirinya dan Arya sering menghabiskan waktu bersama. Gadis itu menghela napas berat, andai kau menemaniku di sini, Mas. Sungguh, aku rindu.
Satu-persatu air mata Rintan luruh. “Happy eighth anniversary, Mas. Kalau Mas ada di sini, pasti bawain aku cokelat sama setangkai mawar merah, terus malamnya ada kejutan candle light dinner. Mas, sungguh, aku kangen kebersamaan kita.” Rintan tergugu. Bahunya berguncang karena tangisnya kini mulai pecah. Gadis itu tak mampu membendung rinai yang mulai menggenang di pelupuk matanya.
“Selamat hari jadi yang ke delapan, Rintan Sayang. Ini untukmu.” Terdengar suara seseorang yang sudah sangat Rintan kenal, berasal dari arah belakang.
Gadis itu berbalik dan betapa terperanjatnya Rintan, tak menyangka dengan sosok yang selama ini sangat dirindukan, kini hadir di hadapannya. Tubuh Rintan bergetar, merasa tak percaya, seolah ia sedang berada di alam mimpi.
“Ya, Allah, Mas Arya ....” Hanya itu yang mampu terucap dari bibir mungilnya. Ia menghambur ke pelukan lelaki yang sangat dicintainya itu.
Lelaki itu memakai kruk. Tumbuh cambang di sekitar dagunya. Rambutnya agak sedikit gondrong. Penampilan Arya sekarang tampak lebih tua dari usianya. Tangan kanannya menggenggam setangkai mawar merah. Arya biarkan sang pujaan tergugu dalam pelukannya.
“Mas, ke mana saja selama ini? Mas tega membiarkanku menunggu selama delapan tahun tanpa kabar?” tanya Rintan dengan suara bergetar di sela-sela isak tangisnya.
“Maafkan aku, Rin. Kecelakaan itu mengakibatkan kedua kakiku harus diamputasi karena sebagian badan bus menimpa kakiku. Aku selama ini dirawat oleh keluarga yang baik hati di Kalimantan sana. Mereka yang mengurus ke rumah sakit, hingga aku berangsur membaik. Maaf aku tak buru-buru pulang. Aku ... aku takut, Rin ....”
“Takut apa, Mas?” Rintan menatap lekat wajah sang pujaan dengan pandangan heran.
“Aku takut kamu melihat keadaanku seperti ini, kamu nggak mau menerimaku lagi. Sempat aku berpikir untuk melepasmu, kamu berhak bahagia dan memiliki masa depan yang baik dengan lelaki normal. Bukan dengan lelaki cacat sepertiku.” Nada bicara Arya bergetar. Netranya mulai berkaca-kaca.
“Mas, selama ini aku selalu setia menantimu. Setiap sore sepulang kerja aku selalu mampir ke taman ini. Berharap Mas datang memenuhi janji. Mas, walau pun semua orang bilang Mas sudah meninggal, hati kecilku selalu membisikkan bahwa Mas masih hidup. Dan, alhamdulillah keyakinanku terbukti. Bagaimana pun keadaanmu, Mas, hati ini hanya milikmu, Mas adalah takdirku. Aku menerimamu apa adanya Mas, karena bahagiaku hanya bersamamu.”
Bergetar Arya mendengar penuturan Rintan. Debar di dadanya kian berpacu. “Jadi masih maukah kamu menjadi istriku, Rin? Walau pun keadaanku begini?”
Rintan mengangguk mantap. Ia semakin mempererat pelukannya. Gadis berlesung pipit itu benar-benar bahagia. Momen inilah yang paling dinantikannya sejak lama. Begitu pun Arya, kebahagiaan membuncah di dadanya, ia merasa bersyukur memiliki kekasih yang begitu tulus mencintainya. Terbukti, walau ia tak lagi seperti dulu, Rintan tetap membuka hati menerimanya kembali.
Ciwidey, 23 Januari 2020
Suci Rahayu
Baca cerpen lainnya di sini:
Indeks Link
Diubah oleh suciasdhan 11-02-2020 07:57
ummuza dan 16 lainnya memberi reputasi
17
Tutup