- Beranda
- Stories from the Heart
Cinta Bersemi di Kedai Serabi
...
TS
suciasdhan
Cinta Bersemi di Kedai Serabi
Kumpulan Cerita Romantis Bikin Baper

Sumber: gambar di sini
Sepagi ini kedai Mak Otih sudah penuh sesak. Serabi buatan Mak Otih memang yang paling terkenal di desa Cipedes ini. Penganan yang terbuat dari campuran tepung terigu yang gurih dan air kelapa, banyak diburu oleh warga desa ini dan menjadi alternatif pilihan untuk sarapan. Cara memasaknya yang masih tradisional—menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat serta kayu bakar di bawahnya untuk mematangkan serabinya—membuat serabi ini memiliki rasa dan aroma yang khas. Varian serabinya hanya dua macam, yaitu topping oncom sangrai untuk rasa asin, dan serabi disiram kuah gula merah atau kinca untuk yang rasa manis. Bahkan, untuk serabi topping oncom bisa ditambahkan telur agar rasanya semakin gurih.
Sopi mengamati tangan Mak Otih yang menyendok adonan serabi ke dalam wajan tanah liat dengan cekatan. Adonan yang masih cair itu kemudian ditaburi oncom sangrai. Asap mengepul dari sana. Aroma serabi yang hampir matang membuat gadis itu menelan saliva berulang kali. Perutnya semakin keroncongan. Terbayang di mulutnya rasa legit kuah kinca bercampur dengan kue serabi yang gurih, lezat rasanya.
Empat orang pemuda iseng mulai melirik nakal ke arah Sopi yang terlihat cantik. Salah satu dari mereka mulai menggodanya.
"Hai, Neng geulis, sendirian aja nih. Boleh Akang temenin?"
"Akang mah mau langsung kenalan aja, boleh enggak?" Seorang pemuda lainnya mulai mendekati Sopi. Sementara dua pemuda yang lainnya hanya tertawa-tawa.
Sopi mulai jengah dengan gangguan dari keempat pemuda itu. Bahkan salah satunya yang tadi minta kenalan mulai berani mencolek lengannya. Segera saja Sopi menepis tangan jahil pemuda jangkung berambut keriting itu. Memangnya aku ini sabun colek apa? pikir Sopi, kesal.
"Widih, si Eneng meuni sombong ih. Belum tahu ya kita ini siapa? Kita teh F4, tapi bukan pemeran di drama Meteor Garden ya. Saya Firman, itu Fikri, Farid, dan Ferdi." Pemuda berkaus biru donker berlogo salah satu superhero terkenal di dunia, menunjuk ke arah ketiga temannya sambil ikut mendekat ke arah Sopi.
Sopi masih membisu, dalam hati ia geram dengan tingkah para pemuda itu. Perempuan di kedai ini kan banyak, kenapa hanya aku yang diperlakukan seperti ini? gumamnya.
Melihat gadis itu beranjak dari tempat duduknya, hendak berlalu dari kedai, keempat pemuda itu malah semakin gencar menggodanya.
"Mau ke mana Neng? Buru-buru amat. Kita kan belum saling mengenal. Tukeran nomor hp aja belum, udah mau pergi. Rumahnya di mana sih? Akang antar ya. Tenang, dijamin aman, selamat sampai tujuan." Pemuda berkaus hitam bergambar logo band Linkin Park mengejar Sopi dan menggenggam tangan gadis itu.
Sopi berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman tangan pemuda itu malah semakin kuat. Ia meringis kesakitan. Keempat pemuda itu tertawa puas.
"Heii, kalian! Lepaskan gadis itu. Belum tahu ya kalau dia itu pacar saya? Seenaknya main antar pacar orang. Yuk, Neng Akang antar." Suara seorang lelaki tampan berdandan ala Kabayan berhasil menghalau keempat pemuda itu. Mereka pun menjauh dari Sopi. Setelah berpamitan pada Emaknya yang tengah membalikkan serabi dari wadah, pemuda itu pun berjalan beriringan dengan sang gadis.
"Yuk, Neng. Enggak usah takut, saya mah bukan lelaki cunihin seperti mereka. Kalau mau jahil ke perempuan, saya selalu ingat sama Emak. Gimana kalau Emak juga digodain kayak gitu? Saya pasti marah besar," ucap lelaki itu setelah agak menjauh dari kedai.
Dalam hati, Sopi memuji ucapan pemuda di sampingnya yang sangat santun dan hormat memperlakukan ibunya. Yang jadi istrinya, sudah pasti akan diperlakukan dengan baik juga. Sopi malu sendiri, dan buru-buru menepis pikiran yang baru saja terlintas di benaknya. Mereka berjalan berdampingan. Keduanya sama-sama merasa canggung, tak ada yang berani membuka percakapan. Hanya sesekali mereka saling beradu pandang, kemudian sama-sama tersenyum dan menunduk, malu. Hingga tiba di tempat tujuan pun, mereka masih diam seribu bahasa.
Sementara itu, Pak Asep yang sedari tadi merasakan perasaannya tak enak, selalu terbayang wajah putri cantiknya. Rasa kuatir menggelayuti pikirannya, takut sesuatu menimpa Sopi. Sesekali ia menatap ke arah jalan, mencari sosok yang membuat hatinya gelisah. Tidak berapa lama, ia melihat gadis itu. Namun, ia tidak sendirian, seorang pemuda jangkung terlihat berjalan di sampingnya.
"Hei, pemuda, siapa kamu? Kenapa tampang anakku seperti ketakutan begitu? Hmm, mau macam-macam ya sama anak Jawara Pencak Silat ini? Hayu lah, Bapak mah enggak takut. Kita tandang di lapang sebelah!" Pak Asep sudah pasang kuda-kuda, bersiap untuk menyerang sosok yang terlihat sebagai ancaman bagi putri tersayangnya. Sopi dan Aden pun bengong.
Dengan kekuatan penuh, Pak Asep bersiap melayangkan pukulan ke arah pemuda tampan yang sedang berdiri di samping putrinya.
“Daddy—Daddy, calm down.” Sopi menghalangi serangan ayahnya dengan menggenggam tangan pria paruh baya itu yang sudah bulat terkepal dengan sempurna.
“Minggir, Sopi. Biar dia merasakan bogem mentah Bapak. Walau Bapakmu ini sudah tua, tapi Bapak masih kuat. Ayo sini, pemuda, lawan!” Pak Asep menghempaskan tangan Sopi yang menghalanginya.
“Pak Asep? Ini benar Pak Asep kan? Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu juga.” Aden mencium punggung tangan pria di hadapannya yang napasnya masih tak beraturan. Emosi memenuhi rongga dadanya. Kedua matanya memelotot ke arah pemuda itu.
“Apa-apaan kamu? Diajak tanding malah cium tangan? Nyalimu ciut, Jang?” Pak Asep menghempaskan tangan Aden dengan kasar.
“Bapak lupa ya? Ini teh Aden, putranya Mak Otih. Dulu waktu SD Aden kan belajar pencak silat dari Bapak. Wah senangnya masih bisa berjumpa dengan guru bela diri favorit Aden.”
Mendengar penuturan pemuda yang berdiri di hadapannya, perlahan-lahan emosi Pak Asep menurun. “Jadi, ini Aden? Masya Allah, meuni kasep. Maafkan Bapak yang terlalu kuatir dengan keselamatan putri Bapak satu-satunya. Maklum, sejak Ibunya meninggal, hanya dia yang Bapak miliki di dunia ini. Bapak enggak mungkin lupa, hanya tadi mah pangling aja, sampai-sampai enggak ngenalin. Kamu kan yang pernah ngompol, ketakutan karena Bapak bentak, hahaha. Terus kamu itu terkenal paling cengeng di antara murid-murid Bapak yang lain. Kesenggol sedikit saja nangis kejer.” Pak Asep menepuk-nepuk pundak bekas murid pencak silatnya itu.
Aden tersipu malu sambil melirik gadis cantik di sampingnya yang sedang bengong menyaksikan percakapan antara dirinya dan Pak Asep. “Jadi, Eneng ini teh putrinya Bapak?” lanjutnya.
“Iya, ini namanya Sopi, anak Bapak. Hayu atuh masuk, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Sopi suguhkan makanan sama minuman.”
Sopi beranjak menuju dapur menyiapkan suguhan untuk sang tamu. Sementara itu Aden dan sang Ayah sudah duduk di kursi ruang tamu. Sesekali, Pak Asep melirik Aden yang mencuri pandang ke arah Sopi. Sepertinya pemuda itu tertarik pada putrinya. Sebuah senyuman tersungging di bibir lelaki paruh baya itu. Sementara Aden, yang kepergok sedang curi-curi pandang, jadi salah tingkah. Hatinya mengakui perempuan itu memang cantik, hanya dandanannya saja yang menurutnya terlalu berlebihan alias menor. Andai gadis itu berdandan sederhana, aura kecantikannya akan terpancar alami. Tidak berapa lama, Sopi muncul dengan baki berisi dua gelas teh manis dan beberapa stoples berisi kue kering juga makanan ringan.
“Ayo—ayo dimakan, Den,” tawar Pak Asep setelah Sopi menaruh semua bawaannya di atas meja.
“Eh iya, ngomong-ngomong serabi pesanan Bapak mana?” Kali ini pandangan mata pria itu beralih pada Sopi.
“My mood is going down, Daddy. So maafkan Sovia yang tak jadi membelinya.”
Aden menatap heran gadis yang duduk di samping Pak Asep. Buset, bukan hanya dandanannya yang lain, cara bicaranya juga aneh, gumamnya.
“Kok bisa?” Kening Pak Asep berkerut. Tak mengerti dengan kalimat yang diucapkan putrinya barusan. Sejurus kemudian, lelaki itu manggut-manggut menyimak cerita putrinya.
“Duh, Den. Maafkan Bapak yang sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Terima kasih telah menyelamatkan putri Bapak." Sudah waktunya Sopi punya pendamping hidup, yang akan melindunginya dari marabahaya, gumam Pak Asep dalam hati sambil menatap lekat-lekat Aden yang sedang mencuri pandang ke arah wajah Sopi. Untung saja, pemuda ini baik hati, jadi dia tetap membiarkan Aden memandang wajah Sopi sampai puas. Kalau pemuda culas yang melakukannya, pasti sudah dia gibas tanpa ampun sampai kapok.
***
“Daddy, ini kopinya.”
“Terima kasih, Sopi.” Gadis cantik itu mengangguk dan beranjak hendak menuju kamarnya.
“Sopi, mau ke mana? Sini duduk dulu sebentar, Bapak mau bicara.”
“Daddy, Sovia mau ke kamar, belum beres merapihkan alis.”
“Bentar doang kok. Enggak nyampe lima belas menit.” Pak Asep menyeruput kopinya. “Sopi, kopi buatan kamu mengingatkan Bapak sama almarhumah Ibumu. Racikannya sama-sama enak. Rasa kopi dan gulanya seimbang, pas.”
Sopi tersenyum melihat Ayahnya yang begitu penuh penghayatan menyeruput kopinya, terlihat sekali pria paruh baya itu menikmati setiap tegukan cairan hitam itu yang masuk ke kerongkongannya.
“Jadi begini, Geulis. Kamu sekarang sudah besar. Kuliah pun sudah selesai.” Pak Asep menatap wajah putri tersayangnya sebelum ia melanjutkan bicara. Pria itu tampak memutar otak mencari kalimat yang pas untuk menyampaikan maksudnya pada Sopi. “Sudah saatnya Bapak melepasmu, Sopi,” lanjutnya.
“Maksud Daddy?” Sopi tercengang mendengar ucapan lanjutan dari Ayahnya. Dahinya berkerut, tak paham dengan arah pembicaraan sang Ayah.
“Begini, Neng. Maksud Bapak—kamu—sudah waktunya kamu punya pendamping hidup.”
“What? Jadi maksud Daddy Sovia harus segera married? Menikah begitu? No, Daddy!”
“Dengar dulu Sopi. Bapak sudah pikirkan matang-matang hal ini. Bapak ....”
“Tapi, Daddy. Sovia enggak mau berpisah dari Daddy.” Sopi mulai terisak.
“Jangan nangis atuh, Neng. Bapak kan jadi ikut sedih. Setelah menikah nanti Sopi boleh kok tinggal di sini. Lagian calon kamu juga tinggalnya deket-deket sini kok.” Pak Asep mengelus lembut punggung putri tercintanya itu.
“Memangnya siapa orangnya, Daddy?” tanya Sopi, heran. Keningnya berkerut, seolah mencari siapa sosok pemuda yang tinggal di dekat sini. Ia menggelengkan kepalanya, nihil. Tak satu pun wajah lelaki yang bisa terbayang di benaknya.
“Kamu mau kan Bapak nikahkan sama Aden?” Pak Asep malah balik bertanya.
Sopi terperanjat mendengar Ayahnya menyebut nama itu. “What? Daddy enggak salah jodohin Sovia sama dia? Orangnya ganteng sih, tapi dandanannya persis seperti si Kabayan. Jangan-jangan dia juga pemalas, sama seperti Kabayan itu.”
“Sopi, kamu ingat waktu dia melindungi kamu dari pemuda-pemuda yang mengganggu?” Sopi mengangguk. “Nah, Bapak rasa dia bisa menjaga kamu dengan baik. Kesan pertama melihat dia, Bapak yakin dia anak yang baik, tidak seperti kebanyakan pemuda lainnya.”
Sopi tertegun. Pak Asep membiarkan gadis itu hanya diam saja, mungkin putrinya sedang mencoba meresapi semua ucapannya. Hanya helaan napas gadis cantik itu yang sesekali terdengar.
Setelah hening beberapa saat, tak lama kemudian, Sopi pun buka suara, “Baiklah, Daddy, beri Sovia waktu untuk berpikir.” Gadis itu menyeret langkahnya menuju kamar, meninggalkan Pak Asep yang di hatinya tengah berharap sang putri mau menerima rencana perjodohan ini.
Satu jam berlalu. Namun, tak ada tanda-tanda Sopi keluar dari kamarnya. Pak Asep pun merasa heran. Ia mulai mengetuk pintu kamar Sopi.
“Sopi, Neng, sarapan yuk.” Tak ada sahutan. “Geulis, Bapak udah bikinin telor ceplok kesukaan kamu. Kita makan bareng yuk.” Tetap tak ada sahutan. “Sopi, lagi apa di dalam? Masih dandan atau lanjutin mimpi? Masa baru juga bangun udah tidur lagi.”
Karena tak terdengar juga sahutan dari Sopi, Pak Asep membuka pintu kamar yang ternyata tak dikunci oleh pemiliknya. Namun, betapa kagetnya Pak Asep saat ia tak menemukan putrinya di dalam kamar itu. Ia mendapati jendela kamar putrinya terbuka lebar.
“Sopi? Kamu di mana, Nak? Ini mah ngajak Bapak main petak umpet ya?” Pak Asep mulai berkeliling ke seluruh ruangan, tetapi tetap saja ia tak menemukan putrinya. “Duh, Sopi. Kamu teh ke mana atuh? Bapak jadi kuatir.” Pak Asep memutuskan kembali ke kamar Sopi, siapa tahu di sana dia bisa menemukan petunjuk. Netra Pak Asep jatuh pada secarik kertas di atas nakas yang berisi tulisan tangan Sopi.
Daddy, maaf, Sovia gak bermaksud bikin Daddy cemas. Sovia hanya kesal mendengar rencana Daddy. Biarlah Sovia bertemu jodoh Sovia dengan sendirinya. Dan Sovia akan menikah setelah benar-benar merasa siap. Don’t worry Daddy, saat Daddy membaca surat ini, Sovia sudah berada di rumah Grandma.
Setelah membaca surat itu, Pak Asep yang sedari tadi pikirannya kalut, kini merasa lega. Bergegas lelaki itu melangkah ke luar hendak menyusul Sopi ke rumah Mak Onah. Wanita itu tampak sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya. Ia merasa heran saat dari kejauhan tampak putranya sedang berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Wanita itu pun menyuruh putranya masuk dan menyodorkan segelas air putih yang langsung diteguk habis oleh Pak Asep.
“Heh, nyari apaan kamu teh? Tuh minum udah Emak ambilin. Kalau cemilan mah kebetulan lagi kosong.” Mak Onah memandang heran putranya yang mengedarkan pandangan ke seluruh sudut rumahnya.
“Mak, Sopi ada di sini?” Kembali Pak Asep mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan di rumah Emaknya.
Kening Mak Onah berkerut, heran dengan pertanyaan putranya. “Kalian kan tinggal serumah, kok nanya Sopi ke Emak?”
“Jadi, Sopi enggak ada di sini?” Pak Asep malah balik bertanya. Wajahnya mulai terlihat panik. Ia pun bangkit dari duduknya.
“Mau ke mana, Sep? Ada apa sebenarnya?” Asep menyerahkan surat yang ditulis Sopi kepada Mak Onah. Sejurus kemudian wanita itu membacanya dengan saksama. Raut wajahnya tampak serius.
“Seharusnya sudah sejam yang lalu dia tiba di sini,” ucap Mak Onah pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri.
“Duh, Sopi teh ke mana atuh ya, Mak?” Hati Pak Asep semakin diliputi rasa kuatir. Peluh mulai bercucuran di pelipisnya. Raut wajah Mak Onah pun sama-sama tegang, ikut merasakan kegelisahan yang sedang melanda putranya.
“Makanya, ini kan bukan zaman Siti Nurbaya. Kamu teh meuni seenaknya jodoh-jodohin Sopi.”
Pak Asep menyesali tindakannya, hingga membuat gadis itu pergi dari rumah. Kini entah di mana putrinya berada. Tak berapa lama, ia pun pamit untuk mencari putri kesayangannya. Namun, Mak Onah yang juga merasa sangat kuatir akan keberadaan cucunya, minta untuk ikut mencari. Akhirnya, mereka berdua berjalan menyusuri desa, berharap menemukan sosok cantik yang sangat dicintai.
“Sep, ngapain kamu bawa Emak ke kedai ini? Kamu belum sarapan? Kenapa tadi enggak makan di rumah Emak atuh?!” Mak Onah tampak kesal saat putranya membawa dia ke kedai serabi milik orang yang sangat dibencinya. Dulu, Mak Otih pernah berusaha merebut sang suami. Untunglah almarhum suaminya itu setia, sehingga tidak tergoda sedikit pun. Matanya menerawang, senyumnya terkembang ketika membayangkan sosok gagah perkasa sang suami yang mirip Gatotkaca.
Pak Asep memandang heran Mak Onah yang memasang muka cemberut. Sungguh, ia tak mengerti mengapa Ibunya begitu membenci Mak Otih dan sama sekali tak mau makam kue serabi yang terkenal lezat ini.
“Assalamuaalaikum, Mak. Aden ada?” Pak Asep mencium takzim punggung tangan Mak Otih. Mak Onah memalingkan wajah melihatnya. Sebal.
“Waalaikumsalam, ada, sebentar ya, Den, Aden, ada yang nyari nih!” teriak Mak Otih. Tidak berapa lama, Aden pun keluar.
“Eh, Pak Asep, ada apa Pak?” Aden mencium tangan Pak Asep, kemudian ia hendak mencium punggung tangan Mak Onah, namun Neneknya Sopi itu tak membalas uluran tangan pemuda ganteng itu.
“Sep, Emak mah pulang aja ya, panas lama-lama berada di sini. Kabari Emak kalau Sopi sudah ditemukan.” Mak Onah melangkahkan kakinya lebar-lebar, bergegas meninggalkan kedai itu, diiringi tatapan bengong Pak Asep dan pandangan heran Aden juga Mak Otih.
“Maafin Emak saya, ya. Beliau lagi sakit gigi, jadinya agak sensitif begitu.” Pak Asep mencoba mencari alasan atas sikap Mak Onah.
Aden memandang heran ke wajah mantan guru pencak silatnya yang kelihatan tegang itu. Pak Asep menceritakan tentang kepergian Sopi dari rumah yang katanya mau minggat ke rumah Nenek, tetapi gadis itu tak diketahui ke mana rimbanya. Setelah pamit pada Mak Otih, mereka berdua pun berangkat menyusuri setiap sudut desa mencari keberadaan gadis cantik itu.
***
“Duh, Den, kita harus cari ke mana lagi ya? Belum terlihat tanda-tanda keberadaan Sopi. Kamu di mana atuh Geulis? Baik-baik aja kan di sana?” Pak Asep terlihat sangat cemas. Wajahnya membiaskan kelelahan. Namun, ia tepiskan rasa itu. Kuatir akan keadaan putrinya lebih besar dibandingkan apapun juga.
“Sabar, Pak, kita belum menyusuri seluruh ruas jalan desa ini. Udah Zuhur, Pak. Kita salat dulu di masjid itu yuk, sambil memanjatkan doa buat Neng Sopi juga.” Aden menunjuk sebuah mesjid besar yang terletak di ujung gang.
Pak Asep mengangguk lemah. Tidak berapa lama, mereka berdua sudah berbaur dengan orang-orang, khusyuk menunaikan salat Zuhur berjamaah di mesjid itu serta memanjatkan doa untuk Sopi.
“Den, kita istirahat sebentar di sini.” Pak Asep menenggak air mineral di dalam botol, kemudian ia menyodorkan satu botol lagi pada Aden. “Nih, minum dulu, Den.”
“Terima kasih, Pak. Oh, ya, boleh Aden tanya-tanya tentang Neng Geulis?” ucap Aden dengan nada ragu dan malu-malu.
“Tentu saja, biar lebih tahu tentang calon istrimu.” Pak Asep memandang wajah pemuda calon menantunya itu, yang raut wajahnya sedang tampak merah jambu itu.
Pipi Aden bersemu merah, hatinya berdesir aneh. “Pak, ngomong-ngomong sejak kapan Ibunya Neng Sopi meninggal?”
“Ibunya meninggal saat melahirkan dia. Makanya Bapak selalu berusaha membahagiakan dia, kasihan sejak kecil dia enggak merasakan kasih sayang seorang Ibu.” Netra Pak Asep berkaca-kaca. Sekelebat bayang wajah sang istri muncul di pelupuk matanya.
Aden manggut-manggut, “Lantas, Pak—maaf sebelumnya kalau Aden lancang, tetapi Aden penasaran sama dandanan juga gaya bicara Neng Geulis yang—maaf, terlihat aneh.”
“Hahaha, iya dia memang unik. Logat bicaranya dan dandanannya seperti itu sejak lulus kuliah jurusan sastra Inggris. Bapak juga enggak tahu dia dapat pengaruh dari mana.” Pak Asep tergelak membayangkan style dandanan dan gaya bicara putri semata wayangnya itu.
Oh, pantesan atuh si Eneng teh begitu. Sekali lagi Aden manggut-manggut.
“Makanya, Den, kalau memang kalian ditakdirkan berjodoh, Bapak titip Sopi ya. Selama ini Bapak belum maksimal membimbing dia, terutama dalam hal agamanya. Tolong, bimbing dia untuk lebih mengenal Islam.” Pak Asep menepuk-nepuk pundak Aden.
Aden mengangguk. “Pak, udah enggak capek kan? Kita lanjutkan mencari Neng Sopi yuk.”
Pak Asep mengangguk, kemudian dua laki-laki itu beranjak dari teras mesjid. Berdua mereka melangkah meninggalkan mesjid, melanjutkan pencarian.
***
Baca cerpen lainnya di sini:
[Link DISINI[URL=]link di sini[/URL]


Sumber: gambar di sini
Sepagi ini kedai Mak Otih sudah penuh sesak. Serabi buatan Mak Otih memang yang paling terkenal di desa Cipedes ini. Penganan yang terbuat dari campuran tepung terigu yang gurih dan air kelapa, banyak diburu oleh warga desa ini dan menjadi alternatif pilihan untuk sarapan. Cara memasaknya yang masih tradisional—menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat serta kayu bakar di bawahnya untuk mematangkan serabinya—membuat serabi ini memiliki rasa dan aroma yang khas. Varian serabinya hanya dua macam, yaitu topping oncom sangrai untuk rasa asin, dan serabi disiram kuah gula merah atau kinca untuk yang rasa manis. Bahkan, untuk serabi topping oncom bisa ditambahkan telur agar rasanya semakin gurih.
Sopi mengamati tangan Mak Otih yang menyendok adonan serabi ke dalam wajan tanah liat dengan cekatan. Adonan yang masih cair itu kemudian ditaburi oncom sangrai. Asap mengepul dari sana. Aroma serabi yang hampir matang membuat gadis itu menelan saliva berulang kali. Perutnya semakin keroncongan. Terbayang di mulutnya rasa legit kuah kinca bercampur dengan kue serabi yang gurih, lezat rasanya.
Empat orang pemuda iseng mulai melirik nakal ke arah Sopi yang terlihat cantik. Salah satu dari mereka mulai menggodanya.
"Hai, Neng geulis, sendirian aja nih. Boleh Akang temenin?"
"Akang mah mau langsung kenalan aja, boleh enggak?" Seorang pemuda lainnya mulai mendekati Sopi. Sementara dua pemuda yang lainnya hanya tertawa-tawa.
Sopi mulai jengah dengan gangguan dari keempat pemuda itu. Bahkan salah satunya yang tadi minta kenalan mulai berani mencolek lengannya. Segera saja Sopi menepis tangan jahil pemuda jangkung berambut keriting itu. Memangnya aku ini sabun colek apa? pikir Sopi, kesal.
"Widih, si Eneng meuni sombong ih. Belum tahu ya kita ini siapa? Kita teh F4, tapi bukan pemeran di drama Meteor Garden ya. Saya Firman, itu Fikri, Farid, dan Ferdi." Pemuda berkaus biru donker berlogo salah satu superhero terkenal di dunia, menunjuk ke arah ketiga temannya sambil ikut mendekat ke arah Sopi.
Sopi masih membisu, dalam hati ia geram dengan tingkah para pemuda itu. Perempuan di kedai ini kan banyak, kenapa hanya aku yang diperlakukan seperti ini? gumamnya.
Melihat gadis itu beranjak dari tempat duduknya, hendak berlalu dari kedai, keempat pemuda itu malah semakin gencar menggodanya.
"Mau ke mana Neng? Buru-buru amat. Kita kan belum saling mengenal. Tukeran nomor hp aja belum, udah mau pergi. Rumahnya di mana sih? Akang antar ya. Tenang, dijamin aman, selamat sampai tujuan." Pemuda berkaus hitam bergambar logo band Linkin Park mengejar Sopi dan menggenggam tangan gadis itu.
Sopi berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman tangan pemuda itu malah semakin kuat. Ia meringis kesakitan. Keempat pemuda itu tertawa puas.
"Heii, kalian! Lepaskan gadis itu. Belum tahu ya kalau dia itu pacar saya? Seenaknya main antar pacar orang. Yuk, Neng Akang antar." Suara seorang lelaki tampan berdandan ala Kabayan berhasil menghalau keempat pemuda itu. Mereka pun menjauh dari Sopi. Setelah berpamitan pada Emaknya yang tengah membalikkan serabi dari wadah, pemuda itu pun berjalan beriringan dengan sang gadis.
"Yuk, Neng. Enggak usah takut, saya mah bukan lelaki cunihin seperti mereka. Kalau mau jahil ke perempuan, saya selalu ingat sama Emak. Gimana kalau Emak juga digodain kayak gitu? Saya pasti marah besar," ucap lelaki itu setelah agak menjauh dari kedai.
Dalam hati, Sopi memuji ucapan pemuda di sampingnya yang sangat santun dan hormat memperlakukan ibunya. Yang jadi istrinya, sudah pasti akan diperlakukan dengan baik juga. Sopi malu sendiri, dan buru-buru menepis pikiran yang baru saja terlintas di benaknya. Mereka berjalan berdampingan. Keduanya sama-sama merasa canggung, tak ada yang berani membuka percakapan. Hanya sesekali mereka saling beradu pandang, kemudian sama-sama tersenyum dan menunduk, malu. Hingga tiba di tempat tujuan pun, mereka masih diam seribu bahasa.
Sementara itu, Pak Asep yang sedari tadi merasakan perasaannya tak enak, selalu terbayang wajah putri cantiknya. Rasa kuatir menggelayuti pikirannya, takut sesuatu menimpa Sopi. Sesekali ia menatap ke arah jalan, mencari sosok yang membuat hatinya gelisah. Tidak berapa lama, ia melihat gadis itu. Namun, ia tidak sendirian, seorang pemuda jangkung terlihat berjalan di sampingnya.
"Hei, pemuda, siapa kamu? Kenapa tampang anakku seperti ketakutan begitu? Hmm, mau macam-macam ya sama anak Jawara Pencak Silat ini? Hayu lah, Bapak mah enggak takut. Kita tandang di lapang sebelah!" Pak Asep sudah pasang kuda-kuda, bersiap untuk menyerang sosok yang terlihat sebagai ancaman bagi putri tersayangnya. Sopi dan Aden pun bengong.
Dengan kekuatan penuh, Pak Asep bersiap melayangkan pukulan ke arah pemuda tampan yang sedang berdiri di samping putrinya.
“Daddy—Daddy, calm down.” Sopi menghalangi serangan ayahnya dengan menggenggam tangan pria paruh baya itu yang sudah bulat terkepal dengan sempurna.
“Minggir, Sopi. Biar dia merasakan bogem mentah Bapak. Walau Bapakmu ini sudah tua, tapi Bapak masih kuat. Ayo sini, pemuda, lawan!” Pak Asep menghempaskan tangan Sopi yang menghalanginya.
“Pak Asep? Ini benar Pak Asep kan? Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu juga.” Aden mencium punggung tangan pria di hadapannya yang napasnya masih tak beraturan. Emosi memenuhi rongga dadanya. Kedua matanya memelotot ke arah pemuda itu.
“Apa-apaan kamu? Diajak tanding malah cium tangan? Nyalimu ciut, Jang?” Pak Asep menghempaskan tangan Aden dengan kasar.
“Bapak lupa ya? Ini teh Aden, putranya Mak Otih. Dulu waktu SD Aden kan belajar pencak silat dari Bapak. Wah senangnya masih bisa berjumpa dengan guru bela diri favorit Aden.”
Mendengar penuturan pemuda yang berdiri di hadapannya, perlahan-lahan emosi Pak Asep menurun. “Jadi, ini Aden? Masya Allah, meuni kasep. Maafkan Bapak yang terlalu kuatir dengan keselamatan putri Bapak satu-satunya. Maklum, sejak Ibunya meninggal, hanya dia yang Bapak miliki di dunia ini. Bapak enggak mungkin lupa, hanya tadi mah pangling aja, sampai-sampai enggak ngenalin. Kamu kan yang pernah ngompol, ketakutan karena Bapak bentak, hahaha. Terus kamu itu terkenal paling cengeng di antara murid-murid Bapak yang lain. Kesenggol sedikit saja nangis kejer.” Pak Asep menepuk-nepuk pundak bekas murid pencak silatnya itu.
Aden tersipu malu sambil melirik gadis cantik di sampingnya yang sedang bengong menyaksikan percakapan antara dirinya dan Pak Asep. “Jadi, Eneng ini teh putrinya Bapak?” lanjutnya.
“Iya, ini namanya Sopi, anak Bapak. Hayu atuh masuk, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Sopi suguhkan makanan sama minuman.”
Sopi beranjak menuju dapur menyiapkan suguhan untuk sang tamu. Sementara itu Aden dan sang Ayah sudah duduk di kursi ruang tamu. Sesekali, Pak Asep melirik Aden yang mencuri pandang ke arah Sopi. Sepertinya pemuda itu tertarik pada putrinya. Sebuah senyuman tersungging di bibir lelaki paruh baya itu. Sementara Aden, yang kepergok sedang curi-curi pandang, jadi salah tingkah. Hatinya mengakui perempuan itu memang cantik, hanya dandanannya saja yang menurutnya terlalu berlebihan alias menor. Andai gadis itu berdandan sederhana, aura kecantikannya akan terpancar alami. Tidak berapa lama, Sopi muncul dengan baki berisi dua gelas teh manis dan beberapa stoples berisi kue kering juga makanan ringan.
“Ayo—ayo dimakan, Den,” tawar Pak Asep setelah Sopi menaruh semua bawaannya di atas meja.
“Eh iya, ngomong-ngomong serabi pesanan Bapak mana?” Kali ini pandangan mata pria itu beralih pada Sopi.
“My mood is going down, Daddy. So maafkan Sovia yang tak jadi membelinya.”
Aden menatap heran gadis yang duduk di samping Pak Asep. Buset, bukan hanya dandanannya yang lain, cara bicaranya juga aneh, gumamnya.
“Kok bisa?” Kening Pak Asep berkerut. Tak mengerti dengan kalimat yang diucapkan putrinya barusan. Sejurus kemudian, lelaki itu manggut-manggut menyimak cerita putrinya.
“Duh, Den. Maafkan Bapak yang sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Terima kasih telah menyelamatkan putri Bapak." Sudah waktunya Sopi punya pendamping hidup, yang akan melindunginya dari marabahaya, gumam Pak Asep dalam hati sambil menatap lekat-lekat Aden yang sedang mencuri pandang ke arah wajah Sopi. Untung saja, pemuda ini baik hati, jadi dia tetap membiarkan Aden memandang wajah Sopi sampai puas. Kalau pemuda culas yang melakukannya, pasti sudah dia gibas tanpa ampun sampai kapok.
***
“Daddy, ini kopinya.”
“Terima kasih, Sopi.” Gadis cantik itu mengangguk dan beranjak hendak menuju kamarnya.
“Sopi, mau ke mana? Sini duduk dulu sebentar, Bapak mau bicara.”
“Daddy, Sovia mau ke kamar, belum beres merapihkan alis.”
“Bentar doang kok. Enggak nyampe lima belas menit.” Pak Asep menyeruput kopinya. “Sopi, kopi buatan kamu mengingatkan Bapak sama almarhumah Ibumu. Racikannya sama-sama enak. Rasa kopi dan gulanya seimbang, pas.”
Sopi tersenyum melihat Ayahnya yang begitu penuh penghayatan menyeruput kopinya, terlihat sekali pria paruh baya itu menikmati setiap tegukan cairan hitam itu yang masuk ke kerongkongannya.
“Jadi begini, Geulis. Kamu sekarang sudah besar. Kuliah pun sudah selesai.” Pak Asep menatap wajah putri tersayangnya sebelum ia melanjutkan bicara. Pria itu tampak memutar otak mencari kalimat yang pas untuk menyampaikan maksudnya pada Sopi. “Sudah saatnya Bapak melepasmu, Sopi,” lanjutnya.
“Maksud Daddy?” Sopi tercengang mendengar ucapan lanjutan dari Ayahnya. Dahinya berkerut, tak paham dengan arah pembicaraan sang Ayah.
“Begini, Neng. Maksud Bapak—kamu—sudah waktunya kamu punya pendamping hidup.”
“What? Jadi maksud Daddy Sovia harus segera married? Menikah begitu? No, Daddy!”
“Dengar dulu Sopi. Bapak sudah pikirkan matang-matang hal ini. Bapak ....”
“Tapi, Daddy. Sovia enggak mau berpisah dari Daddy.” Sopi mulai terisak.
“Jangan nangis atuh, Neng. Bapak kan jadi ikut sedih. Setelah menikah nanti Sopi boleh kok tinggal di sini. Lagian calon kamu juga tinggalnya deket-deket sini kok.” Pak Asep mengelus lembut punggung putri tercintanya itu.
“Memangnya siapa orangnya, Daddy?” tanya Sopi, heran. Keningnya berkerut, seolah mencari siapa sosok pemuda yang tinggal di dekat sini. Ia menggelengkan kepalanya, nihil. Tak satu pun wajah lelaki yang bisa terbayang di benaknya.
“Kamu mau kan Bapak nikahkan sama Aden?” Pak Asep malah balik bertanya.
Sopi terperanjat mendengar Ayahnya menyebut nama itu. “What? Daddy enggak salah jodohin Sovia sama dia? Orangnya ganteng sih, tapi dandanannya persis seperti si Kabayan. Jangan-jangan dia juga pemalas, sama seperti Kabayan itu.”
“Sopi, kamu ingat waktu dia melindungi kamu dari pemuda-pemuda yang mengganggu?” Sopi mengangguk. “Nah, Bapak rasa dia bisa menjaga kamu dengan baik. Kesan pertama melihat dia, Bapak yakin dia anak yang baik, tidak seperti kebanyakan pemuda lainnya.”
Sopi tertegun. Pak Asep membiarkan gadis itu hanya diam saja, mungkin putrinya sedang mencoba meresapi semua ucapannya. Hanya helaan napas gadis cantik itu yang sesekali terdengar.
Setelah hening beberapa saat, tak lama kemudian, Sopi pun buka suara, “Baiklah, Daddy, beri Sovia waktu untuk berpikir.” Gadis itu menyeret langkahnya menuju kamar, meninggalkan Pak Asep yang di hatinya tengah berharap sang putri mau menerima rencana perjodohan ini.
Satu jam berlalu. Namun, tak ada tanda-tanda Sopi keluar dari kamarnya. Pak Asep pun merasa heran. Ia mulai mengetuk pintu kamar Sopi.
“Sopi, Neng, sarapan yuk.” Tak ada sahutan. “Geulis, Bapak udah bikinin telor ceplok kesukaan kamu. Kita makan bareng yuk.” Tetap tak ada sahutan. “Sopi, lagi apa di dalam? Masih dandan atau lanjutin mimpi? Masa baru juga bangun udah tidur lagi.”
Karena tak terdengar juga sahutan dari Sopi, Pak Asep membuka pintu kamar yang ternyata tak dikunci oleh pemiliknya. Namun, betapa kagetnya Pak Asep saat ia tak menemukan putrinya di dalam kamar itu. Ia mendapati jendela kamar putrinya terbuka lebar.
“Sopi? Kamu di mana, Nak? Ini mah ngajak Bapak main petak umpet ya?” Pak Asep mulai berkeliling ke seluruh ruangan, tetapi tetap saja ia tak menemukan putrinya. “Duh, Sopi. Kamu teh ke mana atuh? Bapak jadi kuatir.” Pak Asep memutuskan kembali ke kamar Sopi, siapa tahu di sana dia bisa menemukan petunjuk. Netra Pak Asep jatuh pada secarik kertas di atas nakas yang berisi tulisan tangan Sopi.
Daddy, maaf, Sovia gak bermaksud bikin Daddy cemas. Sovia hanya kesal mendengar rencana Daddy. Biarlah Sovia bertemu jodoh Sovia dengan sendirinya. Dan Sovia akan menikah setelah benar-benar merasa siap. Don’t worry Daddy, saat Daddy membaca surat ini, Sovia sudah berada di rumah Grandma.
Setelah membaca surat itu, Pak Asep yang sedari tadi pikirannya kalut, kini merasa lega. Bergegas lelaki itu melangkah ke luar hendak menyusul Sopi ke rumah Mak Onah. Wanita itu tampak sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya. Ia merasa heran saat dari kejauhan tampak putranya sedang berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Wanita itu pun menyuruh putranya masuk dan menyodorkan segelas air putih yang langsung diteguk habis oleh Pak Asep.
“Heh, nyari apaan kamu teh? Tuh minum udah Emak ambilin. Kalau cemilan mah kebetulan lagi kosong.” Mak Onah memandang heran putranya yang mengedarkan pandangan ke seluruh sudut rumahnya.
“Mak, Sopi ada di sini?” Kembali Pak Asep mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan di rumah Emaknya.
Kening Mak Onah berkerut, heran dengan pertanyaan putranya. “Kalian kan tinggal serumah, kok nanya Sopi ke Emak?”
“Jadi, Sopi enggak ada di sini?” Pak Asep malah balik bertanya. Wajahnya mulai terlihat panik. Ia pun bangkit dari duduknya.
“Mau ke mana, Sep? Ada apa sebenarnya?” Asep menyerahkan surat yang ditulis Sopi kepada Mak Onah. Sejurus kemudian wanita itu membacanya dengan saksama. Raut wajahnya tampak serius.
“Seharusnya sudah sejam yang lalu dia tiba di sini,” ucap Mak Onah pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri.
“Duh, Sopi teh ke mana atuh ya, Mak?” Hati Pak Asep semakin diliputi rasa kuatir. Peluh mulai bercucuran di pelipisnya. Raut wajah Mak Onah pun sama-sama tegang, ikut merasakan kegelisahan yang sedang melanda putranya.
“Makanya, ini kan bukan zaman Siti Nurbaya. Kamu teh meuni seenaknya jodoh-jodohin Sopi.”
Pak Asep menyesali tindakannya, hingga membuat gadis itu pergi dari rumah. Kini entah di mana putrinya berada. Tak berapa lama, ia pun pamit untuk mencari putri kesayangannya. Namun, Mak Onah yang juga merasa sangat kuatir akan keberadaan cucunya, minta untuk ikut mencari. Akhirnya, mereka berdua berjalan menyusuri desa, berharap menemukan sosok cantik yang sangat dicintai.
“Sep, ngapain kamu bawa Emak ke kedai ini? Kamu belum sarapan? Kenapa tadi enggak makan di rumah Emak atuh?!” Mak Onah tampak kesal saat putranya membawa dia ke kedai serabi milik orang yang sangat dibencinya. Dulu, Mak Otih pernah berusaha merebut sang suami. Untunglah almarhum suaminya itu setia, sehingga tidak tergoda sedikit pun. Matanya menerawang, senyumnya terkembang ketika membayangkan sosok gagah perkasa sang suami yang mirip Gatotkaca.
Pak Asep memandang heran Mak Onah yang memasang muka cemberut. Sungguh, ia tak mengerti mengapa Ibunya begitu membenci Mak Otih dan sama sekali tak mau makam kue serabi yang terkenal lezat ini.
“Assalamuaalaikum, Mak. Aden ada?” Pak Asep mencium takzim punggung tangan Mak Otih. Mak Onah memalingkan wajah melihatnya. Sebal.
“Waalaikumsalam, ada, sebentar ya, Den, Aden, ada yang nyari nih!” teriak Mak Otih. Tidak berapa lama, Aden pun keluar.
“Eh, Pak Asep, ada apa Pak?” Aden mencium tangan Pak Asep, kemudian ia hendak mencium punggung tangan Mak Onah, namun Neneknya Sopi itu tak membalas uluran tangan pemuda ganteng itu.
“Sep, Emak mah pulang aja ya, panas lama-lama berada di sini. Kabari Emak kalau Sopi sudah ditemukan.” Mak Onah melangkahkan kakinya lebar-lebar, bergegas meninggalkan kedai itu, diiringi tatapan bengong Pak Asep dan pandangan heran Aden juga Mak Otih.
“Maafin Emak saya, ya. Beliau lagi sakit gigi, jadinya agak sensitif begitu.” Pak Asep mencoba mencari alasan atas sikap Mak Onah.
Aden memandang heran ke wajah mantan guru pencak silatnya yang kelihatan tegang itu. Pak Asep menceritakan tentang kepergian Sopi dari rumah yang katanya mau minggat ke rumah Nenek, tetapi gadis itu tak diketahui ke mana rimbanya. Setelah pamit pada Mak Otih, mereka berdua pun berangkat menyusuri setiap sudut desa mencari keberadaan gadis cantik itu.
***
“Duh, Den, kita harus cari ke mana lagi ya? Belum terlihat tanda-tanda keberadaan Sopi. Kamu di mana atuh Geulis? Baik-baik aja kan di sana?” Pak Asep terlihat sangat cemas. Wajahnya membiaskan kelelahan. Namun, ia tepiskan rasa itu. Kuatir akan keadaan putrinya lebih besar dibandingkan apapun juga.
“Sabar, Pak, kita belum menyusuri seluruh ruas jalan desa ini. Udah Zuhur, Pak. Kita salat dulu di masjid itu yuk, sambil memanjatkan doa buat Neng Sopi juga.” Aden menunjuk sebuah mesjid besar yang terletak di ujung gang.
Pak Asep mengangguk lemah. Tidak berapa lama, mereka berdua sudah berbaur dengan orang-orang, khusyuk menunaikan salat Zuhur berjamaah di mesjid itu serta memanjatkan doa untuk Sopi.
“Den, kita istirahat sebentar di sini.” Pak Asep menenggak air mineral di dalam botol, kemudian ia menyodorkan satu botol lagi pada Aden. “Nih, minum dulu, Den.”
“Terima kasih, Pak. Oh, ya, boleh Aden tanya-tanya tentang Neng Geulis?” ucap Aden dengan nada ragu dan malu-malu.
“Tentu saja, biar lebih tahu tentang calon istrimu.” Pak Asep memandang wajah pemuda calon menantunya itu, yang raut wajahnya sedang tampak merah jambu itu.
Pipi Aden bersemu merah, hatinya berdesir aneh. “Pak, ngomong-ngomong sejak kapan Ibunya Neng Sopi meninggal?”
“Ibunya meninggal saat melahirkan dia. Makanya Bapak selalu berusaha membahagiakan dia, kasihan sejak kecil dia enggak merasakan kasih sayang seorang Ibu.” Netra Pak Asep berkaca-kaca. Sekelebat bayang wajah sang istri muncul di pelupuk matanya.
Aden manggut-manggut, “Lantas, Pak—maaf sebelumnya kalau Aden lancang, tetapi Aden penasaran sama dandanan juga gaya bicara Neng Geulis yang—maaf, terlihat aneh.”
“Hahaha, iya dia memang unik. Logat bicaranya dan dandanannya seperti itu sejak lulus kuliah jurusan sastra Inggris. Bapak juga enggak tahu dia dapat pengaruh dari mana.” Pak Asep tergelak membayangkan style dandanan dan gaya bicara putri semata wayangnya itu.
Oh, pantesan atuh si Eneng teh begitu. Sekali lagi Aden manggut-manggut.
“Makanya, Den, kalau memang kalian ditakdirkan berjodoh, Bapak titip Sopi ya. Selama ini Bapak belum maksimal membimbing dia, terutama dalam hal agamanya. Tolong, bimbing dia untuk lebih mengenal Islam.” Pak Asep menepuk-nepuk pundak Aden.
Aden mengangguk. “Pak, udah enggak capek kan? Kita lanjutkan mencari Neng Sopi yuk.”
Pak Asep mengangguk, kemudian dua laki-laki itu beranjak dari teras mesjid. Berdua mereka melangkah meninggalkan mesjid, melanjutkan pencarian.
***
Baca cerpen lainnya di sini:
[Link DISINI[URL=]link di sini[/URL]

Diubah oleh suciasdhan 30-06-2020 09:33
novianalinda dan 79 lainnya memberi reputasi
80
14.2K
634
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.7KThread•52KAnggota
Tampilkan semua post
TS
suciasdhan
#4
Namaku (Entin) Kartini
Menggapai Asa, Meraih Cita-Cita
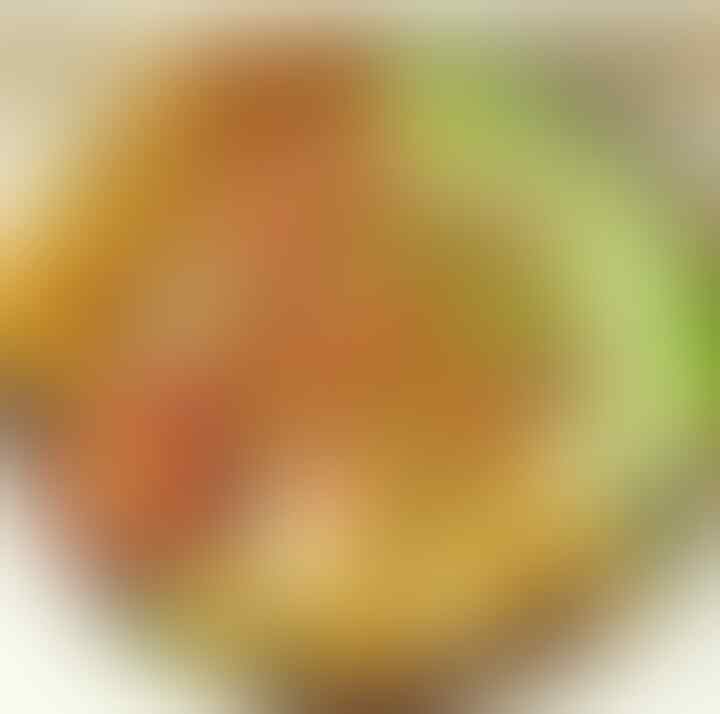
Sumber: gambar di sini
Namaku Entin. Nama lengkapku Entin Kartini, aku lahir di Bandung, tepatnya di daerah Jalan Pungkur. Aku tinggal bersama ibuku, Bu Dewi, karena ayahku sudah lama meninggal sejak usiaku menginjak lima tahun. Dari cerita ibuku, Ayah pria yang sangat baik, beliau lembut namun tegas untuk urusan kedisiplinan, terang saja beliau begitu karena profesinya seorang ABRI. Ibu dan almarhum Ayah sangat mengagumi pahlawan wanita dari Jepara, R.A Kartini, makanya mengapa nama belakangku demikian, harapan mereka aku bisa sehebat pejuang emansipasi wanita tersebut.
Rumahku hampir dekat dengan terminal Kebon Kelapa, yakni tempat persinggahan terakhir beberapa angkutan kota dari berbagai jurusan di kota Bandung. Selain itu, daerah tempat tinggalku dekat dengan alun-alun kota. Dulu, daerah ini tidak begitu ramai, tapi seiring berjalannya waktu, banyak pusat perbelanjaan yang dibangun, sehingga menjadi hiruk-pikuklah keadaannya, lengkap dengan macetnya pula.
Di daerah alun-alun terdapat pula Masjid Raya Bandung, yang sekarang sudah semakin bagus bangunannya, dilengkapi juga dengan rumput sintetis tempat orang-orang berfoto atau bermain bagi anak-anak. Setiap akhir pekan atau liburan sekolah maupun hari besar, daerah alun-alun kota ini penuh sesak oleh pengunjung dari berbagai daerah.

Sumber: gambar di sini
Ini lho masjid yang aku maksud, adem ya.
Kini usiaku menginjak delapan belas tahun, aku baru saja lulus dari sebuah SMA Negeri di kota tercinta ini. Sebenarnya aku ingin sekali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Keguruan. Aku sangat ingin menjadi guru sekaligus menyalurkan hobiku, menulis. Untuk itu aku berencana masuk ke jurusan pendidikan bahasa Indonesia, namun belum kuutarakan maksudku pada Ibu.
“Entin, sini dulu sebentar, Ibu mau bicara,” panggil ibuku di suatu sore yang cerah saat kami tengah duduk santai di beranda rumah.
Inilah saatnya, gumamku dalam hati. Aku segera menggeser posisi dudukku mendekati Ibu. “Iya Bu ada apa?” Netraku terpaku keheranan melihat wajah Ibu yang tampak serius.
“Selamat atas kelulusanmu ya, Nak. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf jika ....” Kalimat Ibu menggantung, kulihat raut wajahnya berubah muram.
Aku hanya terdiam, menunggu Ibu melanjutkan ucapannya. Hening sesaat, terdengar suara Ibu berdehem.
“Ibu tahu, kamu pasti sangat ingin melanjutkan pendidikan kamu ke universitas, seperti kebanyakan teman-teman SMA kamu, hanya saja ...." Kembali Ibu tidak melanjutkan perkataannya. Terdengar helaan napas Ibu yang terasa berat. Sepertinya beliau tidak tega melanjutkan ucapannya.
“Hanya saja apa Bu?” tanyaku memecah keheningan, dan ingin segera menghalau rasa penasaran.
“Kamu tahu, 'kan Ibu hanya seorang juru masak di rumah makan milik Ibu Imas, sementara ayahmu tidak punya pensiunan. Untuk masuk ke universitas bukanlah biaya yang sedikit, Entin, Ibu ....” Kedua netranya sayu, bulir bening menganak sungai di sana. Namun aku sudah bisa menebak ke mana arah pembicaraan Ibu.
Aku memeluk Ibu yang mulai terisak. “Sudah Bu, tidak apa-apa. Nggak usah Ibu pikirkan. Entin mau bantu Ibu saja di rumah makan tempat Ibu bekerja, nanti setiap gajian, uangnya sebagian Entin tabung. Kalau sudah terkumpul, baru Entin memikirkan kuliah,” kataku berusaha menghalau kegelisahan Ibu.
Ibu mendongakkan kepala, menatapku, mengamati kesungguhan perkataanku barusan. “Jangan, Nak, biar Ibu saja yang bekerja, ini sudah kewajiban Ibu menggantikan almarhum ayahmu mencari nafkah.”
“Nggak apa-apa Bu, ini kan untuk sementara, sampai uang Entin cukup untuk biaya kuliah,” kataku mantap.
Ibu memelukku erat, tangisnya pecah. Aku balik memeluknya dan mengusap-usap lembut punggung wanita terkasihku yang umurnya sudah setengah baya ini.
Batinku sendiri pun bergejolak, tetapi aku tak ingin menunjukkannya di depan Ibu. Aku tak mau ia sedih dan terbebani memikirkan hal ini. Terpaksa aku harus mengubur dulu cita-citaku. Aku menghela napas, berusaha sedikit mengusir kegalauanku.
Ini hanya untuk sementara Entin, kamu harus kuat demi Ibu, kelak jika sudah berhasil mencapai impianmu kamu harus membahagiakan dia, batinku lirih.
***
Esoknya, aku ikut ke tempat Ibu bekerja. Jaraknya tidak begitu jauh dari rumah, hingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja. Setelah lima belas menit aku dan Ibu berjalan, akhirnya sampailah kami di sebuah rumah makan khas Sunda yang terletak tidak jauh dari terminal Kebon Kelapa. Bangunannya sederhana, tidak seperti kebanyakan rumah makan yang sudah punya nama di kota Bandung ini. Namun, menurut cerita Ibu, rumah makan ini sudah membuka beberapa cabang di beberapa ruas jalan kota kembang ini.
“Assalamu alaikum." Aku dan Ibu hampir berbarengan mengucapkan salam.
“Waalaikum salam,” jawab seorang perempuan dari dalam rumah makan. Terdengar langkah kaki mendekati kami.
“Eh Bu Dewi, bawa siapa ini? Meuni cantik pisan!” ucap seorang perempuan seumuran Ibu, membuat pipiku bersemu merah. Aku langsung mencium punggung tangannya.
“Ini anak saya Bu Imas, namanya Entin, baru saja lulus SMA, kalau Ibu mengizinkan, dia mau bantu-bantu disini.” Ibu menjelaskan.
“Wah kebetulan sekali, pengunjung akhir-akhir ini semakin banyak, pegawai disini sampai kewalahan melayani." Nada bicara Bu Dewi tampak semringah. Kedua matanya berbinar indah. "Oh iya ngomong-ngomong Neng bisa masak kan?” tanya Bu Imas antusias.
“Panggil Entin saja Bu. Alhamdulillah saya bisa masak beberapa masakan khas Sunda. Semoga saja bisa terpakai sama Ibu," ujarku tanpa bermaksud pamer dan menyombongkan diri.
“Jangan merendah, Nak, Ibu percaya masakan kamu pasti enak. Soalnya Ibu kamu juga salah satu juru masak terbaik disini, kamu bisa mulai kerja hari ini ya." Beliau menggamit lenganku seraya mengajak masuk ke rumah makan miliknya.
“Alhamdulillah, terima kasih Bu." Bahagia rasanya, melamar kerja dan langsung diterima hari itu juga.
Semoga ini menjadi pintu rezeki aku untuk bisa kuliah nanti, harapku. Ibu yang berdiri di sampingku tampak tersenyum senang.
***
Tak terasa sudah sebulan lamanya aku bekerja di rumah makan ini. Alhamdulillah aku telah mendapatkan gaji pertama. Lumayan, aku sudah bisa membuka tabungan dari hasil jerih payahku sendiri. Ditambah lagi uang honor dari karya tulisku yang dimuat di beberapa majalah dan surat kabar, kumasukkan juga ke dalam tabunganku, agar jumlahnya semakin banyak. Alhamdulillah juga beberapa masakan khas Sunda yang kubuat, seperti gepuk, nasi liwet, nasi tutug oncom, dan soto Bandung, kudengar dari Bu Imas menjadi favorit para pengunjung.
Jujur, aku ingin segera mengenyam bangku kuliah, ingin mewujudkan cita-citaku yang terpaksa ditunda karena keterbatasan ekonomi. Kelak aku ingin membangun sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dari kalangan tidak mampu, aku ingin membantu mereka untuk bisa mengejar cita-cita. Iba rasanya hatiku menyaksikan pemandangan anak-anak kecil bertelanjang kaki mengamen di trotoar jalan, sepertinya mereka terpaksa harus putus sekolah. Tatapanku menerawang ke langit-langit rumah makan, mimpiku terlalu tinggi, aku saja masih belum bisa menggapainya.
“Entin, kok melamun, ada apa? Cerita sama Ibu, siapa tahu Ibu bisa membantu.” Suara lembut milik Bu Imas membuyarkan lamunanku.
“Tidak ada apa-apa kok Bu,” jawabku singkat sambil melanjutkan pekerjaanku, membuat gepuk.
“Tidak apa-apa kok melamun, pasti ada yang sedang mengganggu pikiranmu ya? kamu nggak betah kerja disini?” tanya Bu Imas menyelidik.
Aku menggeleng mendengar pertanyaannya. “Saya betah kerja disini Bu, apalagi Ibu sangat baik pada saya, pada Ibu saya juga.”
“Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk bercerita, anggaplah Ibu ini seperti ibumu sendiri. Oh iya ngomong-ngomong kenapa kamu nggak melanjutkan kuliah?” tanyanya.
“Tidak ada biayanya Bu, saya kasihan sama Ibu saya yang harus kerja banting tulang untuk menghidupi kami berdua. Makanya saya ikut kerja ingin mengumpulkan uang untuk biaya kuliah, ingin meringankan beban Ibu juga,” ceritaku panjang lebar.
Entah mengapa dengan Bu Imas aku bisa lebih nyaman untuk bercerita tentang keluh-kesahku dibanding dengan Ibu. Aku hanya tak ingin Ibu sedih memikirkanku dan nantinya terbebani.
Netra Bu Imas berkaca-kaca. Ia membelai lembut kepalaku yang tertutup jilbab biru. "Kamu anak yang baik, Nak, semoga cita-citamu dimudahkan oleh-Nya ya." Aku mengamini do’anya dalam hati.
***
Hari Minggu ini pengunjung rumah makan Ibu Imas lumayan ramai. Aku dibuat sangat sibuk karenanya. Tiba-tiba kulihat ada sesosok lelaki muda menghampiri Bu Imas dan mencium tangan wanita itu.
“Itu Rian, putra semata wayangnya Bu Imas yang memegang cabang rumah makan di Balonggede,” ucap Ibu seolah membaca pikiranku yang keheranan melihat lelaki itu. Sebab, selama aku bekerja disini, baru pertama kalinya melihat sosok lelaki itu. Bu Imas pun tak pernah cerita padaku mengenai putranya.
“Entin sini, kenalan dulu sama anak Ibu!” panggil Ibu Imas sembari melambaikan tangan ke arahku.
Bergegas aku menghampiri mereka, kemudian menerima uluran tangan putra bossku itu.
“Kamu Ekar, 'kan? Yang karya-karyanya ada di majalah dan koran itu? Aku suka sekali dengan karya-karyamu, membacanya mengingatkanku pada sosok pahlawan, R.A Kartini,” katanya antusias.
Aku hanya mengangguk dan terbengong. Dari mana dia tahu nama penaku dan karya-karyaku? Oh ya ampun, aku tepok jidat. Jelas dia tahu, dari biodata dan foto yang terpampang di setiap akhir karyaku.
“Jadi selain jago masak, kamu juga seorang penulis Entin? Hebat!” ucap Bu Imas sambil mengacungkan jempolnya, kemudian ia melirik ke arah putranya dan tersenyum penuh arti. Aku tak mampu menerjemahkan maksud senyuman Bu Imas itu.
***
“Entin sudah tidur?” tanya ibuku sambil mengetuk pintu kamarku dari luar.
“Belum Bu, lagi baca-baca buku,” kataku sambil membukakan pintu untuk Ibu masuk.
Ibu duduk di atas ranjang dan membelai rambutku. “Nggak kerasa kamu sudah besar ya, Nak, Ibu bangga padamu, kamu anak yang baik. Bakatmu banyak, memasak, menulis. Ibu minta maaf ya tidak mampu mewujudkan mimpimu untuk kuliah,” ucapnya mulai terisak.
“Sudah Bu, tidak usah dipikirkan, Entin bukan tidak akan kuliah. Suatu saat nanti Entin pasti kuliah, sekarang kan lagi proses Bu. Proses mengumpulkan dananya dulu." Kugenggam jemarinya erat sembari tertawa berusaha menghibur Ibu.
“Nak, kalau kamu ingin segera mewujudkan impianmu, ada seseorang yang akan mengabulkannya,” ucap Ibu di sela-sela isak tangisnya.
“Maksud Ibu?” Aku mengernyitkan dahi tak mengerti dengan ucapannya barusan.
“Semenjak perkenalan itu, Nak Rian menyukaimu, Nak, dan Bu Imas memang sering bercerita tentangmu. Jadi, Nak Rian bermaksud melamarmu, menikahimu,” Ibu menjelaskan keherananku dengan kalimat yang membuatku seperti tersambar petir.
“Apa Bu? Menikah? Entin masih ingin kuliah Bu, Entin tidak mau terkekang. Entin masih ingin mengejar cita-cita. Entin ingin jadi orang sukses biar bisa bahagiakan Ibu, biar Ibu nggak harus kerja keras lagi cari uang.” Aku mulai menangis dan bergidik membayangkan kehidupan setelah pernikahan. Akan ada yang mengatur hidupku, apalagi setelah punya anak, ribet, nggak bisa kemana-mana, apalagi kuliah.
“Nak, pernikahan itu tidak seseram yang kamu bayangkan, Ibu dulu juga menikah muda. Ibu menjalaninya enjoy saja, hanya pikiranmu yang membuat segalanya rumit. Belum dijalani kok pikirannya sudah bilang ribet. Ibu yakin kamu akan bahagia bersama Nak Rian. Ibu percaya Nak Rian bukan tipe lelaki yang suka mengekang.” Ibu berkata panjang lebar seolah memahami jalan pikiranku.
Hening sejenak. Aku dan Ibu larut dalam jalan pikiran masing-masing. “Keputusan Ibu serahkan padamu, Nak. Ibu tidak akan memaksa. Istikharah, mohon petunjuk, mintalah yang terbaik sama Allah. Tapi kalau Ibu jadi kamu, Ibu akan menerima pinangan Nak Rian, sekarang atau pun nanti kamu tetap akan menjadi seorang istri, toh tidak ada larangan menikah untuk yang kuliah kan? Dua-duanya bisa dijalani.” Ibu beranjak dan melangkahkan kaki dari kamarku.
Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Pikiranku kalut antara harus menerima atau menolak. Entahlah, saat ini aku tak bisa berpikir jernih, semuanya terasa buntu. Aku semakin bergidik membaca biografi R.A Kartini, beliau wafat di usia muda, 24 tahun, setelah melahirkan putranya. Aku nggak mau meninggal di usia muda, batinku lirih.
***
Untuk pertama kalinya aku jalan berdua dengan calon suamiku yang belum sepenuhnya hatiku bisa menerimanya. Kami makan di sebuah restoran di bilangan Dago. Sesekali dia melemparkan candanya yang kubalas dengan senyuman yang dipaksakan. Sepertinya ia bisa menangkap sikapku itu.
“Kamu kenapa Ekar, masih meragukan niat suciku? Atau ada yang mengganjal di hatimu? Ceritakan saja, mungkin bisa diatasi,” katanya sambil terus menyunggingkan senyum.
Aku bingung harus berkata apa, lidahku kelu. Aku tak ingin dia nantinya tersinggung dengan kejujuranku.
“Katakan saja Ekar, jangan merasa tidak enak. Biar bisa membuatmu lega,” ucapnya.
“Sebenaranya ... begini ... bukannya ... saya ....” Terbata-bata aku berkata. Tak tahu harus mulai dari mana, padahal di rumah tadi tekadku sudah bulat untuk mengucapkan semua uneg-uneg dalam hati.
“Tidak mengapa, katakanlah."
Aku menghela napas berat. Kukumpulkan segenap keberanian. Kedua telapak tanganku terasa dingin. Sesekali sudut mataku melirik ke arahnya. Ada perasaan tak nyaman menghampiri. Namun, tekadku sudah bulat. Aku harus mengutarakannya, agar dia tahu apa yang kurasakan.
“Sebenarnya, bukan saya menolak, hanya saja saya belum siap untuk menjadi seorang istri. Saya masih ingin kuliah, ingin mengejar cita-cita yang selama ini tertunda karena tak ada biaya, makanya saya kerja. Mau mengumpulkan uang buat biaya kuliah, saya belum siap menikah. Saya ingin membahagiakan Ibu, selain itu saya ingin mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak tidak mampu. Cukup saya yang merasakan harus kerja dulu agar bisa mengenyam pendidikan," ujarku menjelaskan ganjalan di dada, persis seperti kata-kata yang sudah aku susun di rumah.
Aku menghela napas, lega rasanya, namun ada sedikit rasa kuatir kalau-kalau dia akan kecewa mendengar penuturanku yang jujur dan lugas itu. Alih-alih bersedih, dia malah tertawa, membuatku heran dibuatnya.
“Jadi itu yang selama ini menjadi ganjalan buat Ekar menerimaku? Begini Ekar, aku berjanji setelah kita menjadi suami istri, aku tidak akan mengekangmu. Kau boleh kuliah dimana pun kau mau, aku akan membiayainya. Ekar aku akan bantu kamu mewujudkan impian muliamu itu,” ujarnya mantap tanpa tersirat keraguan sedikit pun.
Aku terlongo, masih tak percaya dengan yang aku dengar barusan. Mungkinkah ini mimpi? Kalau pun iya, rasanya tak ingin segera terbangun. Sebab, hal ini terlalu indah.
“So, Ekar, will you marry me?” pintanya sambil berlutut tepat di hadapanku.
Jantungku berdegup tak karuan. Aku yakin wajah ini sudah bersemu merah karenanya. “Duh jangan begini, malu."
“Will you?” tanyanya sekali lagi. Debaran di dadaku kian kentara. Ada kelegaan dan binar bahagia terpancar di wajahnya melihat anggukan dariku. Tepat di hadapanku, ia sujud syukur sembari mengucap hamdallah.
***
Beberapa tahun kemudian
Sebuah bangunan sekolah dasar dua lantai bercat dinding putih sudah berdiri kokoh di hadapanku. Siswa-siswanya berasal dari kalangan tidak mampu. Semuanya dibebaskan dari biaya pendidikan. Tak hanya itu, Mas Rian juga membiayai kuliahku hingga jenjang S-2. Inilah aku sekarang, Entin Kartini, S.Pd, M.M, salah satu staf pengajar sekaligus kepala sekolahnya.
“Terima kasih, ya Mas, sudah mewujudkan cita-citaku. Aku tak mungkin bisa menggapai semuanya tanpa bantuanmu.” Kugenggam jemarinya erat, dia balas menggenggamnya dengan lembut.
Dia tersenyum, mengecup lembut jemari tanganku. Benar nasihat Ibu waktu itu, menikah tidak seseram yang dibayangkan. Aku bisa tetap menjalankan peranku sebagai seorang istri, memasak masakan khas Sunda kesukaannya, mengajar, mengelola sebuah sekolah, dan juga tetap produktif menulis.
Ciwidey, 14 Januari 2020
Suci Rahayu
Cerpen lainnya:
Indeks Link

Sumber: gambar di sini
Namaku Entin. Nama lengkapku Entin Kartini, aku lahir di Bandung, tepatnya di daerah Jalan Pungkur. Aku tinggal bersama ibuku, Bu Dewi, karena ayahku sudah lama meninggal sejak usiaku menginjak lima tahun. Dari cerita ibuku, Ayah pria yang sangat baik, beliau lembut namun tegas untuk urusan kedisiplinan, terang saja beliau begitu karena profesinya seorang ABRI. Ibu dan almarhum Ayah sangat mengagumi pahlawan wanita dari Jepara, R.A Kartini, makanya mengapa nama belakangku demikian, harapan mereka aku bisa sehebat pejuang emansipasi wanita tersebut.
Rumahku hampir dekat dengan terminal Kebon Kelapa, yakni tempat persinggahan terakhir beberapa angkutan kota dari berbagai jurusan di kota Bandung. Selain itu, daerah tempat tinggalku dekat dengan alun-alun kota. Dulu, daerah ini tidak begitu ramai, tapi seiring berjalannya waktu, banyak pusat perbelanjaan yang dibangun, sehingga menjadi hiruk-pikuklah keadaannya, lengkap dengan macetnya pula.
Di daerah alun-alun terdapat pula Masjid Raya Bandung, yang sekarang sudah semakin bagus bangunannya, dilengkapi juga dengan rumput sintetis tempat orang-orang berfoto atau bermain bagi anak-anak. Setiap akhir pekan atau liburan sekolah maupun hari besar, daerah alun-alun kota ini penuh sesak oleh pengunjung dari berbagai daerah.

Sumber: gambar di sini
Ini lho masjid yang aku maksud, adem ya.
Kini usiaku menginjak delapan belas tahun, aku baru saja lulus dari sebuah SMA Negeri di kota tercinta ini. Sebenarnya aku ingin sekali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Keguruan. Aku sangat ingin menjadi guru sekaligus menyalurkan hobiku, menulis. Untuk itu aku berencana masuk ke jurusan pendidikan bahasa Indonesia, namun belum kuutarakan maksudku pada Ibu.
“Entin, sini dulu sebentar, Ibu mau bicara,” panggil ibuku di suatu sore yang cerah saat kami tengah duduk santai di beranda rumah.
Inilah saatnya, gumamku dalam hati. Aku segera menggeser posisi dudukku mendekati Ibu. “Iya Bu ada apa?” Netraku terpaku keheranan melihat wajah Ibu yang tampak serius.
“Selamat atas kelulusanmu ya, Nak. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf jika ....” Kalimat Ibu menggantung, kulihat raut wajahnya berubah muram.
Aku hanya terdiam, menunggu Ibu melanjutkan ucapannya. Hening sesaat, terdengar suara Ibu berdehem.
“Ibu tahu, kamu pasti sangat ingin melanjutkan pendidikan kamu ke universitas, seperti kebanyakan teman-teman SMA kamu, hanya saja ...." Kembali Ibu tidak melanjutkan perkataannya. Terdengar helaan napas Ibu yang terasa berat. Sepertinya beliau tidak tega melanjutkan ucapannya.
“Hanya saja apa Bu?” tanyaku memecah keheningan, dan ingin segera menghalau rasa penasaran.
“Kamu tahu, 'kan Ibu hanya seorang juru masak di rumah makan milik Ibu Imas, sementara ayahmu tidak punya pensiunan. Untuk masuk ke universitas bukanlah biaya yang sedikit, Entin, Ibu ....” Kedua netranya sayu, bulir bening menganak sungai di sana. Namun aku sudah bisa menebak ke mana arah pembicaraan Ibu.
Aku memeluk Ibu yang mulai terisak. “Sudah Bu, tidak apa-apa. Nggak usah Ibu pikirkan. Entin mau bantu Ibu saja di rumah makan tempat Ibu bekerja, nanti setiap gajian, uangnya sebagian Entin tabung. Kalau sudah terkumpul, baru Entin memikirkan kuliah,” kataku berusaha menghalau kegelisahan Ibu.
Ibu mendongakkan kepala, menatapku, mengamati kesungguhan perkataanku barusan. “Jangan, Nak, biar Ibu saja yang bekerja, ini sudah kewajiban Ibu menggantikan almarhum ayahmu mencari nafkah.”
“Nggak apa-apa Bu, ini kan untuk sementara, sampai uang Entin cukup untuk biaya kuliah,” kataku mantap.
Ibu memelukku erat, tangisnya pecah. Aku balik memeluknya dan mengusap-usap lembut punggung wanita terkasihku yang umurnya sudah setengah baya ini.
Batinku sendiri pun bergejolak, tetapi aku tak ingin menunjukkannya di depan Ibu. Aku tak mau ia sedih dan terbebani memikirkan hal ini. Terpaksa aku harus mengubur dulu cita-citaku. Aku menghela napas, berusaha sedikit mengusir kegalauanku.
Ini hanya untuk sementara Entin, kamu harus kuat demi Ibu, kelak jika sudah berhasil mencapai impianmu kamu harus membahagiakan dia, batinku lirih.
***
Esoknya, aku ikut ke tempat Ibu bekerja. Jaraknya tidak begitu jauh dari rumah, hingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja. Setelah lima belas menit aku dan Ibu berjalan, akhirnya sampailah kami di sebuah rumah makan khas Sunda yang terletak tidak jauh dari terminal Kebon Kelapa. Bangunannya sederhana, tidak seperti kebanyakan rumah makan yang sudah punya nama di kota Bandung ini. Namun, menurut cerita Ibu, rumah makan ini sudah membuka beberapa cabang di beberapa ruas jalan kota kembang ini.
“Assalamu alaikum." Aku dan Ibu hampir berbarengan mengucapkan salam.
“Waalaikum salam,” jawab seorang perempuan dari dalam rumah makan. Terdengar langkah kaki mendekati kami.
“Eh Bu Dewi, bawa siapa ini? Meuni cantik pisan!” ucap seorang perempuan seumuran Ibu, membuat pipiku bersemu merah. Aku langsung mencium punggung tangannya.
“Ini anak saya Bu Imas, namanya Entin, baru saja lulus SMA, kalau Ibu mengizinkan, dia mau bantu-bantu disini.” Ibu menjelaskan.
“Wah kebetulan sekali, pengunjung akhir-akhir ini semakin banyak, pegawai disini sampai kewalahan melayani." Nada bicara Bu Dewi tampak semringah. Kedua matanya berbinar indah. "Oh iya ngomong-ngomong Neng bisa masak kan?” tanya Bu Imas antusias.
“Panggil Entin saja Bu. Alhamdulillah saya bisa masak beberapa masakan khas Sunda. Semoga saja bisa terpakai sama Ibu," ujarku tanpa bermaksud pamer dan menyombongkan diri.
“Jangan merendah, Nak, Ibu percaya masakan kamu pasti enak. Soalnya Ibu kamu juga salah satu juru masak terbaik disini, kamu bisa mulai kerja hari ini ya." Beliau menggamit lenganku seraya mengajak masuk ke rumah makan miliknya.
“Alhamdulillah, terima kasih Bu." Bahagia rasanya, melamar kerja dan langsung diterima hari itu juga.
Semoga ini menjadi pintu rezeki aku untuk bisa kuliah nanti, harapku. Ibu yang berdiri di sampingku tampak tersenyum senang.
***
Tak terasa sudah sebulan lamanya aku bekerja di rumah makan ini. Alhamdulillah aku telah mendapatkan gaji pertama. Lumayan, aku sudah bisa membuka tabungan dari hasil jerih payahku sendiri. Ditambah lagi uang honor dari karya tulisku yang dimuat di beberapa majalah dan surat kabar, kumasukkan juga ke dalam tabunganku, agar jumlahnya semakin banyak. Alhamdulillah juga beberapa masakan khas Sunda yang kubuat, seperti gepuk, nasi liwet, nasi tutug oncom, dan soto Bandung, kudengar dari Bu Imas menjadi favorit para pengunjung.
Jujur, aku ingin segera mengenyam bangku kuliah, ingin mewujudkan cita-citaku yang terpaksa ditunda karena keterbatasan ekonomi. Kelak aku ingin membangun sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dari kalangan tidak mampu, aku ingin membantu mereka untuk bisa mengejar cita-cita. Iba rasanya hatiku menyaksikan pemandangan anak-anak kecil bertelanjang kaki mengamen di trotoar jalan, sepertinya mereka terpaksa harus putus sekolah. Tatapanku menerawang ke langit-langit rumah makan, mimpiku terlalu tinggi, aku saja masih belum bisa menggapainya.
“Entin, kok melamun, ada apa? Cerita sama Ibu, siapa tahu Ibu bisa membantu.” Suara lembut milik Bu Imas membuyarkan lamunanku.
“Tidak ada apa-apa kok Bu,” jawabku singkat sambil melanjutkan pekerjaanku, membuat gepuk.
“Tidak apa-apa kok melamun, pasti ada yang sedang mengganggu pikiranmu ya? kamu nggak betah kerja disini?” tanya Bu Imas menyelidik.
Aku menggeleng mendengar pertanyaannya. “Saya betah kerja disini Bu, apalagi Ibu sangat baik pada saya, pada Ibu saya juga.”
“Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk bercerita, anggaplah Ibu ini seperti ibumu sendiri. Oh iya ngomong-ngomong kenapa kamu nggak melanjutkan kuliah?” tanyanya.
“Tidak ada biayanya Bu, saya kasihan sama Ibu saya yang harus kerja banting tulang untuk menghidupi kami berdua. Makanya saya ikut kerja ingin mengumpulkan uang untuk biaya kuliah, ingin meringankan beban Ibu juga,” ceritaku panjang lebar.
Entah mengapa dengan Bu Imas aku bisa lebih nyaman untuk bercerita tentang keluh-kesahku dibanding dengan Ibu. Aku hanya tak ingin Ibu sedih memikirkanku dan nantinya terbebani.
Netra Bu Imas berkaca-kaca. Ia membelai lembut kepalaku yang tertutup jilbab biru. "Kamu anak yang baik, Nak, semoga cita-citamu dimudahkan oleh-Nya ya." Aku mengamini do’anya dalam hati.
***
Hari Minggu ini pengunjung rumah makan Ibu Imas lumayan ramai. Aku dibuat sangat sibuk karenanya. Tiba-tiba kulihat ada sesosok lelaki muda menghampiri Bu Imas dan mencium tangan wanita itu.
“Itu Rian, putra semata wayangnya Bu Imas yang memegang cabang rumah makan di Balonggede,” ucap Ibu seolah membaca pikiranku yang keheranan melihat lelaki itu. Sebab, selama aku bekerja disini, baru pertama kalinya melihat sosok lelaki itu. Bu Imas pun tak pernah cerita padaku mengenai putranya.
“Entin sini, kenalan dulu sama anak Ibu!” panggil Ibu Imas sembari melambaikan tangan ke arahku.
Bergegas aku menghampiri mereka, kemudian menerima uluran tangan putra bossku itu.
“Kamu Ekar, 'kan? Yang karya-karyanya ada di majalah dan koran itu? Aku suka sekali dengan karya-karyamu, membacanya mengingatkanku pada sosok pahlawan, R.A Kartini,” katanya antusias.
Aku hanya mengangguk dan terbengong. Dari mana dia tahu nama penaku dan karya-karyaku? Oh ya ampun, aku tepok jidat. Jelas dia tahu, dari biodata dan foto yang terpampang di setiap akhir karyaku.
“Jadi selain jago masak, kamu juga seorang penulis Entin? Hebat!” ucap Bu Imas sambil mengacungkan jempolnya, kemudian ia melirik ke arah putranya dan tersenyum penuh arti. Aku tak mampu menerjemahkan maksud senyuman Bu Imas itu.
***
“Entin sudah tidur?” tanya ibuku sambil mengetuk pintu kamarku dari luar.
“Belum Bu, lagi baca-baca buku,” kataku sambil membukakan pintu untuk Ibu masuk.
Ibu duduk di atas ranjang dan membelai rambutku. “Nggak kerasa kamu sudah besar ya, Nak, Ibu bangga padamu, kamu anak yang baik. Bakatmu banyak, memasak, menulis. Ibu minta maaf ya tidak mampu mewujudkan mimpimu untuk kuliah,” ucapnya mulai terisak.
“Sudah Bu, tidak usah dipikirkan, Entin bukan tidak akan kuliah. Suatu saat nanti Entin pasti kuliah, sekarang kan lagi proses Bu. Proses mengumpulkan dananya dulu." Kugenggam jemarinya erat sembari tertawa berusaha menghibur Ibu.
“Nak, kalau kamu ingin segera mewujudkan impianmu, ada seseorang yang akan mengabulkannya,” ucap Ibu di sela-sela isak tangisnya.
“Maksud Ibu?” Aku mengernyitkan dahi tak mengerti dengan ucapannya barusan.
“Semenjak perkenalan itu, Nak Rian menyukaimu, Nak, dan Bu Imas memang sering bercerita tentangmu. Jadi, Nak Rian bermaksud melamarmu, menikahimu,” Ibu menjelaskan keherananku dengan kalimat yang membuatku seperti tersambar petir.
“Apa Bu? Menikah? Entin masih ingin kuliah Bu, Entin tidak mau terkekang. Entin masih ingin mengejar cita-cita. Entin ingin jadi orang sukses biar bisa bahagiakan Ibu, biar Ibu nggak harus kerja keras lagi cari uang.” Aku mulai menangis dan bergidik membayangkan kehidupan setelah pernikahan. Akan ada yang mengatur hidupku, apalagi setelah punya anak, ribet, nggak bisa kemana-mana, apalagi kuliah.
“Nak, pernikahan itu tidak seseram yang kamu bayangkan, Ibu dulu juga menikah muda. Ibu menjalaninya enjoy saja, hanya pikiranmu yang membuat segalanya rumit. Belum dijalani kok pikirannya sudah bilang ribet. Ibu yakin kamu akan bahagia bersama Nak Rian. Ibu percaya Nak Rian bukan tipe lelaki yang suka mengekang.” Ibu berkata panjang lebar seolah memahami jalan pikiranku.
Hening sejenak. Aku dan Ibu larut dalam jalan pikiran masing-masing. “Keputusan Ibu serahkan padamu, Nak. Ibu tidak akan memaksa. Istikharah, mohon petunjuk, mintalah yang terbaik sama Allah. Tapi kalau Ibu jadi kamu, Ibu akan menerima pinangan Nak Rian, sekarang atau pun nanti kamu tetap akan menjadi seorang istri, toh tidak ada larangan menikah untuk yang kuliah kan? Dua-duanya bisa dijalani.” Ibu beranjak dan melangkahkan kaki dari kamarku.
Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Pikiranku kalut antara harus menerima atau menolak. Entahlah, saat ini aku tak bisa berpikir jernih, semuanya terasa buntu. Aku semakin bergidik membaca biografi R.A Kartini, beliau wafat di usia muda, 24 tahun, setelah melahirkan putranya. Aku nggak mau meninggal di usia muda, batinku lirih.
***
Untuk pertama kalinya aku jalan berdua dengan calon suamiku yang belum sepenuhnya hatiku bisa menerimanya. Kami makan di sebuah restoran di bilangan Dago. Sesekali dia melemparkan candanya yang kubalas dengan senyuman yang dipaksakan. Sepertinya ia bisa menangkap sikapku itu.
“Kamu kenapa Ekar, masih meragukan niat suciku? Atau ada yang mengganjal di hatimu? Ceritakan saja, mungkin bisa diatasi,” katanya sambil terus menyunggingkan senyum.
Aku bingung harus berkata apa, lidahku kelu. Aku tak ingin dia nantinya tersinggung dengan kejujuranku.
“Katakan saja Ekar, jangan merasa tidak enak. Biar bisa membuatmu lega,” ucapnya.
“Sebenaranya ... begini ... bukannya ... saya ....” Terbata-bata aku berkata. Tak tahu harus mulai dari mana, padahal di rumah tadi tekadku sudah bulat untuk mengucapkan semua uneg-uneg dalam hati.
“Tidak mengapa, katakanlah."
Aku menghela napas berat. Kukumpulkan segenap keberanian. Kedua telapak tanganku terasa dingin. Sesekali sudut mataku melirik ke arahnya. Ada perasaan tak nyaman menghampiri. Namun, tekadku sudah bulat. Aku harus mengutarakannya, agar dia tahu apa yang kurasakan.
“Sebenarnya, bukan saya menolak, hanya saja saya belum siap untuk menjadi seorang istri. Saya masih ingin kuliah, ingin mengejar cita-cita yang selama ini tertunda karena tak ada biaya, makanya saya kerja. Mau mengumpulkan uang buat biaya kuliah, saya belum siap menikah. Saya ingin membahagiakan Ibu, selain itu saya ingin mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak tidak mampu. Cukup saya yang merasakan harus kerja dulu agar bisa mengenyam pendidikan," ujarku menjelaskan ganjalan di dada, persis seperti kata-kata yang sudah aku susun di rumah.
Aku menghela napas, lega rasanya, namun ada sedikit rasa kuatir kalau-kalau dia akan kecewa mendengar penuturanku yang jujur dan lugas itu. Alih-alih bersedih, dia malah tertawa, membuatku heran dibuatnya.
“Jadi itu yang selama ini menjadi ganjalan buat Ekar menerimaku? Begini Ekar, aku berjanji setelah kita menjadi suami istri, aku tidak akan mengekangmu. Kau boleh kuliah dimana pun kau mau, aku akan membiayainya. Ekar aku akan bantu kamu mewujudkan impian muliamu itu,” ujarnya mantap tanpa tersirat keraguan sedikit pun.
Aku terlongo, masih tak percaya dengan yang aku dengar barusan. Mungkinkah ini mimpi? Kalau pun iya, rasanya tak ingin segera terbangun. Sebab, hal ini terlalu indah.
“So, Ekar, will you marry me?” pintanya sambil berlutut tepat di hadapanku.
Jantungku berdegup tak karuan. Aku yakin wajah ini sudah bersemu merah karenanya. “Duh jangan begini, malu."
“Will you?” tanyanya sekali lagi. Debaran di dadaku kian kentara. Ada kelegaan dan binar bahagia terpancar di wajahnya melihat anggukan dariku. Tepat di hadapanku, ia sujud syukur sembari mengucap hamdallah.
***
Beberapa tahun kemudian
Sebuah bangunan sekolah dasar dua lantai bercat dinding putih sudah berdiri kokoh di hadapanku. Siswa-siswanya berasal dari kalangan tidak mampu. Semuanya dibebaskan dari biaya pendidikan. Tak hanya itu, Mas Rian juga membiayai kuliahku hingga jenjang S-2. Inilah aku sekarang, Entin Kartini, S.Pd, M.M, salah satu staf pengajar sekaligus kepala sekolahnya.
“Terima kasih, ya Mas, sudah mewujudkan cita-citaku. Aku tak mungkin bisa menggapai semuanya tanpa bantuanmu.” Kugenggam jemarinya erat, dia balas menggenggamnya dengan lembut.
Dia tersenyum, mengecup lembut jemari tanganku. Benar nasihat Ibu waktu itu, menikah tidak seseram yang dibayangkan. Aku bisa tetap menjalankan peranku sebagai seorang istri, memasak masakan khas Sunda kesukaannya, mengajar, mengelola sebuah sekolah, dan juga tetap produktif menulis.
Ciwidey, 14 Januari 2020
Suci Rahayu
Cerpen lainnya:
Indeks Link
Diubah oleh suciasdhan 11-02-2020 07:14
meanynovendi dan 13 lainnya memberi reputasi
14