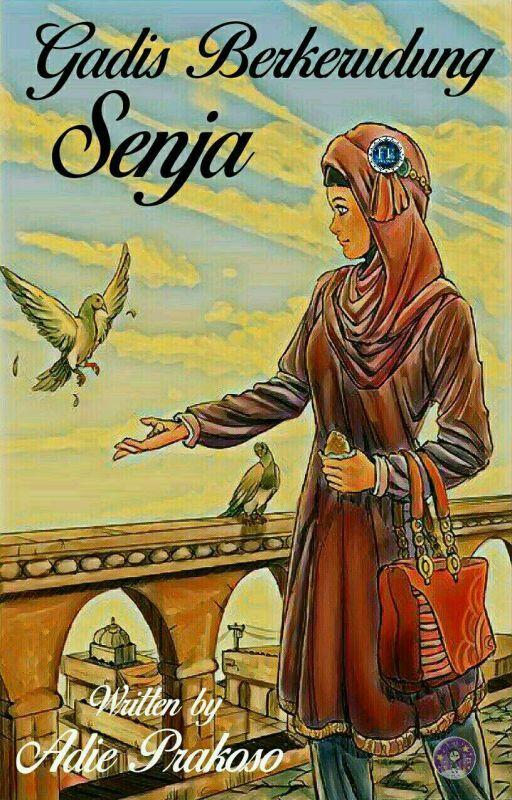Quote:
"Hanafi, kau tahu tidak. Kalau aku boleh bercerita, kenapa aku sampai sekarang belum mencari pasangan pengganti lagi? Hidup menduda?"
Aku menatap mata Pak Jaya, seperti ada rahasia besar yang disimpan di balik bola matanya. "Boleh saja Pak, justru aku suka dengan cerita-cerita cinta yang nyata."
"Cinta sejati itu memang benar adanya. Aku sudah menemukannya, dan aku tak bisa mencari pengganti cinta sejati itu. Terlalu sulit dan mungkin setiap manusia hanya mendapat satu jatah saja di dunia ini. Satu cinta sejati. Dan jangan pernah sia-sia kan cinta sejati yang tulus itu, jagalah sampai maut memisahkan." Pak Jaya mengambil tisu, menyeka ujung matanya.
"Jadi begini, ceritanya." Pak Jaya mengambil napas panjang, sebelum bercerita panjang lebar. Masih ada waktu setengah jam lagi, sebelum sholat isya'.
"Dulu, ketika aku masih remaja se-usia kau. Aku sudah bekerja keras, banting tulang, mengais nafkah, demi mengobati Ibu yang sedang sakit keras di rumah. Aku merantau ke jakarta. Aku hanya lulusan SLTP. Dulu, ijazah SLTP masih bisa bersaing di dunia pekerjaan, bapak melamar sebagai cleaning service di salah satu rumah sakit ternama di ibu kota. Tiga hari selepas melamar, aku mendapat surat dari petugas pos. Jaman dulu tidak memakai hp, jadi kalaupun tidak mendapat surat dari perusahaan yang bersangkutan selama kurang lebih seminggu, ya alamat tidak lulus."
"Lalu?" Aku memotong.
"Aku mendapat surat berisikan panggilan interview. Aku menyambut hangat berita baik itu. Kebetulan, aku sedang bekerja sebagai kuli bangunan, ikut Paman. Aku meminta ijin tidak masuk selama sehari, alasan mendapat panggilan kerja di salah satu rumah sakit swasta. Paman mengijinkan, aku pamit. Bermodalkan alamat yang tertera di kop surat, aku melangkah pergi, naik oplet, tanya-tanya ke warga, sempat tersesat, dan pada akhirnya sampai juga di tempat tujuan, yah, walau agak telat sepuluh menit."
"Aku sudah berdiri di depan rumah sakit yang megah itu. Kalaupun di samakan dengan hotel, mungkin hotel bintang lima. Aku melapor ke satpam jaga, mereka mengijinkan, lantas menunjukkan jalan masuk ke tempat interview. Aku mengangguk, lekas berjalan masuk. Seingatku, ruangan itu ada di lantai dua—di sisi lift. Ruang tamu. Aku melangkah masuk, mengetuk pintu. Didalam sudah ada dua orang yang berpakaian sama sepertiku. Putih-hitam."
"Penyelia itu memberikanku puluhan pertanyaan yang membuatku sedikit gugup saat menjawab. Tapi dengan jawaban kepolosanku, aku diterima. Dua hari setelah itu, aku mulai aktif bekerja di rumah sakit, sebagai tukang bersih-bersih. Jaman dulu, tidak ada kontrak kerja. Jadi kami bekerja se-betah kami. Satu teman kerjaku mengundurkan diri, baru bekerja sehari. Katanya, dia gak kuat bekerja di rumah sakit, melihat darah bermuncratan, bertemu orang sekarat, dan kadang pula bertemu dengan keluarga yang sedang berduka." Pak Jaya mengambil napas sejenak, meneguk teh yang sudah dingin di atas meja.
"Kau tahu, Hanafi. Berapa tahun aku kerja disana sebagai kacung?" Aku menggeleng. "Tiga tahun lebih, dan di rentang waktu itu, aku bertemu dengan cinta sejatiku. Kau pasti tak akan percaya dengan kisah cintaku yang terbilang klasik dan khayal."
Pak Jaya kembali bercerita. "Di tahun kedua bekerja di rumah sakit. Aku menjadi karyawan senior, mungkin paling lawas. Aku dipindahkan ke bagian lantai tiga, tepatnya di ruang VVIP. Ruang khusus bagi orang-orang kaya. Dari situlah aku bertemu dengannya?" Pak Jaya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca.
"Hari itu, aku mulai bertanggung jawab di ruang VVIP. Malam itu, jam sepuluh, aku sedang mempersiapkan kamar untuk pasien baru. Dikarenakan kamar VVIP sudah penuh, tinggal satu kamar yang kosong, dan itupun baru ditinggal pergi sama pasien, eh, ada pasien baru lagi. Macam mana ini, kenapa orang sakit setiap menit selalu ada. Macam orang jatuh cinta, mungkin."
"Satu jam, kelar sudah membersihkan kamar, sudah di steril dengan sinar UV (Ultra-Violet). Semprot dengan wangi-wangian, biar semakin harum dan nyaman. Aku bergegas ke ruang perawat, memberitahu, kalau kamar sudah siap dipakai. Perawat VVIP menelpon IGD, dan dalam waktu sepuluh menit, pasien itu sudah meluncur ke lantai tiga. Aku lekas membuka kamar menggunakan kunci, mempersiapkan dispenser, dan menunjuk-nunjuk fasilitas yang ada. Seperti televisi, kulkas, dispenser, shower, AC, dan telepon. 'Kalau butuh apa-apa, tinggal telepon saja Pak'. Sebelum aku pamit keluar, bapak itu memanggilku, meminta tolong untuk mengangkat bed dibagian kepala pasien agar lebih tinggi. Aku mengganguk, lantas memutarnya."
Aku menatap Pak Jaya takzim. Tak sedikit pun berkedip, ceritanya semakin menarik, aku ingin cepat-cepat selesai. Karena tinggal lima belas menit lagi, waktu bersantai sebelum sholat isya'.
Pak Jaya kembali tersenyum tipis, melanjutkan cerita. "Saat aku berdiri, dan menatap pasien yang terbaring lemah di atas kasur dengan peralatan medis yang masuk ke dalam hidung, dan beberapa perban di wajah dan tangannya. Tapi di balik itu, dia cantik. Matanya menatapku lamat-lamat, setelah itu tersenyum tipis, dari ekspresi wajahnya, mengambarkan kalau dia hendak bilang terima-kasih."
"Aku mulai penasaran dengan perangainya. Lantas merangsek masuk ke ruang perawat, bertanya. Siapa sosok gadis itu? Apa dia korban kecelakaan? Di mana tempat tinggalnya? Sialnya, perawat justru menggodaku dengan kalimat-kalimat yang membuatku malu kala itu. Akhirnya aku tahu namanya dari papan yang terpajang di dinding ruang perawat. Namanya 'Mega Susilowati', korban kecelakaan lalu lintas, alamat rumahnya ada di daerah Jakarta Utara."
"Jadi, Pak Jaya mulai suka nih, sama Mega siapa tadi namanya?" Aku meledek.
Wajah Pak Jaya memerah. "Mega Susilowati."
"Lalu bagaimana kelanjutannya, Pak?" tanyaku penasaran.
"Mulai detik itu, kerjaku jadi semangat. Dan satu hal, satu kamar yang sengaja ku bersihkan dibaris akhir, yakni kamar pasien bernama Mega. Karena aku ingin berbincang-bincang lebih lama dengannya. Entah mengapa, setelah aku melihat tatap matanya dan senyum manisnya di balik peralatan medis itu, semangat kerjaku tumbuh mengakar begitu hebat. 'Assalamualaikum! Permisi Pak, mau dibersihkan dulu, Bapak nunggu diluar sebentar ya.' , Bapak itu mengangguk, tersenyum, lantas berjalan keluar membawa koran tempoe doeloe.
"Sapu dan lap sudah siap, beberapa meja sudah di lap bersih, mengecek perlengkapan yang ada, lepas itu mulai menyapu. Gadis yang terkapar itu menoleh ke sisi kanan, di mana aku sedang sibuk menyapu. Aku memberanikan diri menyapanya, 'Mbaknya sudah baik?'. Dia tersenyum. Aku diam, masih berpikir keras mencari bahan obrolan. 'Oh ya, kalau boleh tahu, mbaknya masih sekolah?'. Dia hanya tersenyum. Aku tambah binggung, lantas mempercepat tugas kerjaku, dan segera keluar. Aku malu bukan main, dia tidak menjawab, hanya tersenyum."
"Mungkin dia belum bisa ngomong kali?" Aku memotong.
Pak Jaya menggeleng, kembali melanjutkan true story-nya.
"Satu bulan berlalu, aku mulai angkat tangan. Aku tak berani menyapanya lagi, dia masih tinggal di kamar itu. Sudah berkali-kali melakukan operasi di kakinya. Tapi masih belum kunjung sembuh. Suatu malam, Bapaknya memanggilku saat hendak pulang. 'Ya, ada apa Pak?'. 'Kau bisa jaga anak-ku malam ini tidak? Tidak usah khawatir soal uang. Aku membutuhkan bantuanmu Dek, aku ada meeting kerja, ini mendadak dan sangat penting.' Bapak itu menatapku penuh harap. Aku mematung di hadapannya. 'Kenapa bapak mempercayakan itu kepadaku? Bukankah aku ini orang asing?'
'Aku percaya padamu Dek, karena kamu itu baik. Anakku sudah bercerita banyak kepadaku. Kamu mau kan?' Bapak itu mengambil lembaran uang seratus ribuan, jumlahnya ada tiga. Aku menelan ludah, jaman dulu, uang ratusan ribu itu sangat banyak, kalaupun dibandingkan dengan sekarang, ada sekitar tiga jutaan rupiah mungkin. Aku menolak. 'Apa kurang?' Bapak itu menambahkan lagi. Aku menjawab tegas, 'aku tidak butuh uang sebanyak itu, Pak. Aku ikhlas kok.' Tapi Bapak itu tetap memasukan uang tiga ratus ribu bahkan ditambah dua lembar lagi ke saku seragamku. Bapak itu menepuk pundakku, lekas pergi."
"Aku kembali menelan ludah, ku ambil uang ratusan ribu itu, ku pegang. Alhamdulilah, dengan datangnya rejeki ini, aku harap bisa mengobati penyakit ibu di kampung. Jam 00.00, ku ketuk pintu kamar tersebut, lekas masuk ke dalam, gadis itu tertidur. Aku duduk di sampingnya, kebetulan ada sofa panjang. Lambat laun, aku ketiduran. 'Hey, bangun! Hey!' Aku terkejut mendengar suara itu, tidak asing bagiku. 'Ngapain kau tidur di sini? Hah?' , Anjas, salah satu karyawan yang sama sepertiku, membangunkanku. Dia masuk sif malam."
"Dia menatapku curiga, 'Di mana Bapaknya gadis itu?' Aku mengucek mata, 'Dia sedang meeting kerja, titip anaknya padaku. Cuma malam ini saja.' Anjas berbisik, 'dapat uang tips berapa?', aku bergegas mengambil satu lembar ratusan ribu ke Anjas, 'Ini, bagi sana sama teman-teman. Jangan sampai bocor ke kordinator ya!' Aku mengancam. Anjas menyeringai lebar, mengipas-ngipaskan uang itu, lantas pergi keluar. Satu-dua perawat masuk, mereka sepertinya sudah di sogok Anjas, hanya tersenyum kecil menggodaku."
"Pagi harinya, aku melaksanakan sholat shubuh di samping gadis itu. Dia sepertinya sudah bangun, berusaha duduk, mengambil air putih. Selepas menjalankan ibadah, gadis itu menyapaku riang. 'Kak, makasih ya, selama ini udah kasih perhatian ke aku, udah menjadi penyemangat dalam hidupku. Berkat kakak, aku mempunyai semangat hidup lagi.' Aku melongo, kalaupun aku bayi, mungkin sudah ngiler dengar kata-katanya. 'Kak! Kok diem!'.
'Eh, iya. Kamu sudah baikan?'
Gadis itu tersenyum ceria, 'Alhamdulilah Kak, tapi...' dia tidak melanjutkan kalimatnya. 'Tapi kenapa?' tanyaku. 'Sepertinya aku tidak bisa berjalan lagi kak?' Matanya mulai berkaca-kaca, perlahan meneteskan air mata."
"Lalu? Terus? Bagaimana?" Aku sudah macam wartawan, bertanya terus, semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya.
"Dua bulan dirawat di rumah sakit, bukan hal yang mudah bagi seorang gadis remaja se-usianya. Dan di hari sabtu, tepat pukul 15.00, dia di ijinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Aku merasa lega dan senang mendengar kabar baik itu. Tapi, ada satu perasaan yang hilang, semenjak gadis itu tak lagi ada di kamar VVIP. Hari-hariku terasa membosanakan, aku sering melamun tak jelas. Suatu hari, aku dapat jatah masuk pagi. Jam istirahat, aku berkunjung ke ruang poliklinik untuk menemui temanku yang sedang berobat. Aku terkejut bukan main, saat melihat gadis itu ada di sana, tersenyum melihatku di atas kursi roda. Dia melambaikan tangan kepadaku, aku salah tingkah, hatiku berbunga-bunga, lantas menhampirinya, bercakap dengannya dan Bapaknya."
"Selepas itu, Bapaknya menyuruhku untuk datang ke rumahnya, malam itu juga. Katanya akan mengadakan syukuran atas anaknya yang semakin hari semakin membaik. Malam itu pula, aku berdandan rapi, meminjam motor paman, melesat ke sebuah kompleks perumahan, mencari rumah nomor-9. Lantas terkejut, rumah nomor-9 membuatku merinding dan merasa tidak pantas untuk masuk ke dalam sana. Rumah yang bak layaknya istana."
"Satpam rumah membukakan gerbang, aku disuruh masuk dan memarkirkan motor di tempat parkir yang sudah disediakan. Gadis itu sudah menyambutku dengan senyuman hangat, dia masih duduk di atas kursi roda. Aku di suruh masuk, di dalam sana sudah ada Bapak dan Ibunya, sepertinya acara syukuran sudah rampung, aku datang telat. Satu hal yang membuatku gugup pada waktu itu, ketika Bapaknya bertanya kepadaku. Pertanyaan itu sungguh di luar nalar pikiran, seumur hidupku, aku baru pernah mendapat pertanyaan seperti itu."
"Pertanyaan macam apa itu?" tanyaku semakin penasaran.
"Kau tahu, Hanafi. Bagaimana rasanya, ketika diberi pertanyaan macam ini, 'Apa Dek, siapa namanya?' Aku menjawab ragu, 'Kusuma Jaya, Pak.' Bapak itu tersenyum, 'Kusuma Jaya, kamu adalah laki-laki luar biasa, berkat kamu, anakku mempunyai semangat hidup lagi. Lantas, apa Dek Jaya sudah punya calon?'. Aku terdiam, lantas kembali berkata, 'belum pak!'."
Aku menatap Pak Jaya tanpa berkedip.
Pak Jaya kembali melanjutkan kisah cintanya. "Suasana menjadi hening sesaat. 'Maukah kamu menjadi suami dari anakku ini?' Aku tersedak, menelan ludah, apa aku sedang bermimpi. Mendapatkan istri cantik dan kaya raya? Ah, tidak mungkin. 'Bagaimana Nak Jaya?' Aku menggaruk kepala yang tidak gatal, lantas menjawab, 'apa anak bapak mau dengan saya?' Gadis itu tersenyum manis, memainkan rambutnya yang tergerai panjang. 'Bagaimana nak?' Bapak menoleh ke arah gadis itu. Gadis itu mengganguk mantap. Hatiku berbunga-bunga, ingin rasanya berteriak ke taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga cantik."
"Lalu? Setelah itu? Bapak menikah dengannya?"
Pak Jaya menyeringai. "Ya. Satu bulan kemudian, kami melangsungkan acara pernikahan. Alhamdulilah, Ibu sudah sembuh, beliau dapat berkunjung ke jakarta. Setiap hari aku merasakan berjuta-juta rasa yang tak bisa ku ungkapkan dengan kata-kata. Gadis itu berusaha menjadi lebih baik dihadapanku. Tapi, suatu hari, dia berkeluh kesah. 'Aku tidak pantas menjadi istri, Mas.' Aku terkejut mendengar kalimat itu, 'tidak pantas kenapa? Kamu adalah segalanya bagiku, Mega.' Gadis itu menunduk di atas kursi roda, menangis. 'Aku tidak bisa berjalan. Sepertinya, aku sudah lupa bagaimana caranya berjalan.' Aku lekas memegang erat tangannya, 'ingat ya. Aku mencintai kamu apa adanya, tulus. Aku terima kamu apa adanya, mau kamu cacat, tidak bisa berjalan, aku terima kamu. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh ya.' Dia kembali tersenyum mendengar kata-kataku tadi."
"Dua-tiga tahun, kami tidak ada masalah lagi. Di tahun ketiga, kami memutuskan untuk beli rumah sendiri, dan rumah inilah saksi cintaku kepadanya, Hanafi. Sampai bertahun-tahun. Tapi, selama bertahun-tahun pula, kami tidak dikaruniai seorang anak. Istriku kembali berpikiran aneh, merasa tidak pantas menjadi istri terbaik. Padahal aku tidak menuntutnya lebih. Hingga malam itu, dia ku temukan tewas di kamar mandi, dengan luka sayatan di tangannya. Aku terkejut, dibuat panik, lekas menghubungi rumah sakit. Beberapa warga kampung sini berusaha ikut menolong. Tapi, Tuhan berkata lain, dia sudah tewas sebelum sampai ke rumah sakit." Pak Jaya mengeluarkan air mata, aku lekas mengambilkan tisu yang sudah tersedia di atas meja.
"Setelah dia meninggal. Aku memutuskan hidup sebatang kara. Karena di dalam hatiku yang paling dalam, masih terukir namanya, cintanya."
Aku ikut terharu mendengar cerita Pak Jaya. Di balik sosok Pak Jaya yang humoris dan kocak itu, ternyata menyimpan duka yang mendalam. Mungkin bagiku—aku tidak akan mampu menjalani hidup, setelah mendapat hal seperti itu. Tapi, beliau masih kuat dan semangat menjalani hidup.
Suara adzan menghentikan cerita menyedihkan ini. Pak Jaya lekas masuk ke dalam kamar, bersiap diri. Aku pun juga. Kami berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat isya' sekaligus tarawih.
"Besok kan Hari jum'at, maukah kau temani Bapak ini ke pemakaman?" Aku mengangguk setuju. "Akan aku kenalkan kau dengan istriku, ku harap dia senang melihatmu, Hanafi."