- Beranda
- Stories from the Heart
Accidentally, You.
...
TS
salmansharkan
Accidentally, You.

Quote:
“That moment when you meet a perfect stranger who makes you feel like life.”

Quote:
Ini cerita tentang Airin saat berada di titik terendah dalam hidupnya. Airin menemukan sosok yang bisa membuatnya tersenyum dan mendadak bahagia dan lalu jatuh cinta.
Quote:
Langkahku melambat seiring dengan hembusan angin pelan menerbangkan ujung rambut panjang sepunggungku. Aku sedang bimbang sekarang. Beberapa jam yang lalu aku mengalami hal yang paling aku benci seumur hidupku: pertengkaran orang tua.
Aku masih tidak mengerti sampai saat ini, apa yang membuat mereka berdua mempertahankan pernikahan mereka sementara mereka selalu bertengkar setiap hari. Apa itu karena aku? Jika memang alasannya demikian, kurasa itu adalah alasan yang bodoh. Aku sudah mulai tidak memedulikan mereka lagi.
Oh ya… kau bisa sebut aku kurang ajar atau tidak menghormati orang tua, tapi seperti itulah adanya sekarang. Ada atau tidak ada aku diantara mereka toh mereka tetap bertengkar juga. Ada atau tidak ada mereka bersamaku, toh aku tetap tidak diperhatikan juga.
Aku baru saja turun dari sepeda motor yang ku gas penuh dari rumah menuju sebuah pantai yang banyak dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke pulau kecil yang kadang terlupakan ini. Aku melangkah ke arah barat daya, ke arah susunan batu pemecah ombak yang dikelilingi oleh pasir-pasir putih. Melepas alas kakiku dan merasakan hangatnya pasir pantai yang membelai lembut telapak kakiku. Ingin sekali aku mengubur kakiku disana, sekarang juga. Kalau bisa sekujur tubuhku sekalian. Kehangatan itu kurasa bisa menggantikan dingin dan bekunya suasana rumah selama lima tahun terakhir ini.
Aku menghembuskan napas berkali-kali. Menarik napas dalam berkali-kali. Mencoba menenangkan diriku dengan cara yang diberitahukan seorang penyiar radio dalam sebuah acara kemarin siang. Aku mencoba menepikan semua masalahku ke sudut otak yang lain, menggabungkannya ke sebuah titik dan lalu memaksa setiap selnya untuk melupakan apa yang telah terjadi dan mengembalikan kenangan-kenangan yang kemungkinan bisa membuat aku tertawa.
Tapi… ah… aku tidak punya banyak kenangan indah. Umurku sudah dua puluh dan aku belum pernah merasakan pengalaman yang bisa ku kenang dengan indah disaat-saat seperti ini. Aku mengerucutkan bibir dan melanjutkan perjalanan ke ujung barat daya pantai itu dengan sepasang alas kaki di tangan kiriku.
Hari masih sangat pagi… Aku meninggalkan rumah sekitar pukul enam dan sekarang masih dingin dan agak berkabut. Debur ombak menemaniku berjalan hampir sendirian di pantai yang biasanya ramai ini. Memanjakan telingaku dengan lembut nyanyiannya ketika menyentuh bibir pantai dan bertemu pasir tempatku menapak. Aku menatap langit yang masih agak gelap di sebelah barat, namun berpadu cahaya khas matahari terbit di sebelah timur. Awan mulai membentuk formasi abstrak khas yang sangat kusuka.
“Lapar…”Aku mengelus perutku. Seharusnya memang ada penjual makanan di dekat parkiran pantai itu tapi aku melewatkannya begitu saja tadi karena pikiranku yang sedang rumit. Tanpa kusadari aku sudah tiba di ujung sebelah barat daya pantai itu. Ada banyak batu-batuan yang sengaja dibuat dan disusun untuk sebagai pemecah ombak disana. Aku duduk di salah satu batu tak jauh dari bibir pantai. Air dingin sesekali mengenai ujung hidungku yang membuatku semakin menggigil.
Aku menarik napas dalam lagi. Berusaha sebisa mungkin berbicara dengan Tuhan dari dalam hatiku. Memohon padanya agar hari ini, sehari saja, aku bisa merasa bahagia. Agar hari ini, sehari saja, aku bisa melepaskan segala beban di pundak, hati dan otakku dan tersenyum. Agar hari ini, aku bisa melupakan semuanya… tidak hanya hari ini saja, tetapi mulai hari ini dan seterusnya.
“Hai…”
Hatiku mencelos. Hampir saja aku berteriak karena terkejut mendengar suara itu masuk melalui telinga kananku. Aku merasakan kehadiran seseorang di sampingku, duduk persis di atas batu di sebelah tempatku duduk. Suara laki-laki. Tubuhku seketika mengejang, ketakutan. Aku sangat tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini: laki-laki dan kejutan. Suara ombak benar-benar menenggelamkan suara langkah kakinya. Aku berusaha untuk tenang dan mengatur kecepatan detak jantungku.
“Mengagetkanmu, eh?” dia bicara dalam bahasa Korea. Aku mengerti sekali. Aku pernah belajar bahasa Korea dan mendapatkan sertifikat. Anehnya, ketika mendengarnya bicara perasaan tegang yang tadi menyerbu itu seketika menghilang. Detak jantungku mulai normal dan aku mulai rileks sekarang.
Kuberanikan diriku untuk menoleh ke kanan, dan disanalah dia duduk, tiga puluh sentimeter dari wajahku. Seorang laki-laki berkulit putih, sangat putih tapi tidak pucat, berambut hitam legam lurus disisir klimis dan dibelah dibagian pinggir, tatapannya tajam dari bola matanya yang sehitam intan, berhidung mancung dan kokoh diatas bibirnya yang tipis kemerahan.
Dia tersenyum… padaku, orang yang tidak dia kenal sama sekali. Senyumnya benar-benar tidak dibuat-buat. Aku bisa membedakannya.
Aku mulai bertanya-tanya, kenapa dia tiba-tiba datang dan menyapaku?
Aku meyakinkan diriku bahwa dia bukan hantu atau semacamnya karena aku tahu betul, penduduk lokal pulau ini masih sangat percaya mitos dan tahayul. Ku gerakkan kakiku dengan sengaja menyentuh ujung sepatunya dengan harapan dia tidak akan merasakan sentuhan itu…
Sepatu… kenapa dia menggunakan sepatu diatas pasir? Bukankah itu aneh?
Otakku mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting sampai-sampai aku lupa aku masih menatapnya sekarang. Matanya… indah sekali… Rasanya seperti menatap sebuah bintang paling terang yang bisa kau lihat di malam hari, seperti melihat keindahan Venus di kala fajar, atau menatap bulan di posisi terdekatnya dengan bumi delapan belas tahun sekali.
“Kau sendiri?” tanya laki-laki itu lagi. Saat itulah aku baru memalingkan pandanganku kembali ke atas batuan yang basah oleh air yang dibawa ombak.
“Bagaimana kau tahu aku berbicara berbahasa Korea?” tanyaku spontan. Separo penasaran separo tidak peduli. Entah bagaimana caranya aku masih ingat wajahnya ketika menatap batu-batu yang ada di depan kakiku itu.
“Kau tidak sadar?” tanyanya merasa aneh.
Aku menoleh, “Hah?” aku tidak mengerti juga.
“Ketika kau datang, memarkirkan sepeda motormu, kau mengumpat dalam bahasa Korea,” jelasnya.
Wajahku memerah seketika. Entah aku ingat atau tidak apa yang aku ucapkan beberapa menit yang lalu. Aku memang suka bicara sendiri ketika sedang berkendara. Entah kenapa itu membuatku merasa lebih baik.
“Benarkah?” aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Dia mengangguk sambil tersenyum simpul. Sesaat pikiranku mulai teralih oleh wajahnya yang memukau itu. Lalu sedetik kemudian aku tersadar oleh ucapannya tadi. “Jadi sejak tadi kau mengikutiku, eh?” nada bicaraku agak tinggi dan menggeser posisi dudukku agak menjauh.
“Wow, tidak, bukan begitu! Aku hanya sedang berlari pagi dari hotel dan ketika mendengar kau bicara, aku, yah… terpikir untuk berjalan-jalan ke tempat ini juga,”
“Alasanmu tidak masuk akal! Kau pasti mengikutiku!” aku berteriak dan sekarang berdiri menjauh darinya.
“Hey, hey, tenang… aku tidak bermaksud… sungguh. Kau tidak percaya? Apakah wajahku terlihat seperti penjahat?” dia menunjuk wajahnya sendiri. Kentara sekali dia takut aku tiba-tiba marah dan pergi dari tempat itu. Entah kenapa aku merasa seperti itu.
“Tidak… kau mirip Wonbin… atau Kangta…? Ah… Kau juga sedikit mirip Choi Siwon…” aku meracau lalu duduk lagi.
Entah wajahku sudah semerah apa aku tidak tahu tetapi aku bisa merasakannya memanas.
Laki-laki itu tertawa sambil menutupi mulutnya dengan kepalan tangan kangannya. Aku melirik kearahnya dan memerhatikan ekspresi wajahnya saat itu. Dia terlihat benar-benar mengagumkan dengan tawanya.
“Kenapa tertawa?” aku berusaha tetap bicara dengan nada marah meskipun aku yakin sebenarnya aku sudah gagal.
“Kau juga menyanyikan sebuah lagu tadi. Fiction dari Beast kalau aku tidak salah dengar, eh?”
Mataku melotot, tercengang. Aku mulai merinding. Laki-laki ini… Wajahnya memang tampan, tapi dengan pendengaran seperti itu… Maksudku, aku bernyanyi tanpa ada niatan untuk didengar oleh siapapun. Aku biasanya bernyanyi untuk diriku sendiri… Bersenandung… Kenapa dia bisa mendengarnya? Bagaimana bisa dia mendengarnya?
“Apakah aku bernyanyi sekeras itu? Kau membuatku takut… Sungguh!” ucapku. Diam, aku masih menatap matanya yang juga menatap mataku. Dia sepertinya bisa membaca pikiranku atau apa, sedetik setelah dia menyelami mataku, ekspresinya berubah.
“Kau sedang ada masalah, eh?”
Hatikuku mencelos. Lagi. Sesegera mungkin aku mengalihkan pandanganku dan mencoba tenggelam dalam birunya samudera di depanku. Membatin. Apakah adegan saling tatap tadi membuat dia bisa membaca semua pikiranku?
“Kau ini penyihir atau apa, sih? Aku selalu takut dengan orang yang bisa membaca pikiran orang lain!” aku berkata jujur dan berteriak. “Rasanya seperti tidak punya privasi!”
Dia tertawa. TERTAWA!
Astaga… pria ini bukan manusia kurasa. Aku bahkan tidak bisa menangkap bagian yang lucu dari kalimat-kalimatku sebelumnya. Tetapi… tawa laki-laki itu, entah kenapa aku merasa sangat senang mendengarnya. Entah kenapa aku sangat senang melihatnya.
“Kau tidak pernah dengar?” dia bertanya.
“Apa?”
“Masalah yang sedang dihadapi seseorang akan sangat terlihat jelas di matanya. Ketika mereka melihat, mereka tidak benar-benar memerhatikan apa yang mereka lihat. Ketika mereka menatap, mereka tidak benar-benar menghiraukan apa yang mereka tatap.”
Aku hanya diam dan–ya–aku sedang menatapnya. Tapi… apakah aku memikirkan hal lain saat ini? Apakah dia tahu aku punya masalah yang sumpah demi Tuhan aku tidak ingin ceritakan pada siapapun bahkan teman terdekatku sekalipun jika memang aku punya?
“Ketika kau menatapku tadi, kau tidak benar-benar memerhatikan mataku… seperti ada pembatas kaca tak terlihat tetapi sangat tebal diantara mataku dan matamu. Dan di dalam kaca itu ada banyak sekali kegundahan yang sekarang sedang menghantui pikiranmu… Benar ‘kan?”
“Aku mulai takut. Sungguh…” kataku jujur, masih menatapnya.
“Kalau begitu, katakan, apa yang harus aku lakukan agar kau tidak takut?”
“Hah?” pertanyaan itu benar-benar aneh.
Dia tertawa lagi. Oh Tuhan… tawa itu… Aku benar-benar seperti sedang berada dalam satu scene di sebuah drama Korea sekarang. Aku mencoba mengembalikan kesadaranku. Mencoba sekali lagi membuang dan menyisihkan semua pikiran tentang masalah-masalahku ke sudut otak yang lain untuk bisa benar-benar memerhatikannya. Entah kenapa ucapannya tentang kaca tebal di depan mataku itu sangat mengganggu pikiranku. Rasanya seperti aku kehilangan ketulusan dalam diriku. Aku menatapnya lagi… Wajah itu… Perpaduan antara Wonbin dan Choi Siwon, sudah jelas.
“Kau mencoba memerhatikanku tanpa memikirkan masalahmu, eh?”
Sebuah tombak sudah menusuk punggungku sekarang. Dia benar-benar mengerikan!
“Aku… errr… aku benar-benar takut karena kau sepertinya tahu apa yang sedang aku pikirkan… Aku yakin kau pasti keturunan seorang penyihir di Korea!”
Dia tertawa lagi. “Hmmm kupikir kami tidak mengenal penyihir di Korea?”
“Tapi penyihir ada di semua negara, bukan?”
“Aku tidak tahu…” jawabnya tegas sambil mengangkat bahu dan mencoba menirukan gaya imut khas member boyband Korea.
“Katakan, bagaimana kau bisa tahu apa yang sedang aku rasakan!”
“Aku hanya menebak,”
“Bohong!”
“Sungguh! Dan sekarang kau mulai merasa takut, kan?”
“BAGAIMANA KAU TAHU?!”
Dia tertawa lagi. Oh aku mulai menyukai suara tawanya.
“Kau tadi bilang begitu.”
Wajahku seakan terbakar. Oh tidak, kali ini benar-benar sedang terbakar. Kakiku tiba-tiba saja gemetaran dan angin yang tadinya menenangkan menjadi sedikit terlalu dingin dan membuatku merinding berlebihan. Aku menunduk dan menahan tawa.
“Kalau kau ingin tertawa, sebaiknya dilepaskan saja… tidak baik menahan tawa. Kau tahu, jika kau menahan tertawa, pusar mu akan bertambah satu,”
“Bohong!” Aku berteriak lalu menutup mulutku sendiri dengan kedua tangan. Membayangkan bagaimana bentuk tubuhku dengan dua pusar. “KAU BOHONG!” jelas sekali ketakutan di wajahku dan dia melihatnya kemudian tertawa.
Dan… untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, aku ikut tertawa… lepas… sepertinya semuanya tidak pernah terjadi. Sepertinya kepalaku kosong, hanya berisi pikiran-pikiran bahagia. Sepertinya setiap sudut dari sel otakku sudah bisa melupakan masalah yang terjadi beberapa minggu belakangan ini. Sepertinya, tidak, yang ini aku yakin, kaca tebal tak terlihat itu sudah menghilang dan kini aku bisa melihat mata laki-laki itu lebih dalam dan lebih jauh dari sebelumnya. Matanya lebih indah dilihat tanpa masalah yang kupendam… dia tersenyum.
“Hai, Airin. Namaku, Mario…”
Tawaku seketika terhenti ketika dia menyebut namaku sementara seingatku aku tidak pernah memberitahukannya.
Aku masih tidak mengerti sampai saat ini, apa yang membuat mereka berdua mempertahankan pernikahan mereka sementara mereka selalu bertengkar setiap hari. Apa itu karena aku? Jika memang alasannya demikian, kurasa itu adalah alasan yang bodoh. Aku sudah mulai tidak memedulikan mereka lagi.
Oh ya… kau bisa sebut aku kurang ajar atau tidak menghormati orang tua, tapi seperti itulah adanya sekarang. Ada atau tidak ada aku diantara mereka toh mereka tetap bertengkar juga. Ada atau tidak ada mereka bersamaku, toh aku tetap tidak diperhatikan juga.
Aku baru saja turun dari sepeda motor yang ku gas penuh dari rumah menuju sebuah pantai yang banyak dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke pulau kecil yang kadang terlupakan ini. Aku melangkah ke arah barat daya, ke arah susunan batu pemecah ombak yang dikelilingi oleh pasir-pasir putih. Melepas alas kakiku dan merasakan hangatnya pasir pantai yang membelai lembut telapak kakiku. Ingin sekali aku mengubur kakiku disana, sekarang juga. Kalau bisa sekujur tubuhku sekalian. Kehangatan itu kurasa bisa menggantikan dingin dan bekunya suasana rumah selama lima tahun terakhir ini.
Aku menghembuskan napas berkali-kali. Menarik napas dalam berkali-kali. Mencoba menenangkan diriku dengan cara yang diberitahukan seorang penyiar radio dalam sebuah acara kemarin siang. Aku mencoba menepikan semua masalahku ke sudut otak yang lain, menggabungkannya ke sebuah titik dan lalu memaksa setiap selnya untuk melupakan apa yang telah terjadi dan mengembalikan kenangan-kenangan yang kemungkinan bisa membuat aku tertawa.
Tapi… ah… aku tidak punya banyak kenangan indah. Umurku sudah dua puluh dan aku belum pernah merasakan pengalaman yang bisa ku kenang dengan indah disaat-saat seperti ini. Aku mengerucutkan bibir dan melanjutkan perjalanan ke ujung barat daya pantai itu dengan sepasang alas kaki di tangan kiriku.
Hari masih sangat pagi… Aku meninggalkan rumah sekitar pukul enam dan sekarang masih dingin dan agak berkabut. Debur ombak menemaniku berjalan hampir sendirian di pantai yang biasanya ramai ini. Memanjakan telingaku dengan lembut nyanyiannya ketika menyentuh bibir pantai dan bertemu pasir tempatku menapak. Aku menatap langit yang masih agak gelap di sebelah barat, namun berpadu cahaya khas matahari terbit di sebelah timur. Awan mulai membentuk formasi abstrak khas yang sangat kusuka.
“Lapar…”Aku mengelus perutku. Seharusnya memang ada penjual makanan di dekat parkiran pantai itu tapi aku melewatkannya begitu saja tadi karena pikiranku yang sedang rumit. Tanpa kusadari aku sudah tiba di ujung sebelah barat daya pantai itu. Ada banyak batu-batuan yang sengaja dibuat dan disusun untuk sebagai pemecah ombak disana. Aku duduk di salah satu batu tak jauh dari bibir pantai. Air dingin sesekali mengenai ujung hidungku yang membuatku semakin menggigil.
Aku menarik napas dalam lagi. Berusaha sebisa mungkin berbicara dengan Tuhan dari dalam hatiku. Memohon padanya agar hari ini, sehari saja, aku bisa merasa bahagia. Agar hari ini, sehari saja, aku bisa melepaskan segala beban di pundak, hati dan otakku dan tersenyum. Agar hari ini, aku bisa melupakan semuanya… tidak hanya hari ini saja, tetapi mulai hari ini dan seterusnya.
“Hai…”
Hatiku mencelos. Hampir saja aku berteriak karena terkejut mendengar suara itu masuk melalui telinga kananku. Aku merasakan kehadiran seseorang di sampingku, duduk persis di atas batu di sebelah tempatku duduk. Suara laki-laki. Tubuhku seketika mengejang, ketakutan. Aku sangat tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini: laki-laki dan kejutan. Suara ombak benar-benar menenggelamkan suara langkah kakinya. Aku berusaha untuk tenang dan mengatur kecepatan detak jantungku.
“Mengagetkanmu, eh?” dia bicara dalam bahasa Korea. Aku mengerti sekali. Aku pernah belajar bahasa Korea dan mendapatkan sertifikat. Anehnya, ketika mendengarnya bicara perasaan tegang yang tadi menyerbu itu seketika menghilang. Detak jantungku mulai normal dan aku mulai rileks sekarang.
Kuberanikan diriku untuk menoleh ke kanan, dan disanalah dia duduk, tiga puluh sentimeter dari wajahku. Seorang laki-laki berkulit putih, sangat putih tapi tidak pucat, berambut hitam legam lurus disisir klimis dan dibelah dibagian pinggir, tatapannya tajam dari bola matanya yang sehitam intan, berhidung mancung dan kokoh diatas bibirnya yang tipis kemerahan.
Dia tersenyum… padaku, orang yang tidak dia kenal sama sekali. Senyumnya benar-benar tidak dibuat-buat. Aku bisa membedakannya.
Aku mulai bertanya-tanya, kenapa dia tiba-tiba datang dan menyapaku?
Aku meyakinkan diriku bahwa dia bukan hantu atau semacamnya karena aku tahu betul, penduduk lokal pulau ini masih sangat percaya mitos dan tahayul. Ku gerakkan kakiku dengan sengaja menyentuh ujung sepatunya dengan harapan dia tidak akan merasakan sentuhan itu…
Sepatu… kenapa dia menggunakan sepatu diatas pasir? Bukankah itu aneh?
Otakku mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting sampai-sampai aku lupa aku masih menatapnya sekarang. Matanya… indah sekali… Rasanya seperti menatap sebuah bintang paling terang yang bisa kau lihat di malam hari, seperti melihat keindahan Venus di kala fajar, atau menatap bulan di posisi terdekatnya dengan bumi delapan belas tahun sekali.
“Kau sendiri?” tanya laki-laki itu lagi. Saat itulah aku baru memalingkan pandanganku kembali ke atas batuan yang basah oleh air yang dibawa ombak.
“Bagaimana kau tahu aku berbicara berbahasa Korea?” tanyaku spontan. Separo penasaran separo tidak peduli. Entah bagaimana caranya aku masih ingat wajahnya ketika menatap batu-batu yang ada di depan kakiku itu.
“Kau tidak sadar?” tanyanya merasa aneh.
Aku menoleh, “Hah?” aku tidak mengerti juga.
“Ketika kau datang, memarkirkan sepeda motormu, kau mengumpat dalam bahasa Korea,” jelasnya.
Wajahku memerah seketika. Entah aku ingat atau tidak apa yang aku ucapkan beberapa menit yang lalu. Aku memang suka bicara sendiri ketika sedang berkendara. Entah kenapa itu membuatku merasa lebih baik.
“Benarkah?” aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Dia mengangguk sambil tersenyum simpul. Sesaat pikiranku mulai teralih oleh wajahnya yang memukau itu. Lalu sedetik kemudian aku tersadar oleh ucapannya tadi. “Jadi sejak tadi kau mengikutiku, eh?” nada bicaraku agak tinggi dan menggeser posisi dudukku agak menjauh.
“Wow, tidak, bukan begitu! Aku hanya sedang berlari pagi dari hotel dan ketika mendengar kau bicara, aku, yah… terpikir untuk berjalan-jalan ke tempat ini juga,”
“Alasanmu tidak masuk akal! Kau pasti mengikutiku!” aku berteriak dan sekarang berdiri menjauh darinya.
“Hey, hey, tenang… aku tidak bermaksud… sungguh. Kau tidak percaya? Apakah wajahku terlihat seperti penjahat?” dia menunjuk wajahnya sendiri. Kentara sekali dia takut aku tiba-tiba marah dan pergi dari tempat itu. Entah kenapa aku merasa seperti itu.
“Tidak… kau mirip Wonbin… atau Kangta…? Ah… Kau juga sedikit mirip Choi Siwon…” aku meracau lalu duduk lagi.
Entah wajahku sudah semerah apa aku tidak tahu tetapi aku bisa merasakannya memanas.
Laki-laki itu tertawa sambil menutupi mulutnya dengan kepalan tangan kangannya. Aku melirik kearahnya dan memerhatikan ekspresi wajahnya saat itu. Dia terlihat benar-benar mengagumkan dengan tawanya.
“Kenapa tertawa?” aku berusaha tetap bicara dengan nada marah meskipun aku yakin sebenarnya aku sudah gagal.
“Kau juga menyanyikan sebuah lagu tadi. Fiction dari Beast kalau aku tidak salah dengar, eh?”
Mataku melotot, tercengang. Aku mulai merinding. Laki-laki ini… Wajahnya memang tampan, tapi dengan pendengaran seperti itu… Maksudku, aku bernyanyi tanpa ada niatan untuk didengar oleh siapapun. Aku biasanya bernyanyi untuk diriku sendiri… Bersenandung… Kenapa dia bisa mendengarnya? Bagaimana bisa dia mendengarnya?
“Apakah aku bernyanyi sekeras itu? Kau membuatku takut… Sungguh!” ucapku. Diam, aku masih menatap matanya yang juga menatap mataku. Dia sepertinya bisa membaca pikiranku atau apa, sedetik setelah dia menyelami mataku, ekspresinya berubah.
“Kau sedang ada masalah, eh?”
Hatikuku mencelos. Lagi. Sesegera mungkin aku mengalihkan pandanganku dan mencoba tenggelam dalam birunya samudera di depanku. Membatin. Apakah adegan saling tatap tadi membuat dia bisa membaca semua pikiranku?
“Kau ini penyihir atau apa, sih? Aku selalu takut dengan orang yang bisa membaca pikiran orang lain!” aku berkata jujur dan berteriak. “Rasanya seperti tidak punya privasi!”
Dia tertawa. TERTAWA!
Astaga… pria ini bukan manusia kurasa. Aku bahkan tidak bisa menangkap bagian yang lucu dari kalimat-kalimatku sebelumnya. Tetapi… tawa laki-laki itu, entah kenapa aku merasa sangat senang mendengarnya. Entah kenapa aku sangat senang melihatnya.
“Kau tidak pernah dengar?” dia bertanya.
“Apa?”
“Masalah yang sedang dihadapi seseorang akan sangat terlihat jelas di matanya. Ketika mereka melihat, mereka tidak benar-benar memerhatikan apa yang mereka lihat. Ketika mereka menatap, mereka tidak benar-benar menghiraukan apa yang mereka tatap.”
Aku hanya diam dan–ya–aku sedang menatapnya. Tapi… apakah aku memikirkan hal lain saat ini? Apakah dia tahu aku punya masalah yang sumpah demi Tuhan aku tidak ingin ceritakan pada siapapun bahkan teman terdekatku sekalipun jika memang aku punya?
“Ketika kau menatapku tadi, kau tidak benar-benar memerhatikan mataku… seperti ada pembatas kaca tak terlihat tetapi sangat tebal diantara mataku dan matamu. Dan di dalam kaca itu ada banyak sekali kegundahan yang sekarang sedang menghantui pikiranmu… Benar ‘kan?”
“Aku mulai takut. Sungguh…” kataku jujur, masih menatapnya.
“Kalau begitu, katakan, apa yang harus aku lakukan agar kau tidak takut?”
“Hah?” pertanyaan itu benar-benar aneh.
Dia tertawa lagi. Oh Tuhan… tawa itu… Aku benar-benar seperti sedang berada dalam satu scene di sebuah drama Korea sekarang. Aku mencoba mengembalikan kesadaranku. Mencoba sekali lagi membuang dan menyisihkan semua pikiran tentang masalah-masalahku ke sudut otak yang lain untuk bisa benar-benar memerhatikannya. Entah kenapa ucapannya tentang kaca tebal di depan mataku itu sangat mengganggu pikiranku. Rasanya seperti aku kehilangan ketulusan dalam diriku. Aku menatapnya lagi… Wajah itu… Perpaduan antara Wonbin dan Choi Siwon, sudah jelas.
“Kau mencoba memerhatikanku tanpa memikirkan masalahmu, eh?”
Sebuah tombak sudah menusuk punggungku sekarang. Dia benar-benar mengerikan!
“Aku… errr… aku benar-benar takut karena kau sepertinya tahu apa yang sedang aku pikirkan… Aku yakin kau pasti keturunan seorang penyihir di Korea!”
Dia tertawa lagi. “Hmmm kupikir kami tidak mengenal penyihir di Korea?”
“Tapi penyihir ada di semua negara, bukan?”
“Aku tidak tahu…” jawabnya tegas sambil mengangkat bahu dan mencoba menirukan gaya imut khas member boyband Korea.
“Katakan, bagaimana kau bisa tahu apa yang sedang aku rasakan!”
“Aku hanya menebak,”
“Bohong!”
“Sungguh! Dan sekarang kau mulai merasa takut, kan?”
“BAGAIMANA KAU TAHU?!”
Dia tertawa lagi. Oh aku mulai menyukai suara tawanya.
“Kau tadi bilang begitu.”
Wajahku seakan terbakar. Oh tidak, kali ini benar-benar sedang terbakar. Kakiku tiba-tiba saja gemetaran dan angin yang tadinya menenangkan menjadi sedikit terlalu dingin dan membuatku merinding berlebihan. Aku menunduk dan menahan tawa.
“Kalau kau ingin tertawa, sebaiknya dilepaskan saja… tidak baik menahan tawa. Kau tahu, jika kau menahan tertawa, pusar mu akan bertambah satu,”
“Bohong!” Aku berteriak lalu menutup mulutku sendiri dengan kedua tangan. Membayangkan bagaimana bentuk tubuhku dengan dua pusar. “KAU BOHONG!” jelas sekali ketakutan di wajahku dan dia melihatnya kemudian tertawa.
Dan… untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, aku ikut tertawa… lepas… sepertinya semuanya tidak pernah terjadi. Sepertinya kepalaku kosong, hanya berisi pikiran-pikiran bahagia. Sepertinya setiap sudut dari sel otakku sudah bisa melupakan masalah yang terjadi beberapa minggu belakangan ini. Sepertinya, tidak, yang ini aku yakin, kaca tebal tak terlihat itu sudah menghilang dan kini aku bisa melihat mata laki-laki itu lebih dalam dan lebih jauh dari sebelumnya. Matanya lebih indah dilihat tanpa masalah yang kupendam… dia tersenyum.
“Hai, Airin. Namaku, Mario…”
Tawaku seketika terhenti ketika dia menyebut namaku sementara seingatku aku tidak pernah memberitahukannya.
Spoiler for INDEX PART 'accidentally, you.':
Diubah oleh salmansharkan 25-01-2018 10:23
Heidymahrani dan 5 lainnya memberi reputasi
6
18.7K
Kutip
62
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.8KThread•52.9KAnggota
Tampilkan semua post
TS
salmansharkan
#1
Quote:
‘there is no friendship, after all. We’re all just friend in a same ship’
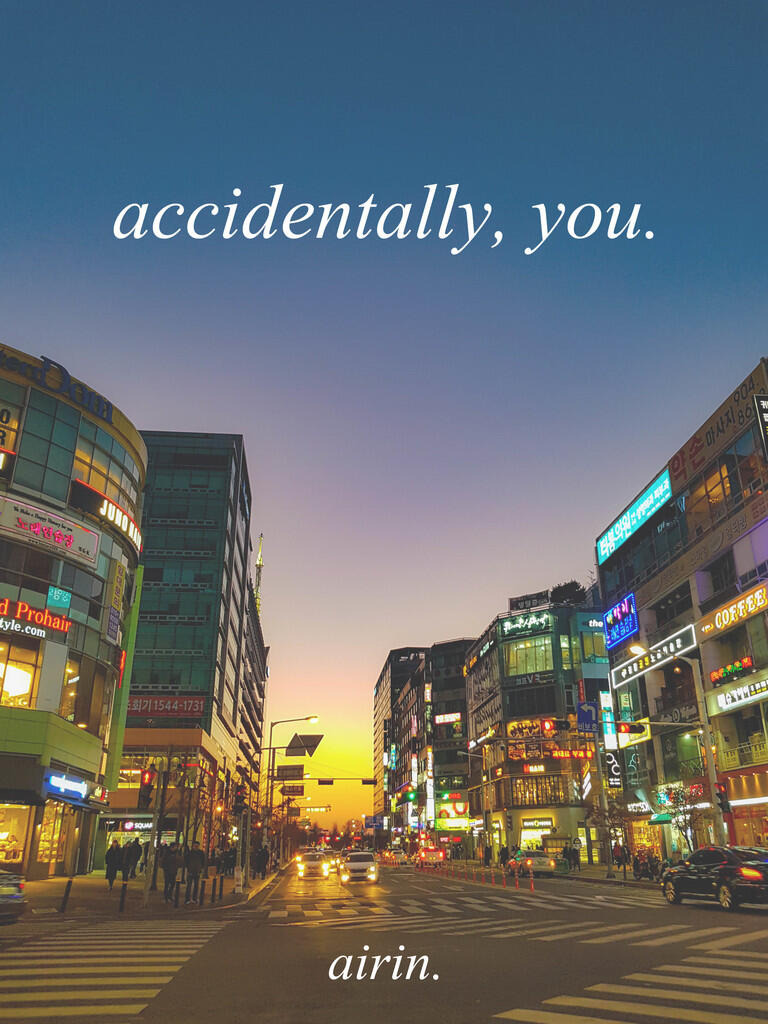
Quote:
Pantai mulai ramai tapi aku tidak peduli. Aku menyukai suasana di pantai ini meskipun banyak sekali wisatawan yang bisa saja merusak kenyamananku dan mungkin juga memperburuk moodku. Aku masih bertahan di atas sebuah batu di sebelah barat daya pantai itu. Diatas pemecah ombak. Duduk diam, terheran-heran dengan kemampuan luar biasa yang sekaligus agak mengerikan yang dimiliki laki-laki bernama Mario itu.
Kepalaku jadi agak pusing. Sekarang aku tidak lagi memikirkan masalah-masalah yang kutinggalkan di rumah, tetapi pusing memikirkan bagaimana laki-laki yang baru saja ku kenal–tidak, aku bahkan tidak mengenalnya–yang baru saja aku temui beberapa menit yang lalu bisa tahu namaku.
Aku memutar otak. Mencoba merangkai kembali kejadian kira-kira satu jam yang lalu. Mulai dari pertengkaran Ibu dan Ayahku–oh sial, aku harus memikirkan ini lagi–yang menyebalkan, kekesalanku kemudian membanting pintu kamar, meraih kunci sepeda motor, menyalakan mesin, menarik gas penuh, tiba di pantai ini, memarkir motorku, berjalan ke pemecah ombak, duduk, dan laki-laki itu datang.
Kemudian dia mengejutkanku dengan menyapaku, berkata bahwa aku ada masalah, bicara sesuatu tentang kaca tebal tak terlihat yang penuh dengan pikiran rumitku, sampai barusan dia menyebut namaku. Aku tidak ingat aku pernah memperkenalkan diri, saling memperkenalkan diri, atau secara tidak sengaja aku menyebut namaku karena tadi aku sempat berpikir laki-laki itu cukup tampan untuk menjadi kekasihku.
Lalu bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia tahu namaku?
“Kau—oh sungguh kau benar-benar–”
Ucapanku terhenti disitu ketika dia mengeluarkan sebuah kartu kecil bewarna biru muda yang sangat aku kenal. Ada fotoku di kartu itu yang aku ingat diambil ketika umurku tujuh belas tahun. Tiga tahun yang lalu.
“Bagaimana benda itu ada padamu!”aku berteriak.
Mario tertawa lagi. Dan kali ini rasanya aku ingin sekali mencekik leher yang kokoh itu. Entah apakah aku bisa melakukannya sebelum meremukkan tanganku. Dia terlihat sangat kuat, laki-laki bernama Mario ini. T-shirt putih tipis yang dipakainya membuat badannya terlihat sangat besar dan kekar. Otot bisepnya jelas sekali. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di udara seperti ini dengan pakaian tipis seperti itu. Pikiranku mulai melantur dan lupa alasan dia datang ke pantai ini untuk berolahraga.
Lama memerhatikan penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki Mario, aku segera merebut KTP ku yang ada ditangannya. “Bagaimana ini bisa ada padamu, hah?!”
Mario lalu mengeluarkan sebuah dompet hitam khas laki-laki yang hampir tidak bisa tertutup rapat dari saku belakang jins hitam pendek yang digunakannya. Mataku mengawasi setiap gerakan tangannya dan tertuju pada kakinya yang jenjang dan tidak lebih besar dari kakiku. Orang ini benar-benar memiliki tubuh yang sempurna meskipun dengan kaki sekecil itu, dia tetap saja terlihat keren.
“Kau menjatuhkannya di tempat parkir,” kata Mario.
Aku merasa menjadi orang yang paling bodoh di dunia hari ini. Bagaimana mungkin aku bisa menjatuhkan dompetku di tempat parkir? Seingatku aku telah memeriksanya sebelum aku turun dari sepeda motor dan dompet itu ada di kantong belakang celana jinsku. Ah… ya, aku lupa ingatanku memang buruk. Kurasa memang aku mungkin menjatuhkannya tadi.
“Menjatuhkannya? Aku tidak tahu. Oh Tuhan,” aku sedikit bingung.
“Kau sedang banyak pikiran. Tentu saja tidak ingat hal kecil seperti itu.”
“Kehilangan dompet itu berarti hal yang besar untukku, dan jangan seenaknya mengatakan bahwa aku sedang banyak pikiran!” aku mengambil dompet itu dengan paksa dari tangannya.
“Boleh aku tahu kenapa?”
“Kenapa apa?"
“Kenapa benda kecil itu berarti besar untukmu?”
“Kenapa aku harus memberitahumu?”
“Kurasa aku pantas karena aku telah mengembalikan dompetmu? Bisa saja kan dompet itu diambil oleh orang lain kemudian membawanya kabur?”
Dia benar juga. Dia berjasa padaku hari ini. Dua kali, seingatku. Selain dia bisa membuatku melupakan sejenak masalah-masalahku, dia mengembalikan dompetku yang terjatuh. Ah, tiga kali. Dia membuatku tertawa. Sial. Kenapa harus orang misterius yang agak menyebalkan ini sih?
“Sebaiknya kau memeriksa isinya dulu, aku bisa saja mengambil selembar uangmu atau kartu kredit dan ATM mu?”
“Kau benar. Jangan kemana-mana sampai aku selesai mengecek semuanya! Kalau ada yang kurang maka kau yang harus bertanggung jawab!”
Mario tertawa lagi.
“Kenapa tertawa?! Sejak tadi kau hanya bisa tertawa!”
“Kau lucu, Airin.”
“Oh ya, terima kasih Mario. Dan hey, bahasa Korea mu sangat bagus omong-omong!” Aku mengeluarkan satu per satu isi dompetku mulai dari kartu mahasiswa, kartu ATM, beberapa lembar uang dan foto. Aku menghela napas lega. Tidak ada yang hilang. Yang paling aku khawatirkan adalah beberapa lembar kertas yang terlipat berbentuk segi empat yang memang sengaja kuletakkan di dalam dompet. Semuanya lengkap.
“Aku pernah tinggal di Korea beberapa tahun,” jawab Mario. “Tidak ada yang hilang?”
“Tidak ada. Terima kasih. Hey! Kau pernah tinggal di Korea?” aku mulai bersemangat dengan topik ini. Entah kenapa setiap kali ada hal-hal yang berhubungan dengan negara Boyband itu aku selalu bisa bersemangat.
“Ya… Aku berencana untuk kembali ke sana dalam waktu dekat ini,”
“Wah… aku sangat ingin ke Korea. Sudah sejak kelas satu SMA.”
“Berapa usiamu sekarang?” tanya Mario.
“Kau sudah tahu. Aku yakin, kau kan bisa membaca pikiran orang!” sindirku dengan tatapan mencela.
Dia tertawa lagi. Entahlah. Setiap kali dia tertawa aku merasa bebanku semakin ringan.
“Aku tidak bisa membaca pikiran siapapun, Airin ssi. Tapi kau benar, aku tahu usiamu dari KTP-mu tadi. Aku sempat membaca dan melihatnya. Foto di KTP itu... lucu sekali,”
“Aku tidak pernah menyukainya. Semua foto di kartu yang ada di dalam dompet ini tidak pernah ada yang bagus. Entahlah, aku tidak begitu suka di foto. Hey, ceritakan tentang Korea. Bagaimana hidup di sana? Pasti kau betah sekali, ya? Maksudku, bagaimana mungkin kau akan bosan hidup di negara yang sama dengan para idolamu!”
“Haha… aku tidak begitu menyukai artis-artis Korea.”
“Kenapa?” tanyaku sedikit kecewa.
“Entahlah… Kau suka?” Mario tiba-tiba tertawa lagi. “Pertanyaan bodoh, eh? Kau bahkan tadi bilang aku mirip Kangta, Wonbin dan Siwon,”
“Memang benar. Kalau kau tidak suka, kenapa kau begitu yakin ketika menyebut nama-nama itu?”
“Oh ayolah… siapa yang tidak mengenal Kangta dan Wonbin? Tidak suka bukan berarti tidak tahu, bukan?”
Hening sejenak. Aku dan Mario saling tatap dan kemudian kami tersenyum bersamaan.
“Kita bahkan menggunakan bahasa Korea sejak tadi,” aku bicara kini dalam bahasa Indonesia. “Kau berasal dari Korea, eh? Maksudku… wajahmu seperti bukan orang Indonesia,”
“Ayahku Indonesia. Dia lahir di Korea karena ayahnya adalah orang Korea. Kurasa kakekku menurunkan warna kulit, bentuk mata dan semua itu padaku,”
“Kau tampan.” ucapan ini meluncur setelah sejak tadi kutahan-tahan. Semoga spontanitas mengerikan ini tidak membuatnya ketakutan.
“Hah?” Mario mengernyit lalu tertawa. “Terima kasih,” dia membungkuk sedikit.
“Kau seharusnya jadi artis. Bukankah orang-orang berwajah oriental dan blasteran sangat laku di negara ini, eh?”
Mario tersenyum kecil. “Kalau saja menjadi artis itu mudah, sudah ku lakukan sejak lama. Aku sudah mencari pekerjaan yang layak sejak empat tahun yang lalu dan tidak pernah mendapatkan satupun. Sedikit kecewa juga. Aku berencana kembali ke Korea dalam waktu dekat–umm yah–kalau aku sudah punya cukup uang. Aku akan mencari kakekku dan memintanya untuk–yah–setidaknya memberikan pekerjaan padaku, eh?”
“Kau pernah kuliah?”
“Tidak… tapi aku punya kemampuan yang orang lain tidak punya. Aku bisa memasak dan kurasa aku bisa jadi koki yang baik,”
“Kalau begitu kau harusnya mengikuti acara pencarian bakat khusus memasak itu. Dengan bakat memasak dan wajah tampan seperti kau, pasti akan sangat bermanfaat untuk acara TV dan rating stasiun TV itu. Kau harus mencobanya…”
Mario tertawa lagi.
“Andai saja mencari pekerjaan itu mudah. Aku akan sangat senang jika suatu hari nanti aku bisa menjadi seorang koki di sebuah restoran,”
“Kau pasti bisa!” aku menepuk punggungnya. Spontan. Lalu kutarik lagi tanganku dengan wajah memerah. Meskipun aku merasa aneh pada apa yang dikatakan Mario tadi, maksudku, bukankah terlalu cepat untuk memberitahu siapa dirimu pada orang lain yang baru saja kau kenal?
Tapi ya sudahlah… aku tidak merasa keberatan. Beberapa cerita itu justru membuatku merasa sangat mengenal Mario. Pertemuan singkat itu terasa lebih lama dari yang seharusnya dan menjelaskan banyak hal juga. Terlepas dari Mario yang sepertinya sangat misterius karena tahu banyak tentangku dan masalahku, kurasa dia memang orang yang baik.
Hening sejenak. Aku mencoba menyusun kembali kalimat-kalimat yang tidak terlalu penting tapi sepertinya akan bisa mencairkan suasana yang kemudian jadi canggung dan rikuh itu. Mataku memandang ke samudera luas di depanku sementara matanya, aku menoleh ingin tahu apa yang dia lihat, ternyata sedang melihat langit.
Dia bilang, masalah seseorang akan terlihat dari matanya… aku tidak begitu mengerti maksudnya itu, tapi ketika aku mencobanya, melihat ke dalam mata Mario… aku baru mengerti. Ya… laki-laki itu juga punya masalah…
“Kau benar tentang kaca tebal tak terlihat itu, omong-omong,” kataku berusaha memancingnya untuk bicara.
“Eh?”
“Aku melihatnya juga… kau juga sedang ada masalah, bukan? Sama sepertiku… tapi…” aku berpikir sebentar berusaha mengelaborasi apa yang ingin aku katakan seperti layaknya seorang peramal. “…masalahmu sepertinya lebih ringan daripada masalahku. Aku melihat kaca tebal itu tetapi tidak lebih tebal dari milikku. Persis ketika kau menatap langit, pantulan biru langit dan putih awan itu terlihat jelas disana,”
Aku tersenyum sambil sedikit membusungkan dada. Merasa puas bisa membalas kata-katanya tadi. Kurasa tebakanku tidak salah karena ekspresi wajahnya tiba-tiba saja berubah antara terkejut dan sedih.
Tapi kemudian dia malah tertawa. LAGI!
“Kau sudah mulai bisa membaca pikiran orang sekarang, eh? Tapi ya, aku memang sedang ada masalah. Kurasa kau sudah tahu?”
“Gila. Aku hanya menebak saja. Aku bukan penyihir seperti kau!”
“Aku juga bukan penyihir!” dia tiba-tiba berteriak.
“Lalu kenapa kau bisa tahu aku sedang ada masalah?!”
“Karena aku melihatnya dari matamu! Dan kau, darimana kau tahu aku punya masalah?!”
“Karena aku melihatnya dari matamu! Katakan, darimana kau tahu namaku? Hah?!”
“Sekedar mengingatkanmu, aku yang mengembalikan dompet dan KTP mu, kalau kau lupa!” dia berteriak lagi sementara aku tidak tahu harus membalas apa. Aku terengah-engah seperti habis berlari seratus meter dikali lima belas. Napasku cepat sekali.
Lalu…
Kami tertawa.
Tertawa. Lepas sekali. Entah sejak kapan tapi aku yakin, ini adalah tertawa paling bahagia yang pernah aku lakukan dan rasakan sepanjang aku bisa tertawa. Aku merasa tidak ada beban apapun. Lagi dan lagi. Aku tertawa bersama dengan orang asing yang baru kukenal tadi. Aku sudah gila! Tapi kalau dengan gila aku bisa merasakan ketenangan seperti ini, aku rela jadi gila sepanjang sisa hidupku.
“Kau benar-benar aneh, Mario.” aku masih menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan tambahan partikel Korea. Aku bingung harus memanggilnya apa. Lebih baik begini saja, aku nyaman dengan panggilan itu dan kurasa dia juga. “…atau hanya aku?” aku tersenyum.
“Maksudnya?”
“Aku merasa sangat nyaman bicara denganmu, entah kenapa, sejak awal kau menghampiriku tadi, aku merasa kau adalah orang yang bisa mendengar semua ceritaku. Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini. Kurasa itulah yang membuat kaca tak terlihat itu semakin tebal karena aku tidak pernah berani menceritakannya pada siapapun. Benar, kan?” ucapanku sepertinya mengisyaratkan bahwa aku percaya pada ucapan Mario tadi dan sedang ada kaca tebal di depan mataku sekarang.
“Kurasa iya… dan kau juga bisa melihat kaca itu di mataku sekarang? Kau bisa membandingkannya dengan milikmu?”
“Punyaku jauh lebih tebal. Jujur saja, kau terlihat sangat bisa mengatasi semuanya sendirian,”
“Aku punya teman, Airin. Semua orang punya teman untuk berbagi. Yah, walaupun temanmu… ahaha lupakan saja. Kau?”
“Aku tidak, sayangnya, kau tahu? Aku tidak pernah percaya pada persahabatan. Kau mengerti kan maksudku? Ketika para wanita berkumpul dan saling menceritakan masalah mereka satu sama lain? Mereka menganggap diri mereka sahabat, padahal dibelakang punggung sahabatnya, satu diantara mereka menusuk yang lain,”
“Cerita-cerita khas film televisi, eh?”
“Yeah, yang seperti itu. Aku pernah mendengar quote dari temanku, ‘there is no friendship, after all. We’re all just friend in a same ship’ dan kau tahu? Aku adalah orang yang mudah percaya omongan orang lain,”
“Dan kau percaya pada quote itu?”
“Ya. Sangat percaya,”
“Kenapa kau begitu yakin?”
“Seseorang pernah menusukku dengan tombak beracun dan kemudian tertawa di atas kapal terbakar dimana aku terperangkap di dalamnya,”
Hening sejenak. Senyum Mario menjadi agak ragu-ragu. Dia menatap ke langit kemudian menghembuskan napas perlahan. Aku bisa merasakan hangatnya napas itu meskipun aku ada di sampingnya. Angin membawa hawa panas Mario sehingga aku merasa sedikit hangat sekarang. Sedikit berlebihan tapi ya… begitulah kenyataannya.
“Lalu, coba katakan padaku apa yang kau lakukan jika kau sedang ada masalah?” Mario menoleh dan bertanya.
“Kabur.” jawabku pasti dengan senyuman kecil tak pasti.
“Hah?”
“Yeah, kabur dari rumah seperti pagi ini. Mengendarai motor dengan kecepatan tinggi ke sebuah tempat dimana aku bisa merasakan ketenangan. Merasakan hembusan angin yang menerbangkan rambutku. Aku selalu suka sensasinya. Merasakan bagaimana pikiranku tenang hanya dengan mendengar debur ombak di depan mataku. Dan, satu lagi, bernyanyi sendiri,”
Mario tersenyum. “Kau sudah bisa mengatasinya sekarang?”
“Sedikit. Hanya perlu satu langkah lagi,”
“Apa itu?”
“Aku biasanya menulis ceritaku, apapun masalah yang sedang aku alami disebuah kertas. Seseorang pernah memberitahuku, jika aku ingin melupakan masalahku, tuliskan semua yang ingin aku ungkapkan di selembar kertas, lalu selipkan di tempat yang mudah kulupakan.”
“Kau mengikuti saran itu?”
“Ya. Aku selalu mencoba untuk mengikutinya,”
“Lalu apakah berhasil? Maksudku, kau bisa melupakan masalahmu setelah itu?”
“Sedikit. Tapi pasti itu karena semua emosiku telah keluar lewat tulisan dan air mataku ketika aku menuliskannya, bukan? Ku dengar air mata juga bisa membuat kita lebih baik dan emosi kita jadi terkontrol,”
“Bisa jadi seperti itu. Kalau boleh aku tahu, tempat yang mudah terlupakan itu...?”
“Dompet.” jawabku tegas.
Mario tertawa lagi. “Dompet? Sudah jelas sekali ya? Maksudku, kau tadi bahkan tidak sadar dompetmu terjatuh. Itukah alasannya? Karena kau mudah lupa dompetmu sendiri?”
“Sepertinya begitu,” aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. “Sudah pasti begitu, ya? Benda kecil itu memang selalu terlupa. Kalau saja semalam aku tidak memasukkannya ke dalam kantong celana jins ini, aku pasti tidak akan membawanya pagi ini,” sekarang wajahku pastinya terlihat bodoh sekali di depan Mario.
“Bagaimana mungkin kau bisa melupakan masalahmu yang kau tulis di kertas yang terselip di dompetmu? Maksudku, ketika kau ingat pada dompetmu, kau pasti akan ingat bahwa ada sesuatu yang tertulis di dalam sana bukan?”
Aku terkejut. Dia benar juga. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Selama ini aku hanya percaya saja bahwa itu bisa membantuku. Memang membantu, walaupun hanya sedikit. Tapi masalah yang barusan Mario katakan itu, tidak pernah terpikirkan.
“Benar juga… Aku tidak pernah berpikir sampai kesana. Ah, temanku itu harus dibunuh,”
Mario tertawa lagi. Entah kenapa aku mulai curiga dia sangat hobi tertawa. Tapi tidak apa-apa, aku suka.
“Siapa yang memberitahukan kau cara seperti itu kalau aku boleh tahu?”
Kepalaku jadi agak pusing. Sekarang aku tidak lagi memikirkan masalah-masalah yang kutinggalkan di rumah, tetapi pusing memikirkan bagaimana laki-laki yang baru saja ku kenal–tidak, aku bahkan tidak mengenalnya–yang baru saja aku temui beberapa menit yang lalu bisa tahu namaku.
Aku memutar otak. Mencoba merangkai kembali kejadian kira-kira satu jam yang lalu. Mulai dari pertengkaran Ibu dan Ayahku–oh sial, aku harus memikirkan ini lagi–yang menyebalkan, kekesalanku kemudian membanting pintu kamar, meraih kunci sepeda motor, menyalakan mesin, menarik gas penuh, tiba di pantai ini, memarkir motorku, berjalan ke pemecah ombak, duduk, dan laki-laki itu datang.
Kemudian dia mengejutkanku dengan menyapaku, berkata bahwa aku ada masalah, bicara sesuatu tentang kaca tebal tak terlihat yang penuh dengan pikiran rumitku, sampai barusan dia menyebut namaku. Aku tidak ingat aku pernah memperkenalkan diri, saling memperkenalkan diri, atau secara tidak sengaja aku menyebut namaku karena tadi aku sempat berpikir laki-laki itu cukup tampan untuk menjadi kekasihku.
Lalu bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia tahu namaku?
“Kau—oh sungguh kau benar-benar–”
Ucapanku terhenti disitu ketika dia mengeluarkan sebuah kartu kecil bewarna biru muda yang sangat aku kenal. Ada fotoku di kartu itu yang aku ingat diambil ketika umurku tujuh belas tahun. Tiga tahun yang lalu.
“Bagaimana benda itu ada padamu!”aku berteriak.
Mario tertawa lagi. Dan kali ini rasanya aku ingin sekali mencekik leher yang kokoh itu. Entah apakah aku bisa melakukannya sebelum meremukkan tanganku. Dia terlihat sangat kuat, laki-laki bernama Mario ini. T-shirt putih tipis yang dipakainya membuat badannya terlihat sangat besar dan kekar. Otot bisepnya jelas sekali. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di udara seperti ini dengan pakaian tipis seperti itu. Pikiranku mulai melantur dan lupa alasan dia datang ke pantai ini untuk berolahraga.
Lama memerhatikan penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki Mario, aku segera merebut KTP ku yang ada ditangannya. “Bagaimana ini bisa ada padamu, hah?!”
Mario lalu mengeluarkan sebuah dompet hitam khas laki-laki yang hampir tidak bisa tertutup rapat dari saku belakang jins hitam pendek yang digunakannya. Mataku mengawasi setiap gerakan tangannya dan tertuju pada kakinya yang jenjang dan tidak lebih besar dari kakiku. Orang ini benar-benar memiliki tubuh yang sempurna meskipun dengan kaki sekecil itu, dia tetap saja terlihat keren.
“Kau menjatuhkannya di tempat parkir,” kata Mario.
Aku merasa menjadi orang yang paling bodoh di dunia hari ini. Bagaimana mungkin aku bisa menjatuhkan dompetku di tempat parkir? Seingatku aku telah memeriksanya sebelum aku turun dari sepeda motor dan dompet itu ada di kantong belakang celana jinsku. Ah… ya, aku lupa ingatanku memang buruk. Kurasa memang aku mungkin menjatuhkannya tadi.
“Menjatuhkannya? Aku tidak tahu. Oh Tuhan,” aku sedikit bingung.
“Kau sedang banyak pikiran. Tentu saja tidak ingat hal kecil seperti itu.”
“Kehilangan dompet itu berarti hal yang besar untukku, dan jangan seenaknya mengatakan bahwa aku sedang banyak pikiran!” aku mengambil dompet itu dengan paksa dari tangannya.
“Boleh aku tahu kenapa?”
“Kenapa apa?"
“Kenapa benda kecil itu berarti besar untukmu?”
“Kenapa aku harus memberitahumu?”
“Kurasa aku pantas karena aku telah mengembalikan dompetmu? Bisa saja kan dompet itu diambil oleh orang lain kemudian membawanya kabur?”
Dia benar juga. Dia berjasa padaku hari ini. Dua kali, seingatku. Selain dia bisa membuatku melupakan sejenak masalah-masalahku, dia mengembalikan dompetku yang terjatuh. Ah, tiga kali. Dia membuatku tertawa. Sial. Kenapa harus orang misterius yang agak menyebalkan ini sih?
“Sebaiknya kau memeriksa isinya dulu, aku bisa saja mengambil selembar uangmu atau kartu kredit dan ATM mu?”
“Kau benar. Jangan kemana-mana sampai aku selesai mengecek semuanya! Kalau ada yang kurang maka kau yang harus bertanggung jawab!”
Mario tertawa lagi.
“Kenapa tertawa?! Sejak tadi kau hanya bisa tertawa!”
“Kau lucu, Airin.”
“Oh ya, terima kasih Mario. Dan hey, bahasa Korea mu sangat bagus omong-omong!” Aku mengeluarkan satu per satu isi dompetku mulai dari kartu mahasiswa, kartu ATM, beberapa lembar uang dan foto. Aku menghela napas lega. Tidak ada yang hilang. Yang paling aku khawatirkan adalah beberapa lembar kertas yang terlipat berbentuk segi empat yang memang sengaja kuletakkan di dalam dompet. Semuanya lengkap.
“Aku pernah tinggal di Korea beberapa tahun,” jawab Mario. “Tidak ada yang hilang?”
“Tidak ada. Terima kasih. Hey! Kau pernah tinggal di Korea?” aku mulai bersemangat dengan topik ini. Entah kenapa setiap kali ada hal-hal yang berhubungan dengan negara Boyband itu aku selalu bisa bersemangat.
“Ya… Aku berencana untuk kembali ke sana dalam waktu dekat ini,”
“Wah… aku sangat ingin ke Korea. Sudah sejak kelas satu SMA.”
“Berapa usiamu sekarang?” tanya Mario.
“Kau sudah tahu. Aku yakin, kau kan bisa membaca pikiran orang!” sindirku dengan tatapan mencela.
Dia tertawa lagi. Entahlah. Setiap kali dia tertawa aku merasa bebanku semakin ringan.
“Aku tidak bisa membaca pikiran siapapun, Airin ssi. Tapi kau benar, aku tahu usiamu dari KTP-mu tadi. Aku sempat membaca dan melihatnya. Foto di KTP itu... lucu sekali,”
“Aku tidak pernah menyukainya. Semua foto di kartu yang ada di dalam dompet ini tidak pernah ada yang bagus. Entahlah, aku tidak begitu suka di foto. Hey, ceritakan tentang Korea. Bagaimana hidup di sana? Pasti kau betah sekali, ya? Maksudku, bagaimana mungkin kau akan bosan hidup di negara yang sama dengan para idolamu!”
“Haha… aku tidak begitu menyukai artis-artis Korea.”
“Kenapa?” tanyaku sedikit kecewa.
“Entahlah… Kau suka?” Mario tiba-tiba tertawa lagi. “Pertanyaan bodoh, eh? Kau bahkan tadi bilang aku mirip Kangta, Wonbin dan Siwon,”
“Memang benar. Kalau kau tidak suka, kenapa kau begitu yakin ketika menyebut nama-nama itu?”
“Oh ayolah… siapa yang tidak mengenal Kangta dan Wonbin? Tidak suka bukan berarti tidak tahu, bukan?”
Hening sejenak. Aku dan Mario saling tatap dan kemudian kami tersenyum bersamaan.
“Kita bahkan menggunakan bahasa Korea sejak tadi,” aku bicara kini dalam bahasa Indonesia. “Kau berasal dari Korea, eh? Maksudku… wajahmu seperti bukan orang Indonesia,”
“Ayahku Indonesia. Dia lahir di Korea karena ayahnya adalah orang Korea. Kurasa kakekku menurunkan warna kulit, bentuk mata dan semua itu padaku,”
“Kau tampan.” ucapan ini meluncur setelah sejak tadi kutahan-tahan. Semoga spontanitas mengerikan ini tidak membuatnya ketakutan.
“Hah?” Mario mengernyit lalu tertawa. “Terima kasih,” dia membungkuk sedikit.
“Kau seharusnya jadi artis. Bukankah orang-orang berwajah oriental dan blasteran sangat laku di negara ini, eh?”
Mario tersenyum kecil. “Kalau saja menjadi artis itu mudah, sudah ku lakukan sejak lama. Aku sudah mencari pekerjaan yang layak sejak empat tahun yang lalu dan tidak pernah mendapatkan satupun. Sedikit kecewa juga. Aku berencana kembali ke Korea dalam waktu dekat–umm yah–kalau aku sudah punya cukup uang. Aku akan mencari kakekku dan memintanya untuk–yah–setidaknya memberikan pekerjaan padaku, eh?”
“Kau pernah kuliah?”
“Tidak… tapi aku punya kemampuan yang orang lain tidak punya. Aku bisa memasak dan kurasa aku bisa jadi koki yang baik,”
“Kalau begitu kau harusnya mengikuti acara pencarian bakat khusus memasak itu. Dengan bakat memasak dan wajah tampan seperti kau, pasti akan sangat bermanfaat untuk acara TV dan rating stasiun TV itu. Kau harus mencobanya…”
Mario tertawa lagi.
“Andai saja mencari pekerjaan itu mudah. Aku akan sangat senang jika suatu hari nanti aku bisa menjadi seorang koki di sebuah restoran,”
“Kau pasti bisa!” aku menepuk punggungnya. Spontan. Lalu kutarik lagi tanganku dengan wajah memerah. Meskipun aku merasa aneh pada apa yang dikatakan Mario tadi, maksudku, bukankah terlalu cepat untuk memberitahu siapa dirimu pada orang lain yang baru saja kau kenal?
Tapi ya sudahlah… aku tidak merasa keberatan. Beberapa cerita itu justru membuatku merasa sangat mengenal Mario. Pertemuan singkat itu terasa lebih lama dari yang seharusnya dan menjelaskan banyak hal juga. Terlepas dari Mario yang sepertinya sangat misterius karena tahu banyak tentangku dan masalahku, kurasa dia memang orang yang baik.
Hening sejenak. Aku mencoba menyusun kembali kalimat-kalimat yang tidak terlalu penting tapi sepertinya akan bisa mencairkan suasana yang kemudian jadi canggung dan rikuh itu. Mataku memandang ke samudera luas di depanku sementara matanya, aku menoleh ingin tahu apa yang dia lihat, ternyata sedang melihat langit.
Dia bilang, masalah seseorang akan terlihat dari matanya… aku tidak begitu mengerti maksudnya itu, tapi ketika aku mencobanya, melihat ke dalam mata Mario… aku baru mengerti. Ya… laki-laki itu juga punya masalah…
“Kau benar tentang kaca tebal tak terlihat itu, omong-omong,” kataku berusaha memancingnya untuk bicara.
“Eh?”
“Aku melihatnya juga… kau juga sedang ada masalah, bukan? Sama sepertiku… tapi…” aku berpikir sebentar berusaha mengelaborasi apa yang ingin aku katakan seperti layaknya seorang peramal. “…masalahmu sepertinya lebih ringan daripada masalahku. Aku melihat kaca tebal itu tetapi tidak lebih tebal dari milikku. Persis ketika kau menatap langit, pantulan biru langit dan putih awan itu terlihat jelas disana,”
Aku tersenyum sambil sedikit membusungkan dada. Merasa puas bisa membalas kata-katanya tadi. Kurasa tebakanku tidak salah karena ekspresi wajahnya tiba-tiba saja berubah antara terkejut dan sedih.
Tapi kemudian dia malah tertawa. LAGI!
“Kau sudah mulai bisa membaca pikiran orang sekarang, eh? Tapi ya, aku memang sedang ada masalah. Kurasa kau sudah tahu?”
“Gila. Aku hanya menebak saja. Aku bukan penyihir seperti kau!”
“Aku juga bukan penyihir!” dia tiba-tiba berteriak.
“Lalu kenapa kau bisa tahu aku sedang ada masalah?!”
“Karena aku melihatnya dari matamu! Dan kau, darimana kau tahu aku punya masalah?!”
“Karena aku melihatnya dari matamu! Katakan, darimana kau tahu namaku? Hah?!”
“Sekedar mengingatkanmu, aku yang mengembalikan dompet dan KTP mu, kalau kau lupa!” dia berteriak lagi sementara aku tidak tahu harus membalas apa. Aku terengah-engah seperti habis berlari seratus meter dikali lima belas. Napasku cepat sekali.
Lalu…
Kami tertawa.
Tertawa. Lepas sekali. Entah sejak kapan tapi aku yakin, ini adalah tertawa paling bahagia yang pernah aku lakukan dan rasakan sepanjang aku bisa tertawa. Aku merasa tidak ada beban apapun. Lagi dan lagi. Aku tertawa bersama dengan orang asing yang baru kukenal tadi. Aku sudah gila! Tapi kalau dengan gila aku bisa merasakan ketenangan seperti ini, aku rela jadi gila sepanjang sisa hidupku.
“Kau benar-benar aneh, Mario.” aku masih menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan tambahan partikel Korea. Aku bingung harus memanggilnya apa. Lebih baik begini saja, aku nyaman dengan panggilan itu dan kurasa dia juga. “…atau hanya aku?” aku tersenyum.
“Maksudnya?”
“Aku merasa sangat nyaman bicara denganmu, entah kenapa, sejak awal kau menghampiriku tadi, aku merasa kau adalah orang yang bisa mendengar semua ceritaku. Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini. Kurasa itulah yang membuat kaca tak terlihat itu semakin tebal karena aku tidak pernah berani menceritakannya pada siapapun. Benar, kan?” ucapanku sepertinya mengisyaratkan bahwa aku percaya pada ucapan Mario tadi dan sedang ada kaca tebal di depan mataku sekarang.
“Kurasa iya… dan kau juga bisa melihat kaca itu di mataku sekarang? Kau bisa membandingkannya dengan milikmu?”
“Punyaku jauh lebih tebal. Jujur saja, kau terlihat sangat bisa mengatasi semuanya sendirian,”
“Aku punya teman, Airin. Semua orang punya teman untuk berbagi. Yah, walaupun temanmu… ahaha lupakan saja. Kau?”
“Aku tidak, sayangnya, kau tahu? Aku tidak pernah percaya pada persahabatan. Kau mengerti kan maksudku? Ketika para wanita berkumpul dan saling menceritakan masalah mereka satu sama lain? Mereka menganggap diri mereka sahabat, padahal dibelakang punggung sahabatnya, satu diantara mereka menusuk yang lain,”
“Cerita-cerita khas film televisi, eh?”
“Yeah, yang seperti itu. Aku pernah mendengar quote dari temanku, ‘there is no friendship, after all. We’re all just friend in a same ship’ dan kau tahu? Aku adalah orang yang mudah percaya omongan orang lain,”
“Dan kau percaya pada quote itu?”
“Ya. Sangat percaya,”
“Kenapa kau begitu yakin?”
“Seseorang pernah menusukku dengan tombak beracun dan kemudian tertawa di atas kapal terbakar dimana aku terperangkap di dalamnya,”
Hening sejenak. Senyum Mario menjadi agak ragu-ragu. Dia menatap ke langit kemudian menghembuskan napas perlahan. Aku bisa merasakan hangatnya napas itu meskipun aku ada di sampingnya. Angin membawa hawa panas Mario sehingga aku merasa sedikit hangat sekarang. Sedikit berlebihan tapi ya… begitulah kenyataannya.
“Lalu, coba katakan padaku apa yang kau lakukan jika kau sedang ada masalah?” Mario menoleh dan bertanya.
“Kabur.” jawabku pasti dengan senyuman kecil tak pasti.
“Hah?”
“Yeah, kabur dari rumah seperti pagi ini. Mengendarai motor dengan kecepatan tinggi ke sebuah tempat dimana aku bisa merasakan ketenangan. Merasakan hembusan angin yang menerbangkan rambutku. Aku selalu suka sensasinya. Merasakan bagaimana pikiranku tenang hanya dengan mendengar debur ombak di depan mataku. Dan, satu lagi, bernyanyi sendiri,”
Mario tersenyum. “Kau sudah bisa mengatasinya sekarang?”
“Sedikit. Hanya perlu satu langkah lagi,”
“Apa itu?”
“Aku biasanya menulis ceritaku, apapun masalah yang sedang aku alami disebuah kertas. Seseorang pernah memberitahuku, jika aku ingin melupakan masalahku, tuliskan semua yang ingin aku ungkapkan di selembar kertas, lalu selipkan di tempat yang mudah kulupakan.”
“Kau mengikuti saran itu?”
“Ya. Aku selalu mencoba untuk mengikutinya,”
“Lalu apakah berhasil? Maksudku, kau bisa melupakan masalahmu setelah itu?”
“Sedikit. Tapi pasti itu karena semua emosiku telah keluar lewat tulisan dan air mataku ketika aku menuliskannya, bukan? Ku dengar air mata juga bisa membuat kita lebih baik dan emosi kita jadi terkontrol,”
“Bisa jadi seperti itu. Kalau boleh aku tahu, tempat yang mudah terlupakan itu...?”
“Dompet.” jawabku tegas.
Mario tertawa lagi. “Dompet? Sudah jelas sekali ya? Maksudku, kau tadi bahkan tidak sadar dompetmu terjatuh. Itukah alasannya? Karena kau mudah lupa dompetmu sendiri?”
“Sepertinya begitu,” aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. “Sudah pasti begitu, ya? Benda kecil itu memang selalu terlupa. Kalau saja semalam aku tidak memasukkannya ke dalam kantong celana jins ini, aku pasti tidak akan membawanya pagi ini,” sekarang wajahku pastinya terlihat bodoh sekali di depan Mario.
“Bagaimana mungkin kau bisa melupakan masalahmu yang kau tulis di kertas yang terselip di dompetmu? Maksudku, ketika kau ingat pada dompetmu, kau pasti akan ingat bahwa ada sesuatu yang tertulis di dalam sana bukan?”
Aku terkejut. Dia benar juga. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Selama ini aku hanya percaya saja bahwa itu bisa membantuku. Memang membantu, walaupun hanya sedikit. Tapi masalah yang barusan Mario katakan itu, tidak pernah terpikirkan.
“Benar juga… Aku tidak pernah berpikir sampai kesana. Ah, temanku itu harus dibunuh,”
Mario tertawa lagi. Entah kenapa aku mulai curiga dia sangat hobi tertawa. Tapi tidak apa-apa, aku suka.
“Siapa yang memberitahukan kau cara seperti itu kalau aku boleh tahu?”
Diubah oleh salmansharkan 25-01-2018 10:13
0
Kutip
Balas