- Beranda
- Stories from the Heart
Catatan Seorang Pengangguran 2 (Masih Kisah Nyata)
...
TS
mukamukaos
Catatan Seorang Pengangguran 2 (Masih Kisah Nyata)


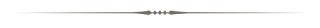
Quote:
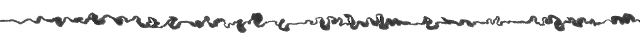

Ilustrasinya Kevin
Catatan 32. Lembaran Baru
“Ada apa, Nak?” Seorang pria berpakaian serba hitam dengan senyum mengembang dan wajah menyenangkan datang menyapa gue yang sedang duduk sendirian. Misa telah usai hampir 1 jam lalu. Namun gue masih enggan beranjak dari tempat ini.
Gue menatapnya sebentar, mengangkat secuil senyum, lalu menggeleng. Tidak apa-apa.
“Siapa namamu?”
“Kevin,” jawab gue. “Silvester Kevin Setyawan.”
“Saya baru melihat Nak Kevin di sini beberapa minggu terakhir. Pendatang?” tebaknya ramah. Pria yang ditaksir berusia sekitar 40 tahunan ini duduk di sebelah gue.
“Bapa…”
“Panggil saja Romo,” potongnya lembut.
Gue mengangguk. “Romo, saya mau tanya.”
Romo menatapku dengan lembut. Air mukanya yang tenang menyiratkan kedamaian. Garis-garis halus di sekitar matanya menunjukkan bahwa pria itu kerap tersenyum.
“Apakah saya masih pantas untuk minta ampun?” tanyaku dengan begitu berat.
Romo tersenyum. “Tidak ada kata terlambat untuk minta ampun pada-Nya.”
“Tapi apakah dosa saya pastiakan diampuni?”
“Dia Maha Baik,” balasnya. “Asalkan kamu mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti Dia akan menghapus segala dosamu.”
“Segalanya?”
Romo mengangguk.
“Meskipun saya pernah menghilangkan nyawa seseorang?”
“Namanya siapa, Pak?” tanya pria paruh baya berlogat khas Medan yang menjadi supir gue pagi ini. Mobil kijang hitam yang katanya hasil nyewa membawa gue keluar dari bandara. Parfum mobil model gantung bergambar penguin yang isinya tinggal separuh mengayun ke kanan dan kiri seiring laju mobil yang semakin cepat.
“Kevin,” jawab gue sambil menatap jauh ke luar jendela. “Dan jangan panggil saya Bapak. Saya lebih muda dari Bapak.”
Si Bapak yang pandanganannya tidak lepas dari jalan, mengerutkan kening. “Uh, maksudnya gimana, ya, Pak?”
Gue menatapnya heran. “Maksudnya, panggil saja ‘Mas’. Saya lebih muda dari situ.”
Si Bapak manggut-manggut. “Iya, baik, Mas, Pak.”
Gue menggeram. “Terserah.”
“Kita mau kemana, Pak?”
“Tempat yang bagus.”
“Dimana itu?”
“Terserah.”
Keluar dari bandara, Pak Supir yang mengendalikan mobil supaya baik jalannya belok ke arah kiri. Pemandangan yang berbeda seketika terhampar sejauh mata memandang.
“Pak, eh, Mas Kevin asalnya darimana?” tanya Pak Supir mengisi kekosongan.
“Jawa.”
“Ngapain ke sini, Mas, eh, Pak? Liburan?”
Gue menggeleng. “Nggak apa-apa.”
Pak Supir tertawa kecil. “Bukannya lancang. Aku jadi supir lebih dari 5 tahun dan udah sering dengar jawaban seperti itu. Dan… maaf-maaf. Biasanya orang yang bilang, ‘nggak apa-apa’ itu justru ada masalah.”
Ucapannya cukup menohok. Namun gue juga tidak dapat mengelak. Orangtua itu benar. Gue datang ke mari karena masalah. Atau lebih tepatnya, menghindar dari kenyataan.
Kenyataan yang mana? Kenyataan bahwa gue membuat Bapak kecewa. Dan rupanya, kemarahan beliau jauuuh dari yang gue bayangkan.
Namun maaf, gue tidak akan menceritakan bagaimana detailnya. Biarlah gue dan TS saja yang pada malam itu melihat, tahu persis kejadiannya seperti apa.
Tapi jangan merasa kecewa. Coba bayangkan saja rasanya melihat konflik antara Bapak dan anak yang begitu heboh dan mengerikan, sampai-sampai salah satu dari mereka terpaksa angkat kaki dari rumah.
Bisa? Tidak pun juga tak mengapa. Gue berdoa semoga tiada yang melihat atau bahkan mengalami. Amin.
“Pak, tahu perumahan XXX?” tanyaku menyebut nama salah satu kompleks perumahan.
“Wah, udah kelewatan, Pak, eh, Mas. Mau putar balik?”
Gue menggeleng. “Nanti saja.”
Pak Supir mengangguk. “Jadi lanjut jalan nih, Pak, eh, Mas?”
Gue mengangguk.
Semakin menuju ke selatan, pemandangan yang tersaji juga kian berubah. Rumah-rumah mulai jarang, begitu juga pepohonan. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya perbukitan gersang bertanah putih. Sesekali terdapat warung kecil-kecil di pinggir jalan.
Beberapa menit kemudian, aku melihat sebuah bangunan tinggi di kejauhan yang tertutup bukit.
“Nah, itu tempat paling terkenal di Batam. Namanya Jembatan Barelang,” ucap Pak Supir ceria. “Kata orang, belum ke Batam kalau belum ke sana. Tenang, Mas, eh, Pak. Di sini nggak dipungut biaya masuk. Alias geratis.”
Pak Supir pun memarkirkan mobil.
“Boleh turun, Pak?” tanya gue.
“Boleh… boleh. Mau salto, kayang, atau apapun terserah kau. Aku tunggu sini. Kau, kan, belum bayar. Hehe.” Pria berkemeja abu-abu itu nyengir.
Gue tersenyum tipis, lalu turun dari mobil. Menikmati keindahan Jembatan Barelang ditambah desir angin yang berhembus segar.
“Setahu aku, ini kompleks yang Bapak, eh, Mas maksud. Tapi kalau nomor rumahnya aku kurang tahu. Soalnya terakhir kali ke sini belum begini bentuknya,” terang Pak Supir dengan kepala berputar ke segala arah. Mengamati.
Gue mengangguk, kemudian membayar ongkos padanya.
Sebelum turun dari mobil, tahu-tahu Pak Supir berkata, “Mas, eh, Pak. Kau nggak mau tahu siapa namaku?”
Kedua alis gue menyatu. “Siapa?”
Pak Supir nyengir lebar. Dia menjulurkan tangannya yang kekar. “Kenalin, aku Kevin.”
“Oh.” Sungguh berfaedah sekali.
Ada alasan mengapa Batam menjadi tempat pelarian. Pertama, gue belum pernah ke sini. Kedua, ada salah satu saudara yang statusnya sudah dicoret dari daftar keluarga tinggal di kota ini. Bagaimana gue bisa tahu? Karena anaknya pernah jadi partner kerja gue di Jakarta dulu. Dan jangan tanya caranya gue bisa diijinkan tinggal di rumahnya. Karena ceritanya panjaaaang.
Menurut kertas kecil yang gue bawa-bawa, rumahnya benar yang ini. Rumah warna ungu dengan pagar tralis yang nyaris membuatnya seperti penjara.
Dengan yakin, gue panggil nama pemilik rumah. Sepi. Sekali lagi, tidak ada jawaban. Dua kali masih sama. Di percobaan ketiga, salah satu tetangga keluar dari rumahnya dan menghampiri gue. Seorang perempuan.
“Cari Om Heru, Bang?” tanyanya ramah dengan logat khas Batak.
Gue mengangguk. “Kira-kira ada apa nggak, ya, Bu?”
“Oh, Om Heru sekeluarga pindah ke luar kota tadi malam.”
Gue terkesiap dan langsung lemas mendengarnya. “Pindah?!” jawab gue kaget. Padahal tadi malam Om Heru bilang ada di rumah. Sia-sia, dong, jauh-jauh dari Jawa ke mari.
Perempuan di depan gue mengangguk. “Kalau boleh tahu, Abang siapanya?”
“Saya saudara. Keponakan.”
“Oh, dari Jawa?”
Kedua mata gue memicing. “Kok, tahu?” tanya gue penasaran.
Perempuan berkaos putih ketat itu tersenyum. “Saya kebetulan dipasrahi bawa kunci rumah ini, Bang. Dipasrahin sama Om Heru. Katanya semalam bakal ada saudaranya yang tinggal di rumah dia.”
Gue manggut-manggut. Syukur, deh, kalau gitu.
“Tapi aku nggak tahu ternyata saudaranya ganteng banget. Hahaha,” lanjut perempuan muda itu sambil menowel lengan gue dengan genit. “Sebentar, ya, Bang? Aku ambilin kunci dulu.”
Gue mengangguk. Melihatnya berjalan menuju rumahnya. Edan! Cantik bener dia, Kev.
Tidak… jangan mikir mesum.
“Maaf, ya, Bang kalau banyak debunya. Aku betulan nggak tahu kalau saudaranya bakal datang hari ini. Kirain besok atau lusa. Biar aku bisa bersih-bersih dulu, gitu,” kata perempuan bersambut panjang sebahu itu ketika kami memasuki ruang tamu.
“Nggak apa-apa. Saya bisa bersihin sendiri. Makasih, loh, Bu…”
Perempuan berkulit putih itu merengut. “Jangan panggil, Bu, lah. Panggil saja Maria.”
“Iya. Makasih, loh, uhm, Mbak Maria.”
Maria tersenyum. “Eh, omong-omong, usia kau berapa, Bang?”
“Usia kau dulu.”
“Baru 24,” jawabnya. “Ih, Abang ini ditanya malah balik nanya. Usianya berapa, Abang Ganteng?”
“Lebih tua beberapa tahun dari situ.”
Maria manggut-manggut. “30?” tebaknya.
Gue menggeleng cepat. “Nggaklah! Emang aku kelihatan setua itu, ya?"
"Nggak juga, sih. Emang berapa?"
"Yang jelas, usia kita nggak beda jauh.”
“Lebih tua?”
Gue mengangguk. Puas?
“Ya udah kalau gitu, Bang. Aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa nggak usah sungkan buat datang ke rumah. Hehe,” jawabnya centil sembari menunjuk rumah sebelah.
“Eh, tunggu-tunggu,” kataku saat Maria hendak pergi.
“Apa?”
“Mbak tahu kenapa Pak Heru sekeluarga pindah?”
“Oh, itu. Ini sekalian informasi aja, ya, Bang? Di perumahan ini sering kemalingan. Tapi anehnya, yang sering jadi target si maling tuh rumah ini.”
Gue mematung. Sumpeh lo?
Maria tergelak. Dia menowel lenganku. Lagi. “Bercanda, Bang! Tegang amat mukanya. Hahaha. Pak Heru pindah karena ada kerja di sana.”
Kampret! “Aku kira beneran.”
“Tapi bener loh, Bang. Di perum ini suka ada maling. Makanya kalau keluar rumah, pintu gerbang sama pintu rumahnya dikunci.”
“Ya, oke, oke. Makasih. Saya mau bersih-bersih diri dulu.”
Maria mengangguk, pamit, lalu keluar.
Ada sebuah pohon mangga di pekarangan rumah Om Heru. Kurus, tidak terawat, dan wujudnya mirip yang ada di mantan kantorku di Jakarta. Rumah sederhana yang gue tinggali ini memiliki 1 kamar tidur di lantai bawah dan 2 kamar di lantai atas, satu ruang tamu sederhana, 1 kamar mandi, dan balkon di lantai 3 untuk mencuci dan jemur dengan pemandangan super.
Gue kurang paham sebabnya Om Heru dicoret dari daftar keluarga besar. Kata Bapak, sih, ada ‘pelanggaran’. Entahlah. Toh bukan masalah gue. Karena mau dicoret atau tidak, gue bersyukur Om Heru masih sudi menampung ponakannya yang ganteng tinggal dirumahnya.
“PINDAH KE BATAM?!” seru Dimas ketika gue beritahu kepindahan kawannya via telepon. “LU MAU JUAL DIRI? KOK, NGGAK NGAJAK-NGAJAK GUE?” lanjutnya. Lebih nyaring.
“Ngajak lu jual diri? Mendingan gue dagang lotek.”
“Kok nggak bilang-bilang thoKev? Sobatmu yang gaul ini kecewa.”
“Kecewa kenapa?”
“Lu bakal ketemu banyak cewek cantik di sono. Bikin iri.”
“Emang di Jakarta udah kehabisan cewek sampe ngomong kek gitu?”
“Ho-oh.”
“Haha! Makanya main tuh yang jauh. Jangan ngeue mulu sama Dinda. Bosen, kan?”
Dimas mendesis. “Kevin mamen, nggak ada ceritanya main sama janda bikin bosen,” jawabnya kalem.
“Terus ngapain iri?”
“Gimana nggak iri? Lu di Jawa aja ada yang berani kasih obat kuat biar bisa gituan. Gimana di Batam? Bisa-bisa lu diculik trus dijadiin budak. Heuheuheu.”
“Kalau dibayar mah gue mau. Nyahaha!”
“Tuh kan, bener kata gue. Lu pasti mau jual diri. Ngaku!”
“….”
“Ngaku!”
“Serah.”
“Kevin, my bro. Sumpah gue kaget sama keputusan lu. Tapi ini pendapat jujur dari lubuk hati gue yang dalem. Lu itu pinter, ganteng, cowok high class banget, deh.”
“Terus?”
“Pesen gue, kalau lu mau jual diri… patok tarif yang tinggi, ye? xoxo.”
Sialan.
Sebagai tamu yang baik, malam harinya gue melapor ke Ketua RT setempat perihal kehadiran gue. Pak Imron, selaku ketua RT, menyambut gue begitu ramah. Usai berbincang-bincang sebentar dan memberitahukan untuk menyerahkan beberapa berkas padanya supaya tidak dianggap pendatang gelap, gue pun pulang.
Suasana di Batam benar-benarberbeda jauh dari Jawa. Meski sama-sama perumahan, namun nuansanya lain.
Yang paling mencolok dan bikin kurang betah adalah suhunya. Butuh usaha lebih untuk adaptasi. Gue pernah mendengar Batam itu kota panas. Tapi gue tidak menyangka kalau panasnya keterlaluan. Bahkan, satu hari ini saja gue sudah mandi sampai 4 kali saking panasnya! Tidak heran kalau banyak rumah yang gue lihat di daerah ini memiliki AC.
Gue melempar senyum ramah ke beberapa orang yang nongkrong di depan rumah. Beberapa dari mereka menyapa, yang gue balas dengan ramah.
“Orang baru, Bang?” tanya salah satunya.
Gue mengangguk. “Iya.”
“Tinggal dimana?”
“Di rumah Bapak Heru.”
“Ohhh… Om Heru yang pindah ke Jawa? Iya, iya, iya. Abang ini saudaranya?”
Gue mengangguk.
“Bakal tinggal lama?”
“Kayaknya begitu,” jawab gue antara yakin dan tidak.
“Semoga betah, ya, Bang,” balasnya ramah.
“Iya. Saya pamit dulu.”
“Eh, Bang, tunggu!” panggilnya menghentikan langkah gue.
“Ya? Kenapa?”
“Cuma mengingatkan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pintu gerbangnya dikunci. Suka ada maling.”
Usai kalimat itu terucap, gue mendadak ingat sesuatu. Astaga! Pintu gerbang cuma ditutup dan pintu rumah tidak dikunci!
Tergesa-gesa, gue setengah berlari menuju rumah. Di tengah jalan, gue berjumpa dengan Maria. Perhatian gue seketika teralihkan oleh pakaian yang ia kenakan. Mengingatkan gue pada Dinda. Ketat. Perempuan cantik itu menenteng sebuah kresek besar.
“Bang Kevin darimana?” sapanya.
“Dari Pak RT. Kamu?”
“Ambil cucian di laundry”
Gue mengangguk.
“Eh, Bang! Kok gerbangnya dibiarin terbuka, sih? Aku, kan, udah bilang, suka ada maling berkeliaran.”
Gue terkejut. “Terbuka? Perasaan tadi saya tutup, deh.”
Maria menggeleng. “Kebuka, Bang. Serius. Coba cek sendiri.”
Hening.
Kami berdua saling bertatapan.
DEG!
Mampus!
Batam, 2015
“Ada apa, Nak?” Seorang pria berpakaian serba hitam dengan senyum mengembang dan wajah menyenangkan datang menyapa gue yang sedang duduk sendirian. Misa telah usai hampir 1 jam lalu. Namun gue masih enggan beranjak dari tempat ini.
Gue menatapnya sebentar, mengangkat secuil senyum, lalu menggeleng. Tidak apa-apa.
“Siapa namamu?”
“Kevin,” jawab gue. “Silvester Kevin Setyawan.”
“Saya baru melihat Nak Kevin di sini beberapa minggu terakhir. Pendatang?” tebaknya ramah. Pria yang ditaksir berusia sekitar 40 tahunan ini duduk di sebelah gue.
“Bapa…”
“Panggil saja Romo,” potongnya lembut.
Gue mengangguk. “Romo, saya mau tanya.”
Romo menatapku dengan lembut. Air mukanya yang tenang menyiratkan kedamaian. Garis-garis halus di sekitar matanya menunjukkan bahwa pria itu kerap tersenyum.
“Apakah saya masih pantas untuk minta ampun?” tanyaku dengan begitu berat.
Romo tersenyum. “Tidak ada kata terlambat untuk minta ampun pada-Nya.”
“Tapi apakah dosa saya pastiakan diampuni?”
“Dia Maha Baik,” balasnya. “Asalkan kamu mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti Dia akan menghapus segala dosamu.”
“Segalanya?”
Romo mengangguk.
“Meskipun saya pernah menghilangkan nyawa seseorang?”
****
3 bulan yang lalu
“Namanya siapa, Pak?” tanya pria paruh baya berlogat khas Medan yang menjadi supir gue pagi ini. Mobil kijang hitam yang katanya hasil nyewa membawa gue keluar dari bandara. Parfum mobil model gantung bergambar penguin yang isinya tinggal separuh mengayun ke kanan dan kiri seiring laju mobil yang semakin cepat.
“Kevin,” jawab gue sambil menatap jauh ke luar jendela. “Dan jangan panggil saya Bapak. Saya lebih muda dari Bapak.”
Si Bapak yang pandanganannya tidak lepas dari jalan, mengerutkan kening. “Uh, maksudnya gimana, ya, Pak?”
Gue menatapnya heran. “Maksudnya, panggil saja ‘Mas’. Saya lebih muda dari situ.”
Si Bapak manggut-manggut. “Iya, baik, Mas, Pak.”
Gue menggeram. “Terserah.”
“Kita mau kemana, Pak?”
“Tempat yang bagus.”
“Dimana itu?”
“Terserah.”
Keluar dari bandara, Pak Supir yang mengendalikan mobil supaya baik jalannya belok ke arah kiri. Pemandangan yang berbeda seketika terhampar sejauh mata memandang.
“Pak, eh, Mas Kevin asalnya darimana?” tanya Pak Supir mengisi kekosongan.
“Jawa.”
“Ngapain ke sini, Mas, eh, Pak? Liburan?”
Gue menggeleng. “Nggak apa-apa.”
Pak Supir tertawa kecil. “Bukannya lancang. Aku jadi supir lebih dari 5 tahun dan udah sering dengar jawaban seperti itu. Dan… maaf-maaf. Biasanya orang yang bilang, ‘nggak apa-apa’ itu justru ada masalah.”
Ucapannya cukup menohok. Namun gue juga tidak dapat mengelak. Orangtua itu benar. Gue datang ke mari karena masalah. Atau lebih tepatnya, menghindar dari kenyataan.
Kenyataan yang mana? Kenyataan bahwa gue membuat Bapak kecewa. Dan rupanya, kemarahan beliau jauuuh dari yang gue bayangkan.
Namun maaf, gue tidak akan menceritakan bagaimana detailnya. Biarlah gue dan TS saja yang pada malam itu melihat, tahu persis kejadiannya seperti apa.
Tapi jangan merasa kecewa. Coba bayangkan saja rasanya melihat konflik antara Bapak dan anak yang begitu heboh dan mengerikan, sampai-sampai salah satu dari mereka terpaksa angkat kaki dari rumah.
Bisa? Tidak pun juga tak mengapa. Gue berdoa semoga tiada yang melihat atau bahkan mengalami. Amin.
“Pak, tahu perumahan XXX?” tanyaku menyebut nama salah satu kompleks perumahan.
“Wah, udah kelewatan, Pak, eh, Mas. Mau putar balik?”
Gue menggeleng. “Nanti saja.”
Pak Supir mengangguk. “Jadi lanjut jalan nih, Pak, eh, Mas?”
Gue mengangguk.
Semakin menuju ke selatan, pemandangan yang tersaji juga kian berubah. Rumah-rumah mulai jarang, begitu juga pepohonan. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya perbukitan gersang bertanah putih. Sesekali terdapat warung kecil-kecil di pinggir jalan.
Beberapa menit kemudian, aku melihat sebuah bangunan tinggi di kejauhan yang tertutup bukit.
“Nah, itu tempat paling terkenal di Batam. Namanya Jembatan Barelang,” ucap Pak Supir ceria. “Kata orang, belum ke Batam kalau belum ke sana. Tenang, Mas, eh, Pak. Di sini nggak dipungut biaya masuk. Alias geratis.”
Pak Supir pun memarkirkan mobil.
“Boleh turun, Pak?” tanya gue.
“Boleh… boleh. Mau salto, kayang, atau apapun terserah kau. Aku tunggu sini. Kau, kan, belum bayar. Hehe.” Pria berkemeja abu-abu itu nyengir.
Gue tersenyum tipis, lalu turun dari mobil. Menikmati keindahan Jembatan Barelang ditambah desir angin yang berhembus segar.
****
“Setahu aku, ini kompleks yang Bapak, eh, Mas maksud. Tapi kalau nomor rumahnya aku kurang tahu. Soalnya terakhir kali ke sini belum begini bentuknya,” terang Pak Supir dengan kepala berputar ke segala arah. Mengamati.
Gue mengangguk, kemudian membayar ongkos padanya.
Sebelum turun dari mobil, tahu-tahu Pak Supir berkata, “Mas, eh, Pak. Kau nggak mau tahu siapa namaku?”
Kedua alis gue menyatu. “Siapa?”
Pak Supir nyengir lebar. Dia menjulurkan tangannya yang kekar. “Kenalin, aku Kevin.”
“Oh.” Sungguh berfaedah sekali.
****
Ada alasan mengapa Batam menjadi tempat pelarian. Pertama, gue belum pernah ke sini. Kedua, ada salah satu saudara yang statusnya sudah dicoret dari daftar keluarga tinggal di kota ini. Bagaimana gue bisa tahu? Karena anaknya pernah jadi partner kerja gue di Jakarta dulu. Dan jangan tanya caranya gue bisa diijinkan tinggal di rumahnya. Karena ceritanya panjaaaang.
Menurut kertas kecil yang gue bawa-bawa, rumahnya benar yang ini. Rumah warna ungu dengan pagar tralis yang nyaris membuatnya seperti penjara.
Dengan yakin, gue panggil nama pemilik rumah. Sepi. Sekali lagi, tidak ada jawaban. Dua kali masih sama. Di percobaan ketiga, salah satu tetangga keluar dari rumahnya dan menghampiri gue. Seorang perempuan.
“Cari Om Heru, Bang?” tanyanya ramah dengan logat khas Batak.
Gue mengangguk. “Kira-kira ada apa nggak, ya, Bu?”
“Oh, Om Heru sekeluarga pindah ke luar kota tadi malam.”
Gue terkesiap dan langsung lemas mendengarnya. “Pindah?!” jawab gue kaget. Padahal tadi malam Om Heru bilang ada di rumah. Sia-sia, dong, jauh-jauh dari Jawa ke mari.
Perempuan di depan gue mengangguk. “Kalau boleh tahu, Abang siapanya?”
“Saya saudara. Keponakan.”
“Oh, dari Jawa?”
Kedua mata gue memicing. “Kok, tahu?” tanya gue penasaran.
Perempuan berkaos putih ketat itu tersenyum. “Saya kebetulan dipasrahi bawa kunci rumah ini, Bang. Dipasrahin sama Om Heru. Katanya semalam bakal ada saudaranya yang tinggal di rumah dia.”
Gue manggut-manggut. Syukur, deh, kalau gitu.
“Tapi aku nggak tahu ternyata saudaranya ganteng banget. Hahaha,” lanjut perempuan muda itu sambil menowel lengan gue dengan genit. “Sebentar, ya, Bang? Aku ambilin kunci dulu.”
Gue mengangguk. Melihatnya berjalan menuju rumahnya. Edan! Cantik bener dia, Kev.
Tidak… jangan mikir mesum.
****
“Maaf, ya, Bang kalau banyak debunya. Aku betulan nggak tahu kalau saudaranya bakal datang hari ini. Kirain besok atau lusa. Biar aku bisa bersih-bersih dulu, gitu,” kata perempuan bersambut panjang sebahu itu ketika kami memasuki ruang tamu.
“Nggak apa-apa. Saya bisa bersihin sendiri. Makasih, loh, Bu…”
Perempuan berkulit putih itu merengut. “Jangan panggil, Bu, lah. Panggil saja Maria.”
“Iya. Makasih, loh, uhm, Mbak Maria.”
Maria tersenyum. “Eh, omong-omong, usia kau berapa, Bang?”
“Usia kau dulu.”
“Baru 24,” jawabnya. “Ih, Abang ini ditanya malah balik nanya. Usianya berapa, Abang Ganteng?”
“Lebih tua beberapa tahun dari situ.”
Maria manggut-manggut. “30?” tebaknya.
Gue menggeleng cepat. “Nggaklah! Emang aku kelihatan setua itu, ya?"
"Nggak juga, sih. Emang berapa?"
"Yang jelas, usia kita nggak beda jauh.”
“Lebih tua?”
Gue mengangguk. Puas?
“Ya udah kalau gitu, Bang. Aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa nggak usah sungkan buat datang ke rumah. Hehe,” jawabnya centil sembari menunjuk rumah sebelah.
“Eh, tunggu-tunggu,” kataku saat Maria hendak pergi.
“Apa?”
“Mbak tahu kenapa Pak Heru sekeluarga pindah?”
“Oh, itu. Ini sekalian informasi aja, ya, Bang? Di perumahan ini sering kemalingan. Tapi anehnya, yang sering jadi target si maling tuh rumah ini.”
Gue mematung. Sumpeh lo?
Maria tergelak. Dia menowel lenganku. Lagi. “Bercanda, Bang! Tegang amat mukanya. Hahaha. Pak Heru pindah karena ada kerja di sana.”
Kampret! “Aku kira beneran.”
“Tapi bener loh, Bang. Di perum ini suka ada maling. Makanya kalau keluar rumah, pintu gerbang sama pintu rumahnya dikunci.”
“Ya, oke, oke. Makasih. Saya mau bersih-bersih diri dulu.”
Maria mengangguk, pamit, lalu keluar.
****
Ada sebuah pohon mangga di pekarangan rumah Om Heru. Kurus, tidak terawat, dan wujudnya mirip yang ada di mantan kantorku di Jakarta. Rumah sederhana yang gue tinggali ini memiliki 1 kamar tidur di lantai bawah dan 2 kamar di lantai atas, satu ruang tamu sederhana, 1 kamar mandi, dan balkon di lantai 3 untuk mencuci dan jemur dengan pemandangan super.
Gue kurang paham sebabnya Om Heru dicoret dari daftar keluarga besar. Kata Bapak, sih, ada ‘pelanggaran’. Entahlah. Toh bukan masalah gue. Karena mau dicoret atau tidak, gue bersyukur Om Heru masih sudi menampung ponakannya yang ganteng tinggal dirumahnya.
“PINDAH KE BATAM?!” seru Dimas ketika gue beritahu kepindahan kawannya via telepon. “LU MAU JUAL DIRI? KOK, NGGAK NGAJAK-NGAJAK GUE?” lanjutnya. Lebih nyaring.
“Ngajak lu jual diri? Mendingan gue dagang lotek.”
“Kok nggak bilang-bilang thoKev? Sobatmu yang gaul ini kecewa.”
“Kecewa kenapa?”
“Lu bakal ketemu banyak cewek cantik di sono. Bikin iri.”
“Emang di Jakarta udah kehabisan cewek sampe ngomong kek gitu?”
“Ho-oh.”
“Haha! Makanya main tuh yang jauh. Jangan ngeue mulu sama Dinda. Bosen, kan?”
Dimas mendesis. “Kevin mamen, nggak ada ceritanya main sama janda bikin bosen,” jawabnya kalem.
“Terus ngapain iri?”
“Gimana nggak iri? Lu di Jawa aja ada yang berani kasih obat kuat biar bisa gituan. Gimana di Batam? Bisa-bisa lu diculik trus dijadiin budak. Heuheuheu.”
“Kalau dibayar mah gue mau. Nyahaha!”
“Tuh kan, bener kata gue. Lu pasti mau jual diri. Ngaku!”
“….”
“Ngaku!”
“Serah.”
“Kevin, my bro. Sumpah gue kaget sama keputusan lu. Tapi ini pendapat jujur dari lubuk hati gue yang dalem. Lu itu pinter, ganteng, cowok high class banget, deh.”
“Terus?”
“Pesen gue, kalau lu mau jual diri… patok tarif yang tinggi, ye? xoxo.”
Sialan.
****
Sebagai tamu yang baik, malam harinya gue melapor ke Ketua RT setempat perihal kehadiran gue. Pak Imron, selaku ketua RT, menyambut gue begitu ramah. Usai berbincang-bincang sebentar dan memberitahukan untuk menyerahkan beberapa berkas padanya supaya tidak dianggap pendatang gelap, gue pun pulang.
Suasana di Batam benar-benarberbeda jauh dari Jawa. Meski sama-sama perumahan, namun nuansanya lain.
Yang paling mencolok dan bikin kurang betah adalah suhunya. Butuh usaha lebih untuk adaptasi. Gue pernah mendengar Batam itu kota panas. Tapi gue tidak menyangka kalau panasnya keterlaluan. Bahkan, satu hari ini saja gue sudah mandi sampai 4 kali saking panasnya! Tidak heran kalau banyak rumah yang gue lihat di daerah ini memiliki AC.
Gue melempar senyum ramah ke beberapa orang yang nongkrong di depan rumah. Beberapa dari mereka menyapa, yang gue balas dengan ramah.
“Orang baru, Bang?” tanya salah satunya.
Gue mengangguk. “Iya.”
“Tinggal dimana?”
“Di rumah Bapak Heru.”
“Ohhh… Om Heru yang pindah ke Jawa? Iya, iya, iya. Abang ini saudaranya?”
Gue mengangguk.
“Bakal tinggal lama?”
“Kayaknya begitu,” jawab gue antara yakin dan tidak.
“Semoga betah, ya, Bang,” balasnya ramah.
“Iya. Saya pamit dulu.”
“Eh, Bang, tunggu!” panggilnya menghentikan langkah gue.
“Ya? Kenapa?”
“Cuma mengingatkan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pintu gerbangnya dikunci. Suka ada maling.”
Usai kalimat itu terucap, gue mendadak ingat sesuatu. Astaga! Pintu gerbang cuma ditutup dan pintu rumah tidak dikunci!
Tergesa-gesa, gue setengah berlari menuju rumah. Di tengah jalan, gue berjumpa dengan Maria. Perhatian gue seketika teralihkan oleh pakaian yang ia kenakan. Mengingatkan gue pada Dinda. Ketat. Perempuan cantik itu menenteng sebuah kresek besar.
“Bang Kevin darimana?” sapanya.
“Dari Pak RT. Kamu?”
“Ambil cucian di laundry”
Gue mengangguk.
“Eh, Bang! Kok gerbangnya dibiarin terbuka, sih? Aku, kan, udah bilang, suka ada maling berkeliaran.”
Gue terkejut. “Terbuka? Perasaan tadi saya tutup, deh.”
Maria menggeleng. “Kebuka, Bang. Serius. Coba cek sendiri.”
Hening.
Kami berdua saling bertatapan.
DEG!
Mampus!
BERSAMBUNG
NEXT. CATATAN 33 : LOWONGAN KERJA
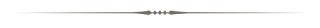
Story by Mukamukaos
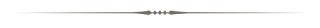
JANGAN LUPA CENDOL, KOMEN, RATE, SHARE, KRITIK & SARAN










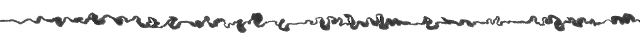
Polling
0 suara
Apakah Agan dan Sista termasuk orang yang gampang beradaptasi dengan lingkungan baru?
kafeinc dan 134 lainnya memberi reputasi
125
273.2K
1.2K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart
32.2KThread•46.4KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya
 ) cerita seru yang ia alami setelah kejadian heboh di akhir catatan lalu.
) cerita seru yang ia alami setelah kejadian heboh di akhir catatan lalu.