- Beranda
- Stories from the Heart
Komala
...
TS
janahjoy35
Komala
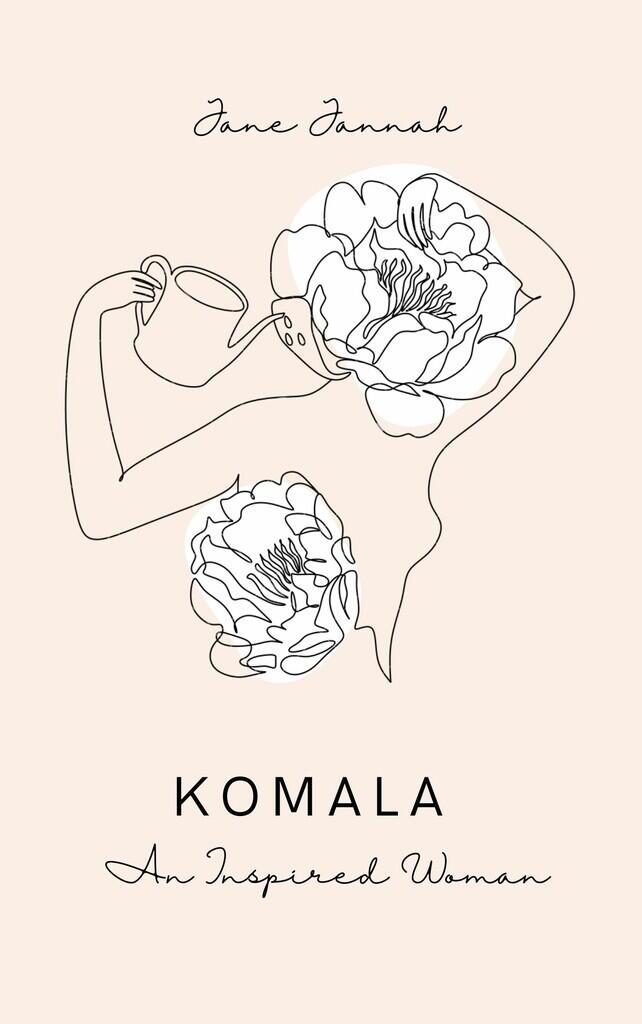
Prolog
"Bikin malu Bapak, kamu!" bentak Guntur sambil menunjuk tepat muka Komala yang kuyu.
"Udah, Pak..." Widya berkata lirih mencoba menenangkan emosi Guntur.
Guntur menghela napas, frustasi. "Saya malu sama kamu, Wid. Saya yang minta kamu untuk membesarkan dia, dulu. Tapi, lihat! beraninya dia menaruh kotoran di muka kita." kata Guntur sambil menjatuhkan tubuhnya ke sofa.
"Qodarullah, semua sudah terjadi." Widya mendekati Komala, mengelus sayang anak angkatnya yang kembali menangis tersedu.
"Maafin Mala, Pak." Komala bersimpuh di kaki Guntur.
Guntur mengusap wajahnya, memejamkan matanya. Perlahan, bahunya mulai bergetar. Guntur, pensiunan polisi pangkat bintang 2 itu menangis.
1. Komala, namanya.
Saat itu musim penghujan. Hampir setiap sore, hujan deras mengguyur kota. Guntur tiba dirumah dengan wajah pucat dan cemas.
"Widya, kita harus berangkat ke Purwakarta. Sekarang!" katanya sambil terburu-buru mengganti baju dinasnya.
"Ada apa, Pak?" Tanya Widya, cemas.
"Adikku, gugur saat bertugas, Widya." Guntur terduduk di sisi ranjang.
"Innalillahi... Guruh, Pak?"
"Iya, Guruh. Siapa lagi adikku, Wid?"
"Bapak sabar, Bapak tenang dulu. Aku siapin keperluan kita untuk kesana." Kata Widya sambil bergegas mengambil koper untuk mengkemas beberapa baju miliknya dan Guntur.
***
Opel kapitan p2 melaju menerobos hujan.
"Perjalanan masih sangat jauh, Bapak tidur aja dulu." Kata Widya sambil membantu Guntur mengancingkan jaketnya.
"Kasian sekali adikku itu, Widya. Dia belum sempat bertemu dengan anaknya." kata Guntur dengan pandangan menerawang keluar kaca mobil. "Pelan amat kamu bawa mobilnya, Run." keluh Guntur pada supirnya, Harun.
"Gak apa, pelan-pelan aja, Run. Hujan, bahaya kalau ngebut." Widya memperingatkan Harun yang mulai menginjak pedal gas. "Memangnya Lastri sudah melahirkan, Pak?"
"Pagi tadi aku dapat kabar gembira kelahiran keponakanku itu, Widya. Sorenya aku dapat kabar duka kematian ayahnya. Malang sekali keponakanku, Widya. Malang sekali nasib Guruh, Widya." Guntur memejamkan matanya lalu menyandarkan kepalanya di jok.
Widya diam. Jika sudah seperti ini, tandanya Guntur sudah tidak mau di ganggu apalagi di tanya-tanya. Widya hanya menepuk-nepuk lengan suaminya yang usianya terpaut 20 tahun itu.
***
Nuansa duka begitu kental di kediaman rumah Lastri. Riuh sesak keluarga dan tetangga yang turut hadir untuk berbelasungkawa tidak bisa menghilangkan kesan sunyi dan sepi dari perasaan Lastri yang baru saja menjadi janda.
Lastri masih terbaring lemah di kamar saat Widya dan Guntur sampai dirumah mereka.
"Pak Guntur, untung Bapak sudah datang." kata Soleh, tetangga sekaligus pesuruh keluarga Guntur di Purwakarta.
"Kenapa, Pak Soleh?"
"Neng Lastri, Pak. Sejak menerima kabar meninggalnya Pak Guruh, Neng Lastri mendadak diem, tidak mau nyusuin anaknya. Kasian anaknya, nangis terus belum kena ASI," kata Soleh sambil mengekori Guntur yang menerobos masuk ke kemar utama.
Suara tangisan bayi menggema di dalam kamar. Bayi itu meronta dalam balutan selendang, tangannya mengais-ngais mencari pelukan hangat sang ibu. Sementara Lastri, Ibu sang bayi, hanya menatap kosong jendela kamar yang basah karena tampias air hujan.
"Widya! tolong Widya!" seru Guntur memanggil istrinya yang langsung sibuk membantu menyiapkan perlengkapan untuk menyambut jenazah Guruh.
"Iya, Pak. Sebentar." kata Widya sambil berjalan cepat menemui suaminya di kamar utama.
"Tolong anak itu, Widya. Aku tidak tega mendengar tangisannya."
Widya langsung menggendong bayi yang baru lahir itu. Di dekapnya bayi itu dengan penuh kasih sayang. "Pak Soleh, saya bisa minta tolong air hangat?"
"Boleh, Bu." Soleh bergegas menuju dapur.
Widya menatap wajah bayi yang mulai berangsung reda tangisnya. "Cantik sekali anakmu, Lasti." kata Widya.
Tiba-tiba saja, Lasti tertawa terbahak-bahak. Lalu menangis, meraung sejadinya membuat semua orang yang ada dirumah itu kaget sekaligus heran.
"Aku tidak mau anak itu!" seru Lastri dengan tatapan nyalang ke arah Widya yang tengah menggendong anaknya. "Aku hanya mau suamiku. Aku tak bisa tanpa suamiku!" jeritnya.
"Widya, tolong bawa dan jaga dulu anak ini. Sebentar lagi mobil yang bawa jenazah Guruh datang." Kata Guntur sambil menggiring Widya yang tengah menggendong bayi keluar kamar.
"Iya! Bawa pergi anak itu! Aku tidak ingin anak itu tanpa suamiku!" teriak Lastri.
"Pak Soleh, tolong kunci pintu kamar Bu Lastri!" perintah Guntur kepada Soleh yang baru datang tergopoh-gopoh membawa segelas air.
"Ba- baik, Pak. Ini air?" Pak Soleh terlihat bingung.
Guntur langsung mengambil gelas yang di bawa Soleh dan menyusul Widya ke kamar tamu.
***
"Kita kasih nama siapa bayi ini, Pak?" tanya Widya.
"'Komala, namanya.' itu yang pernah dikatakan Guruh padaku, dulu." Guntur mengusap wajahnya gusar. "Widya, apakan kamu bersedia merawat anak ini? Aku tidak tega kalau harus menitip anak di Pak Soleh. Dia dan istrinya sudah sangat tua. Kamu liat sendiri, Lastri tidak menginginkan anak ini, bahkan dia seperti orang gila, sekarang."
Mata Widya terbelalak saking kaget. "Aku sudah berencana meminta bayi ini untuk aku rawat, Pak. Tentu aku mau." kata Widya, gembira.
"Terimakasih, Widya." Guntur mencium kening istrinya. "Sungguh kamu adalah pemberian Tuhan yang terindah." katanya, membuat Widya tersipu.
"Kamu pemberian Tuhan yang terindah." Widya mengecup sayang pipi Komala.
Guntur tersenyum melihat istrinya yang begitu tulus mencintai keponakannya.
***
Quote:
medh1221 dan 9 lainnya memberi reputasi
10
1.3K
23
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Stories from the Heart

31.4KThread•41.4KAnggota
Tampilkan semua post
TS
janahjoy35
#15
KOMALA
7. Sekeping puzzle
Suara ketukan di pintu kamar kost Komala terdengar gaduh. Komala meletakan reglet dan stylus ─penggaris berlubang dan paku penusuk kertas yang biasa digunakan tunanetra menulis Braille, di meja.
Wajah Bu Nadine tersenyum ramah begitu Komala membuka pintu kostnya. “Ada telepon untuk kamu,” kata Bu Nadine.
“Baik, Bu. Terimakasih. Sebentar saya kebawah.” Jawab Komala sopan.
Bu Nadine tersenyum, lalu beranjak meninggalkan kamar kost Komala.
Komala bergegas memakai celana training panjang. Dia tidak terbiasa keluar kamar dengan pakaian minim. Dengan tergesa, Komala turun ke lantai satu dan langsung menerobos masuk rumah Bu Nadien menuju sebuah ruangan yang terletak diantara dapur dan ruang tamu yang dijadikan perpustakaan pribadi bergaya retro oleh Bu Nadien. Tidak salah “Tante Nyetrik” menjadi julukan untuk Bu Nadien. Beliau suka hal-hal yang classic.
“Hallo,” sapa Komala begitu gagang telepon menyentuh daun telinga kanannya.
“Mala, ini Bapak.”Suara Guntur terdengar tegas walaupun di telepon.
“Iya, Pak. Bapak sama Mamah sehat?”
“Yah, ya… kami sehat. Kamu apa kabar, Nak?”
“Mala sehat, Pak.”
“Mala, kamu bisa pulang hari ini?” Nada suara Guntur terdengar resah dan terburu-buru.
“Ada apa, Pak?” tanya Komala, panik. “Mamah beneran sehat, kan, Pak?”
“Ini bukan soal Mamah, ini soal ibu kamu. Ibu kamu sakit… Ibumu ingin bertemu kamu. Katanya, itu permintaan terakhirnya.” kalimat Guntur diakhiri dengan helaan napas panjang.
Untuk sesaat, Komala tertegun. Kata “Ibu─wanita yang melahirkannya” terdengar asing baginya. Pernah beberapa kali sejak dia mengetahui bahwa Widya bukanlah ibu yang melahirkannya, Komala berharap ibu kandungnya itu akan tiba-tiba datang dan menjemputnya. Bukan karena Komala tidak bahagia bersama Guntur dan Widya, tapi setidaknya dia tidak akan merasa di buang oleh ibu kandungnya.
“Mala…” panggil Guntur dari balik telepon, suaranya terdengar lembut.
Suara Guntur yang lembut terdengar lirih di telinga Komala, Komala menghela napas. “Ibu ada disana, Pak?” tanyanya.
“Tidak. Ibumu di Purwakarta. Kalau kamu bisa pulang hari ini, kita bisa berangkat bersama kesana, besok.”
“Bapak berangkat besok?”
“Iya, kita berangkat besok.”
“Mala harus izin dulu ke sekolah, Pak. Mala berangkat langsung dari sini aja, gimana?”
“Yakin, kamu? tidak takut, kamu?” Nada suara Guntur terdengar khawatir.
Komala terkekeh. Guntur masih saja menganggapnya seperti anak kecil. “Mala udah gede, Pak.”
Guntur menghela napas. “Baiklah, catat alamatnya!”
Komala bergegas mengambil ballpoint dan sticky note yang biasa di letakan Bu Nadien di meja disamping pesawat telepon.
Setelah selesai menulis alamat rumah Ibunya, sebelum memutus sambungan telepon, Komala menyempatkan untuk bercakap-cakap sebentar bersama Widya untuk melepas kangen.
***
“Nah, ini dia.” Suara Bu Nadien mengagetkan Komala yang baru saja keluar dari dalam rumah. “Udah? Gimana, kabar orang tua kamu, sehat?”
Mata Komala terbelalak, kekagetannya bertambah tiga kali lipat. Bukan karena Bu Nadine, tapi karena sosok laki-laki yang sudah mau satu bulan ini menghilang dan membuatnya resah.
“Bahri?!” serunya.
Seketika Bahri berdiri dari duduknya, tersenyum lebar sekali. “Komala, apa kabar?” sapanya.
Komala mengerutkan keningnya, matanya menatap tajam Bahri. Bisa-bisanya kau tiba-tiba datang setelah lama hilang, lalu dengan santainya kau bertanya apa kabar? Kabarku, buruk. Dan itu karena kamu.
Bu Nadien tersenyum melihat reaksi kaget Komala. “Kalau gitu, Ibu tinggal dulu, ya, Nak Bahri.” Bu Nadien beranjak berdiri, tersenyum ramah kepada Bahri lalu mengangguk lembut kepada Komala, masih dengan senyum yang menghiasi wajah timur tengahnya, Bu Nadien masuk ke dalam rumah.
Komala duduk di bangku teras yang tadi di duduki oleh Bu Nadien. Wajahnya merengut kesal.
“Ada apa kamu kemari?” tanyanya ketus.
“Kata Ibu Kost kamu, waktu itu kamu nungguin aku, ya? Maaf aku tidak datang,”
Ih, Bu Nadien! Apa coba maksudnya. Gerutu Komala dalam hati.
Bahri menatap lembut Komala. “Aku pikir kamu tidak akan nungguin aku,” Bahri terkekeh.
Komala memutar bola matanya kesal. “Ya! Aku salah karena terlalu berharap sama manusia.” gerutunya.
Bahri terkekeh. “Kamu gak mau tanya, kenapa aku tidak datang?”
“Untuk apa?!”
Bahri tersenyum melihat wajah Komala yang jelas sekali dia kesal. “Malam itu, setelah aku anter kamu kesini, aku kecelakaan.” Bahri membuka sepatunya lalu menarik keatas bagian celana yang menutupi betis kanannya. Bekas luka jahitan terlihat memanjang dari punggung kaki, melewati mata kaki sampai ke betis. Garis putih kemerahan menunjukan kondisi luka yang masih dalam proses penyembuhan.
Komala terperangah. Reflek, kedua tangannya menutup mulutnya yang tiba-tiba tebuka. “Ya ampun, Bahri…” katanya lirih. Mata Komala mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba saja dia ingin menangis. “Maafkan aku… “ Komala terisak.
“Eh! Kenapa kamu nangis?” Bahri mendekati Komala, menepuk-nepuk pundak Komala lembut.
Selama ini aku fikir, mudah sekali kamu melupakanku. Begitu saja hilang tanpa kabar. Ternyata aku salah.Tangis Komala semakin menjadi. “Ibu…” panggil Komala lirih. Entah bagaimana, kejadian yang menimpa Bahri tiba-tiba membuatnya teringat pada ibu kandungnya. Untuk pertama kalinya, dia berfikir positif tentang ibu kandungnya dan hal itu membuatnya merasa bersalah sekaligus merindukan ibu kandungnya itu.
“Kenapa, Ibu kamu?” tanya Bahri sambil duduk berlutut di depan Komala yang semakin larut dalam tangis.
“Ibu sakit. Aku harus segera pulang.”
Bahri mengambil tangan Komala, menggenggamnya erat. “Kapan kamu mau pulang? Aku antar, ya!”
Komala menatap nanar wajah Bahri, air mata terus berderai membasahi kedua pipinya yang putih bersih.
Bahri membelai pipi Komala, menghapus bulir-bulir air mata di pipi Komala. “Kali ini aku akan hati-hati, aku tidak akan membuat kamu menunggu lagi.” Kata Bahri dengan tatapan lembut dan dalam yang membuat Komala yakin lalu mengangguk patuh.
***
Setelah mendapatkan izin cuti untuk beberapa hari dari Pak Triadji, Komala bergegas menemui Bahri yang sudah menunggunya di pos satpam. Kali ini Bahri betul-betul menepati janjinya.
Zafar, penjaga sekolah sekaligus satpam melepas keduanya dengan mendoakan keselamatan untuk keduanya dan kesembuhan untuk ibunya Komala.
Motor CB100 milik Bahri melaju sedang, meninggalkan sekolah tempat Komala ngajar. Komala melingkarkan tangannya memeluk Bahri. Menghangatkan udara pagi yang lumayan dingin menusuk kulit. Tanpa mereka sadari, keduanya tersenyum menikmati sensasi yang terasa menggelitik perut masing-masing.
***
Tidak sulit untuk menemukan kediaman Satria Yudha, kediaman keluarga besar Guntur di perkampungan kecil di Purwakarta.
“Kalau boleh tau, Neng ini siapa? Ada perlu apa mencari kediaman Alamarhum Pak Satria?” tanya Bapak paruh baya pemilik warung kopi tempat Komala dan Bahri singgah untuk beristirahat.
“Saya Komala, anaknya Bapak Guntur.” Jawab Komala, sopan.
“MasyaAllah, anak Pak Guntur? Kenapa gak bilang dari tadi, atuh.” Bapak itu tergopoh keluar dari dalam warungnya.
Komala tersenyum kikuk, sementara Bahri menatap Bapak itu, heran.
“Jang! Ujang!” Bapak pemilik warung kopi berteriak sambil melambaikan tangan memanggil sorang anak laki-laki yang tengah asik bermain layangan di lapangan di sebrang warungnya. Tanpa menyahut, anak itu berlari ke warung.
“Aya naon, Bah?”(Ada apa, Bah?) tanya anak laki-laki yang kira-kira usianya memasuki awal baligh itu, matanya menatap penuh selidik ke arah Bahri dan Komala.
“Yeuh, anteurkeun tamu na Pak Guntur ka imah Bah Soleh!” (Tolong antar tamunya Pak Guntur kerumah Abah Soleh) pinta Bapak pemilik warung sambil menepuk pundak ringkih anak lelaki itu. Anak itu mengangguk nurut.
“Mangga, Neng. Diantar sama si Ujang, ya.” (Silahkan, Neng. Diantar sama Ujang, ya) kata Bapak pemilik warung sambil mengangguk sopan pada Komala dan Bahri.
“Hatur nuhun, Pak.” (terimakasih, Pak) Kata Komala seraya mengangguk sopan kepada Bapak pemilik warung.
Sebelum mengikuti si Ujang yang sudah beranjak untuk memandu jalan, Komala berbalik mendekati Bahri yang sedang menyalakan mesin motornya. “Aku jalan kaki sama anak itu, ya. Gak apa-apa, kan?”
“Oh, kamu mau jalan kaki? Yaudah gak apa-apa,” Kata Bahri sambil tersenyum jahil lalu menarik gas meninggalkan Komala dan berhenti tepat disamping Ujang. “Naik, Jang. Si Neng itu mau jalan kaki, jadi kamu aja yang naik.” Bahri terkekeh sambil mengedipkan sebelah matanya pada Komala yang terbengong menatapnya.
“Bahri?!” seru Komala tidak mengerti.
“Kamu tunggu dulu disini, nanti aku jemput kamu kalau udah tau rumahnya Abah Soleh,” teriak Bahri lalu melaju meninggalkan Komala yang masih bengong bersama Bapak pemilik warung yang terkekeh melihat kejahilan Bahri pada Komala.
“Sinih, Neng. Gak lama juga nanti pacarnya balik lagi,” kata penjaga warung. “Pacar Neng itu gak mau Neng capek,” lanjutnya kemudian kembali terkekeh "Padahal mah, udah deket." Lagi-lagi Bapak pemilik warung terkekeh, kali ini sambil geleng-geleng kepala.
Komala mengangkup kedua pipinya yang menghangat. Ucapan Bapak pemilik warung membuatnya malu sekaligus bahagia.
Tidak sampai sepuluh menit Komala menunggu. Suara motor Bahri terdengar mendekat. Seketika Komala beranjak, berdiri antusian dengan senyum yang merekah serta tatapan berbinar menatap Bahri. Dia belum pernah sebahagia ini. Bertemu dengan Ibu kandungnya di temani orang asing yang entah bagaimana terasa sangat dekat dan akrab. Kehadiran Bahri seperti sekeping puzzle yang mampu melengkapi bagian yang selama ini kosong dalam dirinya.
***
0
Tutup