Heningnya malam antarkan getaran nestapa hatiku,

Bersambung ke bab II
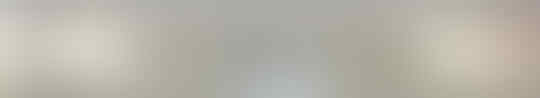

diri ini onggokan debu kelak tersapu ombak waktu.
– saking penggalan tutur Kalih Pingpitu
BAB I
(Raden Rangga)
(Raden Rangga)

Gbr diambil dr : islamidia.com
Semilir udara pagi menusuk tulang dan matahari masih sembunyi dalam selimut malam, tapi sayup-sayup sudah terdengar suara kesibukan di beberapa rumah. Bau nasi ditanak, tercium samar-samar, seiring suara kesibukan di dapur. Di rumah lain ada juga yang diwarnai tangisan bayi dan dendang si ibu bernyanyi berusaha menenangkan si jabang bayi.
Perlahan-lahan, sebuah kademangan kecil di pinggiran Kerajaan Watu Galuh, bangun dari tidurnya. Seiring langit pagi yang berubah warna, hari yang baru pun dimulai.
Pintu-pintu rumah mulai terbuka, para lelaki berangkat bekerja, entah itu ke ladang dan sawah, ataupun pekerjaan lainnya seperti berburu, pande besi, pedagang dan sebagainya. Para wanita pun memiliki kesibukannya mereka, ada yang sibuk di dapur, ada pula yang pergi mencuci ke sungai. Sementara yang masih anak-anak mulai berkumpul membentuk kelompok-kelompok, sibuk dengan permainan serta petualangan mereka sendiri.
Denyut-denyut kehidupan mengisi seluruh kademangan, …, kecuali di satu tempat.
Tepat berada di tengah-tengah pemukiman penduduk Kademangan Jati Asih, terlihat sebuah rumah yang pintu dan jendelanya masih tertutup rapat.
Di sekeliling rumah itu terhampar kebun yang cukup luas. Kebun itu dipenuhi tanaman tapi terlihat tidak terawat, dipagari pagar bambu, tapi ala kadarnya saja.
Seperti juga pintu rumah yang masih tertutup, pintu pagar yang sudah legrek itu, juga masih berdiri malas menghalangi jalan masuk orang ke dalam pekarangan.
Suasana di sekitar rumah itu jadi makin sunyi, karena setiap orang yang akan melewati rumah itu akan berjalan dengan hati-hati dan sesedikit mungkin mengeluarkan suara, seperti takut membangunkan seseorang atau sesuatu.
Yang sedang berjalan bersama sambil ngobrol dengan tetangga, begitu mendekati rumah tersebut akan menutup mulut dan baru setelah lewat, mereka kembali mengobrol dengan penuh semangat. Yang berjalan sendirian dan menghibur diri dengan bersiul-siul, akan berhenti bersiul ketika lewat di depan rumah tersebut.
Bahkan anak-anak pun terlihat lebih menahan diri waktu melewati rumah tersebut, meskipun yang namanya anak-anak, sudah tentu susah buat menahan tawa dan canda.
Ketika penduduk Kademangan Jati Asih sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, rumah itu pun jadi semakin terasa sunyi. Meski letaknya di tengah-tengah rumah-rumah yang lain, kesunyian-nya membuat rumah itu seperti berada di dunia yang berbeda. Sebuah pulau terasing di tengah keramaian.
--------
Matahari perlahan-lahan merayapi langit, selambat siput tapi ajeg dan pasti. Tak pernah terhenti setarikan nafas pun, mengikuti tulisan Sang Maha Pencipta. Langit biru cerah, sesekali disaput awan tipis. Angin berhembus sepoi-sepoi, membuat rumput dan bunga liar bergoyang, mengayunkan tarian tanah surga. Burung-burung mengiringinya dengan kicauan, berpadu dengan gemericiknya air sungai dan suara kesibukan di kejauhan.
Rumah dan pekarangannya yang luas itu, tenggelam dalam tidur dengan nyenyaknya.
----------
Ketika matahari tepat sampai di tengah hari, pintu rumah itu tiba-tiba berderit terbuka perlahan-lahan.
Seorang laki-laki dengan rambut panjang tak berikat, berjalan keluar, gerak-geriknya serba kemalas-malasan, seakan mau berlomba, siapa yang bisa berjalan lebih lambat, melawan matahari yang berada tepat di atas kepalanya.
Sambil meregangkan badan, laki-laki itu menatap langit yang sudah terang benderang. Lalu lama terdiam, seperti orang lupa ingatan.
Waktu terus berlalu. Angin berhembus silir-silir. Suara bebek berkuak sayup-sayup terdengar di kejauhan. Gemericik suara air sungai kecil di belakang rumah, dan laki-laki itu hanya diam menatapi langit.
Sampai tiba-tiba terdengar perutnya berkeruyuk, “Kruuuk.....kluthuk kluthuk...”
Laki-laki itu pun menundukkan kepala, mengamati perutnya sendiri dan bergumam, “Oalah...ra duwe isin... saben dina njaluk diiseni...” (terjemahan : dasar tak tahu malu, setiap hari minta diisi)
Kalau dilihat dari dekat, laki-laki itu tak terlalu tua, wajahnya tidak tampan, namun memiliki lekuk-lekuk garis wajah yang tegas dan berwibawa. Alisnya tebal dan membentuk garis yang tajam, memayungi matanya yang kemalas-malasan. Bibir-nya sedikit tersenyum, terlihat ringan tak ada beban hidup.
Sayangnya penampilan yang mestinya menarik itu, terpolusi dengan bau pemalas yang melekat erat pada dirinya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kesan pemalas itu terpatri di sudut-sudut ekspresi gerak-gerik tubuhnya.
Masih dengan kemalas-malasan laki-laki itu pergi ke dapur di belakang rumah. Di antara onggokan sisa kayu bakar, terlihat masih ada sisa-sisa singkong dengan kulit menghitam.
Diambilnya mangkok dari bathok kelapa dan tak lama kemudian dia menyibukkan diri mengupas kulit singkong yang sudah hangus itu dengan jari-jari tangannya.
Tangannya terlihat liat dan kokoh, dengan otot padat dan pembuluh menyembul menghiasi lengan. Telapak tangan dan jari-jari-nya terlihat keras dengan kulit tebal dan bekas luka di sana sini.
Tak berapa lama kemudian, laki-laki itu sudah bersantai di halaman belakang rumahnya. Berteduh di bawah pohon yang rindang. Dengan nikmatnya dia mengunyah singkong bakar sambil menekuni beberapa gulungan daun lontar.
Mulutnya tak berhenti mengunyah, sementara matanya menyusuri huruf demi huruf. Ketika membaca sorot matanya tampak serius, hilang bau malas yang tadi menguar dari aura tubuhnya. Mengamati sorot matanya, seperti melihat ke permukaan danau yang dalam, tenang tanpa riak gelombang.
------
Tiba-tiba sorot mata yang tenang itu berubah menjadi tajam.
Daun telinganya bergerak-gerak seperti telinga kelinci. Sesaat kemudian alisnya berkerut. Jarinya menggurat-gurat tanah, menghitung-hitung sesuatu.
“Hmm.... sepertinya raja tua itu akhirnya mangkat juga...”, desisnya.
Dengan hati-hati dia meletakkan gulungan-gulungan lontar ke dalam sebuah kotak kayu, kemudian menutupnya baik-baik. Laki-laki itu pun bangkit berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Ketika dia keluar ke halaman depan, kotak kayu yang berisi gulungan lontar itu sudah tidak berada di tangan-nya.
Penampilannya juga sudah berubah.
Rambutnya sudah digelung dan dirapikan, meskipun masih terlihat kemalas-malasan, namun aura wibawa yang terpendam, sedikit terpancar dari penampilannya sekarang ini.
Dia bersihkan amben bambu yang ada di depan rumahnya, sesudah itu dia siapkan satu kendi besar air minum dan 4 buah gelas dari potongan bambu. Sisa singkong bakar yang belum habis dia makan, dia hidangkan pula di sebuah piring dari tanah liat.
Laki-laki itu mengamat-amati hidangan yang sudah dia siapkan, sepotong singkong yang terlalu kecil dia ambil dan dilontarkan ke mulutnya sendiri., “Hehee... lumayan...”
Entah, maksudnya sajian di amben itu yang lumayan enak dilihat, atau singkong yang dia kunyah yang lumayan rasanya.
Setelah menyiapkan semuanya, dia pun pergi untuk membuka pintu pagar pekarangan. Baru saja dia membuka pagar, di ujung jalan terlihat empat orang laki-laki berlari tergopoh-gopoh menuju ke arahnya.
Melihat lelaki pemalas itu, ke empat laki-laki itu yang sedang berlari itu menghentikan larinya. Mereka berjalan cepat dengan sedikit membungkukkan badan, menunjukkan rasa hormat.
“Aduh den... ketiwasan den... ketiwasan.... Raden Rangga... kademangan kita tertimpa musibah.” Ujar salah satu dari empat orang laki-laki itu dengan nafas masih memburu, begitu mereka sampai di hadapan si lelaki pemalas.
Di antara mereka berempat, dialah yang tertua dan berjalan paling depan.
Laki-laki yang dipanggil Raden Rangga itu dengan tenang menepuk-nepuk pundak laki-laki tua itu, “Sudah...sudah...cup...cup...cup... Seperti langit mau rubuh saja...”
“Eh... ya...” Ki Demang bingung tak tahu harus menjawab apa.
Suasana yang tadinya tegang jadi sedikit cair. Entah siapa, Ki Demang mendengar salah seorang pengikutnya tertawa kecil. Karena tak mungkin dia marah pada Raden Rangga, akhirnya dia cuma bisa melotot pada tiga orang lain yang ikut datang bersama dia.
“Ki Demang jangan panik dulu. Mari masuk ke dalam, baru nanti ceritakan perlahan-lahan, apa yang terjadi, hingga Ki Demang jadi panik seperti sekarang ini.” Ujar Raden Rangga tidak memperpanjang godaannya pada Ki Demang.
Tanpa menunggu empat tamunya dia berjalan menuju ke amben di depan rumah.
Ketenangan-nya menular ke empat laki-laki yang lain. Tinggal sebersit rasa cemas masih menghiasi raut wajah mereka. Laki-laki yang dipanggil Raden Rangga itu memang jauh lebih muda dari mereka berempat. Namun, wibawa dan ketenangan yang memancar dari dirinya, membuat mereka merasa menemukan pegangan yang bisa mereka percaya dalam menghadapi semua masalah.
“Minum dulu.”, ujar Rangga singkat.
Empat lelaki itu melihat empat buah gelas yang sudah disediakan, tepat empat sesuai jumlah mereka yang datang. Lalu teringat pula, Rangga yang pemalas dan hampir tidak pernah keluar dari rumah, sudah menunggu mereka di depan pagar, ketika mereka tiba.
Ki Demang dan tiga orang pengikutnya saling berpandangan. Dari sorot mata mereka, terlihat rasa kagum. Selesai mereka minum beberapa teguk, Rangga mengangsurkan singkong bakar ke arah mereka.
“Baik sekarang coba Ki Demang coba ceritakan dengan runut, tidak perlu terburu-buru,” kata Rangga berwibawa.
“Pagi ini, datang menemui kami, seorang cantrik asuhan Resi Natadharma, membawa kabar genting...” Sampai di situ, Ki Demang terlihat berat untuk melanjutkan.
Raden Rangga tidak berkata apa-apa, hanya menunggu Ki Demang melanjutkan penuturannya.
Akhirnya Ki Demang pun melanjutkan degan terbata-bata, “Sang prabu dikabarkan sudah berpulang seminggu yang lalu.... dan putera mahkota Pangeran Puguh yang sekarang bertakhta, dengan gelar Prabu Jannapati.”
Ki Demang dan tiga lelaki yang lain, mengamati baik-baik raut wajah Rangga, berharap melihat dia menunjukkan reaksi tertentu. Namun mereka hanya bisa menelan rasa penasaran, karena wajah Rangga biasa-biasa saja, tak bergejolak sedikit pun.
“Itu saja?”, tanya Rangga.
“Resi Natadharma mengingatkan, sikap raja yang sekarang, bisa jadi berbeda dengan almarhum kanjeng prabu yang sudah wafat”, jawab Ki Demang.
“Itu saja?”, tanya Rangga.
Ki Demang tampak ragu-ragu sebelum menambahkan, “Ini bukan pesan dari Resi Natadharma, tapi dari cerita cantrik yang menjadi utusan. Menurutnya, akan ada pembersihan oleh raja yang baru. Terlihat satuan-satuan pasukan dari beberapa kadipaten, yang diminta berkumpul ke ibu kota.”
“Sementara Pangeran Adiyasa, adik Pangeran Puguh, yang sebelumnya sempat didukung beberapa orang menteri dan penasehat agar dipilih menjadi putera mahkota, pergi tetirah ke Kadipaten Banyu Urip, sehari setelah upacara pengangkatan Prabu Jannapati.”
“Itu saja?”, untuk ketiga kalinya Rangga bertanya.
Ki Demang terlihat ragu, tapi akhirnya menganggukkan kepala, “Itu saja Den.”
Rangga tersenyum, “Kalau tidak ada yang lain, aku ingin melanjutkan tidur siangku.”
Ki Demang dan tiga tamu yang lain saling berpandangan.
Seorang dari mereka, seorang laki-laki setengah baya dengan badan kekar dan berkumis tebal, memberanikan diri untuk bertanya pada Rangga, “Raden... apa kita tidak perlu bersiap-siap?”
“Bersiap-siap untuk apa Ki Jagabaya?”, Rangga balik bertanya.
“Siap-siap... eh... bagaimana tentang kabar akan ada pembersihan...”, ragu-ragu Ki Jagabaya berusaha menjawab.
Raden Rangga tertawa kecil, lalu berdiri dari duduknya, dan mengangguk ke arah pintu keluar. Ke-empat tetamunya pun, terpaksa ikut berdiri dan dengan setengah hati berjalan pergi.
Ketika Ki Demang berjalan melewati dirinya, Rangga menepuk pundak lelaki tua itu, “Jangan kalian pikirkan tentang ruwetnya urusan di ibu kota. Aku kenal baik siapa itu Pangeran Puguh, percayalah, kademangan ini baik-baik saja.”
Mendengar jawaban Rangga, hati ke-empat tamunya pun jadi sedikit lega. Mereka tidak percaya pada raja yang baru ini, tapi mereka percaya Rangga. Rangga mengantar mereka sampai ke pagar depan, selama berjalan dia terlihat diam dan berpikir. Ke-empat tamunya itu tidak berani mengganggu.
Ketika mereka hendak berpamitan, Rangga berkata, “Setidaknya untuk saat ini, biarkan semuanya berjalan seperti biasa.”
Ki Demang dan Ki Jagabaya saling berpandangan, wajah mereka terlihat hikmat. Resi Natadharma tidak mungkin mengirimkan utusan jika tidak ada berita yang sifatnya genting. Namun bila gosip dari cantrik itu benar, mereka pun tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan kademangan kecil seperti kademangan mereka menghadapi satuan khusus sebuah kerajaan. Itu sebabnya mereka merasa panik. Ketenangan dan jaminan dari Rangga memang menguatkan hati mereka, tapi tetap saja rasa terancam itu tidak hilang dari hati mereka.
“Kami mengerti Den”, jawab mereka hampir serempak.
“Aku akan meninggalkan Kademangan Jati Asih untuk beberapa waktu. Tidak lama ... tidak akan lebih dari seminggu. Kalau ada yang mencariku, Ki Demang suruh saja dia menunggu, atau meninggalkan pesan.”, Rangga menambahkan.
“Apakah kepergian Raden perlu kami rahasiakan?”, tanya Ki Demang.
Rangga menggelengkan kepala, “Tidak usah, hanya akan membuat kecurigaan yang tak perlu.”
Rangga masih menunggu Ki Demang dan yang lain hilang di ujung jalan, sebelum dia kembali ke dalam rumah. Tak ingin kepergiannya dilihat banyak orang, baru setelah mendekati tengah malam, Rangga berjalan meninggalkan Kademangan Jati Asih.
Membawa buntalan di atas pundak, Rangga berjalan menelusuri pematang-pematang sawah, jauh dari rumah-rumah penduduk. Sesekali terlihat sekelompok peronda yang berjalan mengitari jalan-jalan di Kademangan Jati Asih, namun tidak sulit bagi Rangga untuk bersembunyi dari pandangan mata mereka. Hanya dengan berhenti bergerak saja, dalam sepersekian tarikan nafas, keberadaan-nya seperti mengabur dari kesadaran orang-orang lain di sekelilingnya. Jangankan dari kejauhan dan tersembunyi dalam gelap. Rangga bisa saja berdiri satu meter di depan mereka, tanpa mereka sadar ada orang di depannya.
Rangga tidak berlari, hanya berjalan saja, bahkan langkah-langkahnya tidak terlihat cepat bergegas, tapi tubuhnya ringan seperti tertiup angin. Kalau memakai jubah putih, sudah terlihat melayang-layang seperti arwah gentayangan.
Rangga dengan cepat sampai ke perbatasan Kademangan, tak ada halangan yang berarti selama perjalanan.
Namun, ketika setapak saja kakinya baru melangkah meninggalkan batas kademangan Jati Asih, tiba-tiba satu sosok berkelebat cepat, jauh lebih cepat dari gerakan Rangga, menghadang jalannya. Suara angin berkesiur mengikuti lontaran sepasang kepalan tangan ke arah dada Rangga.
Rangga tidak kalah cepat bereaksi, tubuhnya menyurut mundur, seringan bulu yang tertiup angin. Dua tangannya bergerak menyambut kepalan lawan dengan telapak tangan yang terbuka. Ketika kedua pasang tangan itu bertemu, tidak terdengar suara benturan yang keras. Bahkan hampir-hampir tidak ada suara benturan sedikitpun. Namun tenaga yang dibawa dua tinju itu teredam oleh dua telapak tangan Rangga.
Dengan ringan tubuh Rangga melayang mundur, memasuki kembali tapal batas Kadengan Jati Asih, sementara sosok yang menyerang dirinya juga tidak maju memburu.
Matahari masih jauh dari terbitnya, ketika Rangga sampai di batas terluar Kademangan Jati asih. Orang-orang yang normal, masih nyenyak dalam tidurnya, tapi di garis perbatasan Kademangan Jati Asih, diapit dua gapura penanda batas, berdiri dua sosok saling berhadapan, dengan kaki terpentang menancap kukuh di bumi.
Perlahan-lahan, sebuah kademangan kecil di pinggiran Kerajaan Watu Galuh, bangun dari tidurnya. Seiring langit pagi yang berubah warna, hari yang baru pun dimulai.
Pintu-pintu rumah mulai terbuka, para lelaki berangkat bekerja, entah itu ke ladang dan sawah, ataupun pekerjaan lainnya seperti berburu, pande besi, pedagang dan sebagainya. Para wanita pun memiliki kesibukannya mereka, ada yang sibuk di dapur, ada pula yang pergi mencuci ke sungai. Sementara yang masih anak-anak mulai berkumpul membentuk kelompok-kelompok, sibuk dengan permainan serta petualangan mereka sendiri.
Denyut-denyut kehidupan mengisi seluruh kademangan, …, kecuali di satu tempat.
Tepat berada di tengah-tengah pemukiman penduduk Kademangan Jati Asih, terlihat sebuah rumah yang pintu dan jendelanya masih tertutup rapat.
Di sekeliling rumah itu terhampar kebun yang cukup luas. Kebun itu dipenuhi tanaman tapi terlihat tidak terawat, dipagari pagar bambu, tapi ala kadarnya saja.
Seperti juga pintu rumah yang masih tertutup, pintu pagar yang sudah legrek itu, juga masih berdiri malas menghalangi jalan masuk orang ke dalam pekarangan.
Suasana di sekitar rumah itu jadi makin sunyi, karena setiap orang yang akan melewati rumah itu akan berjalan dengan hati-hati dan sesedikit mungkin mengeluarkan suara, seperti takut membangunkan seseorang atau sesuatu.
Yang sedang berjalan bersama sambil ngobrol dengan tetangga, begitu mendekati rumah tersebut akan menutup mulut dan baru setelah lewat, mereka kembali mengobrol dengan penuh semangat. Yang berjalan sendirian dan menghibur diri dengan bersiul-siul, akan berhenti bersiul ketika lewat di depan rumah tersebut.
Bahkan anak-anak pun terlihat lebih menahan diri waktu melewati rumah tersebut, meskipun yang namanya anak-anak, sudah tentu susah buat menahan tawa dan canda.
Ketika penduduk Kademangan Jati Asih sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, rumah itu pun jadi semakin terasa sunyi. Meski letaknya di tengah-tengah rumah-rumah yang lain, kesunyian-nya membuat rumah itu seperti berada di dunia yang berbeda. Sebuah pulau terasing di tengah keramaian.
--------
Matahari perlahan-lahan merayapi langit, selambat siput tapi ajeg dan pasti. Tak pernah terhenti setarikan nafas pun, mengikuti tulisan Sang Maha Pencipta. Langit biru cerah, sesekali disaput awan tipis. Angin berhembus sepoi-sepoi, membuat rumput dan bunga liar bergoyang, mengayunkan tarian tanah surga. Burung-burung mengiringinya dengan kicauan, berpadu dengan gemericiknya air sungai dan suara kesibukan di kejauhan.
Rumah dan pekarangannya yang luas itu, tenggelam dalam tidur dengan nyenyaknya.
----------
Ketika matahari tepat sampai di tengah hari, pintu rumah itu tiba-tiba berderit terbuka perlahan-lahan.
Seorang laki-laki dengan rambut panjang tak berikat, berjalan keluar, gerak-geriknya serba kemalas-malasan, seakan mau berlomba, siapa yang bisa berjalan lebih lambat, melawan matahari yang berada tepat di atas kepalanya.
Sambil meregangkan badan, laki-laki itu menatap langit yang sudah terang benderang. Lalu lama terdiam, seperti orang lupa ingatan.
Waktu terus berlalu. Angin berhembus silir-silir. Suara bebek berkuak sayup-sayup terdengar di kejauhan. Gemericik suara air sungai kecil di belakang rumah, dan laki-laki itu hanya diam menatapi langit.
Sampai tiba-tiba terdengar perutnya berkeruyuk, “Kruuuk.....kluthuk kluthuk...”
Laki-laki itu pun menundukkan kepala, mengamati perutnya sendiri dan bergumam, “Oalah...ra duwe isin... saben dina njaluk diiseni...” (terjemahan : dasar tak tahu malu, setiap hari minta diisi)
Kalau dilihat dari dekat, laki-laki itu tak terlalu tua, wajahnya tidak tampan, namun memiliki lekuk-lekuk garis wajah yang tegas dan berwibawa. Alisnya tebal dan membentuk garis yang tajam, memayungi matanya yang kemalas-malasan. Bibir-nya sedikit tersenyum, terlihat ringan tak ada beban hidup.
Sayangnya penampilan yang mestinya menarik itu, terpolusi dengan bau pemalas yang melekat erat pada dirinya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kesan pemalas itu terpatri di sudut-sudut ekspresi gerak-gerik tubuhnya.
Masih dengan kemalas-malasan laki-laki itu pergi ke dapur di belakang rumah. Di antara onggokan sisa kayu bakar, terlihat masih ada sisa-sisa singkong dengan kulit menghitam.
Diambilnya mangkok dari bathok kelapa dan tak lama kemudian dia menyibukkan diri mengupas kulit singkong yang sudah hangus itu dengan jari-jari tangannya.
Tangannya terlihat liat dan kokoh, dengan otot padat dan pembuluh menyembul menghiasi lengan. Telapak tangan dan jari-jari-nya terlihat keras dengan kulit tebal dan bekas luka di sana sini.
Tak berapa lama kemudian, laki-laki itu sudah bersantai di halaman belakang rumahnya. Berteduh di bawah pohon yang rindang. Dengan nikmatnya dia mengunyah singkong bakar sambil menekuni beberapa gulungan daun lontar.
Mulutnya tak berhenti mengunyah, sementara matanya menyusuri huruf demi huruf. Ketika membaca sorot matanya tampak serius, hilang bau malas yang tadi menguar dari aura tubuhnya. Mengamati sorot matanya, seperti melihat ke permukaan danau yang dalam, tenang tanpa riak gelombang.
------
Tiba-tiba sorot mata yang tenang itu berubah menjadi tajam.
Daun telinganya bergerak-gerak seperti telinga kelinci. Sesaat kemudian alisnya berkerut. Jarinya menggurat-gurat tanah, menghitung-hitung sesuatu.
“Hmm.... sepertinya raja tua itu akhirnya mangkat juga...”, desisnya.
Dengan hati-hati dia meletakkan gulungan-gulungan lontar ke dalam sebuah kotak kayu, kemudian menutupnya baik-baik. Laki-laki itu pun bangkit berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Ketika dia keluar ke halaman depan, kotak kayu yang berisi gulungan lontar itu sudah tidak berada di tangan-nya.
Penampilannya juga sudah berubah.
Rambutnya sudah digelung dan dirapikan, meskipun masih terlihat kemalas-malasan, namun aura wibawa yang terpendam, sedikit terpancar dari penampilannya sekarang ini.
Dia bersihkan amben bambu yang ada di depan rumahnya, sesudah itu dia siapkan satu kendi besar air minum dan 4 buah gelas dari potongan bambu. Sisa singkong bakar yang belum habis dia makan, dia hidangkan pula di sebuah piring dari tanah liat.
Laki-laki itu mengamat-amati hidangan yang sudah dia siapkan, sepotong singkong yang terlalu kecil dia ambil dan dilontarkan ke mulutnya sendiri., “Hehee... lumayan...”
Entah, maksudnya sajian di amben itu yang lumayan enak dilihat, atau singkong yang dia kunyah yang lumayan rasanya.
Setelah menyiapkan semuanya, dia pun pergi untuk membuka pintu pagar pekarangan. Baru saja dia membuka pagar, di ujung jalan terlihat empat orang laki-laki berlari tergopoh-gopoh menuju ke arahnya.
Melihat lelaki pemalas itu, ke empat laki-laki itu yang sedang berlari itu menghentikan larinya. Mereka berjalan cepat dengan sedikit membungkukkan badan, menunjukkan rasa hormat.
“Aduh den... ketiwasan den... ketiwasan.... Raden Rangga... kademangan kita tertimpa musibah.” Ujar salah satu dari empat orang laki-laki itu dengan nafas masih memburu, begitu mereka sampai di hadapan si lelaki pemalas.
Di antara mereka berempat, dialah yang tertua dan berjalan paling depan.
Laki-laki yang dipanggil Raden Rangga itu dengan tenang menepuk-nepuk pundak laki-laki tua itu, “Sudah...sudah...cup...cup...cup... Seperti langit mau rubuh saja...”
“Eh... ya...” Ki Demang bingung tak tahu harus menjawab apa.
Suasana yang tadinya tegang jadi sedikit cair. Entah siapa, Ki Demang mendengar salah seorang pengikutnya tertawa kecil. Karena tak mungkin dia marah pada Raden Rangga, akhirnya dia cuma bisa melotot pada tiga orang lain yang ikut datang bersama dia.
“Ki Demang jangan panik dulu. Mari masuk ke dalam, baru nanti ceritakan perlahan-lahan, apa yang terjadi, hingga Ki Demang jadi panik seperti sekarang ini.” Ujar Raden Rangga tidak memperpanjang godaannya pada Ki Demang.
Tanpa menunggu empat tamunya dia berjalan menuju ke amben di depan rumah.
Ketenangan-nya menular ke empat laki-laki yang lain. Tinggal sebersit rasa cemas masih menghiasi raut wajah mereka. Laki-laki yang dipanggil Raden Rangga itu memang jauh lebih muda dari mereka berempat. Namun, wibawa dan ketenangan yang memancar dari dirinya, membuat mereka merasa menemukan pegangan yang bisa mereka percaya dalam menghadapi semua masalah.
“Minum dulu.”, ujar Rangga singkat.
Empat lelaki itu melihat empat buah gelas yang sudah disediakan, tepat empat sesuai jumlah mereka yang datang. Lalu teringat pula, Rangga yang pemalas dan hampir tidak pernah keluar dari rumah, sudah menunggu mereka di depan pagar, ketika mereka tiba.
Ki Demang dan tiga orang pengikutnya saling berpandangan. Dari sorot mata mereka, terlihat rasa kagum. Selesai mereka minum beberapa teguk, Rangga mengangsurkan singkong bakar ke arah mereka.
“Baik sekarang coba Ki Demang coba ceritakan dengan runut, tidak perlu terburu-buru,” kata Rangga berwibawa.
----------
“Pagi ini, datang menemui kami, seorang cantrik asuhan Resi Natadharma, membawa kabar genting...” Sampai di situ, Ki Demang terlihat berat untuk melanjutkan.
Raden Rangga tidak berkata apa-apa, hanya menunggu Ki Demang melanjutkan penuturannya.
Akhirnya Ki Demang pun melanjutkan degan terbata-bata, “Sang prabu dikabarkan sudah berpulang seminggu yang lalu.... dan putera mahkota Pangeran Puguh yang sekarang bertakhta, dengan gelar Prabu Jannapati.”
Ki Demang dan tiga lelaki yang lain, mengamati baik-baik raut wajah Rangga, berharap melihat dia menunjukkan reaksi tertentu. Namun mereka hanya bisa menelan rasa penasaran, karena wajah Rangga biasa-biasa saja, tak bergejolak sedikit pun.
“Itu saja?”, tanya Rangga.
“Resi Natadharma mengingatkan, sikap raja yang sekarang, bisa jadi berbeda dengan almarhum kanjeng prabu yang sudah wafat”, jawab Ki Demang.
“Itu saja?”, tanya Rangga.
Ki Demang tampak ragu-ragu sebelum menambahkan, “Ini bukan pesan dari Resi Natadharma, tapi dari cerita cantrik yang menjadi utusan. Menurutnya, akan ada pembersihan oleh raja yang baru. Terlihat satuan-satuan pasukan dari beberapa kadipaten, yang diminta berkumpul ke ibu kota.”
“Sementara Pangeran Adiyasa, adik Pangeran Puguh, yang sebelumnya sempat didukung beberapa orang menteri dan penasehat agar dipilih menjadi putera mahkota, pergi tetirah ke Kadipaten Banyu Urip, sehari setelah upacara pengangkatan Prabu Jannapati.”
“Itu saja?”, untuk ketiga kalinya Rangga bertanya.
Ki Demang terlihat ragu, tapi akhirnya menganggukkan kepala, “Itu saja Den.”
Rangga tersenyum, “Kalau tidak ada yang lain, aku ingin melanjutkan tidur siangku.”
Ki Demang dan tiga tamu yang lain saling berpandangan.
Seorang dari mereka, seorang laki-laki setengah baya dengan badan kekar dan berkumis tebal, memberanikan diri untuk bertanya pada Rangga, “Raden... apa kita tidak perlu bersiap-siap?”
“Bersiap-siap untuk apa Ki Jagabaya?”, Rangga balik bertanya.
“Siap-siap... eh... bagaimana tentang kabar akan ada pembersihan...”, ragu-ragu Ki Jagabaya berusaha menjawab.
Raden Rangga tertawa kecil, lalu berdiri dari duduknya, dan mengangguk ke arah pintu keluar. Ke-empat tetamunya pun, terpaksa ikut berdiri dan dengan setengah hati berjalan pergi.
Ketika Ki Demang berjalan melewati dirinya, Rangga menepuk pundak lelaki tua itu, “Jangan kalian pikirkan tentang ruwetnya urusan di ibu kota. Aku kenal baik siapa itu Pangeran Puguh, percayalah, kademangan ini baik-baik saja.”
Mendengar jawaban Rangga, hati ke-empat tamunya pun jadi sedikit lega. Mereka tidak percaya pada raja yang baru ini, tapi mereka percaya Rangga. Rangga mengantar mereka sampai ke pagar depan, selama berjalan dia terlihat diam dan berpikir. Ke-empat tamunya itu tidak berani mengganggu.
Ketika mereka hendak berpamitan, Rangga berkata, “Setidaknya untuk saat ini, biarkan semuanya berjalan seperti biasa.”
Ki Demang dan Ki Jagabaya saling berpandangan, wajah mereka terlihat hikmat. Resi Natadharma tidak mungkin mengirimkan utusan jika tidak ada berita yang sifatnya genting. Namun bila gosip dari cantrik itu benar, mereka pun tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan kademangan kecil seperti kademangan mereka menghadapi satuan khusus sebuah kerajaan. Itu sebabnya mereka merasa panik. Ketenangan dan jaminan dari Rangga memang menguatkan hati mereka, tapi tetap saja rasa terancam itu tidak hilang dari hati mereka.
“Kami mengerti Den”, jawab mereka hampir serempak.
“Aku akan meninggalkan Kademangan Jati Asih untuk beberapa waktu. Tidak lama ... tidak akan lebih dari seminggu. Kalau ada yang mencariku, Ki Demang suruh saja dia menunggu, atau meninggalkan pesan.”, Rangga menambahkan.
“Apakah kepergian Raden perlu kami rahasiakan?”, tanya Ki Demang.
Rangga menggelengkan kepala, “Tidak usah, hanya akan membuat kecurigaan yang tak perlu.”
Rangga masih menunggu Ki Demang dan yang lain hilang di ujung jalan, sebelum dia kembali ke dalam rumah. Tak ingin kepergiannya dilihat banyak orang, baru setelah mendekati tengah malam, Rangga berjalan meninggalkan Kademangan Jati Asih.
Membawa buntalan di atas pundak, Rangga berjalan menelusuri pematang-pematang sawah, jauh dari rumah-rumah penduduk. Sesekali terlihat sekelompok peronda yang berjalan mengitari jalan-jalan di Kademangan Jati Asih, namun tidak sulit bagi Rangga untuk bersembunyi dari pandangan mata mereka. Hanya dengan berhenti bergerak saja, dalam sepersekian tarikan nafas, keberadaan-nya seperti mengabur dari kesadaran orang-orang lain di sekelilingnya. Jangankan dari kejauhan dan tersembunyi dalam gelap. Rangga bisa saja berdiri satu meter di depan mereka, tanpa mereka sadar ada orang di depannya.
Rangga tidak berlari, hanya berjalan saja, bahkan langkah-langkahnya tidak terlihat cepat bergegas, tapi tubuhnya ringan seperti tertiup angin. Kalau memakai jubah putih, sudah terlihat melayang-layang seperti arwah gentayangan.
Rangga dengan cepat sampai ke perbatasan Kademangan, tak ada halangan yang berarti selama perjalanan.
Namun, ketika setapak saja kakinya baru melangkah meninggalkan batas kademangan Jati Asih, tiba-tiba satu sosok berkelebat cepat, jauh lebih cepat dari gerakan Rangga, menghadang jalannya. Suara angin berkesiur mengikuti lontaran sepasang kepalan tangan ke arah dada Rangga.
Rangga tidak kalah cepat bereaksi, tubuhnya menyurut mundur, seringan bulu yang tertiup angin. Dua tangannya bergerak menyambut kepalan lawan dengan telapak tangan yang terbuka. Ketika kedua pasang tangan itu bertemu, tidak terdengar suara benturan yang keras. Bahkan hampir-hampir tidak ada suara benturan sedikitpun. Namun tenaga yang dibawa dua tinju itu teredam oleh dua telapak tangan Rangga.
Dengan ringan tubuh Rangga melayang mundur, memasuki kembali tapal batas Kadengan Jati Asih, sementara sosok yang menyerang dirinya juga tidak maju memburu.
Matahari masih jauh dari terbitnya, ketika Rangga sampai di batas terluar Kademangan Jati asih. Orang-orang yang normal, masih nyenyak dalam tidurnya, tapi di garis perbatasan Kademangan Jati Asih, diapit dua gapura penanda batas, berdiri dua sosok saling berhadapan, dengan kaki terpentang menancap kukuh di bumi.
Bersambung ke bab II








